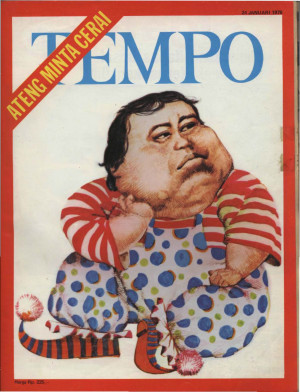BERLAPIS-LAPIS layar warna-warni menutupi panggung sempit di
depan layar bioskop Benteng itu. Serentak dengan tingkahan musik
pengantar bercampur komentar penyiar radio, layar pun tersingkap
beriring. Di balik sana, di atas panggung, tergelar amat rapi
set ruang tamu sebuah rumah tinggal keluarga menengah. Pemain
akhirnya muncul, dan tatkala mereka mulai berbicara, suara
mereka terdengar utuh menggema di seluruh ruang bioskop Benteng
yang terletak di pantai kota Ujung Pandang itu. "Pemain di
panggung itu cuma menyesuaikan gerak mulutnya dengan suara
mereka yang telah kita rekam terlebih dahulu", komentar Kolonel
Djamaluddin Effendi, pengarang dan sutradara pementasan yang
populer dengan sistim full dubbing tersebut.
Sembari terus mengepul-ngepulkan asap tembakau dari pipanya,
kolonel yang kepala intel ini bercerita panjang lebar tentang
sistim dubbing itu. Perwira menengah yang telah bertugas lama di
Ujung Pandang ini mula-mula bersinggungan dengan soal seni
tatkala beberapa tahun silam ia mulai menulis novel.
Karangan-karangannya yang lahir secara subur itu kemudian
tersiar pula lewat udara dalam bentuk sandiwara radio RRI Ujung
Pandang. "Ketika itu saya mulai menyadari bahwa penduduk kota
ini kurang hiburan, dan sandiwara radio saja tentu tidak cukup",
begitu Djamaluddin bercerita. Ketika ia berniat juga muncul di
panggung, sudah jelas tidak mungkin, "sebab kota ini sama sekali
tidak punya panggung, apa lagi gedung yang pantas untuk
pementasan", kataya pula.
Nah, putar akallah sang kolonel. "Kalau tak ada rotan akar pun
jadilah." Dan bioskop Benteng pun dimanfaatkan, dengan membangun
panggung kecil di depan layar. "Ini tidak gratis, lho. Pembuatan
panggung dari batu kita tanggung sendiri, dan setiap malam
pertunjukan kita harus membayar 75 ribu pada direksi bioskop",
tukas Djamaluddin. Dan dalam gedung bioskop yang begitu besar
dengan akustik yang terlalu buruk (suara musik gemuruh dari klab
malam di sampingnya terdengar menusuk dalam bioskop tua ini)
hasrat bersandiwara cara normal hanya akan mendongkolkan hati
pembeli karcis yang duduk di belakang. Djamaluddin pun teringat
akan sandiwara radionya itu. Bisa dibayangkan apa yang lahir
dari kombinasi "akar-akar" itu, bukan?
Walhasil kini di Ujung Pandang telah hadir sebuah sandiwara
kombinasi: panggung dan radio. Grup pimpinan Kolonel Djamaluddin
Effendi itu bernama Teater Angkasa, dan setiap malam pertama
pertunjukan mereka sekaligus juga bisa diikuti lewat RRI Ujung
Pandang. Unik memang, terutama bagi para pemainnya yang sebagian
juga bekas pemain pentas. Soal mensinkronkan gerak mulut dengan
suara yang sudah terekam itulah soal utama. "Satu dua pementasan
pertama memang masih berat, karena pada saat itu rekaman dibuat
betul-betul berdasarkan sandiwara radio, tanpa memperhitungkan
kemungkinan gerak di atas panggung", komentar seorang pemain
Teater Angkasa. Tapi Djamaluddin ini punya cara untuk
melakukan perbaikkan. Setiap selesai pertunjukan, ia selalu
minta pendapat teman-temannya, tapi terutama Rahmah Arge, Ketua
Dewan Kesenian Ujung Pandang. Konon dari pengalaman 7 kali
pertunjukan di tahun 1975 -- juga tahun ditemukannya sistim
dubbing itu -- plus pendapat dan saran teman-temannya, kini
rekaman Teater Angkasa telah pula memperhitungkan segala
kemungkinan di atas panggung. "Kami menggunakan stop watch untuk
menghitung waktu gerak pemain-pemain di atas panggung", kata
Djamaluddin pula. Sudah tentu cara seperti ini toh belum bisa
menjamin sinkron sepenuhnya. "Tapi dibanding dengan
pertunjukannya yang dulu-dulu, pertunjukan Embun Pagi ini sudah
jauh lebih sempurna", begitu Rahman Arge mengomentari teknik
pertunjukan yang berlangsung awal Januari 1976 ini.
Soal mutu? "Wah, saya tidak berani bicara", sambut Djamaluddin
dengan senyum. Dan pemimpin grup teater yang satu ini pun
mengumumkan sebuah pengakuan. "Saya terakhir nonton sandiwara di
tahun empatpuluhan. Jadi bisa saudara bayangkan selera dan
pcrkembangan saya,bukan?" Kepada Salim Said dari TEMPO
Djamaluddin menyatakan keinginannya menonton pementasan berbagai
teater mutakhir di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. "Tapi saya ini
kan selalu sibuk kalau lagi ke Jakarta", keluhnya.
Bukan cuma di Jakarta, juga di Ujung Pandang Djamaluddin selalu
sibuk, hingga menyaksikan pementasan drama Dewan Kesenian Ujung
Pandang yang memang jarang itu, juga tidak sempat. "Tapi saya
selalu mengikuti kegiatan teman-teman dan bahkan ikut mendorong
mereka", tukas Djamaluddin pula. Sebagai kepala intel, tentulah
logis kalau kolonel ini mengetahui semua yang terjadi, dan dari
pengetahuanya itulah ia bersama seniman-seniman Ujung Pandang
ikut mendesak Wali Kota Patompo -- untuk segera membangun sebuah
gedung kesenian yang pantas untuk kota yang berharap punya
"dimensi budaya" itu. Juga dari kedudukannya yang amat strategis
itulah barangkali Djamaluddin tahu bahwa kegiatannya berteater
itu telah menarik banyak penonton dalam sekian malam
berturut-turut. Katanya: "Kalau dari segi mutu barangkali saya
dinilai kurang, dari segi, mendidik orang menonton pementasan
saya yakin kegiatan kami telah berbuat banyak. Mudah-mudahan
penonton yang saya bina ini kemudian bisa mendapat suguhan
beragam sandiwara oleh seniman-seniman di kota ini". Kalimat
yang terakhir ini diucapkan oleh Djamaluddin ketika baru saja
menyinggung kedudukannya sebagai pejabat yang tidak bisa selalu
berada di suatu tempat. "Sebelum MPP atau pergi dari sini, saya
ingin meninggalkan sesuatu untuk Ujung Pandang".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini