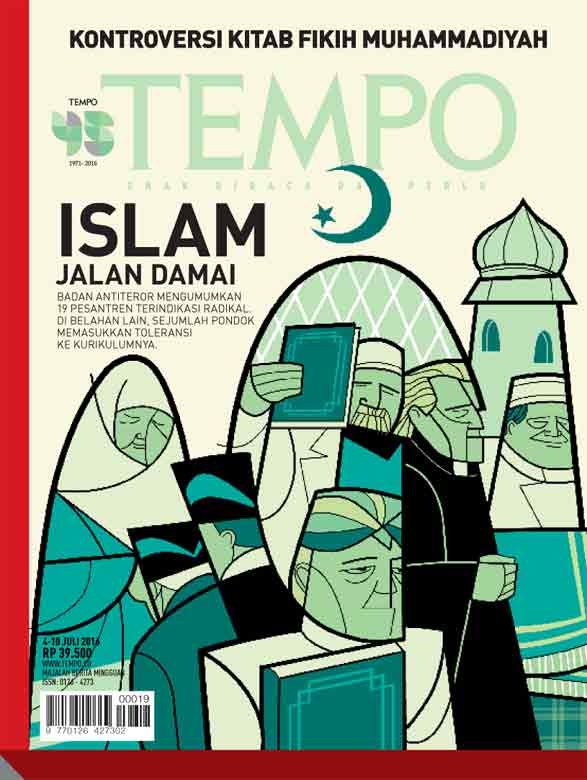Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
RADEN MANDASIA SI PENCURI DAGING SAPI
Penulis: Yusi Avianto Pareanom
Penerbit: Banana Publishing (2016)
Tebal: 450 halaman
NOVEL dengan sampul depan berlabel "Sebuah Dongeng" ini mencampuradukkan beragam unsur kultur pop: cerita silat Kho Ping Hoo dan Jaka Sembung; karakter Tintin, Kapten Haddock, bahkan si anjing Snowy (Milo di terjemahan versi terbaru); referensi dari Asterix dan Obelix; kisah Nabi Isa dan Nabi Yunus yang dicampursari (mash-up) dengan Pinokio dan Moby Dick; film laga 300, dan masih banyak lagi.
Dengan ketangkasan dan kecerdikan Yusi bersilat kata, pamer wawasan jadi bumbu cerita yang sedap. Bukan hanya dialog antarkarakter yang terasa hidup, adegan demi adegan di dalam buku ini diceritakan dengan sangat lancar dan sinematik sehingga menimbulkan keasyikan membaca. Ini sudah terasa sejak halaman pertama ketika kita berkenalan dengan Raden Mandasia dan Sungu Lembu—nama yang terakhir tokoh utama sekaligus narator buku ini.
Salah satu motif yang juga dipakai Yusi untuk menebar pesona kepada pembacanya adalah makanan. Bermacam jenis makanan dari berbagai penjuru dunia antah-berantah yang diciptakannya mendapat porsi yang istimewa di buku ini. Contohnya daging sapi buatan Raden Mandasia: "…daging-daging yang cukup dibakar dua sisi sebentar saja sampai setengah matang supaya keempukannya terjaga sehingga lumer saat digigit…" (halaman 20). Semakin saya mengikuti sepak terjang Sungu Lembu dan Raden Mandasia, saya kadang merasa mereka seperti duo foodie snob dan travel junkie dari zaman Majapahit yang keluar dari saluran televisi gaya hidup.
Pilihan Yusi menulis dengan gaya ini membuat saya dengan girang menjuluki karya ini sebagai sebuah "babad milenial". Yusi melakukan campursari antara tokoh-tokoh dari dongeng masa lalu dan dongeng masa kini dengan memukau. Bahkan Yusi mengadon pemikiran rasional dengan takhayul di dalam ataupun di antara karakter-karakternya—sebuah siasat yang sungguh canggih.
Tapi ada yang mengusik saya, yaitu karakter Sungu Lembu (dan kebanyakan karakter laki-laki lainnya) yang terlampau macho dan seksis. Dalam sebuah diskusi pada peluncuran buku ini—saya menjadi salah satu pembicaranya—Yusi mengatakan bahwa Sungu Lembu memang sengaja ia bentuk menjadi karakter yang politically incorrect untuk menggulirkan cerita. Ini memang sepenuhnya hak Yusi sebagai penulis, tapi sampai sekarang saya sebenarnya masih mempertanyakan mengapa Yusi merasa perlu narator yang politically incorrect untuk menggulirkan ceritanya.
Sudah banyak sastrawan dunia yang menulis ulang atau mencuri dongeng-dongeng yang sudah familiar di kalangan pembaca mereka untuk kemudian didaur ulang menjadi dongeng yang baru. Tapi mereka melakukannya dengan maksud yang jelas, misalnya untuk melawan nilai-nilai moral yang berlaku pada masa itu. Salah satu contoh yang lebih spesifik, misalnya, untuk melawan nilai-nilai patriarki yang menindas dan membatasi gerak-gerik perempuan, seperti yang dilakukan Angela Carter lewat kumpulan ceritanya yang berjudul The Bloody Chamber. Buku ini bahkan dianggap tidak hanya menulis ulang, tapi juga memanfaatkan motif-motif dongeng untuk lebih jauh mengeksplorasi bagaimana laki-laki dan, terutama, perempuan menemukan atau kehilangan diri mereka.
Dibandingkan dengan The Bloody Chamber, dongeng Yusi lebih mengeksplorasi kehidupan laki-laki yang heteronormatif, khususnya laki-laki ABG semi-seksis seperti Sungu Lembu, karena ialah narator di cerita ini. Hasilnya, saya sebagai pembaca, suka atau tidak, harus melihat dunia di dalam buku ini lewat mata Sungu Lembu. Konsekuensinya, karakter-karakter perempuan di buku ini, baik yang berperan kecil maupun besar, dilukiskan sebagai hidangan yang sama sensualnya seperti makanan-makanan yang disantap Sungu Lembu dan Raden Mandasia. Semua perempuan beragam rupa, bentuk, asal-usul, serta profesi tak lain dan tak bukan berfungsi untuk melayani selera kedua lelaki tersebut. Kadang mereka begitu anggun dan suci, tapi tetap saja jadi tontonan, bahkan suguhan, buat memuaskan mata laki-laki.
Saya berduka mengikuti perjalanan hidup perempuan-perempuan di dalam buku ini. Banyak perempuan yang berpengaruh di dalam kehidupan Sungu Lembu, tapi hanya sedikit yang bertahan cukup lama dan berumur panjang. Dan, dalam novel sepanjang 450 halaman ini, perempuan selalu menghabiskan hidup mereka di dalam ruangan—dari dapur, ruang tamu, rumah judi, sampai, tentu saja, kamar tidur.
Nyai Manggis adalah salah satu karakter perempuan "kuat" dalam kisah ini, tapi kekuatannya tetap saja digambarkan bersumber dari kecantikan paras dan tubuhnya. Boleh saja memang memandang kedua hal tersebut sebagai kekuatan perempuan, tapi apakah kekuatan perempuan hanya itu?
Nyai Manggis mendapat banyak sekali perlindungan dari laki-laki. Ia bisa mencapai posisi yang disegani sebagai pemilik rumah dadu dan pejuang bawah tanah melawan kekuasaan rezim Watugunung—karena laki-laki. Hal ini diakuinya sendiri ketika ia menyadari ternyata ia mencintai Bandempo karena laki-laki itu "menghormati dan memberinya kepercayaan" (halaman 154). Bukankah ini sesuatu yang kontradiktif, terutama ketika kita mengingat bangsa kita menolak bahwa kemerdekaan Indonesia "diberikan" kepada kita?
Tokoh perempuan yang sebenarnya menjadi favorit saya adalah Parwati, salah satu tokoh dengan hidup terpendek di buku ini. Ia penari ronggeng yang tidak termakan bujuk rayu Sungu Lembu sehingga Sungu Lembu menjadi terobsesi dan mengikuti rombongan tari Parwati sampai satu setengah bulan. Mereka akhirnya bercinta, tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan bayangan Sungu Lembu. Begitu tidak sesuainya, Sungu Lembu malah "hanya bertahan sebentar" (halaman 116) serta merasa telah "dimanfaatkan" dan "kotor" (halaman 117). Tak lama kemudian Parwati sakit parah dan…, ya benar, ia menemui ajalnya.
Perempuan dalam penglihatan Sungu Lembu—sebagai konsekuensi sudut pandangnya sebagai penggulir cerita yang politically incorrect dan naif, jadi sering digambarkan sebagai sekadar suguhan bagi laki-laki—ya seperti daging sapi. Sungguh malang dongeng perempuan dalam novel campursari Yusi Pareanom.
GRATIAGUSTI CHANANYA, PENYAIR
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo