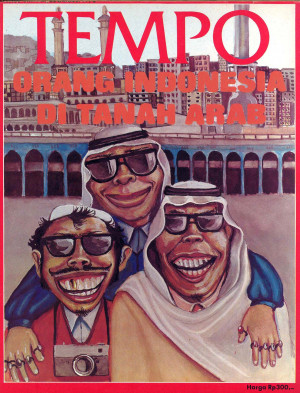SATRIA, seorang pengukir kayu dan bekas pelukis, bersikap bagai
Prabu Yudistira yang bijaksana dan besar jiwa. Martinah
isterinya, ia persilakan bercinta dengan Asmo, kawannya yang
penyair -- semata-mata karena yang terakhir ini membantu hampir
sepenuhnya ekonomi keluarga mereka yang berantakan. Sang isteri
meskipun tetap berusaha setia melaksanakan janji cinta, harus
berjujur hati pula terhadap proses hubungannya dengan Asmo --
apalagi suaminya menyiram api cinta.
Demikianlah bertempat di Art Gallery Senisono, Yogya, 4 dan 5
Oktober, drama Sebuah Jalan Ke Kutub dimulai oleh sikap dingin
Asmo. Di rumah yang setengah berantakan dan buram, ia mengukir
kayu, memainkan alat pahatan, tak-tok-tak-tok yang iramanya sama
sekali tidak menyembunyikan kenyataan bahwa sebenarnya ada sekam
yang membara di balik sikap dingin dan 'bijaksana'.
Seluruh lakon memang berusaha menekan sejauh mungkin emosi.
Genthong Hariono Seloali, pengarang dan sutradara, memaksudkan
ini untuk konsep teaternya. Tidak saja pada pola vokal, akting,
dialog, tapi juga pada inti peristiwa dramatiknya. Untung Basuki
sebagai Satria dan Fadjar Suharno sebagai Didi, teman Satria,
yang biasa main drama dengan vokal keras ala Bengkel Teater,
harus memberi takaran sedemikian rupa. Juga Nining Sulasdhi
(Martinah). Genthong sendiri, pemeran Asmo, di samping ngomong
dengan intonasi Eropa hingga terasa lucu, pun berdialog amat
dingin, gumam-gumam atau bisik.
Dari segi 'drama teriak', penampilan ini terasa seperti drama TV
atau sandiwara RRI. Genthong menyebut drama ini sebagai 'drama
kamar'. "Kalau orang sudah pinter, tak perlu ngomong emosionil,
apalagi teriak," ujar Genthong. Tokoh-tokoh dalam drama ini
tergolong "pinter", sehingga ada bagian panjang yang lebih tepat
disebut diskusi kebudayaan. Akibatnya intensitas yang sebenarnya
cukup terbangun sejak awal, jadi kendor.
Pola Sebuah Jalan Ke Kutub realistik sekali. Ini berbenturan
dengan sementara pandangan yang menganggap bahwa teater berbeda
dengan film karena film lebih realistis. Pementasan itu
mengungkapkan realitas kehidupan dengan bentuk, esensi, logika
dan konteks yang sama sekali realis. Tetapi kemudian terbelah
keutuhannya ketika nama-nama Jawa seperti Satria, Asmo dan
Tinah, harus mengucapkan kalimat-kalimat yang struktur dan
tata-idiomnya terlalu Jerman. Cara berpikir, pingpong, taktis
diplomatis obrolannya, sukar ditemukan dalam cara berpikir
umumnya orang kita. Sementara itu kejadian-kejadian yang
disuguhkan begitu dingin dan 'rasionil' -- membuat orang
bertanya apakah benar kita sudah demikian 'lapang dan dewasa'
dalam melayani benturan antara kebanaran dan kebenaran.
Pada akhir adegan ternyata sikap bijaksana Yudhistira pada Asmo
itu hanya bungkus dari kompleks psikologis yang sebenarnya ia
alami. Diam-diam Satria memukul tengkuk Asmo dengan besi.
Mengikat penyair itu di kursi dalam keadaan pingsan, kemudian
mengguyur seluruh rumah dengan minyak tanah meskipun akhirnya ia
kembali ragu untuk segera membakar rumah itu.
Didi, pelukis yang frustrasi karena masalah keluarga, sejak
semula amat membenci gejala percintaan isteri sahabatnya itu
dengan Asmo. Ia berniat membunuh penyair ini. Tetapi Asmo licin.
Ia berhasil mempermainkan kompleks psikologis Didi lewat
kata-kata sehingga pelukis itu akhirnya menancapkan pisau ke
dadanya sendiri.
Satria bernyanyi setengah linglung untuk jenazah sahabatnya,
sambil berjanji mengurusi keuarga Didi (keadaan yang selama ini
membuat pelukis ini frustrasi. Sementara itu Asmo dan Tinah
berangkulan. Di sinilah muncul pertanyaan tentang "realitas
manusia mana?". Asmo dan Tinah berhasil menggapai kebahagiaan
yang diusahakannya lewat proses yang lama. Mereka berdekapan di
atas mayat Didi serta penderitaan baru Satria -- meskipun yang
terakhir ini berucap: "Kawinlah kalian ! Aku restui . . . "
Sadisme berlangsung dengan tenang dan dingin. Bisakah ini
terjadi pada masyarakat kita? Apakah pelaku itu tidak lebih
tepat bernama Jerry, Bob, Dick dan Susan saja? Apalagi ada Asmo
yang katanya membantu biaya rumah tangga Satria hanya dengan
uang hasil penjualan puisi-puisi. Demikian suburkah Indonesia?
Genthong 8 tahun di Munchen, kawin dan beranak di sana. Orang
dari Akademi Der Bildenden Kunste Munchen ini tidak sepenuhnya
bertahan sebagai wong Jowo. Permainannya sendiri untuk ukuran
Yogya datar, kurang progresi, tak ada greget, seperti juga
keseluruhan lakon yang memang kurang dinamik.
Hanya untung yang kuat, Harno yang total, sementara Nining amat
rapi. Keempatnya dari teater yang berbeda: Bengkel Teater,
Teater Dinasti dan Teater Gadjah Mada. Tetapi mereka tampil
dalam nama baru, Teater Tikar, di bawah Sanggarbambu. Ini
merupakan salah satu contoh kerjasama antar teater di Yogya,
tapi dengan mutu yang kurang menguntungkan.
Emba Ainun Nadjib
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini