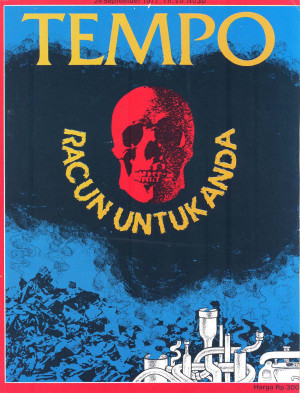INI bukan pertama kalinya, naskah Jayaprana karya Jef Last
--terjemahan H. Rosihan Anwar - dimainkan di TIM. Jakarta.
Pertama kali dahulu dilakukan oleh Teater Populer. Kini di
tangan Studiklub Teater Bandung dengan sutradara Suyatna Anirun.
Kedua-duanya mengambil tempat di Teater Arena. Kedua-duanya juga
mencoba memanfaatkan unsur-unsur Bali lewat kostum, tetabuhan -
meskipun hasilnya berbeda.
Dengan kunjungan penonton yang tipis, tontonan yang berlangsung
34 September itu ditandai oleh beberapa hal yang agaknya khas
STB. Ada terasa keinginan untuk mengontrol pertunjukan supaya
berlangsung dengan manis dan halus - sebagaimana dahulu mereka
pernah berhasil dengan naskah Moliere.
Pada dasarnya Jayaprana adalah lakon cinta yang didasarkan atas
sebuah cerita yang dianggap pernah benar-benar terjadi di
Buleleng, Bali. Sampai saat ini kuburan Jayaprana misalnya
masih dapat diketemukan. Dalam kehidupan teater tradisionil Bali
yang disebut arja - Jayaprana merupakan lakon dua cerita yang
semata-mata bersumber pada hawa nafsu. Tetapi Jef Last telah
membuatnya bergeser menjadi lakon perjuangan klas.
Aslinya, Jayaprana adalah seorang anak yang dipungut Raja di
sebuah desa yang ludas dilahap wabah. Setelah besar anak itu
diberi kesempatan memilih jodob. Tetapi gadis pilihannya,
Layonsari, ternyata begitu cantiknya sehingga menggugurkan iman
Raja. Dengan maksud ambil oper, Jayaprana dikirim ke Teluk
Terima untuk memadamkan kerusuhan di sana. Tapi kemudian ia
dibunuh oleh Sawunggaling. Tidak otomatis Layonsari pindah ke
tangan kaja, tentunya. Wanita itu justru bunuh diri setelah
mendengar kematian jagoannya. Maka Raja pun mengamuk edan karena
peristiwa ini. Kemudian ia sendiri terbunuh oleh rakyat.
Sebaliknya dalam lakon Jef Last, Jayaprana adalah seorang
panglima. Ia menolak anugerah raja, karena merasa kemenangan-
kemenangannya dalam pertempuran tak lain karena jasa tentaranya.
Ia pun berharap rakyat dibebaskan dari pajak yang berat. Muncul
pula tokoh "Paman Raja" yang iri pada kedudukan anak muda itu.
Dengan berbagai akal ia berusaha menjatuhkannya. Selanjutnya
cerita berjalan sama -- meskipun jelas arah pergolakan adalah
rongrongan terhadap status quo, perlawanan terhadap feodalisme
yang angkara.
Tersipu-sipu
Setting, yang memangku pementasan anak-anak Bandung ini, dibalut
oleh kain hitam. Dekat tembok belakang berderet seperangkat
gamelan. Kemudian ada 3 bidang level yang berusaha menolong
mengangkat para pemain - tetapi tidak berhasil menggarap ruang.
Hanya level mati, yang bahkan mengunci kemungkinan gerak pemain.
Kostum yang mengambil dasar warna coklat tampak dikerjakan
dengan bersungguh-sungguh. Juga ada perhatian yang teliti pada
peralatan pentas. Hanya malihat ketelitian tersebut tidak muncul
karena arus permainan yang tertahan-tahan.
Kedua badut (para pesuruh) yang hakekatnya menggenggam jiwa
lakon mengikuti struktur teater Bali berada di tangan pemain
yang lemah. Mereka yang seharusnya memberi komentar irama serta
memadatkan jarak antara banyolan dan fikiran-fikiran pengarang
serta fikiran-fikiran para tokoh, bermain tersipu-sipu. Dialog
dilontarkan sedemikian sederhananya, seningga jangankan
keintiman karena dapat mereka garap. Muncul pun tidak. Ini
menyebabkan adegan menjadi lamban: letupan-letupannya seperti
terbungkus oleh filter.
A. Sudrajat misalnya, yang memainkan Wijil sangat lemah
dialognya, sementara Bodin S (pesuruh Raja) pada dasamya
memiliki potensi yang baik, tapi tergencet oleh ketidakmampuan
Wijil. Eka Gandara WK (Raja), Tjetje Raksa Muhammad (Paman Raja)
serta Yessy Anwar (Jayaprana), juga tak berhasil menghidupkan
peran. Terutama karena garis penyutradaraan Suyatna Anirun tak
jelas.
Jayaprana Jef Last, kendatipun menjadi drama sosial,
sesungguhnya tak lepas dari jiwa teater Bali yang penuh
improvisasi di mana kelantangan ekspresi, merupakan mata lembing
yang utama. Dan bukan kemulusan dan kecantikan. Diskusi-diskusi,
yang melupakan kesibukan penting dalam lakon jadi lebih
merupakan perdebatan orang-orang di sekitar meja daripada sebuah
peristiwa yang berakar di bumi. Barangkali dengan visualisasi
yang lebih kaya, duka carita ini tidak akan menjadi seduka yang
kita saksikan di arena itu.
Putu Wijaya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini