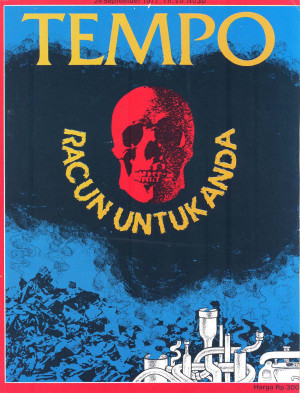INGATAN terhadap Topeng Cirebon belum juga memudar. Di Teater
Arena TIM, 7 dan 9 September 1977, ditampilkan pula wayang gedog
alias wayang topeng oleh grup Siswo Among Bekso dari Keraton
Yogyakarta. Ini adalah kelompok tari yang gigih untuk
mempertahankan tari klasik gaya Yogyakarta.
Agak berbeda dari biasanya, kali ini Siswo Among Bekso sekaligus
mengadakan pameran pakaian adat keraton (yang walaupun tak bisa
dibilang jelek, lebih baik rasanya jika diselenggarakan
terpisah).
Nomor tari malam pertama adalah Wayang Topeng, dengan mengambil
lakon Bancak Kromo, yang sebagaimana kebanyakan tontonan topeng
ditimba dari siklus Panji. Ceritanya begini:
Prabu Klana Sewandana dari Kerajaan Bantarangin, meminang Dewi
Tamioyi puteri Kediri - yang sebenarnya telah dipertunangkan
dengan Raden Panji Asmarabangun dari Jenggala. Bahkan sebentar
lagi pernikahan hendak dilaksanakan. Lalu, selagi di istana
orang sibuk mempersiapkan segalanya, calon pengantin puteri
menerima tamu gelap di keputerian - seorang perjaka yang halus
dan tampan: Jatipitutur namanya. Tamioyi berhasil dibujuk
tamunya dan jatuh cinta terperdaya. Dan setelah kedatangan tamu
yang tak diundang itu dilaporkan kepada raja oleh emban,
gegerlah seisi istana.
Anehnya, tak seorang berhasil menangkap pencari ini. Bahkan
Imaji, calon mempelai yang gagah perkasa itu pun, tak berdaya
melawannya. Doyok, abdi Panji, rupanya tahu gelagat. Cepat ia
merubah diri menjadi Pituturjati - yang seperti pinang dibelah
dua dengan Jatipitutur. Setelah peperangan yang seru, akhirnya
keduanyapun berubah menjadi wujud semula: Bancak dan Doyok,
keduanya abdi Panji. Wasana cerita. Dewa memutuskan bahwa Dewi
Tamioyi memang dijodohkan dengan Bancak. Dan kalau Dewa
menghendaki, siapa yang berani melawan, 'kan?
Sebagaimana lakon topeng yang lain, cerita diakhiri dengan
perang antara Prabu Klana Sewandana bersama bala tentaranya
melawan para pahlawan Jenggala dan Kadiri.
Di Luar Istana
Seperti halnya di Cirebon, tontonan topeng ini mulanya tontonan
rakyat-khusus ditarikan oleh dalang-dalang. Di daerah Yogya.
sejauh yang diingat orang, pada tahun 1850 telah terdapat
tontonan topeng. Penarinya para dalang wayang kulit. Romhongan
semacam ini ngamen keluar masuk desa untuk memeriahkan upacara
setempat. Tapi lama-kelamaan ada langganan tetap, hanya karena
tempat mainnya yang berpindah-pindah, tah banyak instrumen yang
bisa dibawa: saron, gender, gong dan kendang cukuplah.
Topeng biasanya dipentaskan hanya di siang hari. Dan sebagaimana
tontonan rakyat di Jawa lainnya, ia cenderung tidak ekonomis
dengan waktu. Kalau di Cirebon dibutuhkan sehari penuh untuk
satu lakon, di Yogya bisa sampai tiga hari. Di beberapa tempat
di Sala, orang benar-benar tak berani main topeng pada malam
hari, takut tertimpa petaka kata mereka. Dalam pesta yang meriah
biasanya siang hari orang menanggap topeng dan malam harinya
wayang kulit.
Tak jauh beda dengan rekannya di Cirebon, di Yogya pun seorang
dalang (penari) topeng memerankan beberapa peranan dengan
mengganti-ganti topeng yang dipakai. Tapi yang sangat unik
adalah dandanannya yang masih sangat sederhana. Sebagai hiasan
kepala hanya digunakan jamang, dari kartun atau kulit, dihiasi
daun-daunan. Yang masih segar (berwarna hijau) untuk tokoh-tokoh
dari Jenggala dan Kadiri, sedang untuk tokoh-tokoh dari seberang
(Sabrang) digunakan daun-daun yang telah berwrna kuning
kemerahan. Hanya khusus bagi Klana -- sang Raja - dipakai
songkok.
Tanpa Bibir Bawah
Sudah sejak zaman Kerajaan-Kerajaan Kadiri, Majapahit,
Kartasura, tontonan topeng ini diperhatikan, dilupakan, dan
diangkat lagi ke lingkungan istana. Sekalipun demikian tak
pernah ada bukti-bukti tertulis bahwa tontonan ini pernah
ditangani secara tuntas oleh ahli-ahli dari istana. Lagi pula
pembinaannya lebih bersifat tak langsung. Di Yogya pembinaan ini
pernah dilakukan oleh Krida Beksa Wirama sehabis Perang Dunia
II. Sayang sekali saat ini bekas-bekasnya tak menggores kentara.
Barangkali memang tidak terlalu mudah untuk meng"halus"kan
tontonan yang pada dasarnya dinamis dan penuh spontanitas ini.
Ada beberapa hal yang terasa mengganggu dalam pentas Siswo Among
Bekso. Pertama-tama masalah topeng itu sendiri, yang untuk
menggaulinya dibutuhkan waktu yang tak sedikit. Pada seorang Ibu
Suji (Cirebon) yang telah lebil dari setengah abad menjadi
dalang (TEMPO 6 Agustus), topeng dan penari telah benar-benar
menyatu.
Dan kesan seperti itu belum nampak pada pentas Yogya di Teater
Arena ini. Topeng yang seharusnya membantu sebaliknya justru
lebih banyak mengganggu ekspresi gerak para penari. Nampak
misalnya dalam adegan jaranan dan tarian kelompok lainnya:
terasa mempersulit penari untuk mencari posisi, bahkan ada
kalanya mengganggu stabilitas adeg dan angkatan kaki.
Boleh jadi topeng nemang tidak cocok dengan adegan 'kelompok
serempak' macam ini. Sebab, sebagai bandingan, adegan dengan
jumlah penari lebih sedikit (percintaan antara Jatipitutur dan
Tamioyi, serta adegan Lembuamiluhur Ragil Kuning dan
Kudoreradi) nampak bersih, rapi dan mengesankan.
Masalah kedua yang perlu diperhatikan adalah antawecana atau
dialog. Agaknya bukan tanpa alasan jika penari topeng di luar
Istana mengenakan topeng dengan menggigit sepotog kulit yang
ditempel pada bagian dalam bibir topeng. Karena jika penari
hendak melakukan dialog dengan mudah ia dapat mengangkat
topengnya dan dialog dapat jelas didengar. Itulah makanya banyak
juga topeng yang dibukanya separo muka, tanpa bibir bawah.
Hasil ada lagi cara untuk menjaga dialog ini. Seperti yang
lazim dilakukan di Bali: tugas ngomong-omong diserahkan kepada
orang lain, baik dalang ataupun bonderes. Sebaliknya di
lingkungan istana, saat ini, kebanyakan topeng dipakai dengan
mengikatkannya ke irah-irahan. Kelihatannya praktis memang, tapi
akibatnya dialog penari tak dapat terdengar jelas oleh penonton.
Baik disebut bonderes (Bali), bodor (Cirebon) atau punakawan
(Jawa), adegan dagelan mengambil peranan yang penting di dalam
topeng. Adegan ini sangat digemari khalayak, sehingga tontonan
bisa bertahan sehari penuh atau bahkan sampai tiga hari.
Barangkali karena kecenderungan tontonan ningrat yang harus
"apik" dan "halus", maka dianggap tidak pada tempatnya untuk
menonjolkan adegan ini - padahal sangat perlu untuk mengendorkan
ketegangan. Bayangkan saja kalau tontonan wayang kulit yang
semalam suntuk itu tidak dilengkapi goro-goro.
Kecenderungan lain, setelah "naik pangkat", topeng ini lebih
diabadikan untuk menjelaskan cerita. Jika di luar istana
adegan-adegan-adegan dapat dikembangkan dengan bebas dan
hidup di kisah adegan berhenti sebagai penopang cerita
semata-mata. Ini jelas bukan kesalahan Siswo Among Bekso sebab
dalam keadaan semacam itulah ia mewarisinya.
Secara keseluruhan wayang gedog ini kurang tuntas digeluti.
Barangkali karean latihan yang cuma sebulan itu. "Ada beberapa
hal yang menjadi penghambat," Dinusatomo BA - ketua rombongan
menjelaskan "Wayang Topeng baru untuk pertama kalinya coba
digarap oleh Siswo Among Bekso. Lagi pula tak cukup waktu."
Memang, usaha menghidupkan kembali wayang topeng ini patut
dihargai. Dengan penari-penari yang dipunyai, Siswo Among Bekso
akan mampu tampil lebih mengesankan. Tontonan topeng telah naik
pangkat, cuma lantaran wisudanya tidak dipersiapkan secara
matang, ia jadi kikuk sendiri. Kurang sreg.
Sal Murgiyanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini