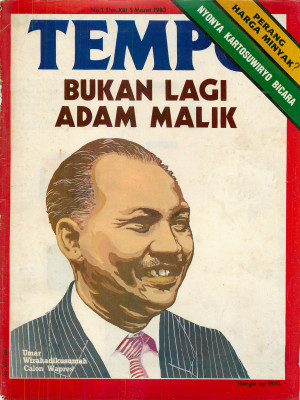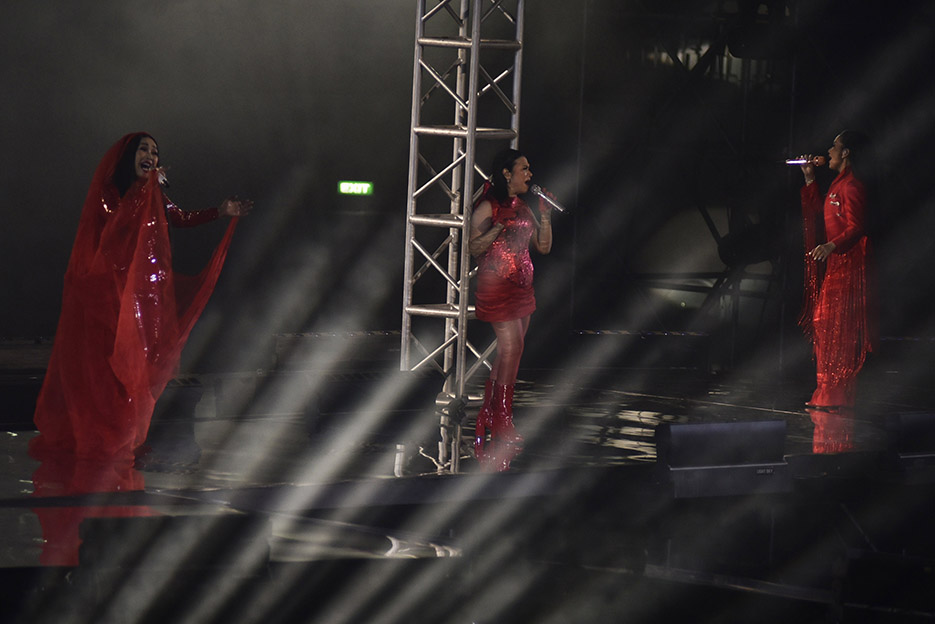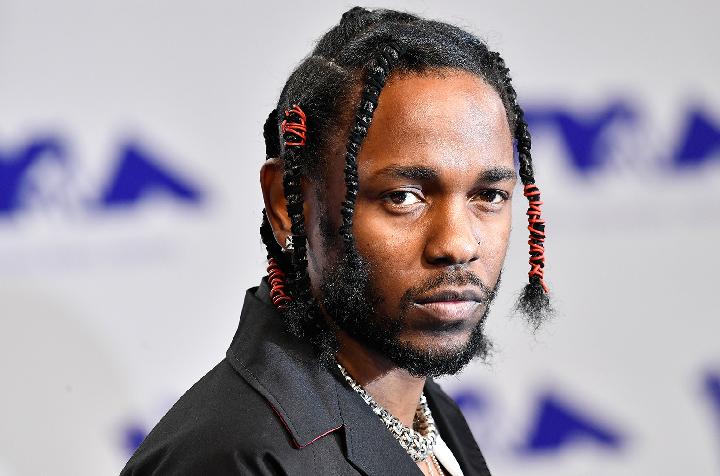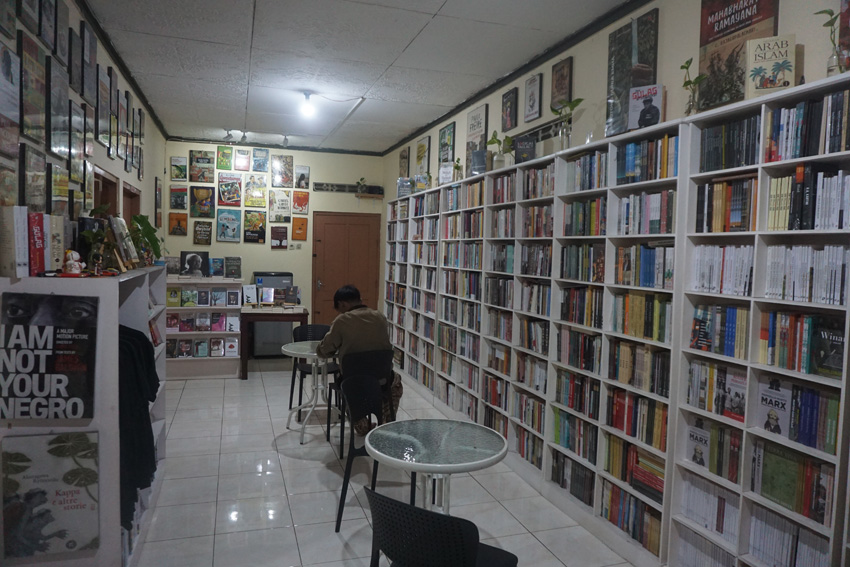BUNGA RAMPAI PEREKONOMIA DESA
Penyunting: Sajogyo
Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, IPB, 1982, 299 halaman.
Perekonomian desa di Indonesia masih punya tempat tersendiri
rupanya. Yayasan Obor Indonesia dan IPB menerbitkan 15 karangan
yang disunting oleh Sajogyo.
Mula-mula pembaca diperkenalkan dengan polemik tentang dualisme
ekonomi di Indonesia yang dimulai oleh tesis Dr. Boeke tiga
puluh tahun lalu. Empat karangan disajikan tentang hal ini. Dua
karangan membahas hasil "revolusi" hijau di Indonesia, dua
karangan lagi membahas masalah kredit di desa. Juga ada artikel
tentang gula dan tebu, tentang swasembada beras, dan BUUD.
Tulisan Boeke yang terkenal tentang dualisme ekonomi diambil
dari karangannya, Economic Policy of Dal Societies as
Exemplified By Indonesia, yang diterbitkan pada 1953. Tesis
Boeke adalah, di negara terbelakang terdapat dua sistem ekonomi
yang satu tradisional dan subsisten, yang lain kapitalistis dan
modern. Dua sistem ini beroperasi dengan cara sendiri-sendiri,
bergerak secara terpisah dan saling tak mempengaruhi.
Implikasi terpenting untuk kebijaksanaan dari analisa Boeke
adalah seperti yang dikatakan Vernon Ruttan: "tidak ada gunanya
memperkenalkan teknologi dan lembaga-lembaga Barat ke Indonesia,
dan tidak mungkin merumuskan kebijaksanaan ekonomi yang berlaku
untuk seluruh negara."
Sadli rnengakui kebenaran beberapa teori Boeke, sekalipun curiga
tentang adanya motif politik di belakangnya. Benjamin Higgins
sebenarnya dengan meyakinkan menentang teori Boeke. Dia
meraRukan ketepatan analisis empirik Boeke, dan menunjukkan
beberapa kasus bisa digunakannya analisis ekonomi neoklasik
Barat untu menganalisa ekonomi negara kurang maju. Sayang sekali
penyunting tidak memasukkan tulisan Higgins ini.
Mubyarto masih menunjukkan, karangan-karangannya yang terbaik
masih tetap tentang gula dan tebu rakyat. Salah satu makalahnya
yang dimuat penyunting menyimpulkan, sekalipun tebu memberi
penghasilan lebih banyak dibanding beras, biaya dan risiko yang
ditanggung petani juga lebih besar. Karenanya Mubyarto
menekankan perlunya kebijaksanaan yang memberi kepastian harga
gula.
Dua artikel membahas respons petani terhadap program modernisasi
di bidang pertanian. Soewardi melihat berhasilnya modernisasi
pertanian di Jawa Barat karena para petani sudah cukup punya
persiapan dalam tahun-tahun sebelumnya, dengan ikut sertanya
mereka dalam berbagai program intensifikasi.
Sedang Deuster melihat, bagaimana revolusi hijau berhasil di
Sumater Barat dan gagal di Sulawesi Selatan karena faktor
kultural: di Sumatera Barat petaninya lebih terdidik, lebih
banyak melakukan perjalanan, dan sikapnya lebih terbuka.
Sebaliknya petani di Sulawesi Selatan pendidikannya lebih
rendah, tak banyak keluar kampung, dan sikapnya lebih tertutup.
Dengan latar belakang ini, petani Sumatera Barat lebih efisien
menggunakan faktor produksi.
Dua artikel membahas struktur perkreditan di bidang pertanian.
Sudjanadi Ronodiwiryo, setelah melakukan penelitian di Karawang,
berkesimpulan bahwa kredi massal a la Inmas dan Bimas punya
banyak kelemahan. Karenanya harus di gunakan untuk keadaan
darurat saja seperti kebutuhan menaikkan produksi beras.
Ace Partadireja, berdasarkan penelitian tentang ijon di 16 desa
di Jawa, membuat uraian menarik tentang macam ijon, sifatnya,
dan keuntungan serta risikonya bagi si pelepas uang serta biaya
bagi si petani peminjam. Ace memperingatkan agar penghapusan
ijon dilakukan hati-hati karena tindakan drastis bisa
menimbulkan disrupsi oleh adanya hubungan sosiologis antara
petam dan pengiion. Ace mengusulkan pendekatan tak langsung -
kebijaksanaan yang meningkatkan penghasilan tani - dan menjaga
stabilitas harga pertanian. Bila ini berhasil, kebutuhan akan
ijon dengan sendirinya akan berkurang.
Soedarsono Hadisapoetro (sekarang Menteri Pertanian) bersama
Suprapto Gunawan dan Djuwari, dalam karangan yang diterbitkan
Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, mencoba memberi
penilaian awal tentang BUUD - yang pertama kali diperkenalkan
pada musim tanam 1969/1970. Atas dasar penelitian mereka
terhadap beberapa BUUD di sekitar Yogyakarta, mereka mencatat
beberapa kelemahan BUUD: kedudukan hukumnya yang kurang jelas,
karena sebenarnya cuma federasi Koperta, sedang transaksi yang
dilakukan meliputi jumlah besar. Kurang adanya hubungan langsung
dengan petani, karena petani hanya anggota Koperta.
Namun mereka mencatat beberapa sumbangan positifnya: menambah
penghasilan petani dan memperluas kesempatan kerja. Mereka
mengusulkan bimbingan pemerintah, tapi bukan intervensi.
D.H. Penny dan Masri Singarimbun mencoba mengemukakan model
hubungan antara kenaikan pendapatan dan konsumsi beras untuk
Indonesia berdasarkan data-data BPS 1967 dan 1969. Kesimpulan
yang diambil: pada satu tingkat pendapatan tertentu, kenaikan
konsumsi beras tak besar lagi. Menurut mereka, rumus swasembada
yang lebih memuaskan adalah bila elastisitas pendapatan terhadap
permintaan beras maksimum 0,01.
Penulis memperingatkan, usaha swasembada akan tertumbuk faktor
kultural: petani ini Jawa condong memproduksikan beras sebanyak
yang perlu untuk konsumsinya sendiri. Mereka tak berminat
memproduksikan lebih untuk konsumsi pasar. Bagi petani Jawa
yang sifatnya terlutup, pasar adalah dunia luar yang asing, yang
sejak zaman penjajahan membebani mereka dengan tanaman paksa,
pajak, inflasi, dan jatuh-bangunnya harga ber1s. "Pasar" telah
meninggalkan trauma yang, membekas. Mereka condong
menghindarinya.
Buku ini diterbitkan pada 1982. Tapi sayang karangan yang
dikumpulkan agak ketinggalan, karena data yang digunakan
penulis kebanyakan data sekitar awal 19-an Banyak perubahan
telah terjadi di sektor pertanian dan di desa sendiri, yang
memerlukan pengamatan lagi.
Winarno Zain
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini