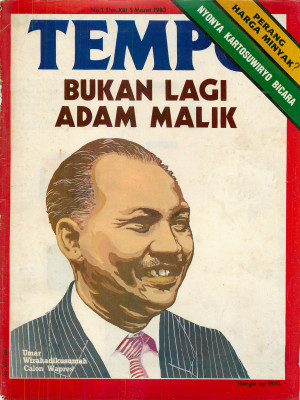PROFIL DUNIA FILM INDONESIA
Oleh: Salim Said
Penerbit: PT. Grafiti Pers
MASALAH mutu, karakter dan kecenderungan film Indonesia adalah
hal yang tak pernah selesai dibahas. Bagi orang perfilman,
segala masalah juga lingkaran setan - yang harus dihadapi dalam
pembuatan sebuah film, cukup difahami. Tetapi orang awam
terpelajar, misalnya, yang hanya mau tahu hasil akhir, tak
terlalu bermurah hati. Keputusan mereka: film Indonesia
brengsek, dengan hanya sedikit perkecualian.
Buku ini tidak ditulis sekedar untuk menjawab segala cemooh.
Buku yang asal mulanya skripsi sarjana ini berusaha menjawab
sejumlah pertanyaan dasar dari berbagai kalangan. Mengapa film
Indonesia tidak menampilkan manusia dan persoalan Indonesia?
Mengapa film Indonesia cuma tiruan film impor kelas dua atau
tiga Mengapa kemewahan, seks dan kekerasan terlalu
ditonjolkan? Mengikuti jejak perfilman Indonesia dari tahun
20-an, penulis mengungkapkan mengapa dan bagi nama perfilman
Indonesia sampai pada bentuknya yang sekarang. Orientasi dalam
gelas mendominasi sejarah perfilman Indonesia, karena memang
orang-orang Tionghoa yang memelopori bidang bergerak
semata-mata atas pertimbangan komersial.
Setelah Indonesia merdeka, Usmar Ismail bersama kawan-kawan
dalam Perfilman berusaha memulai suatu tradisi yang berorientasi
pada movement neo-Realisme Itali. Yaitu film sebagai ekspresi,
untuk menampilkan wajah Indonesia. Usaha ini gagal karena
harus berkompromi dengan kenyataan kekurangan modal, sikap
masyarakat yang belum siap menerima gambaran dirinya lewat layar
putih, dan sensur yang ketat.
Pola Tionghoa yang berakar pada genre Hollywood kembali unggul.
Bahkan percobaan di akhir tahun 60-an untuk menembus cara kerja
Tionghoa ini melalui Dewan Produksi Film Nasional (DPFN) hanya
berakhir dengan pembubaran lembaga tersebut oleh pemerintah -
dengan alasan pemborosan. Sampai saat ini peta bumi
permasalahannya pada dasarnya masih sama. Unsur-unsur komersial,
tujuan-tujuan artistik, kondisi masyarakat, peran pemermtah,
saling bertarung dengan kekuatan yang sama sekali tak
berimbang,dan tak menentu.
Memang sejarah perfilman Indonesia adalah kisah yang sarat
kompromi. Peniruan pada pola Hollywood yang berlandaskan pada
standarisasi - formula pictures--resep-resep yang teruji
popularitasnya, maupun star system, berasal dari sebuah industri
raksasa yang tak hendak mengambil risiko dalam bentuk apa pun.
Ia jelas jauh dari ideologi pendobrakan, sebaliknya malih
memperkuat pola dan norma yang sudah ada.
Implikasi dan efek orientasi dagang ini menyelusup ke mana-mana.
Penjiplakan terhadap film asing murahan - Amerika, Mandarin
ataupun India - menjadi kelaziman. Tema-tema musiman pun cukup
dikenal publik: tema remaja, horor, cinta, kekerasan, komedi
slap-stick dan lain-lain muncul dan berlalu bagai jamur. Apa
saja, asal memenuhi selera publik, laku dan untung. Akhirnya
film Indonesia jatuh menjadi sekadar hiburan, "dalam arti yang
tidak selalu sehat" (hlm.3), tak berkarakter - setidaknya bukan
karakter Indonesia - dan diperciki semangat "coba-coba", tapi
selalu dalam batas-batas pola yang dikenal.
Produsen film memang penjaja mimpi, tapi mimpinya juga "belum
sebuah impian Indonesia" (hlm.6). Ia "tidak memijakkan kakinya
di bumi Indonesia, sebab mimpi yang indah toh senatiasa berkisah
mengenai dunia yang tidak selalu kita kenal" (hlm.3). Produser
tampaknya memegang segala dan semuanya dalam film, mulai dari
modal dan cara penggunaannya, castng, sampai pada cerita yang
mereka karang sendiri - ramuan berbagai unsur pelaris.
Tokoh-tokoh pun dibuat sebagai "salinan dari bintang luar . . .
(yang) . . . menyebabkan film kita kehilangan watak" (hlm.5).
Di antara produsen sendiri, yang relatif sedikit jumlahnya,
terjadi semacam persekongkolan (Mafia?) yang sukar ditembus
pihak-pihak lain. Prinsip "uanglah yang bicara" nyata benar
dipraktekkan, apalagi karena sempitnya pasar di Indonesa (kurang
lebih 2.000 bioskop). Sedang pembuat film, termasuk
sutradaranya, merasa posisi dan peran produser itu wajar saja
karena mereka memulai karier dari bawah (88,75%), "karena butuh
kerja" (hlm.120), tidak seperti halnya dalam sastra, musik atau
seni rupa yang setidaknya membutuhkan bakat dan idealisme.
Proses sosialisasi itu, penyerapan nilai-nilai dan kebiasaan
yang telah melembaga, membuat mereka mampu mengidentifikasikan
diri hampir secara totar dengan keinginan, perhitungan maupun
kesulitan para produser.
"Ah, film ini betul-betul cuma tempat cari makan saja, bukan
untuk memDerjuangkan cita-cita" hlm.109) - kata-kata para
pembuat film. Mereka bukan selalu tidak sadar akan linkaran
setan yang tidak terlalu mudah diputuskan.
Kondisi perfilman Indonesia memang tidak bisa terlepas dari
kondisi sosial, politik dan ekonomi umumnya. Apakah karena itu
tidak pernah terdapat masa gemilan dalam perfilman Indonesia?
Yang jelas, tampaknya polarisasi antara idealisme dan
komersialisme yang disebut Salim Said dalam bukunya, sudah
begitu saling mendekat, sehingga ibarat lelucon untu bicara
tentang idealisme.
Buku ini ditulis hampir semata-mata secara deskriptif, tanpa
teori atau analisa yang terlalu mendaJam, meski tak bisa
dihindari di sana sini penulis mengambil perbandingan dengan
negara-negara lain --terutama Amerika, yang memang sumber
terbesar berbagai pola media, tidak hanya film. Mungkin percuma
jua berteori bila kondisi perfilman Indonesia yang masih sering
disebut industri rumah itu begitu sederhana dan gamblang. Sayang
penulis tidak memberikan perbandingan dengan negara-negara dari
Dunia Ketiga, seperti Filipina atau India misalnya.
Buku ini tidak dapat dikatakan memberikan sesuatu yang terlalu
baru. Juga tidak terlalu lengkap. Tidak berbicara mengenai peran
bookers misalnya. Atau mengenai pemasaran, pembinaan selera,
tingginya pajak tontonan, atau Polcy pemerintah yang senantiasa
berubah-ubah. Namun ia cukup berhasil menyusun gambaran profil
(belum wajah) menjemukan dan kusam perfilman Indonesia - secara
lugas, sederhana, singkat (seperti brosur), tidak teknis, tidak
teoritis, agak tawar mungkin, tapi dengan penjelasan tentang
mengapanya. Bar dapat disebut suatu pengantar. Tetapi karena
langkanya bukubuku demikian, kehadirannya welcome juga.
Julia I. Surgakusuma
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini