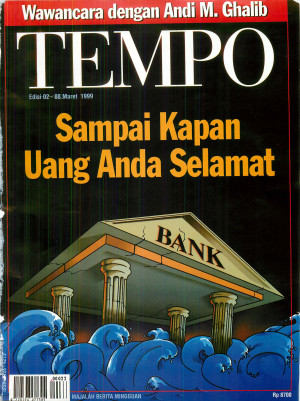Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
| Pameran Gambar | ||
| Karya | : | Agus Suwage |
| Tempat | : | Galeri Milenium, Jakarta |
| Waktu | : | 10 Februari - 7 Maret 1999 |
Khalayak seni rupa mengenal Agus Suwage sebagai perupa yang banyak menggunakan media gambar, baik sebagai bagian dari karya seni instalasi maupun gambar sebagai sebuah karya independen. Ia memiliki satu keunikan. Agus menggunakan bahan-bahan yang bagi kebanyakan perupa diperlakukan sebagai bahan untuk pengerjaan dasar karya seni rupa, misalnya pensil konte, pensil warna, charcoal (arang), gouache, kertas, cardboard, dan belakangan ia juga mengerjakan karya gambar di atas kain kanvas. Secara teknis pengerjaannya memang tak serumit teknik seni rupa lainnya, tapi Suwage justru memanfaatkan kesederhanaan teknik gambar untuk secara efektif menangkap gagasan dalam waktu yang relatif singkat.
Kesederhanaan teknik ini menjadi kontras dengan caranya memperlakukan gagasan itu ke dalam cara berpikir yang terasa sangat rumit. Kerumitan cara berpikir itu kadang menyiratkan sebuah citra gagasan absurd yang seolah lepas dari fakta sosial yang ada. Visualisasi hal-hal yang tak masuk akal dalam karya Suwage pada suatu masa hanya menjadi sebuah gaya bahasa yang hiperbol dari sejumlah benturan sosial yang terjadi. Dalam karyanya berjudul The Last Supper (1985), tampak figur setengah badan dalam posisi kepala di bagian bawah tergantung dengan pisau dan garpu yang menancap di badannya yang berlumuran darah. Adapun di bagian bawah, sejumlah figur dan wajah yang lebih mirip wajah hewan kelaparan berebutan memangsa tubuh yang mengerang kesakitan. Visualisasi ini adalah sebuah teks dalam konteks suatu masa ketika represi politik sedang berada pada tahap yang paling beringas. Suara-suara yang berbeda tiba-tiba hilang begitu saja di balik kekuasaan absolut aparatus. Kekejaman terhadap kemanusiaan terjadi di bilik-bilik embargo informasi yang berlangsung secara sistematis sehingga kehidupan seolah berjalan normal. Waktu itu kekejaman politik menjadi pikiran yang absurd bagi khalayak. Tapi, ketika kekuasaan lemah, rezim berganti, keberingasan politik menjadi masif dan terbuka. Kekuasaan institusional digantikan oleh kekuasaan massa. Saat itu absurditas Suwage justru menjadi realitas. Ketika banyak orang marah kepada sekelompok orang yang disebut "ninja" di Banyuwangi, menyeret sosok manusia tanpa kepala dengan sepeda motor; atau seorang pria berkulit gelap dihajar dengan bilah bambu oleh massa hingga mati dalam peristiwa Ketapang, Jakarta.
Meski cukup banyak perupa yang menjadikan fenomena sosial sebagai subject matter, Suwage memperlakukannya dengan cara yang sangat khas dan cenderung memotretnya dengan kacamata yang sangat pribadi. Boleh dikata Suwage jarang menggambarkan kerumunan figur yang jumlahnya lebih dari lima orang. Pada karya-karya di awal karirnya sebagai perupa (tahun 1980-an), ekspresi dan gagasannya sangat liar. Sebuah karya gambarnya tanpa judul berangka tahun 1985 menyajikan figur telanjang dengan tangan terikat di belakang. Tapi keliaran ekspresinya mulai berkurang tahun 1990-an. Pada pameran ini bisa dilihat pergeseran itu. Meski tetap merupakan gambaran pergumulan pribadi terhadap benturan-benturan sosial, eksplorasi rupa Suwage tampak semakin steril, goresan garisnya lebih terjaga, dan bahkan pada taraf tertentu mulai tampak kecenderungan melakukan stilasi. Karyanya berjudul Daughter of Democrazy I (1996) atau Tiga Badut (1996) kuat dalam simbol dan bentuk, tapi keliaran ekspresinya semakin teredusir. Namun, yang menarik hingga saat ini, Suwage tetap mampu mempertahankan karya gambar sebagai karya independen, meski sejumlah karyanya menempatkan gambar sebagai salah satu elemen karya seni rupa.
Memang tak banyak perupa yang menggunakan gambar sebagai karya independen. Tapi sejumlah perupa muda di Yogyakarta dengan latar belakang pendidikan seni grafis—sebagaimana juga Agus Suwage—mulai menggunakan tradisi menggambar sebagai media ekspresi. Ada pula yang membentuk kelompok Apotik Komik, yang menghasilkan karya komik alternatif. Umumnya mereka tak terlalu pusing dengan apresiasi khalayak seni rupa yang rendah terhadap media gambar dan tak pernah berpretensi menaikkan pamor media gambar. Bagi mereka, gambar atau media apa pun tak lebih dari sebuah alat yang bisa ditekuk semaunya untuk menyampaikan gagasan.
R. Fadjri
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo