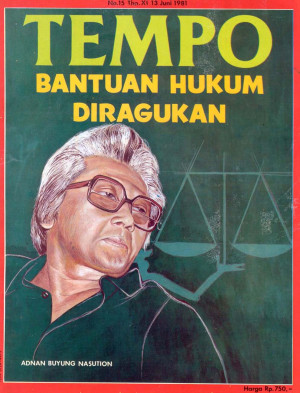SEPERTI sebuah usaha mengangkat barang punah. Goethe Institut,
di Jakarta, pusat kebudayaan Jerman, 6 Juni yang lalu
mempergelarkan jenis wayang yang sudah nyaris tak dikenal --
disebut 'wayang beber'. Bahkan menyertainya dengan pameran
selama 19 hari -- sejak tanggal 1. Pameran itu mengetengahkan
foto-foto perlengkapan wayang beber yang diambil oleh fotografer
Dieter Lotze, dan salinan lukisan berbagai adegan wayang
tersebut oleh pembuat wayang Djumadi.
Goethe Institut, yang menyelenggarakan acara itu dalam program
rutin pertukaran budaya, memang bukan yang pertama kali
mengetengahkannya di tahun-tahun terakhir. Wayang beber pernah
dipergelarkan di Taman Ismail Marzuki dalam acara Pekan Wayang
1969 - tanpa pameran. Juga tanpa pameran dipentaskan di Gedung
Kepatihan Yogya, Juli tahun lalu. Yang pertama diambil dari
Cilacap, yang kedua dari Gunung Kidul, Yogya.
Sedang yang dipertontonkan Goethe Institut berasal dari Karang
Talun, Pacitan, Jawa Timur. Dan memang, seperti ditulis oleh
Karl Mertes untuk folder yang dibagikan di institut Jerman itu,
wayang beber hanya tinggal dua tiga buah saja lagi di Jawa
Tengah dan Timur. Bahkan yang di Yogya itu sudah lebih tidak
operasional (lihat box).
Ini memang barang kuno -- meski tak diketahui jelas sebenarnya,
seberapa kunonya. Pak Sarnen Gunacarita misalnya, dalang Pacitan
itu, menuturkan perangkat wayang tersebut (terdiri dari 6
gulung, tiap gulung berisi 4 gambar secara berurutan seperti
komik, dan terbuat dari kulit yang halus) dahulu didapat dari
nenek moyangnya yang bernama Ki Naladerma. Sang datuk
menerimanya sebagai hadiah dari Brawijaya, Raja Majapahit --
setelah ia berhasil menyembuhkan putri sang raja. Tapi juga
terdapat beberapa petunjuk bahwa umurnya sebenarnya baru sekitar
250-300 tahun.
Hanya saja, dalam buku Wayang oleh Ir. Sri Mulyono misalnya, ada
disebut keterangan K.P.A. Kusumadilaga Sasramiruda -- bahwa
Prabu Bratana dari Majapahit membuat wayang beber di tahun 1361.
Jadi memang jenis kuno -- meski juga tidak berarti lebih kuno
dari wayang kulit, konon.
Dan yang muncul di Goethe Institut itu memang barang kuno --
lebih kuno daripada menyenangkan. Penonton yang separuhnya orang
Jerman itu, di ruang yang berkapasitas kurang dari 100 orang,
duduk bersila di hadapan sebuah kotak berukuran sekitar 30 x 125
cm. Ada seorang dalang, dua pembantu dan empat pemain instrumen
-- yang hanya terdiri dari rebab, kenong, ketuk, kempul, kendang
dan gong. Sangat bersahaja. Ditambah sesajen nasi lengkap dengan
ayamnya, pisang dan bunga -- serta asap kemenyan.
Cerita yang dibawakan adalah kisah Jaka Kembang Kuning alias
Panji Asmara Bangun -- dan memang wayang beber termasuk jenis
'wayang gedog' yang mengisahkan cerita Panji. Sang Panji, di
sini, bersama dengan Prabu Klana dari "kerajaan asing",
memperebutkan Dewi Sekartaji putri raja Kediri yang diberi nama
Brawijaya. Melewati lekuk liku, perang tanding maupun
penyamaran, sang panji sudah ditebak akan menang dan menang.
Namun pementasan tidaklah seru. Berbeda dengan wayang kulit yang
penuh sabet menyabet (cara menggerakkan boneka-boneka kulit yang
disebut sabetan itu memang lincah), di sini semua cerita
sekedar dituturkan. Gulungan digeser untuk menampakkan gambar
nomor dua, misalnya, atau diganti dengan gulungan baru, dan
tembang serta dialog diteruskan menurut gambar. Ini memang lebih
merupakan "seni lukis yang dibunyikan", dan hampir bukan teater.
Dan sebagai seni rupa, ia sejenis dengan relief-relief di candi
Hindu Jawa.
Dengan wajah dalang yang tersembunyi di balik gambar itu, suara
yang datar dan rata -- dan kebetulan pula tertelan-telan --
serama lebih tiga jam dari Pak Sarnen yang berumur 60 tahunan
itu memang hampir hanya memamerkan pusaka kuno.
Tak heran bila wayang beber jarang sekali dimainkan kini--bahkan
konon di awal abad ini orang mengira jenis itu sudah punah. Ia
hanya dipakai untuk keperluan semi-agama -- tolak bala atau
hajat tertentu yang lain, misalnya. Memang: tak ada karawitan
yang terbangun demikian sempurna (dan teks yang bisa terus
diperbarui) seperti pada wayang kulit, tak ada dramaturgi yang
masak seperti pada wayang orang atau wayang topeng.
Ditambah lagi dengan ulah pengkeramat-keramatan, yang membuat
"tidak sembarang orang bisa menggauli." Wayang Pak Sarnen itu,
misalnya, disimpan secara bergilir di 16 keluarga di Pacitan
--tiap keluaga kebagian 1 bulan. Yang boleh membuka kotak hanya
sang dalang. Untuk mengeluarkan gulungan saja diperlukan
pembakaran kemenyan. Untuk memainkan, sesajen harus lengkap.
Bahkan, gambar ke-24 tidak pernah boleh dibuka -- dan dimainkan.
Konon itu gambar adegan perkawinan sang Panji dan Sekartaji.
Pak Sarnen dewasa ini memang sedang menyiapkan dalang pengganti:
seorang putranya dan seorang kemanakan. Tapi itu agaknya karena
adanya perhatian yang bersifat kelembagaan -- dan bukan tuntutan
publik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini