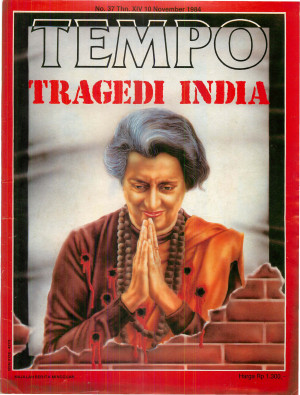DUA ABAD PENGUASAAN TANAH Penyunting: Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi Penerbit: Gramedia, Jakarta, 1984, 344 halaman KUMPULAN 10 karangan ini sungguh memukau. Kita dibawa dari situasi dan kondisi pedesaan di Jawa abad lalu sampai pada keadaan tahun 1980-an oleh sejumlah kecil pengamat jeli. Tapi di antara penyumbang pemikiran tak seorang pun ahli hukum. Jua tak ada suatu laporan resmi pemerintah, walau para penulis merujuk dan mengutip dari sumber itu. Sejak Orde Baru, barulah pada akhir Repelita II pemerintah mulai menanggapi suara resah dalam masalah ini. Dalam Kata Pengantar, penyunting mencatat Laporan Menteri Riset, atas permintaan Presiden pada 1978, mengenai masalah itu. Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk suatu badan nasional yang diketuai Menteri Penertiban (kini: Pendayagunaan) Aparatur Negara (PAN) -- yang beranggotakan 12 dirjen (antardepartemen) dan seorang wakil Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), sebagai "penjaga gawang". Pembentukan badan ini didukung Keppres 1980, sebagai pengingat bahwa atas dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 ketentuan pengaturan masalah tanah tetap dilanjutkan. Dapat dicatat di sini bahwa selama Repelita III tak pernah tersiar kegiatan atau keputusan dari badan nasional itu. Dalam praktek memang Departemen Dalam Negeri (yang berwewenang dalam hal agraria) yang mengatur permainan. Lagi-lagi pendekatan yuridis paling menonjol yaitu prioritas dalam usaha memperlancar pembagian sertifikat tanah kepada pemilik yang sah. Selama ini, unsur "pembagian tanah", yang sejak 1960 umumnya dapat dihindari oleh penguasa tanah yang "berlebihan", masih mendukung ide "landreform". Kata "landreform" memang tak pernah masuk idiom bahasa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kita -- baik pada Repelita III maupun yang kini berlaku. Dalam hal ini, rumusan GBHN 1983 menunjukkan suatu kemajuan: di bawah "pemerataan" (unsur pertama Trilogi Pembangunan) tercantum bahwa itu mencakup "pengaturan pemilikan, penguasaan minimal dan maksimal atas tanah, serta masalah yang menyangkut pembukaan tanah baru". Situasi keragaman nyata dalam pola penguasaan tanah desa di Jawa baik sekitar 110 tahun lalu (Kano, pada Bab 2, mengutip survei khusus pemerintah Hindia Belanda) maupun di awal abad ini. Itu dilengkapi data sejak 1950-an sampai kini -- penelitian Kano (Bab 8) dengan kasus satu desa, penelitian Billah dan kawan-kawan (Bab 9) di Jawa Tengah kasus 10 desa di Jawa (Bab 10 oleh Wiradi) yang diteliti berulang-ulang selama 10 tahun terakhir. Ternyata, sudah lama kesempitan tanah dan ketunakismaan mencirikan lapisan bawah di desa-desa di Pulau Jawa. Dapatkah hasil Sensus Pertanian 1983/84 Biro Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran sekaya penelitian di atas? Disadari bahwa survei meluas dalam Sensus itu tak dapat dikenakan tuntutan tersebut. Dengan definisi beragam hak penguasaan tanah, sampai di mana jangkauan hasil Sensus dapat memberikan "persambungan" berarti pada apa yang ditemukan peneliti dengan pendekatan detail? POLA penguasaan tanah menentukan peluang berusaha dan bekerja di desa. Onghokham (Bab I) menunjuk kepada nasib "penguasa", para "priayi" Jawa, yang oleh pemerintah Hindia Belanda telah dilepaskan dari ikatan tanah menjadi golongan bergaji tetap. Kini pegawai dan alat negara itu lebih dari 3 juta orang di antara 32 juta rumah tangga penduduk Indonesia. Sedangkan Aass (Bab 5) menunjuk pada proses terciptanya golongan buruh di desa: pertama, sebagai pendukung perkebunan besar (bentuk industri modern yang pertama kali dikenal orang desa) kedua, sebagai klien buruh tani pada petani lapisan atas di desa. Sampai di mana pola penguasaan tanah, di dalam perkembangan penduduk yang dahsyat di pedesaan Jawa, membawa rakyat ke polarisasi yang gawat? Lyon (Bab 5) menunjuk pada situasi konflik awal 1960-an (zaman parpol bersaing menjadi pembela) dan peletusan kekerasan di Jawa Tengah dan Jawa Timur (1965-66) sebagai aksi pembalasan terhadap eksponen "aksi sepihak", yang menilai pelaksanaan Landreform 1960 lamban. Apakah langkanya berita mengenai soal tanah di desa sejak Repelita III berarti "tak seberapa lagi ada masalah"? Konon, dari surat-surat yang masuk ke alamat pimpinan HKTI, masalah tanah masih merupakan topik utama. Setiap peneliti dapat belajar banyak dari kumpulan karangan dalam buku ini, baik karena banyak menyajikan angka (ada 70 tabel) maupun rujukan kepustakaan (tujuh halaman daftar pustaka pada tiga karangan, dan lebih dari 300 catatan kaki pada lima karangan lain). Moga-moga buku ini disusul buku kedua dengan tema mengenai pola penguasaan tanah di pulau-pulau lain. Misalnya, apa dampak hak baru HPH yang diberikan pada perusahaan besar (di samping HGU)? Apa pengaruh pembukaan tanah baru, baik oleh penduduk lama maupun pendatang seperti transmigran? Sayogyo *) Kepala Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB, Bogor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini