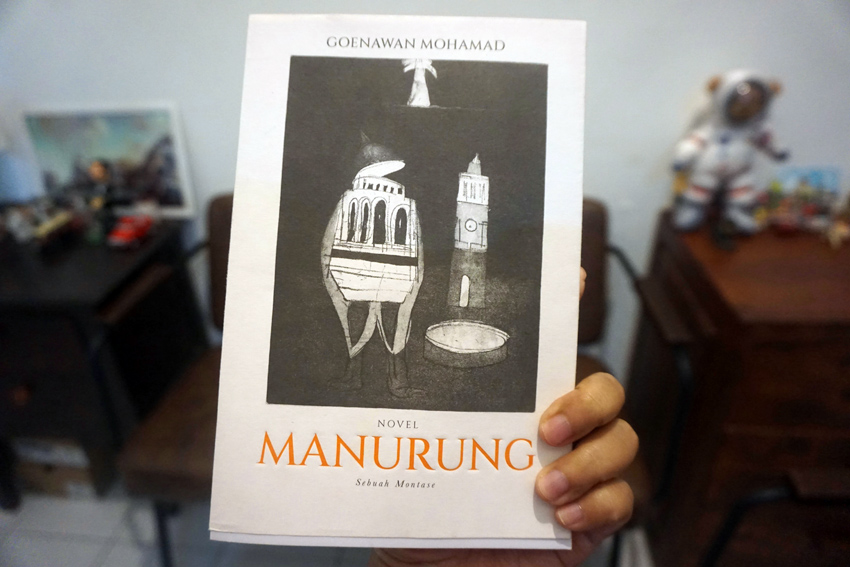Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N sejak 14 Februari hingga 8 September 2024.
Etnomusikolog Aris Setiawan mengkritik nilai kompetisi atau menang-kalah di FLS2N 2024.
Hakikat seni sejatinya mempertemukan orang dari latar belakang berbeda untuk menjalin nilai kebersamaan, bukan persaingan.
Fenomena Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) di Indonesia yang saat ini berlangsung cukup menarik untuk disimak. Semua sekolah di Indonesia dari pelbagai tingkatan turut serta dalam festival itu. FLS2N adalah lomba dalam banyak bidang seni, seperti musik, teater (pantomim), puisi, menggambar, melukis, dan kriya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo