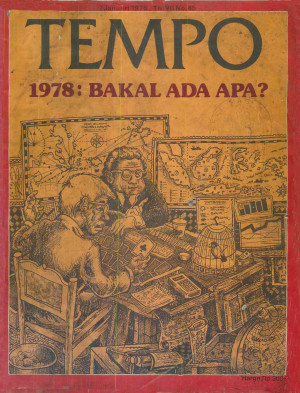MACBETH, naskah: William Shakespeare saduran: Rendra
sutradara: Amak Baljun & Arifin C. Noer
produksi: Teater Kecil
MACBETH yang disadur Rendra adalah Macbeth seorang sutradara.
Seorang penterjemah seperti almarhum Trisno Sumardjo, akan
memperhatikan kata-kata Shakespeare dengan perincian arti.
Seorang sutradara agaknya lebih mengacuhkan efek kata-kata itu
dalam ruang, dalam hubungannya dengan daya tangkap penonton.
Maka Rendra pun menterjemahkan "a tale... full of sound and
fun" dengan "hidup adalah cerita penuh kasak-kusuk ...."
Desis dan getar kata-kata Inggeris dengan kekayaan
monosilabelnya serta variasi tekanannya - bisa bergerak tangkas,
bijak dan merdu. Warna semacam itu agaknya teramat sukar untuk
diwujudkan kembali dalam bahasa Indonesia, walaupun makna
kata-katanya dapat diterjemahkan. Maka Rendra nampaknya memilih
jalan pintas. Ia mencoba memperoleh efek laim Yakni, efek
semacam kejutan, bukan kemerduan. Dari sini diperhitungkan akan
ditarik perhatian penonton (dalam pementasan Rendra, biasanya
penonton itu hadir penuh sesak di ruang luas) agar kemudian
mereka terperangkap dalam isi fikiran kalimat-kalimat itu.
Risikonya: bisa terjadi sebuah Macbeth yang penuh hentakan
hampir tanpa suasana tragis. Pementasan Teater Kecil di Teater
Arena Taman Ismail Marzuki (28 Desember s/d 1 Januari)
setidaknya bisa memberi kesan, bahwa risiko itu memang nyaris
tak terelakkan Macbeth, seperti karya Shakespeare lain, terutama
Richard III, pada dasarnya adalah sebuah cerita tentang nafsu
kekuasaan. Perwujudannya adalah teror. Teror itu berlepotan
darah keruh, tapi juga berbuduk oleh rasa dosa yang suram. Namun
pementasan Teater Keeil kali ini (saya menonton pada malam ke-2)
terasa lowong dari apa yang pokok: suasana teror yang dilakukan
Macbeth untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, dan suasana
tersiksa dosa, yang pada saat yang sama menyebabkan Macbeth
nampak kesepian dan terkutuk.
Teror
Mungkin karena lakon ini mencoba menghindar dan tempo yang
lambam Adegan demi adegan berganti cepat, sering terlampau
mendadak. Satu bagian yang sebelum sepenuhnya larut sertamerta
disergap adegan berikutnya. Rem bahkan dipasang pakem di paduan
suara dan bloking pasukan. Mungkin karena batas batas itulah
ruang tampak terlampau sempit.
Maka kita tak sempat melihat bagaimana kian dalam dan kian
busuknya luka Macbeth, setelah hatinya berlobang kena pancing
ambisi dan pengharapan besar. Kita bankan tak sempat melihat
nafsu kekuasaan itu sebagai luka yang tertoreh, dalam jiwa
Macbeth, melainkan hanya melihatnya sebagai suatu keiibukan
politik. Maka teror yang dilakukan Macbeth malam itu cuma
mendatar. Teror itu tidak bertahap ke arah yang kian tidak masuk
akal. Pembersihan terhadap Nyonya Macduff dan anak-anaknya
tampak seperti hal rutin, bukan sebagai suatu eskalasi kekejaman
kekuasaan yang makin korup dan makin menderita sakit
sebab-curiga.
Akhir dari Macbeth juga seolah mendadak. Ketika ia roboh, ia
hanya roboh seperti seorang raja jahat yang secara rutin harus
mati di adegan terakhir cerita anak. Ia roboh tanpa putus-asa
dan kekecewaan yang tandas, begitu ia menyadari bahwa ia
ternyata selama itu telah terbujuk oleh sang nasib ke dalam
jebakan yang kejam. Riwayatnya berakhir seperti Cakil dalam
adegan "perang kembang" wayang kulit - tanda kebenaran gugurnya
seorang Rahwana di ujung pertempuran habis-habisan.
Charlie Sahetapy memang pilihan terbaik di antara para pemain
Teater Kecil untuk Macbeth: sosoknya kena, ekspresi wajahnya
bisa kuat, tapi memang sulit memainkan Macbeth sebagai tokoh
tragis dengan bahasa yang berteriak dan dalam tempo yang seperti
terburu. Atau barangkali sutradara menyadari, bahwa tempo itu
perlu dipercepat karena takut lakon akan membosankan - melihat
bahwa warna suara dan cara berbicara para pemain tidak bisa
diarahkan untuk bervariasi.
Ada sesuatu yang tak lazim pada grup Teater Kecil tapi terjadi
malam itu, mungkin karena kurang intensifnya latihan: banyak
suara ditarik ke dekattenggorokan (seperti pemain sandiwara TVRI
yang mau "dramatis") dan tekanan tergelincir di suku kata yang
salah. Suara-suara ramai pun melolong agak sewarna dan senada.
Agak sewarna dan senada juga adalah kombinasi Ny. Macbeth
(Yayang Pamontjak) dengan Macbeth. Yayang mungkin pemain
berbakat, tapi mungkin saya terlalu terpesona kepada seorang Ny.
Macbeth lain: wanita Jepang dalam film Kurosawa yang termashur
itu, Tahta Darah. Ia begitu putih, bagaikan sutera halus, begitu
menerawang, seakan-akan tidak riil, seakan-akan penampilan roh
jahat yang menjerumuskan Macbeth atau unsur pembujuk yang licik
dalam jiwa Macbeth sendiri. Wanita Jepang itu nampak sebagai
kontras bagi kejantanan Macbeth yang wungkul, yang mentah, yang
liat, lurus dan jujur - tapi juga sebagai pelengkap sang suami.
Yayang tidak jadi kontras bagi Charlie. Karena itu juga ia tak
jadi pelengkap, melainkan penambah-nambah. Keduanya seperti
bersaing dalam bicara. Keduanya akhirnya memang bisa
mencapekkan. Untung Teater Kecil selalu kaya akan variasi:
adegan peri oleh Ungke Tompoh - yang berjenggot, gendut tapi
berkutang dan menggeliat-geliat seperti wanita dan tiap kali
bersuara "hehe" - tetap jitu. Lebih baik lagi adalah adegan Juru
Kunci (Donnan Borisman) serta adegan Macbeth dengan para
pembunuh bayarannya (Dorman Borisman dan Zubaedi).
Tapi sebuah pertunjukan yang hanya dapat dikenang karena
selingannya paling-paling adalah sebuah tontonan yang pas-pasan
saja, bukan?
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini