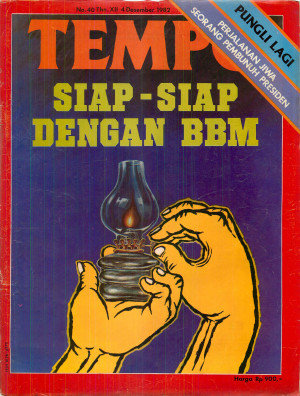MACAPAT terdengar lagi, pelan menelusup di antara kesibukan
kota. Di Jakarta, akhir November, PN ala Pustaka mengadakan
malam macapat membawakan Serat Centhini. Dan di Yogyakarta, di
gedung Javanologi, di Museum Sono Budoyo dan di gedung Kepatihan
sampai sekarang tiap minggu ada malam macapat.
Bahkan di kota andong itu kini muncul kelompok-kelompok kecil di
kampung-kampung yang mempelajari macapat. Menurut Sudibjo
Hadisutjipto, ahli kesusastraan Jawa dari Fak. Sastra UI dan
anggota redaksi PN Balai Pustaka, di Surabaya kini pun macapat
mulai terdengar lagi.
Kesenian macapat dulu, memang, di daerah Yogya dan Solo, hidup
di kraton maupun kampung-kampung. Waktu itu macapat bukan saja
pengisi acara dalam selamatan kelahiran bayi misalnya. Tapi juga
berperan sebagai cara menularkan ajaran hidup bagi anak-cucu.
Tembang-tembang yang dibawakan biasanya berisi sejarah,
adat-istiadat, pelajaran moral.
Sesungguhnya sudah sejak lama di Yogyakarta ada usaha gigih
melestarikan macapat. Di.sebuah ruang berukuran 4 x 3 « m, di
sudut barat kraton Yogyakarta, dengan hanya diterangi lampu neon
20 wat, macapat diajarkan ,kepada yang berminat. Resminya
kegiatan ini disebut Sekolah Macapat. Di sini macapat diajarkan
dengan sungguhsungguh, dengan guru yang menguasai metode
mengajar.
Sekolah ini didirikan pada 1950 atas inisiatif KRT. H.
Madukusumo almarhum. Tapi pada 1960, karena kesibukan bangsawan
itu ditambah keadaan politik yang ternyata mempengaruhi sektor
kebudayaan juga waktu itu, terpaksa sekolah ini ditutup. Baru
pada 1977 dibuka kembali oleh R. Rio Prodjowijardjo, yang tamat
dari sekolah ini pada 1955. Hingga sekarang sekolah ini dikelola
oleh Kawedanan Hageng Punokawan Kridomardowo, sebuah badan di
dalam lingkup organisasi kraton Yogyakarta.
Pak Prodjo, demikian panggilan sehari-harinya, dibantu dua guru
lagi ialah Brotoasmoro dan Prawoto. Tiga guru ini agaknya
memadai, karena sekolah ini pun hanya mempunyai tiga kelas: I,
II dan III. Tiap kelas hanya masuk seminggu sekali di hari yang
berlainan (Selasa Kamis dan Minggu), Jumlah murid seluruhnya 56
orang, rata-rata berusia di atas 30 tahun. Syarat menjadi siswa
di sini bisa membaca Latin.
Meskipun sekolah scni suara, tes suara itu sendiri juga tak ada.
Biaya sekolah sangat mu rah: Rp 100 per bulan. Tiga guru itu pun
hanya meridapat honorarium Rp 100 tiap kali datang mengajar
untuk sekitar dua jam -- pelajaran dimulai pukul 16.00.
Kebanyakan siswa adalah pensiunan pegawai negeri, guru sekolah,
anggota ABRI dan pegawai kraton Yogya.
Tentang metode mengajarnya, memang masih tradisional. Hanya
menirukan guru menembang, lain. tidak. Seperti bisa dilihat
pekan lalu, sewaktu 18 siswa kelas I sedang belajar. Mereka
duduk di kursi reot yang ditata berhimpitan, hingga pundak
mereka bersentuhan. Mereka memang tidak perlu menulis. Tugas
para murid Itu hanya menatap ke depan, menirukan guru
menembang. Mula-mula Pak Prodjo, 65 tahun, menembangkan Sekar
Pangkur. Maka ruang pengap itu seperti berubah, digetarkan suara
seorang tua. Seperti terlupakan bau apak di situ, yang ada hanya
suara nyaring halus yang melagukan Duda Kasmaran (Duda Jatuh
Cinta). Selesai Pak Prodjo, murid-murid menirukan bersama-sama.
Sesudah itu satu per satu menembangkan lagi lagu tadi.
Demikianlah pelajaran berjalan dari minggu ke minggu.
Pak Prodjo dengan waspada menyimak tiap suara siswanya. Bila
suara itu kurang tepat atau sumbang ia membetulkan. Caranya,
dengan membunyikan saron, untuk memberi contoh nada suara yang
betul. Di sekolah ini saron berfungsi sebagai garpu tala. Dan
harap diketahui, bahasa pengantar di sekolah ini bahasa Jawa
halus (krama inggil).
ADAPUN "kurikulum" sekolah itu pun sangat sederhana. Kelas I
mempelajari sekar elit. Ialah, jenis tembang yang sampai
sekararg masih banyak dikenal--semuanya ada 11 jenis. Misalnya,
dandang gula, sinom, angkur, durma, pucung, asmardana. Kelas II
mempelajari sekar tengahan, yang sudah agak jarang didengar.
Menurut Sudibjo Hadisutjipto, jenis tembang sekar tengahan
kira-kira ada delapan, antara lain lonthang, kenyakedhiri,
branuasmara, sumekar. Di kelas III yang dipelajari ialah sekar
ageng. Jenis tembang ini yang semuanya ada 146 jenis boleh
dikata di msyarakat umum sudah tak terdengar lagi. Jarang
sekali yang masih bisa menembangkan antara lain manggalagita,
banjaransari, gurisa, wahingrat -jenis sekar ageng itu.
Bila Pak Prodjo menganggap ada siswa yang sudah menguasai
pelajaran, ujian diadakan. Para pengujinya terdiri dari para
ahli macapat yang kini masih ada di Yogyakarta. Untuk lima tahun
terakhir ini baru ada dua kali ujian kenaikan kelas.
Lalu, apakah yang dicari para siswa itu? "Saya ingin dengan
betul menembangkan macapat," tutur Pak Guno, 55 tahun, pelawak
Yogya yang pernah menjadi gurunya Bagio S, yang kini duduk di
kelas III. Lain lagi Srie Rejeki yang juga sudah duduk di kelas
III yang sehari-hari dipanggil Cik Eng itu. Bagmya bukan lagunya
yang penting, tapi isi tembang yang dibawakan. "Saya merasa
banyak menimba ilmu dari tembang-tembang macapat," kata cewek
Sipit ini.
Diktat tembang-tembang memang dikutip dari karya-karya pujangga
Jawa ternama. Misalnya Serat Wedhatarna Wulangreh, dan
tembang-tembang lama yang dihimpun oleh Ki Hadjar Dewantara
dalam buku Sari Swara terbit 1936.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini