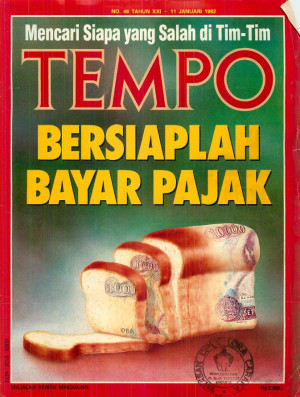MENURUT penulisnya, ini adalah buku tentang Indonesia yang diperbandingkan dengan Korea Selatan. Mengapa? Menurut Arief, pada tahun 1945, dua negara itu mempunyai banyak persamaan. Samasama baru merdeka, miskin, ekonomi pertanian yang dominan, dan lain-lain. Kini, Kor-Sel sudah menuju barisan negeri industri kapitalistis maju. Sementara Indonesia, menurut Arief, masih terseok-seok. Mengapa bisa begitu? Pertanyaan inti inilah yang hendak dijawab Arief. Meskipun cenderung menekankan persamaan itu, ia pun pasti sadar bahwa sesungguhnya terdapat banyak perbedaan. Misalnya, secara geografis, geopolitis, dan sejarah penjajahannya. Jepang baru mulai menjajah negara itu tahun 1910 dan mengakhirinya pada 1945. Perbedaan penting lagi, Jepang memperlakukan Korea, yang secara geografis sangat dekat, sebagai "perluasan" industri, yang pada saat itu sedang berkembang pesat di Jepang sendiri. Akibatnya, kolonialisme Jepang menyebabkan transformasi struktur sosial Korea secara radikal. Kelas tuan tanah hancur lebur dan muncul benih dari sebuah kelas pekerja industri, yang akan menjadi tulang punggung industrialisasi di Kor-Sel setelah merdeka. Arief tampaknya tak begitu memperhitungkan pentingnya perbedaan sejarah kolonialisme di kedua negara yang menentukan perkembangan selanjutnya. Landreform yang dilakukan Kor-Sel setelah PD II, sebagai reaksi atas landreform di KorUt, telah mempercepat peralihan modal dan tenaga kerja ke sektor industri. Awal industrialisasi di Korea sebetulnya dimulai pada zaman kolonial. Berbeda dengan Indonesia, penjajah tak peduli untuk mengembangkan industri. Perbedaan lain, yang sebenarnya juga dicatat Arief, adalah masa 10-15 tahun setelah "merdeka". Kor-Sel dijadikan benteng antikomunisme oleh AS, apalagi setelah perang di Semenanjung Korea awal 1950-an ("perang saudara" yang sukar dibandingkan dengan kasus PRRI-Permesta yang dianggap Arief sebagai padanannya di Indonesia). Dana dari AS pada tahun 1950-an telah memungkinkan Pemerintahan Syngman Rhee memupuk kelompok-kelompok bisnis yang nanti akan sangat berperan dalam industrialisasi, yang dikembangkan pada masa diktator berikutnya, Park Chunghee. Indonesia, lain sama sekali. Tak ada dana yang demikian signifikan di tangan negara untuk menumbuhkan sebuah kelas kapitalistis. Mengingat perbedaan-perbedaan tersebut, apakah ada gunanya membandingkan Indonesia dan Kor-Sel? Tentu saja ada. Studi semacam ini membantu menghilangkan kesan bahwa Indonesia serba unik, serba tak bisa dibandingkan. Lagi pula, mengingat banyaknya orang yang kini menunjuk Kor-Sel sebagai model yang patut diteladan Indonesia. Buku ini mempunyai relevansi langsung dengan perdebatan kontemporer tentang pembangunan. Arief pasti bukan termasuk orang yang dengan mudah mengatakan bahwa model Korea dapat diadopsi begitu saja. Namun, dalam melakukan perbandingannya, Arief mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan itu. Misalnya, faktor perbedaan lingkungan internasional yang dihadapi Kor-Sel waktu memulai industrialisasi berorientasi ekspor pada awal tahun 1960-an dan Indonesia yang baru memulainya pada pertengahan 1980-an, hampir tak digubris. Jadi, terlepas dari banyaknya catatan kesejarahan umum yang terdapat dalam studi Arief ini dan dari pendekatannya yang secara umum dapat disebut "struktural", makna sesungguhnya dari sejarah perkembangan kelas sosial serta pergeseran dalam pembagian kerja internasional hanya secara superfisial membentuk penjelasan yang ditawarkannya. Tampaknya Arief lebih ingin menyumbangkan konsep "negara otoriter birokratis rente" yang pernah dipakai oleh Olle Tornquist dan Richard Tanter untuk menganalisis Indonesia. Konsep negara ini tak efisien dan telah gagal menciptakan sebuah burjuasi yang mandiri. Ini adalah kebalikan dari "negara otoriter birokratis pembangunan" yang berkembang di Korea. Sebagai kategori deskriptif -- yang menjelaskan ciri-ciri dan cara kerja rezim-rezim yang berbeda -- mungkin penggunaan konsep-konsep ini ada gunanya. Tapi, sebagai bagian dari perdebatan teoritis mendasar tentang sifat negara seperti hubungan negara dan kelaskelas sosial, otonomi relatif negara, dan batasan struktural otonomi relatif di negeri-negeri dunia ketiga, konsep-konsep ini sebenarnya tak banyak menyumbang. Dan Arief tampaknya menganggap bahwa konsep-konsep itu termasuk dalam perspektif bahwa negara adalah "superotonom" terhadap masyarakat. Arief juga tampak mengulangi "idealisasi" yang dilakukan banyak orang terhadap sebuah burjuasi. Kesan yang diperoleh, Kor-Sel sedang menuju sistem yang lebih demokratis hanya karena burjuasinya kini menuntutnya. Aneh sekali bahwa Arief sama sekali mengabaikan peranan gerakan buruh yang beraliansi dengan mahasiswa -- yang begitu aktif dan militan -- dalam perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Dalam sebuah negeri yang kapitalismenya berkembang maju, akan tumbuh sebuah kelas pekerja industri di sisi lain. Vedi R. Hadiz *) Penulis adalah Ketua Pelaksana Harian Yayasan SPES, Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini