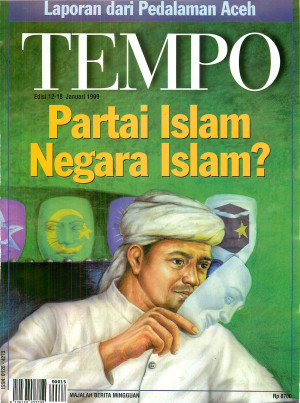Sore itu, kawasan Lentengagung, Jakarta Selatan, basah setelah guyuran hujan deras. Sisa-sisa genangan air di sana-sini tak menghalangi pengunjung berbondong-bondong menuju tanah lapang di sebelah stasiun kereta. Di sanalah komedi keliling kelompok Kelana Karya, yang berasal dari Demak, Jawa Tengah, mempertunjukkan sebuah karya.
Di satu sudut, ada tenda besar tempat pemain Roda-Roda Setan beraksi, yang menampilkan atraksi motor melompati api, menyetir dengan satu tangan, dan melompat dari atas dengan mata tertutup kain hitam. Di luar, atraksi lain yang tak kalah memikat seperti Kincir Angin, Helikopter Terbang, Komedi Putar Asyik, Kereta Tamasya, dan Rumah Setan Usil telah menanti. Masing-masing bisa dinikmati hanya dengan tarif Rp 1.000.
Bagi masyarakat, hiburan murah seperti komedi keliling seperti penyejuk di masa krisis. Mereka bisa menikmati berbagai atraksi tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. "Anak-anak sudah lama ingin naik kincir angin seperti di Dunia Fantasi. Tapi harga karcis di sana mahal banget. Mending buat beli beras," ujar Sarifah, salah seorang pengunjung. Nah, di tempat ini, Sarifah, yang saat itu datang bersama kedua anaknya, mengaku cukup mengeluarkan uang Rp 15 ribu. Hasilnya? Tak mengecewakan. Dua gadis kecil Sarifah, berusia tujuh dan delapan tahun, asyik menikmati permainan komedi putar.
Yang mungkin tak terpikirkan oleh pengunjung, nasib para pekerja komedi keliling tidak ceria. Sekalipun pengunjung melimpah, pendapatan mereka sehari tak lantas melonjak. Maklum, biaya operasional sehari-hari cukup mencekik. Untuk beberapa atraksi, penggunaan bahan bakar bensin, yang harganya kini mencapai Rp 1.000 per liter, adalah sebuah keharusan.
Belum lagi biaya tak resmi seperti pungutan dari aparat ataupun preman setempat. Namun, pemberian uang perlindungan ini tidak lantas menjamin pertunjukan bisa berlangsung aman. Preman tetap usil, sementara aparat tidak banyak membantu. Bahkan, bila uang yang disodorkan dirasa kurang, ulah aparat bisa lebih menjengkelkan. "Sering mereka bersikap seolah-olah kita dilindungi, tapi nyatanya kita harus jalan sendiri," tutur Aang, koordinator kelompok.
Biaya lain yang harus dipikul adalah perizinan. Tak jelas berapa persisnya tarif resmi yang harus dibayar. Para pegawai di Kantor Pemerintah Daerah DKI yang berwenang mengurusi masalah ini hanya mengangkat bahu ketika dijumpai TEMPO. Menurut Aang, biasanya Kelana Karya langsung mengontak calo yang akan menyediakan lokasi sesuai dengan perjanjiannya dengan pemerintah daerah dan kelurahan setempat. Namun, itu bukan berarti semuanya berjalan mulus. Tak jarang, ketika kelompok ini sudah membayar uang muka, ternyata lokasi tak bisa dipakai.
Bagi Kelana Karya, yang sudah kenyang makan garam dunia pertunjukan keliling, ada cara yang dipakai untuk menyiasati uang yang diperoleh. Kelompok yang berdiri sejak 1969 ini mengumpulkan seluruh pendapatan pada satu hari. Jumlah tersebut dibagi empat dengan persentase yang sama, yang nantinya akan dialokasikan untuk gaji karyawan, pemilik, dana operasional, dan tabungan karyawan.
Sebetulnya, setoran pendapatan untuk kelompok ini tidak selalu diwajibkan. M. Ali, pemilik atraksi lempar gelang, mengaku setoran yang dibayarkannya bersifat sukarela. "Mereka sudah seperti keluarga. Jadi, saya sesanggupnya saja. Bisa Rp 20 ribu, Rp 15 ribu, atau cuma Rp 10 ribu," ujar Ali, yang kini berusia 56 tahun.
Penghasilan Ali sendiri tidak menentu. Bila sedang ramai, ia bisa membawa Rp 40 ribu dalam satu hari. Sebaliknya, kala apes, ia terpaksa harus puas dengan Rp 5.000. Perolehan Ali memang sangat bergantung pada rasa penasaran pengunjung. Dengan membayar Rp 100, pengunjung akan mendapatkan satu gelang yang dilemparkan ke mulut botol.
Hiburan yang ditawarkan kelompok ini sebenarnya tidak terbatas pada atraksi untuk anak-anak. Pengunjung bisa berjoget sepuasnya di pertunjukan dangdut dan jaipong. Namun, pertunjukan ini hanya seminggu sekali, pada hari Jumat, ketika malam sudah larut.
Sayang, pertunjukan dangdut sekarang kurang diminati. Selain penarinya jarang berlatih—sehingga berkesan asal goyang—iringan musiknya yang tidak lagi menggunakan musik hidup juga membuat suasana dingin. Setelah biaya pemain musik terasa berat, kelompok ini memang hanya menggunakan tape dan kaset.
Meski megap-megap, bertahannya kelompok ini di tengah derasnya tawaran hiburan lain ternyata tetap menarik. "Mereka itu kenyal dalam bertahan hidup. Selain itu, secara sosiologis, memang ada pasar yang merupakan jatahnya," ujar Saini K.M., pengamat budaya. Mungkin karena pasar yang sudah tetap itu, juga karena krisis moneter yang menghantam kehidupan, justru kehidupan komedi keliling—betapapun sukarnya—tetap bisa bertahan.
Yusi A. Pareanom, Hani Pudjiarti, Darmawan Sepriyossa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini