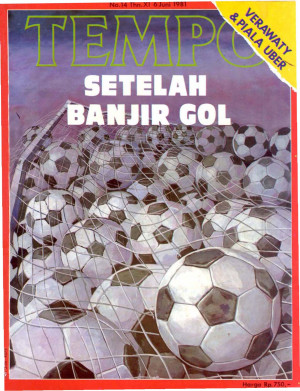PENGAKUAN PARIYEM
Linus Suryadi AG, Sinar Harapan, Jakarta 1981,
244 halaman daftar kosa kata Jawa-Indonesia dan dua kata
pengantar.
PENGAKUAN Pariyem penuh dengan istilah Jawa. Bagi pengamat
kesusastraan Indonesia percampuran dengan bahasa daerah itu
sudah nampak biasa, karena telah dipersiapkan oleh karya lain,
oleh pengarang-pengarang sebelumnya. Sajak Darmanto Yatman dan
lakon Akhudiat tidak sedikit menggunakan kata dan ucapan Jawa.
Gubahan cerita Nyai Dasima oleh S.M. Ardan mengandung omongan
khas Jakarta. Sedang dalam roman terkenal Atheis Achdiat Karta
Mihardja bermunculan dengan amat kerapnya kata-kata Sunda.
Dalam Pengakuan Pariyem karangan Linus Suryadi AG ini penggunaan
kata bahasa daerah sudah mencapai tahap ekstrim. Sehingga oleh
pengarangnya dirasa perlu memberi daftar kosa kata
Jawa-lndonesia seluas 57 halaman di bagian belakang bukunya.
Istilah bahasa daerah dalam kesusastraan Indonesia bertugas
memberi warna lokal pada cerita -- supaya kejadian dapat
mengesankan realitas. Tetapi dengan kembali menjemput kata dan
ungkapan bahasa daerah itu rupanya ada semacam pengakuan yang
diam-diam tak terungkapkan. Ialah, bahwa bahasa Indonesia kurang
ekspresif sifatnya untuk menyatakan sesuatu secara hemat dan
tepat.
Mungkin pada Linus telah timbul pertanyaan: bagaimana menyatakan
secara ekspresif pengertian menjuluk atau mbok-mboken dalam
bahasa Indonesia, kecuali dengan uraian panjang yang tidak
langsung mengena pada intinya. Seperti, 'mengangkat kepala untuk
diletakkan di atas bantal (setelah merosot)' dan 'masih
bergantung kepada ibu'.
Saking banyaknya istilah Jawa dipergunakan dalam cerita ini,
beberapa di antaranya luput dimasukkan dalam daftar kosa kata.
Seperti kata pari taneg, weton, nJawani dan ungkapan nggege
mangsa, nrimo ing pandum, yang niscaya akan menghambat pembaca
bukan Jawa untuk memahami pengakuan Pariyem dengan sepenuhnya.
Kecuali pada roman Atheis, istilah bahasa daerah dalam
kesusastraan Indonesia bertujuan mengungkapkan jagat rakyat
kecil. Bahasa campuran Indonesia-daerah yang bercorak tak resmi
itu merupakan pengucapan diri yang paling tepat bagi lapisan
masyarakat yang tak resmi pula. Dalam Pengakuan Pariyem, tokoh
rakyat kecil yang tampil adalah Maria Magdalena Pariyem dari
desa Wonosari Gunung Kidul, yang menjadi babu keluarga bangsawan
Cokrosentono di kota Yogyakarta -- kedudukan hidup yang
berulang-ulang disebut dalam prosa-lirik ini.
Nama Maria Magdalena didapatnya dari pastur Belanda ketika ia
bersekolah SD Kanisius di Wonosari. Tetapi berbeda dengan Maria
Magdalena di dalam kitab Injil yang sadar akan dosanya, Maria
Magdalena dari Gunung Kidul ini tidak mengenal dosa. Dia tidak
merasa terikat kepada dogma agama dan dia membenarkan naluri
alam. Kehidupan mengalir dengan wajar dan tidak ada penyesalan
yang menggoda batinnya. Pariyem lebih dekat kepada kejawaannya
daripada kepada agama Katoliknya, "Bila dia itu orang Jawa
tulen," katanya, "tak usah merasa perlu ditanya-perkara dosa."
Seks Pariyem
Dasar kepercayaan Pariyem adalah mistik Jawa. Dan Linus lewat
angan-angan dan pengalaman Pariyem mengutarakan berbagai
perbuatan dan gagasan yang terbit dari pandangan hidup itu.
Pariyem merupakan penjelmaan gagasan Linus tentang sikap
kejawen: "Hidup mesti selaras dengan alam agar umur kita awet
dan panjang. " Keselamatan tergantung kepada harmoni kita dengan
alam. Di samping itu berlaku pedoman supaya kita tahu takar dan
batas: berpikir dan merasa harus sak madya saja, antara rasa dan
pikir selaras sehingga hidup berjalan, 'berdesir'.
Berpegang pada patokan hidup itu Pariyem memperoleh sikap yang
diidam-idamkan olehnya. Yakni, keikhlasan menerima segala rupa
nasib yang datang, sikap lega-lila. Ia tidak menolak nasibnya
sebagai babu, karena hukum alam menentukan bahwa ada priyayi,
ada babu, dan kedua-duanya tak terpisahkan.
Kehidupan seks Pariyem, yang dibentangkan dalam buku ini tanpa
disidhem dan didekam juga sekedar mengikuti aliran alam yang
tidak terhambat oleh cuaca batin yang gelap."Saya mau mengalir
saja, saya krasan ada di dalamnya," katanya. Dia tidak gusar
ketika hilang keprawanannya oleh teman sekampungnya, Kliwon.
Juga kemudian setelah menjadi babu di Yogya, ia melayani
kebutuhan bermain cinta putra majikannya dengan lega-lila juga.
Bahkan setelah hubungan itu membuahkan anak, ia rela menerima
keturunan itu, dan tidak menjadi soal baginya apakah ia akan
dinikah atau tidak.
Linus, 30 tahun, lewat pengakuan Pariyem tidak saja
menggambarkan dunia batin seorang wanita Jawa, seperti yang
dinyatakan di bawah judul bukunya. Tetapi ia memaparkan pula
masarakat di lingkungan Pariyem dengan kebiasaan-kebiasaan dan
tatacaranya. Ia pun mempergunakan tokoh Pariyem untuk menegaskan
sikapnya terhadap kehidupan sosial dewasa ini. Dan rasa humor
yang halus menyertai kritiknya, sesuai dengan kesantaian gaya
hidup Pariyem.
Satu pokok pikiran Linus yang penting yang dikemukakannya lewat
Pariyem adalah mengenai pendirian budayanya, yang disebutnya
ngelmu krasan. Pendirian itu berpegang pada orientasi,
krasannya, pada negeri serta tradisi sendiri. Sikap ini
dihadapkan bertentangan dengan universalisme yang dianut penyair
modern seperti Chairil Anwar dan Sitor Situmorang -- yang oleh
Linus disifatkan sebagai "orang-orang mengembarakan batin/dan
mencari jangkar ke seberang/Dengan buminya merasakan asing/tidak
dekat dan tidak akrab."
Ganjil & Tak Kena
Pengakuan Pariyem merupakan buah sastra Indonesia yang paling
bagus selama barang lima tahun ini. Dalam bentuk prosa-lirik
yang serba ringkas dan bervariasi gaya penuturannya, karya ini
telah berhasil mencakup ruang-lingkup kehidupan yang luas.
Dengan menjamah segi Jasmam, sambil mengajak masuk ke dalam
relung jagat manusia Jawa. Angan-angan, gagasan serta realisme
kehidupan jalin-menjalin dengan manisnya dalam cerita ini.
Tetapi ada sesuatu yang terasa masih ganjil dan tak kena. Linus
memang dengan meyakinkan memaparkan cita-cita kejawen yang
secara umum masih diakui sebagai nilai dan pedoman hidup yang
berharga dalam masyarakat Jawa. Tetapi pertanyaan timbul waktu
membaca buku ini: menurut kenyataannya, masih mungkinkah kita
menjumpai seorang babu seperti Pariyem itu di dalam rumah
tangga, di Yogya atau di kota lain di Jawa Tengah? Bukankah
Pariyem hanya tinggal penjelmaan cita saja tentang etika Jawa,
yang tidak lagi dapat kita temukan pada tingkah laku pembantu
rumah tangga di Jawa?
Pariyem yang digambarkan dalam buku Linus ini hanya mungkin ada
barang empat puluh tahun yang lalu -- sekarang sudah bungkuk
dengan gigi ompong di rumah sebuah keluarga modern, seperti
keluarga bangsawan Cokrosentono itu, Hubungan babu-majikan yang
santai dan ramah dan penuh pengabdian seperti yang dikemukakan
Linus boleh dikata sudah tak ada di Jawa.
Barangsiapa setelah membaca Pengakuan Pariyem berkeinginan
menemukan babu seperti dia, terang akan penasaran dan kecewa.
Pariyem hanya tinggal suatu kerinduan.
Subagio Sastrowardoyo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini