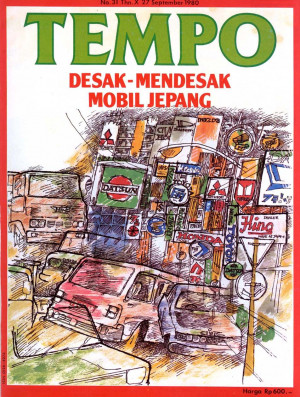MODEL atau rencana -- atau populer disebut disain -- untuk
kerajinan rakyat, ternyata bisa berarti banyak. Misalnya yang
terlihat di Cibaduyut, Bandung. Suatu saat para pengrajin sepatu
di situ mendapat model dari luar negeri. Mengira model itu bisa
ditiru dengan gampang, dibikinlah sepatu yang "sama". Hasilnya
ternyata tak memuaskan. Pembuatannya makan waktu lama -- jadi
harganya harus mahal. Kecuali itu kualitasnya pun tak bisa
persis.
Itu diceritakan oleh Widagdo, Ketua Ikatan Ahli Disain Indonesia
(IADI) kepada TEMPO, sewaktu jam istirahat Seminar Pekan Disain
I pekan lalu di Hotel Indonesia Sheraton -- Jakarta. Maka
seorang anggota IADI yang kebetulan menemui kasus tersebut,
tutur Widagdo pula, mencari sebab-musababnya -- dan ketemu. Ini
disain sepatu tersebut ternyata diciptakan untuk produksi dengan
mesin modern -- bukan "mesin" Cibaduyut. Jadi, sekarang,
disarankan untuk tetap meniru bentuknya -- tapi hanya itu. Cara
pengerjaannya sama sekali lain: dianyam. Dan konon sukses.
Disain ternyata memang tak hanya berurusan dengan keindahan.
Banyak aspek tersangkut di situ: kepraktisan, keawetan,
kemungkinan produksi massal, kemurahan, misalnya. Hal-hal itulah
yang digarap para disainer yang tergabung dalam IADI yang
berpusat di Bandung itu. Mereka, selama ini, menciptakan disain
berbagai barang kerajinan rakyat yang sudah ada -- atau
mengembangkannya dengan mencari kemungkinan agar lebih bermutu.
Pameran itu sendiri diikuti beberapa kelompok kerajinan rakyat,
Senirupa ITB, Sekolh Tinggi Seni Rupa Indonesia "Asri" Senirura
Universitas Trisakti Jakarta, dan tentu saja IADI sendiri.
Berbagai hasil kerajinan seperti tas (dari kulit maupun bahan
lain), sepatu, keranjang, tempat barang atau tempat ikan, kera
mik, mebel rotan atau bambu, yang telah diwarnai pembaharuan
disain, diperlihatkan.
Atau Kampungan
IADI sendiri, berdiri 1977 dan bekerjasama dengan Badan
Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), sudah banyak melakukan
riset ke berbagai daerah kerajinan rakyat. Tapi seberapa jauh
tanggapan para pengrajin terhadap disain baru mereka itu,
sebenarnya belum diketahui. Untuk itu "kami belum pernah riset,"
tutur Widagdo, dosen Interior Disain di ITB itu. "Tapi para
pengrajin itu sendiri biasanya telah menyeleksi: yang kira-kira
laku, ya dibikin. Yang tidak ya tidak." Para pengrajin memang
lebih mementingkan laku tidaknya produksi daripada segi
artistik, tentu saja.
Tapi tentang manfaat sentuhan disain baru itu, Lembaga
Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
punya data. Kerajinan rotan di Tegalwangi, Jawa Barat, misalnya,
yang dibina IADI sejak tahun 70an, menunjukkan akumulasi modal
yang makin meningkat. Tahun 1975, modal pengrajin kecil, sedang
dan menengah di situ tercatat Rp 42 ribu, Rp 350 ribu dan Rp 1,6
juta. Empat tahun kemudian, setelah dengan intensif mereka
diperkenalkan dengan disain kerajinan rotan yang dikembangkan,
modal itu meningkat Rp 150 ribu, Rp 1,4 juta dan Rp 10 juta.
"Padahal itu semua terjadi sementara manajemennya tetap seperti
semula," kata Utomo Dananjaya, orang LP3ES. Dengan kata lain:
memang ada pengaruh disain terhadap pasaran.
Lagipula biasanya, dengan pengembangan disain, hasil kerajinan
rakyat tak lagi dipandang remeh atau "kampungan." Tak lagi ada
pandangan model 20 tahun yang lalu, seperti diceritakan Dr.
Sudjoko dalam salah satu seminar kesenian. Menurut Sudjoko, juga
dosen ITB, orang yang berumah bambu biasanya orang miskin.
Karena itu lantas timbul anggapan bahwa barang-barang dari bambu
remeh, murah. Padahal, coba saja disainnya diubah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini