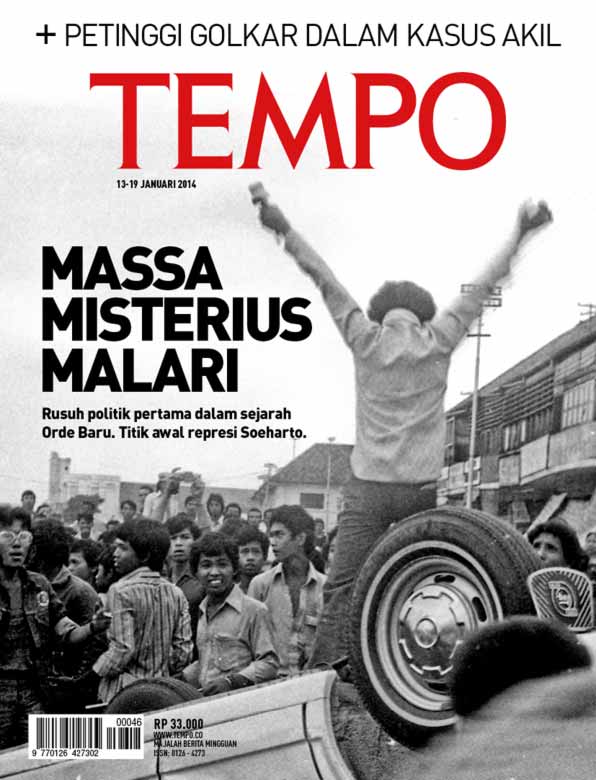Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
ORIENTASI BARU ISLAM-BARAT
Judul: The Future of Islam
Penulis: John L. Esposito
Penerbit: Oxford: Oxford University Press
Tahun: 2013 (soft cover)
Tebal: 256 halaman
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo