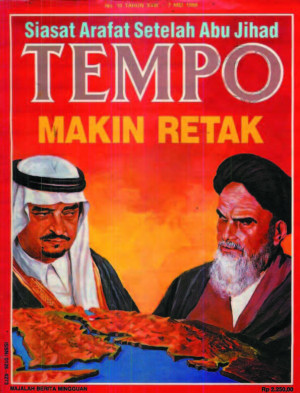LUKISAN kebanggaan Chaw I-Chou adalah Pagi Musim Semi di Istana Han. Berukuran 30 cm x 6,485 meter, lukisan itu diciptakannya selama 15 bulan. Lukisan yang memanjang dalam bentuk scroll atau gulungan ini pada 29 sampai 3 Mei dipamerkan di Balai Budaya, Jakarta. Lukisan di atas kertas tersebut merupakan episode kehidupan Putri Wang Chao Chuin - permaisuri raja di zaman dinasti Han. Sebuah dongeng panjang yang berisi kegilaan terhadap perempuan, hubungan politik, dan uang suap atau sogok kebetulan si tokoh penerima suap itu adalah seorang pelukis. "Lukisan ini merupakan kitab moral bagi saya. Dan itu tidak saya jual," ujar Chou, yang hanya sehari dua saja memamernya di Balai Budaya. Kisah pelukis yang menerima suap itu agaknya jadi bayangan menjijikkan baginya. Seniman, dalam pikirannya, seharusnya putih terhadap duit. Seni diciptakan untuk kemurnian hati dan pikiran. Seni bukan untuk dijual-jual. Dan Chaw I-Chou siap menerima risiko. Selama 40 tahun melukis, kehiJupannya melata. Chou (beragama Islam) tidak kaya. Lelaki 67 tahun ini tidak memelihara nafsunya, atau yang dianggapnya profan dan mondial. Selama hidupnya, ia tak lebih dari 10 kali menonton film. Karena geraknya berkait dengan seni lukis, kemudian oleh banyak orang dia disebut master. C.M. Hsu, konsultan ahli seni lukis Cina (dia penyusun buku koleksi lukisan Cina milik Adam Malik) dan anggota International of Science, Letters and Arts mengangkat Chou sebagai seorang master Chinese painting di republik ini -- di samping Shi Zhongan dan Peng Guoqi. Lukisan-lukisan Chou membahagiakan. Merasakan gagasan visualnya, Pagi Musim Semi di Istana Han memang tidak orisinil. Itu diubahnva kembali dari lukisan Chiu Ying - seniman dinasti Ming (1368-1644). Namun, dari penguasaan teknik, Chou bagai melangkahi segalanya, hingga lebih estetik dan sempurna. Chou lahir di Guangchou. Ia ber-shio monyet. Ketika usianya 19 tahun, ia muhibah ke Medan sebagai karyawan studio foto. Setelah 1950-an belajar melukis pada Huang Dufeng--tokoh seni lukis yang kini hidup di Guilin, Cina - dia meninggalkan foto dan mengganti dengan mopit. Oleh karena karyanya yang antipesanan itu sulit laku, lalu ia mengajar melukis untuk sekadar makan. Hina pindah ke Jakarta awal 1980-an ia mendapat banyak murid. Dan 40 yang berbangsa asing. Tempat tinggalnya di Jalan Telesonic, Jakarta Selatan, dipinjamkan oleh seorang Belanda yang menjadi muridnya. Rumahnya di Medan juga hasil kekaguman orang padanya. Rumah Chou diperbaiki - sambil tiap bulan karyakaryanya itu dibeli. Tidak kurang dari 400 lukisan Chou kini dikoleksi si pengagumnya yang berdarah Jerman itu. Dengan menyodorkan beberapa tema referensif dari mitologi Cina, karya-karyanya memadukan akuarel dan dry brush. Paling umum adalah taferil-taferil, yang melukiskan satwa-satwa Chao yang tidak terlampau atraktif berulah - kecuali memang bergerak, bergeming, tercercap bermain bersama angin. Burung, belalang, atau kelelawar seperti menciptakan puisi bersama ranting bambu dan bunga plum. Dari jajarari yang dipamerkan itu, yang paling cantik adalah Pertemuan Delapan Belas Orang Cendekiawan. Warnanya jernih, bentuknya rinci, serta kontur Chou yang lembut itu terarah. Ia menawarkan kekaguman. Karena kisah 18 murid pilihan Budha itu, yang disebut arhat, muncul sebagai karya pepal yang mengajarkan santun. Tarikan pena-bulu Chou yang lincah di atas Xuan zhi (sebutan kertas khusus untuk lukisan Cina) merupakan penghormatan tinggi kepada Meng Tian, pencipta kuas lancip itu. "Dari sini semua bermula," katanya. Ia mengangkat sebatang kuas. Ia bayangkan Meng Tian yang hidup di zaman dinasti Qin, 250 tahun Sebelum Masehi. Artinya, semua berawal dari yang sangat dasar. Sekitar 100 lukisan Chou yang dipamerkan, sedari awal, tidak pernah diangankannya akan dibeli orang. Apalagi di Indonesia, seni lukis Cina yang menacu pada pola klasik itu masih jauh dari jamahan komersial. Kecuali kalau hoki. Ia muncul ke permukaan, setelah sebelumnya pameran di Medan (1972), Balai Budaya (1975), dan Taiwan, 1985. Itu hanya untuk memenuhi hasratnya bertemu dengan banyak orang. Sepercik pikiran pendekar, karena selama ini orang datang padanya, tapi ia jarang mendatangi orang lain? Bagaimana dengan pasar? Chou menempel harga lukisannya dari Rp 300 ribu sampai di atas Rp 10 juta, itu ibarat "perlawanan dagang" terhadap seni lukis kontemporer. Di beberapa galeri di Jakarta Kota tersedia lukisan-lukisan Cina, tetapi tanpa menyentuh yang klasik, karena condong ke karya cat minyak kontemporer semacam Lee Man Fong. Dalam suasana Cina The Last Emperor yang laris, Chou tak heran bila lukisannya tidak laku. Ia tetap tegar, walau karyanya yang bercorak klasik itu kian terjepit. Karena ia juga menyadari bahwa pemasaran seni klasik di sini memang tidak ada koordinasi. Agus Dermawan T.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini