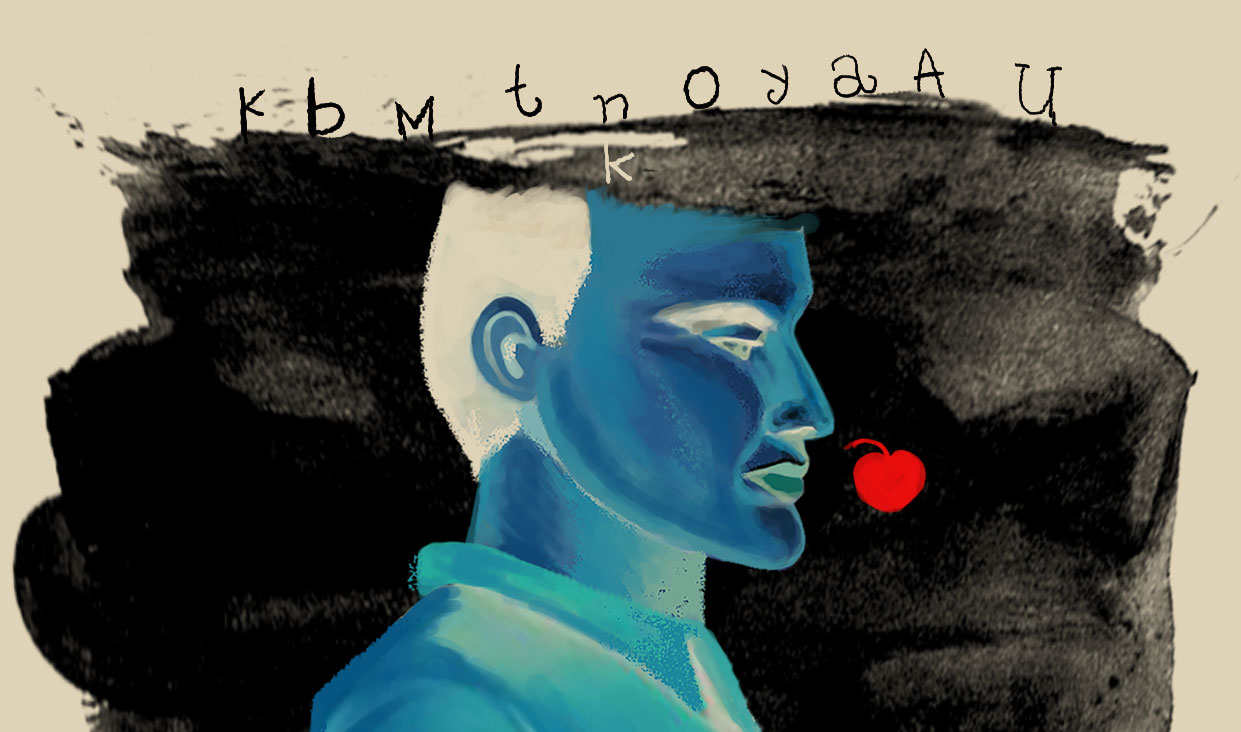Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Cioko, puisi Widya Mareta.
Menuju Jalan Filsuf, puisi Vito Prasetyo.
Widya Mareta
Cioko
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lihatlah meja-meja ini:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

meja makan para setan
yang baru saja dibukakan jalan.
Di kelenteng-kelenteng,
manusia saling berebut persembahan
untuk dibawa pulang.
Sementara di sini,
kita masih bergurau tentang apa pun yang tak ada,
makan bersama walau berbeda meja
dalam batasan waktu yang ditentukan para dewa.
Arwah-arwah lapar
diedarkan kembali pada bulan ke tujuh
setelah dipenjara sekian lama
bersama doa-doa yang telah menjauh.
Gurihnya asap sesaji
bak tarian ruh
lengkapi warta bagi lapar yang paling mustahil tunai:
lapar yang gagal merdeka,
lapar yang baka.
Tapi mari lupakan rasa lapar hari ini
seperti kaulupakan lapar di hari kemarin,
sebab sup ini telah pucat
tiba waktunya untuk sekarat.
Lilin-lilin tak lagi mengingat nasib sumbunya
saat semua kertas terbakar habis
dikepung udara.
Kini zat-zat yang larut tak lagi punya nama.
Pada lambungku,
pada lambungmu,
di mana rasa perih telah didentumkan keras sekali
hingga hanya tersisa lenguh.
Jarum jam menggelinding dari punggung waktu yang terjal
begitu cepat bagai racun tanpa penawar.
Tunggulah aku pada kesempatan lainnya
bersama mendung yang beredar
menyiarkan kabar:
aku selalu hidup,
walau semua daging terasa abu.
*) Cioko tradisi masyarakat Tionghoa pada pertengahan bulan 7 kalender lunar. Manusia memberi sesaji kepada para arwah leluhur dan dewa-dewi sebagai bentuk penghormatan.
Vito Prasetyo
Menuju Jalan Filsuf
dan tulang rusuk ini, tempat
mengisah luka
di malam yang pecahkan keberanian
dorong-mendorong
angin hempaskan tangan
menggoncang balok penjagalan
lalu ucapkan: pertemuan kematian
karat besi hanya meniru lapuknya kayu
dimana air mata tuntaskan perihnya raga
dan tulang memutih
sebening salju, kaku
tinggalkan aib
menusuk buih-buih sajak kehidupan
mari lantunkan kata-kata abadi
kereta jalan mengikuti arah pikiran
disitu, malaikat pernah menaruh galaksi
berisi tentang pecahnya saturnus dan jupiter
hingga langit berkubang duka
mengapa kita meng-amini-nya
langit, di atas segalanya
ribuan sinar tersisa
memberangus kesesatan
menuju bukit-bukit untuk duduk bertafakur
seperti Isa Almasih mendaki bukit golgota
diiringi lonceng-lonceng
mengalunkan simphoni dari kastil
engkau masih saja bertanya,
: itukah jalan kebenaran
kita singkap kembali luka
untuk menerangkan puisi Khalil Gibran
tersimpan rapi di perapian cinta
saat kubabat rumput ilalang
di musim hujan bermandikan salju
dan bayi-bayi kecil ditinggal ibunya
mencari kitab kebenaran
di sepenggal catatan perang, masa tirani
raja-raja bertangan besi
petaka angin kembali menggoncang
di bumi, yang tinggal sepertiga zaman
binatang-binatang tak lagi buas
duduk tenang, di singgasana kapitalis
adalah socrates, aristoteles telah kehilangan filosofi
biarkan puisi ini terbaring
menuju pemakaman angin
karena filosofi tidak selalu benar
di zaman ini
di peradaban baru
Malang, 2021
Widya Mareta lahir di Tangerang, Banten, pada 1994. Buku puisinya, Puasa Puisi (2021), termaktub dalam 5 Besar Kusala Sastra Khatulistiwa 2021. Ia menetap di Tangerang.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo