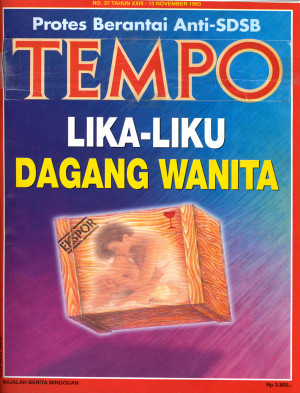Buku ini memuat surat-surat seorang peneliti Amerika pada masa demokrasi liberal. Sebuah potret kehidupan politik. Namun penulisnya tak ingin membuat analisa dan teori politik. TAHUN 1950-an rasanya memang sengaja dihidupkan dalam kenangan. Baik oleh Orde Lama maupun Orde Baru. Masa ini disebut sebagai masa ''Demokrasi Liberal'', yang pantas diingat untuk sederetan kesalahan dalam menerapkan demokrasi yang dianggap ''tak sesuai dengan alam budaya Indonesia''. Sehubungan dengan keadaan demokrasi kala itu, surat-surat Boyd R. Compton menjadi amat menarik untuk dibaca ulang. Compton, yang lahir di Los Angeles 1925, menggaet MA dari University of Washington, Seattle. Karena gagal memasuki Cina akibat Revolusi Kebudayaan, ia lalu mengalihkan minatnya dan tinggal selama lima tahun (1952-1956) di Indonesia, untuk meneliti sejarah kontemporer Indonesia. Ia kemudian ke Leiden untuk melanjutkan penelitiannya, tapi tak dapat dirampungkan. Dan kini ia menjadi presiden sebuah perusahaan yang mengembangkan energi angin di negeri berkembang. Selama tinggal di Indonesia, Compton menulis serangkaian surat laporan kepada International of Current World Affairs, lembaga yang membiayainya. Berbeda dengan buku-buku kajian ilmu politik, surat-surat ini tak berpretensi teoretis, walaupun umumnya memiliki bobot analisa yang mendalam. Juga sewaktu ditulis dalam bentangan waktu antara tahun 1952 dan 1956, surat-surat itu tak merekonstruksi suatu kurun sejarah dalam suatu bangunan pemahaman atau penafsiran yang menyeluruh. Pengantar Fachry Ali lebih lagi mencoba memberikan pancang analisa, agar surat-surat yang semula berserak-serak itu terlihat kaitannya dalam suatu rangkuman pemahaman. Ini semua memang amat membantu untuk membentuk citra buku itu sebagai rekaman tentang sebuah zaman. Compton sendiri, dalam retrospeksi, mengelompokkan surat- suratnya itu dalam dua gugus. Gugus pertama berdasarkan anggapan yang optimistis terhadap Islam modernis yang sedang ''menunjukkan jalan ke masa depan'', dengan akar kelas pengusaha, dan titik berat pada hukum. Sejarah menunjukkan perkembangan yang lain, sehingga Compton sendiri dalam prakatanya mengakui kekeliruan anggapan itu. Kesan tentang kuatnya Masyumi dan lapisan pengusaha yang sedang tumbuh memberikan harapan akan lahirnya kelas menengah pribumi yang akan menjadi penopang pembangunan ekonomi dan demokrasi. Gugus kedua, yang kemudian dianggapnya sebagai pendekatan yang lebih benar, adalah pengamatannya terhadap Soekarno dan berbagai kelompok yang tengah bersaing untuk menguasai birokrasi, yang membawanya kepada catatan penting bahwa tak satu kelompok pun dapat memonopoli kekuasaan. Ada empat kelompok besar yang dicatatnya: Islam, Komunis, Nasionalis radikal (terutama Soekarno), dan Tentara (para panglima teritorial). Menyimpulkan kurun ini, Compton menyebut periode itu Indonesia sedang mencari bentuk. Soekarno, katanya, ''memahami proses ini dan menanggapinya dengan intuisi yang cemerlang ... dia hampir secara sempurna mencerminkan pertarungan nilai-nilai itu untuk menemukan sebuah ekspresi Indonesia'', dengan aktor kunci: bangsa Indonesia sendiri. Surat-surat itu seperti rekaman fotografis dari suatu peristiwa atau persoalan, yang diambil dengan lensa yang fokus dan pencahayaannya bagus, tetapi tetap merupakan sebuah rekaman sesaat. Seperti sebuah album, ia mengisahkan potongan-potongan perjalanan untuk memahami Indonesia sebagai republik muda. Dari Peristiwa 17 Oktober yang kontroversial, kericuhan dalam tentara, ketegangan antara pusat dan daerah, percaturan politik partai pada peringkat nasional maupun lokal, peranan Soekarno, kedudukan Cina, sampai ke kehidupan kampung Jakarta dan rakyat kecil seperti si Omah. Tak terlewatkan adalah soal seni budaya seperti tarian muda-mudi dan kedudukan bahasa Indonesia. Islam sebagai kekuatan yang cukup besar juga memperoleh porsi yang sepadan dalam surat-surat itu. Dari telaah mengenai rekah- rekah koalisinya dengan PNI, sampai ke faksi-faksi Natsir dan Isa Anshari, bahkan sampai ke kunjungan ke Pekajangan, untuk melihat kekuatan politik Islam dan kalangan usahawan di lapangan. Sayang sekali, surat-surat ini berakhir sekitar satu tahun sesudah Pemilu 1955, sehingga puncak dari kurun kemelut itu apa yang kemudian disebut ''kemacetan'' Konstituante dan Dekrit 5 Juli 1959 tak sempat terekam. Aswab Mahasin
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini