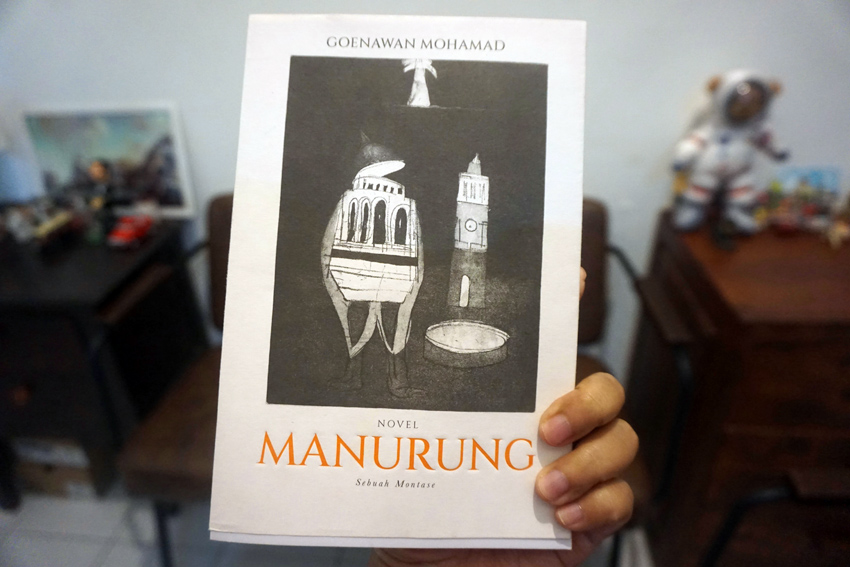Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pelukis Roesli (almarhum) pernah bilang, sekitar 1972, ia tak pernah memperbaiki goresan tangannya: ”Kalau saya tak puas, (lukisan) saya buang. Saya ambil kanvas baru, untuk melukis baru.” Sebab, baginya, ”Sapuan kuas harus orisinal. Sekali jadi.”
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo