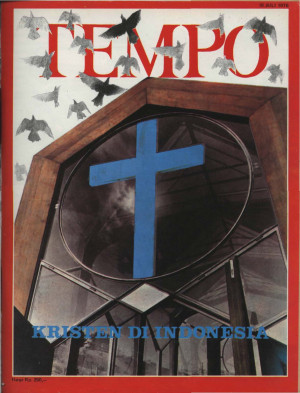AGUNG
Karya: Ikranagara
Sutradara: Ikranagara
Produksi: Teater (Siapa) Saja
***
INGIN menikmati pertunjukan Ikranagara? Orang ditawari pertama
kali untuk menerima "keindahan pentas". Level-level yang disusun
menurut selera yang manis, panggung yang dibikin ramai kalau
perlu dengan lampu-lampu, dan gerak-gerak para pemain yang
eksplosif dan mau-gagah. Bukan berarti Ikranagara tak punya
ambisi untuk membawakan sesuatu yang lebih dari itu. Hanya saja,
apa yang suka disebut Ikra sebagai 'yang teatrikal', yang
kenyataannya tak lain dari kemampuan yang hanya berhenti di
panggung, memang merupakan "perjuangan" Ikra yang paling besar.
Bila ia menyatakan misalnya, seperti ditulis dalam folder untuk
pertunjukannya terakhir ini: "seluruhnya tunduk pada yang
teatrikal", maka memang tidak berarti para sutradara lain tidak
mengindahkan unsur-unsur panggung atau kekuatan teatrikal
tentunya -- meskipun mereka tak usah berteriak. Bedanya: Ikra
menganggap pengertian 'teater' itu harus diperhitungkan kembali"
dengan mempertimbangkan kedudukan panggung itu.
Padahal, sekiranya pernyataan Ikra di atas difahami tanpa
ruwet-ruwetan, maka yang ingin dicapainya sebenarnya tak beda
dengan apa yang sudah diperbuat rekan-rekan yang lain. Putu
Wijaya atau Sardono misalnya. Teater, bagi mereka berdua --
setidak-tidaknya pada pertunjukan-pertunjukan terakhir untuk
Putu Wijaya -- bukanlan seni yang bermula dari konsep, apa lagi
konsep tertulis. Panggung, dan apa yang "dengan sendirinya"
terjadi di panggung, haruslah merupakan satu kehidupan yang
betapapun juga memberi orang satu kekayaan. Dan kekayaan itu
adalah imaji-imaji (images) murni. Pada Ikra dan ini bedanya,
yang disebut "yang teatrikal" itu kenyataannya tak lain dari
teknik -- dan ini diharapkannya mencukupi semuanya. Kalaupun ia
ingin untuk juga memberi tekanan pada imaji, maka hal yang tidak
cukup ia sadari adalah bahwa imaji bukanlah barang yang bisa
dibawa beitu saja oleh itu 'daya teatrik' . Sepert bisa
dilihat pada Putu -- tanpa menyatakan bahwa dia ini selalu
sangat berhasil -- imaji bangkit dan sampai kepada penonton,
hanya bila sesuatu bentuk yang dipilih si seniman lahir dari
sesuatu kebutuhan dari dalam -- yang lazimnya tak begitu jelas
dan tak begitu disadari. Katakanlah, didorong oleh warna
tertentu dari 'pembawaan dalam'. Dengan kata lain bukan
bentuknya yang pertama kali dikejar, seperti pada Ikra yang muda
ini.
Rendra
Pada Ikra, pernyataan "semuanya tunduk pada yang teatrikal"
lantas berarti bahwa muatan itu (pesan, amanat, fikiran, atau
"isi") tunduk kepada teknik atau kemampuan pemanggungan. Di
siniorang lantas tak bisa mengerti: apa bedanya Ikra dengan
Arifin C. Noer misalnya, kalau begitu. Bukankah Arifin --
apalagi Rendra -- juga mengantarkan pesan-pesan yang kadang
diakui dengan jelas bahwa itu memang pesan atau misi) lewat itu
'kepandaian teatrikal'? Bukankah berbeda dengan Putu atau
Sardono, Arifin dan Rendra menjadikan kemampuan panggung tak
lain sebagai perantara meskipun pengertiannya antara dua orang
terakhir itu agak berbeda?
Tetapi baiklah. Barangkali maksud Ikra, teknik lebih penting
dari "isi". Maka yang terjadi adalah apa yang terjadi pada
pementasannya terakhir, Agung, 14-18 Juni di Taman Ismail
Marzuki. Dan ini memang lebih khas mewakili kecenderungan Ikra
yang teatrikal itu -- dalam menghargai "isi". Sebab Agung,
dibanding tontonannya terdahulu yang diberi judul Para Naratot
(TEMPO 27 September 1975), maupun lebih-lebih Topeng (TEMPO 3
Mei 1975), lebih mempunyai sosok yang jelas. Sosok ini dibangun
dari hubungan tokoh yang diberi nama Agung (bekas raja) bersama
puteranya -- yang kelihatan masih punya wibawa, dan kalau tak
salah dimaksud sebagai "korban peredaran zaman" -- dengan dua
fihak lain. Pertama fihak pejabat pemerintah yang memegang
kunci- situasi waktu itu (ini lukisan keadaan pada rezim
Sukarno). Kedua dengan tokoh bernama Mohidin, seorang pengusaha
dan bekas pemimpin Masyumi (yang sudah dibubarkan) bersama kedua
anaknya --yang di sini mewakili kebenaran dan sekaligus korban
fitnah.
Dari tema semacam itu, seorang pengarang bagus akan bisa
menyusun cerita yang hidup, sarat, dan menyentuh. Lihatlah
misalnya adegan Mohidin. Monolognya dibawakan dengan bagus oleh
pemain bernama Yusuf (satu-satunya nama yang tidak boleh
ditinggalkan, di samping Ikra sendiri sebagai pemain putera
Agung). Monolog itu, menggambarkan situasi waktu itu bagi tokoh
yang tampak sekali berangkat dari lingkungan Islam yang salih
dan keras. Sangat komunikatif baik dari segi penyampaian si
pemain maupun pemilihan dialog yang tangkas dari si pengarang.
Juga pertengkaran Mohidin dengan nonya-nyonya penggede yang
datang ke rumahnya untuk meminta "sumbangan sukarela" (yang
sudah ditentukan jumlahnya) tepat ketika ia baru mengambil air
sembahyang untuk maghrib. Penonton bersorak membela Mohidin,
tertawa, dan mengangguk-angguk.
Ditenggelamkan
Tetapi, oleh perkara "yang teatrikal" itu tadi, bahan-bahan
yang bagus itu ditenggelamkan ke bawah "wibawa panggung". Ada
kemauan ekspresi pada Ikra.Sejak semula, sosok yang ada dalam
lakon ini diantarkan tidak dalam aturan yang biasa. Cerita
tentang Agung, Mohidin dan lain-lain itu, dipotong dalam
kepingan-kepingan yang tidak berurut, dan di sela-selanya
diwujudkan berbagai formasi dan adegan peralihan yang lancar
sekali. Cara memotong-motong lakon itu sendiri, bagus -- dan
menyebabkan apa yang digambarkan bukan "hanya" sebuah cerita,
melainkan satu kesan keseluruhan. Tapi ekspresi yang
dimuncratkan terutama dengan mempergunakan tali-tali yang
bergantungan -- dengan bombastis -- betapapun sedapnya dilihat
dengan semangat remaja, terasa dibangunkan semata-mata buat
kepentingan suasana pentas -- dan bukan sehubungan dengan ide
besar di luar itu. Dengan kata lain: keributan tersebut terasa
dilancarkan untuk pemuasan diri Ikra sendiri atau para pemain
yang "teatrikal" itu.
Tak heran bila yang didapati dalam pertunjukan ini hanya lukisan
keadaan yang semua orang sudah tahu, ditambah para pemain muda
yang menggeram-geram, plus panggung arena yang apik yang tak ada
hubungannya dengan lakon. Adapun apa yang difahami sebagai
bobot, yang -- tanpa perasaan risi dihubung-hubungkan Ikra
dengan "pandangan kosmos atau filosofis saya", seperti ditulis
dalam folder, payah untuk dijumpai. Sama payahnya untuk menebak:
mengapa lakon ini bernama Agung -- dan bukan Mohidin, misalnya
saja -- selain bahwa dengan nama Agung, tontonan ini mendapat
"cap Bali". (Dan memang, selain Bali sekarang ini lagi keren,
bahan yang dikandung lakon ini sebenarnya boleh merupakan
dokumentasi tentang Bali pada satu periode -- kali ini Bali yang
lebih banyak Islam).
Hanya saja, belum pernah sebuah teater di TIM ditonton oleh
pengunjung yang begitu sedikit, seperti kali ini. Dengan
tambahan: hampir iap malam bisa dilihat orang-orang, kebanyakan
"wajah-wajah baru" ataupun orang asing, yang meninggalkan kursi
sebelum tontonan usai. Bisa difahami. Lepas dari bagian Mohidin
yang menarik, makanan "teatrikal" yang disuguhkan itu rupanya
kelewat "sulit". Apa yang bisa dirasakan orang, bila setelah
mencoba "menembus" hiruk-pikuk di pentas, ternyata tidak
menjumpai sesuatu yang menyentuh batin atau mendukung makna".
Jangankan Ikranagara. Bahkan Putu Wijaya, yang banyak mencari
komunikasi dengan penonton dengan mengingkari intelek itu -- dan
boleh dibilang gemilang -- kalau mau terus-menerus begitu
lama-lama bisa ditinggalkan orang juga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini