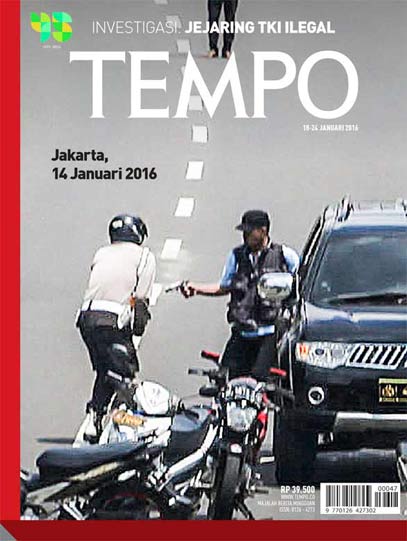Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bayang-bayang para penari itu terdapat di tujuh panel putih. Seorang penari menggebrak, memukul bayangannya sendiri. Bayangan itu langsung pecah menyebar. Tak begitu lama, di tujuh panel itu muncul visual orang-orang melakukan bunuh diri. Tubuh tergantung, leher dibelit tali. Gaya menggambarnya model manga, komik Jepang.
Kelompok Nibroll dari Tokyo terkenal menggarap pertunjukan tari dengan bahasa multimedia yang kuat. Malam itu, 10 Januari lalu, di Teater Arena Taman Budaya Surakarta, sedari menit awal mereka menyajikan permainan visual video mapping. Ruang tiba-tiba dipenuhi garis-garis seperti barcode atau simbol tagar, lalu timbunan padat angka.
Garis-garis tagar dan tumpukan angka itu mula-mula hanya ditembakkan ke panel, tapi kemudian meluber sampai membalut para penari. Menarik menyaksikan angka-angka itu berkeruntelan menyudut menjadi satu, lalu lepas menghambur. Dalam bungkusan berbagai macam "kode visual grafis" dari dunia komputer itu, tubuh para penari bergerak cepat, tangkas, pas.
Segera kita dapat menangkap pertunjukan berjudul Real Reality ini berbicara mengenai problem manusia urban dalam kota yang semakin digital. Mikuni Yanaihara, sang koreografer, mungkin berbicara tentang bagaimana di dunia yang makin dibentuk oleh permainan simulacra (permainan image dan citra), manusia mengalami "kekosongan". Setelah gambar orang melakukan bunuh diri, para penarinya, misalnya, berulang-ulang mengatakan, "I 'm really don't know anything. I have no space, no character, no landscape…."
Tatkala muncul seseorang membawa raket badminton dan kemudian melakukan gerakan smash dan backhand (meski ayunannya agak salah karena lebih mirip ayunan pemain tenis), Mikuni Yanaihara seolah-olah ingin membawa kita ke dunia benda sehari-hari sebelum era virtual ini. Para penari ke sana-kemari mendorong sebuah peti. Dari peti itu, mereka mengeluarkan piala, mainan kereta, kotak musik, dan bagian atas mesin jahit manual. "Dulu ibuku suka sekali menjahit, tapi sekarang sudah rusak," kata seorang penari. Seorang penari lain menggunakan sarung tangan bisbol, lalu seolah-olah menangkap dan melempar bola.
Dari peti itu, mereka kemudian juga mereka mengeluarkan teropong, kamera tua, weker jadul, dan televisi kuno. Mereka mencoba menggunakan barang-barang itu, yang ternyata sudah tidak berfungsi. Apa yang canggih pada masanya tidak sesuai lagi dengan teknologi masa kini. Para penari lalu memporak-porandakan barang itu. Mereka bergerak cepat, dengan arah saling diagonal.
Yang mengejutkan, kemudian terdengar suara gedebum benda-benda jatuh dari belakang. Sejak semula kita melihat remang-remang, di belakang panel-panel, ada panggung di ketinggian. Di situ terdapat meja belajar dengan sebuah jambangan bunga. Muncul kemudian seorang perempuan, yang duduk seakan-akan bekerja.
Ia menyobek-nyobek kertas, menebarkannya ke bawah. Ia lalu menjatuhkan barang apa saja di sampingnya satu per satu: buku-buku, gelas, piring, sendok, kap lampu. Setiap kali selesai melakukan itu, ia dengan tenang tetap menyemprot bunga di vas. Terakhir ia membuang kursi ke bawah, menimbulkan bunyi gedebum. Adegan ini disusul jatuhnya pakaian-pakaian bekas seperti hujan memenuhi lantai.
Dalam tiap pementasannya di berbagai negara, Nibroll menggandeng seniman setempat untuk terlibat. Di Solo, mereka mengajak penari Agus Margiyanto. Agus ikut berlatih dalam waktu yang cukup singkat, hanya lima hari. Dia mengikuti latihan dengan cukup intensif. "Berlatih selama enam-delapan jam sehari," ujar Agus.
Ide Nibroll tentang kehampaan manusia dalam sosiologi dunia digital yang makin bertumpu pada komunikasi dan citra-citra virtual dibanding pengalaman nyata sesungguhnya sederhana. Tapi cara eksekusinya membuat terasa lebih segar dan aktual. Video mapping, misalnya. Banyak koreografer di sini telah menggunakan medium ini, tapi kerap masih menjadikannya sekadar aksesori, latar, hiasan panggung, atau aksen-aksen pemanis belaka. Sedangkan video mapping di tangan Nibroll mampu menjadi "pemain" tersendiri dalam koreografi.
Pada titik ini, yang sangat penting adalah kemampuan mencerna duduk persoalan yang terjadi. Telah banyak teori simulacra dari para ahli yang mengungkap paradoks-paradoks dunia virtual dalam masyarakat konsumen. Apa manfaatnya, apa dampak-dampaknya. Hal-hal dasar seperti itu yang terasa sebelum pertunjukan telah dipahami atau dikunyah benar oleh koreografer seperti Mikuni Yanaihara. Maka ia bisa membuat struktur koreografi yang berlapis-lapis, tapi inti persoalan tetap terlihat. Ia juga bisa membuat permainan multimedia menjadi tidak kenes-kenesan atau canggung. Yang begini ini yang belum banyak dicapai koreografer muda kita.
Seno Joko Suyono, Ahmad Rafiq
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo