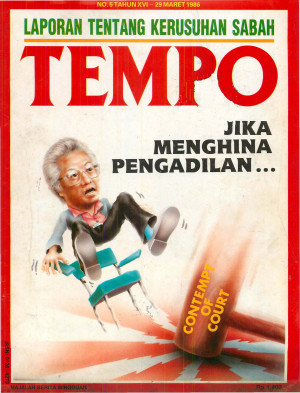PERDAGANGAN DAN INDUSTRI DALAM PEMBANGUNAN Oleh: Sumitro Djojohadikusumo Penerbit: LP3ES, Jakarta, 1985, 133 halaman KETIKA ekonomi Indonesia memburuk pada 1982, Sumitro Djojohadikusumo sudah bukan menteri lagi. Ketika penerimaan pemerintah mulai menurun, dia merupakan orang pertama yang menganurkan pemerintah menunda pembangunan beberapa proyek, terutama yang memerlukan komponen impor yang besar. Tapi, pemerintah, "demi mempertahankan momentum pembangunan", berniat meneruskan pembangunan proyek-proyeknya seperti yang direncanakan. Baru ketika keadaan benar-benar buruk pada 1983, dan devaluasi harus dilakukan, pemerintah mengakui bahwa dia tak mampu meneruskan proyek-proyek tersebut. Pembangunan proyek-proyek besar ternyata harus dijadwalkan kembali -- seperti dianjurkan Sumitro. Ketika pembelian dolar mencapai puncaknya pada awal Maret ini, akibat adanya spekulasi tentang devaluasi, Sumitro, yang tak memegang satu jabatan pun di pemerintahan, bertemu dengan Presiden Soeharto. Seusal pertemuan itu, ia menegaskan bahwa devaluasi tak perlu. Sehari kemudian, arus pembelian dolar mereda, dan kursnya, yang sempat naik beberapa kali, turun kembali. Adakah ini menandakan bahwa Sumitro masih berfungsi lebih dari satu lembaga ekonomi? Empat tulisannya yang terbaru, dua di antaranya bersumber dari ceramah YansJ diberikan di Universitas Indonesia dan Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, keduanya di Jakarta, dikumpulkan dan diterbitkan dalam satu buku oleh LP3ES. Artikel pertama yang belum pernah diterbitkan, mengungkapkan pengamatan Sumitro tentang betapa masih menyesakkannya perdagangan luar negeri bagi negara berkembang. Bagi mereka, perdagangan luar negeri merupakan usaha yang sia-sia, sekalipun dibantu dengan beberapa cara dan teknik tersendiri. Preferensi yang ditawarkan negara industri sudah kehilangan arti karena, dalam prakteknya, pemberian preferensi diutamakan untuk kelompok mereka sendiri. Integrasi ekonomi ke dalam blok-blok perdagangan, seperti ASEAN, tak akan jalan, karena adanya perbedaan kepentingan di antara anggotanya. Sementara itu, kebijaksanaan perdagangan imbal-beli, suatu praktek yang makin meluas kini, dinilainya lebih mahal, tidak efisien, dan malah merugikan, karena sering menyaingi barang ekspor yang sama, yang dijual lewat saluran biasa. Adalah Sumitro yang kurang setuju adanya dikotomi yang dipertentangkan antara "kebijaksanaan ekonomi terbuka" dan "kebijaksanaan ekonomi tertutup", seperti dikemukakan beberapa ekonom. Kebijaksanaan ekonomi terbuka diasosiasikan dengan kebijaksanaan orientasi ekspor, sedangkan kebijaksanaan ekonomi tertutup dengan orientas inndustri substitusi Impor. Yang pertama dianggap sebagai mukjizat yang membereskan semua masalah, sedangkan yang kedua dianggap sebagai biang keladi semua masalah. Sumitro berpendapat bahwa negara yang kini melakukan kebijaksanaan ekonomi terbuka tadinya mungkin juga menempuh kedua kebijaksanaan itu dalam proses yang cukup lama. Masalah proteksi industri dalam negeri masih terus menimbulkan pro dan kontra di antara para menteri. Masalah ini juga disorot secara khusus oleh Bank Dunia dalam laporannya tentang ekonomi Indonesia tahun lalu. Tak heran kalau Sumitro perlu membahas secara panjang lebar masalah ini. Tema yang dikemukakan memang tak berbeda dengan apa yang sering diperbincangkan. Proteksionisme di Indonesia sudah menjurus terlalu jauh, dan sudah ke tingkat yang cukup memanjakan beberapa industri. Proteksi paling besar ternyata dinikmati oleh industri yang sudah mapan. Dan, beberapa distorsi yang diakibatkannya telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sumitro mensinyalir bahwa para pejabat masih kurang mengerti beda antara proteksi nominal dan proteksi efektif. Dia menyarankan diadakannya lebih banyak diskusi di antara pejabat tentang masalah ini. Sumitro juga menyesalkan argumen "kelebihan kapasitas" dan "pasaran sudah jenuh", yang selalu dikemukakan asosiasi industri untuk memperoleh perlindungan dari impor. Sebuah pertanyaan mendasar, menurut Sumitro, harus dikemukakan: kejenuhan pasar ini terjadi pada tingkat harga berapa dan struktur biaya yang bagaimana ? Yang terjadi kemudian adalah pembatasan kuantitatif impor beberapa jenis barang dilakukan tanpa pertimbangan ekonomi yang jelas. Sumitro, yang mengarang beberapa buku teks tentang Ekonomi Pembangunan, selalu melihat masalah kebijaksanaan ekonomi dalam kemampuannya untuk menciptakan penyesuaian struktural. Bagi Sumitro, pembangunan ekonomi tak lain adalah perombakan struktural. Karena itu, setiap kebijaksanaan, apakah dilakukan Indonesia di bidang perdagangan luar negerinya, ataukah dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia dalam menyalurkan bantuan ke Dunia Ketiga, haruslah mengarah kepada tujuan ini. Kebijaksanaan yang mengarah pada penyesuaian struktural hanya bisa diformulasikan lewat sebuah strategi jangka panjang yang konsisten. Kebijaksanaan ekonomi di banyak negara dilihat Sumitro lebih banyak merupakan respons jangka pendek, tanpa strategi jangka panjang yang jelas. Buku ini memang belum menjawab beberapa pertanyaan yang mengganggu akhir-akhir ini. Apakah APBN, kalau perlu, dilakukan dengan pembiayaan defisit? Bagaimana sebenarnya pemerintah memandang peranan sektor swasta? Apakah inisiatif untuk eksperimen dan dobrakan-dobrakan baru harus dikorbankan demi menjaga stabilitas moneter? Membaca buku ini, lalu membandingkannya dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita sekarang, memang menimbulkan rasa khawatir. Jangan-jangan kumpulan tulisan Sumitro ini akan menjadi suara sia-sia seorang ekonom tua, yang berdiri di pinggir lapangan sambil menyaksikan para pemain beradu kekuatan. Barangkali dia juga gundah melihat kebijaksanaan ekonomi Indonesia tidak lagi menjadi monopoli para ekonom. Winarno Zain
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini