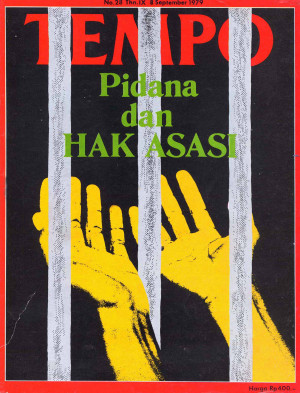THE DEER HUNTER
Sutradara: Michael Cimino
SEKELOMPOK orang duduk khidmat di sekitar meja. Dengan suara
lirih tapi ikhlas mereka menyanyi God Bless America. Sebuah
rasa syukur tentang sebuah tanahair -- itulah adegan penutup The
Deer Hunter.
Dalam film yang bercerita tentang sejllmlah pemuda Arnerika yang
berperang di Vietnam, akhir seperti itu bisa membikin kita ingin
mendehem, setengah tidak percaya bahwa film ini tidak dibikin
oleh semacam PFN-nya Washington. Atau kita teringat tentang John
Wayne ang baru saja mati--meskipun ia sempat memberikan piala
Oscar buat The Deer Hunter sebagai film terbaik 1978.
Superpatriot John Wayne tiap pagi berterimakasih kepada Gusti
Allah karena ia dilahirkan sebagai orang Amerika, dan karenanya
ia membuat film superpatriotik berbau propaganda seperti The
Alamo dan The Green Berets. Kini tidakkah sutradara Michael
Cimino hanya kelanjutan John Wayne dengan nada yang lebih
rendah?
Bagi seorang Indonesia, tentu tak ada salahnya patriotisme. Ada
sesuatu yang indah dan berharga di situ--baik selama ataupun
setelah bulan Agustus. Karena itu juga ada sesutu yang indah
dalam The Deer Hunter. Tetapi keindahannya tetap dalam kategori
kecengengan yang halus. Terasa bahwa ia akhirnya hanya semacam
penghibur bagi luka hati orang Amerika setelah perang terpahit
dalam sejarah mereka itu.
Film ini tidak berpangkal pada satu tokoh. Ini adalah cerita
yang bisa dilupakan nama-nama perannya sejumlah kawan erat, para
buruh pabrik baja keturunan Ukrainia dari Clairton, kota kecil
di negeri bagian Philadelphia, yang mengisi hidup dengan
kegembiraan sederhana: minum bir, berburu kijang, berdansa
sampai sempoyongan, berantem, tak begitu dekat dengan cewek
saking intimnya mereka satu sama lain, dan tak dirundung rasa
bersalah secara bertele-tele dalam menikmati hasil kerja mereka
yang bersahaja.
"Non-pribumi"
Juga mereka tak bertele-tele dalam melihat perang di Vietnam.
Keturunan imigran ini, seraya mempertahankan adat "non-pribumi"
mereka di tengah Amerika yang luas, adalah sejumlah patriot
kecil. Mereka ikut ke Vietnam dcngan antusiasme secukupnya.
Adakah para patriot kecil itu abai dalam soal moral? Tidak. Tapi
moral, bagi pemuda buruh dari kota kecil ini, tak ada
sangkut-pautnya dengan perkara hak Amerika untuk berperang, satu
soal yang bagi mereka pasti terasa dibikin-bikin. Moral, bagi
mereka ini, adalah setiakawan. Brutalnya perang, kejamnya
orang-orang yang telah dikorek perikemanusiaannya oleh
lalulintas peluru, oleh bangkai dan kekuasaan, hanyalah
latarbelakang. Latar itu justru memberikan aksentuasi pada
pentingnya setiakawan yang mendasar.
Maka hantu yang paling mengerikan bukanlah perang itu sendiri,
melainkan sebuah permainan judi yang paling laknat: rulet Rusia.
Dalam permainan ini kita tahu, sebuah pistol enam peluru
dikosongkan slindernya, lalu diisi dengan cuma sebutir pelor.
Seseorang harus menempelkan ujung laras pistol ini ke pelipisnya
sendiri, dan menarik picu. Satu dari enam kemungkinan si pistol
bisa meledak Satu dari enam kemungkinan orang itu akan berlobang
di kepalanya.
Demikianlah yang terjadi ketika para prajurit Amerika itu
tertangkap pasukan Vietkong, dan sepasang demi sepasang harus
memainkan rulet Rusia untuk dirinya. Artinya, sepasang demi
sepasang mereka harus menyadari: bila pistol tak meledak di
pelipis saya, ia mungkin sekali akan meledak di pelipis kawan
saya. Keselamatan seseorang akan makin mendekatkan kematian bagi
kawannya. Tak ada yang lebih melantakkan solidaritas ketimbang
nasib seperti itu.
The Deer Hunter toh akhirnya berkisah bahwa Michael (Robert de
Niro) berhasil melawan nasib dan kemestian ini--dan terus
melawannya. Ia mengatasi kelemahan manusia, kelemahannya sendiri
dan sahabat-sahabatnya.
Syahdan, seorang sahabatnya -- dalam guncangan jiwa yang parah
--meneruskan diri jadi barang taruhan perjudian maut itu di
dunia dekaden bawah tanah Saigon. Michael mencoba menariknya
kembali. Tapi ia berhadapan dengan kenyataan: maut akhirnya
adalah milik masing-masing. Kegembiraan pada saat kita terlepas
daripadanya bisa juga jadi semacam candu bagi masing-masing.
Sahabat itu mai di seberang mejanya, dengan pelipis berlobang
dan berasap--sementara di sekitar para petaruh berteriak-teriak
terus, mengacung-acungkan uang terus. Seperti nimpi buruk.
Menyepelekan Sejarah
Perang Vietnam dalam film ini akhirnya juga sebuah mimpi buruk.
Orang-orang Clairton itu pulang dengan seorang mati dan seorang
lagi kehilangan kaki. Semua dipulihkan kembali oleh Michael,
oleh persahabatan dan patriotisme sederhana.
Semacam Komedi Manusia karya William Saroyan, novel tentang
keluarga yang ditinggal mati seorang anak dalam Perang Dunia
ke-I? Tidak. Saroyan berbicara dengan mengharukan kepada setiap
orang. The Deer Hunter agaknya cuma efektif berbicara kepada
khalayak Arnerika. Kita yang berada di tahun 1979 di Indonesia
(dan hanya memperhatikan perang di Vietnam dengan jarak
emosional), tak cukup dibikin terharu. Juga tak cukup dibikin
marah.
Jane Fonda, wanita bersuara lantang itu, yang atas nama moral
memihak Vietnam Utara dan mengecam negerinya sendiri, mengutuk
The Deer Hunter sebagai cerita perang yang "rasialis", suatu
versi Departemen Pertahanan Amerika. Pekikan Fonda termasuk
hal-hal yang sebagai orang Indonesia tak teramat kita fahami.
Tapi juga tak begitu kita fahami pemikiran sutradara Cimino,
untuk tidak menampilkan permainan rulet Rusia bukan sebagai
sesuatu yang simbolis, melainkan historis. Ia dengan demikian
menyepelekan sejarah yang sebenarnya bahwa perang Vietnam
bukanlah cuma kekejaman sepihak.
Tapi barangkali film ini hanya suatu ikhtiar, ketika orang
Amerika ingin mengenang Perang Vietnam tanpa suara John Wayne,
atau Jane Fonda. Rupanya di luar film macam Superman dan Star
Wars, film-film Amerika -- bersama guncangnya zaman studio besar
serta meluasnya flm TV--kian ditujukan buat berbicara pada
khalayak yang lebih spesifik. Dan The Deer Hunter adalah contoh
suatu dialog yang bukan milik kita.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini