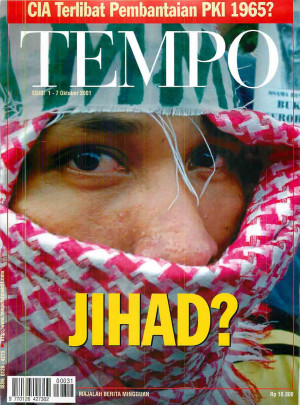PANGGUNG itu terasa begitu luas dan kosong. Hanya seorang perempuan duduk membeku di pojok kanan depan. Cahaya dari atas menerangi wajahnya yang sayu, mungkin menunggu tenaga yang hendak membangkitkannya. Ia tampak begitu terikat kepada meja dan kursi, yang berwarna sama dengan pakaiannya, hijau muda. Seakan perkakas sederhana inilah asal-muasalnya. Ketika musik berhenti, ia bangkit. Inilah pembuka nomor tari berjudul Solo, yang dibawakan sendiri oleh koreografernya, Henrietta Horn.
Nona Horn, 33 tahun, datang bersama kelompok teater-tarinya, Folkwang Tanzstudio, untuk pentas penutup pada Art Summit III, yang selesai akhir September lalu.
Dalam teater-tari (tanztheater), koreografer berupaya membebaskan diri dari gerak indah dan kembali ke gerak sehari-hari, bahkan ke gerak paling kasar dan liar sekalipun. Yang asyik, pembebasan itu tak mungkin terlaksana sepenuhnya, sebab ia telanjur ter-bebani (dan mencintai) khazanah tari. Properti yang sering benda fungsional dalam kehidupan nyata, bukan lagi pelengkap atau ornamen, tapi bagian hakiki dari gerak. Meja dan kursi itu, misalnya, seakan pusat gravitasi di keluasan tak terbatas.
Kita tercekam menunggu apa yang hendak dilakukan si penari untuk mengisi luas panggung. Dengan cahaya yang menyorot efisien dari samping dan atas bergantian, gerak tubuhnya adalah relief hidup, yang muncul dari kegelapan dan kekosongan.
Ia mencoba melepaskan diri dari properti, tapi juga harus bertolak daripadanya. Selang-seling musik dan sunyi seperti menahan irama gerak yang hendak terbangun. Ia bertopang dagu, menjatuhkan dadanya pada meja, menelungkup, bangkit kembali, mendongak ke langit, merentangkan dan menekuk tangan dan kaki, memutar tubuh, dan berpaling. Rangkaian gerak ini diulang-ulangnya sampai kecepatan tertinggi yang bisa dicapainya. Ia lalu berhenti, mengosongkan keliaran yang baru saja menguasai tubuhnya. Kita dapat memandangi ekspresi mukanya yang lega, pasrah, tapi yang segera gelisah kembali.
Nomor sepanjang 25 menit ini adalah penggalian terhadap posisi yang sungguh dasar dalam hidup sehari-hari: duduk, berdiri, dan berjalan. Di dalamnya termaktub gagasan tentang keterikatan dan pembebasan diri. Ada saatnya si penari menjauhkan kursi dari meja. Dan ia mondir-mandir antara dua propertinya seperti mengarungi jalan tak berujung, dengan langkah biasa atau berjinjit. Secara mendadak ia bisa juga merentangkan atau menekuk tubuh: ia memparodikan tari modern. Jika ia lelah, ia menggelantung pada sandaran kursi, atau mengelus-elusnya. Terkadang ia seperti hendak hilang dari pandangan, dan kita kembali tercenung oleh keluasan dan kegelapan.
Namun, panggung yang tak terbatas itu seakan mengerut ketika lampu yang menyala tiba-tiba dari bawah depan membuat bayangan raksasa meja pada layar di latar belakang. Pun siluet sang penari tampak menjadi penari kedua atau sesosok hantu yang menyihirnya. Dalam tingkahan musik dawai dan perkusi membran, keduanya berupaya saling membebaskan, tapi juga bersaing. Sejenak kita tenggelam ke ambang yang nyata dan yang maya. Sungguh permainan terang dan lindap yang nyaris gaib.
Pada koreografi Nona Horn yang kedua, Der Auftaucher (Emerging), sepuluh penari berpakaian hitam dan kelabu itu juga potensi yang siap meledak. Pada awalnya, mereka berdiri dan duduk pada tepi-tepi panggung, seperti saling menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Satu-dua orang merentangkan badan pada sandaran kursi. Suara mendesis giring-giring yang dimainkan seorang penari memenuhi ruang. Ketika seseorang melonjak dari kursinya, yang lain berebut mengikutinya. Sorot lampu dari atas menerangi mereka bergantian.
Ternyatalah para penari mencemburui gerak satu sama lain. Mereka bersaing, namun juga saling menyelaraskan diri. Jika mereka bergerak serentak, satu-dua orang atau pasangan selalu menyebal dari puncak ke-serentakan.
Terkadang mereka tampak sebagai arus yang satu, bergerak padu searah mengisi keluasan panggung, sesaat kemudian mereka menjadi sekian arus yang bertabrakan. Musik (antara lain tango dan gitana) yang merangsang gerak dapat berhenti tiba-tiba, sehingga para penari membeku dalam puncak geraknya. Pada hening itu mereka tampak sebagai orang yang takjub dengan kehadiran kelompoknya, juga kemampuannya menari. Bila tak menari, mereka memindah-mindahkan kursi, seperti menyusun geometri yang bisa mendukung gerak, atau menyediakan sejumput ruang bagi rekan atau saingan untuk unjuk kebolehan.
Pada beberapa momen, Auftaucher adalah parodi terhadap tari modern, tango, flamenco, bahkan tanztheater itu sendiri; juga ter-hadap laku di luar panggung: mencinta, mencemburui, mengejek, menantang. Setiap mencapai keseriusan, pola selalu mencair kembali ke gerak sehari-hari. Menarik kita amati bahwa pasangan penari sama sekali tak bersentuhan badan, sekalipun jarak mereka sudah begitu dekat. Termasuk pada adegan berkelahi antara dua lelaki di pengujung: keduanya hanya bergantian mendoyongkan tubuh ke depan dan belakang. Sementara para penari lain bersorak-sorai, menyarankan suasana pesta rakyat atau permainan kanak-kanak.
Nomor sepanjang 40 menit ini terasa liar namun rapi, eksplosif tapi juga tertib. Panggung yang kosong (kecuali terisi kursi) dan monokromatik begitu menggarisbawahi bahwa para penampil sedang melaksanakan nalar-tari, bukan mengumbar jurus. Pun humor dan kepahitan ternyata terbit dari disiplin gerak. Sunyi, desis giring-giring, ketukan pada kursi, dan musik, adalah pengawal disiplin itu, dan sesekali saja menjadi bumbu pedas.
Bagi saya, pentas Folkwang Tanzstudio adalah pentas tari terbaik dalam Art Summit III. Membandingkan dengan kelompok dari Essen Jerman ini, grup-grup tari yang lain—kebetulan dari Asia—terasa mubazir: ber-indah-indah dalam hamburan gerak, rupa, dan suara. Atau steril, dalam arti masih menghafal kosa bentuk tari modern. Singkatnya, ke-kurangan nalar tari. Apa boleh buat, jika Eropa lebih piawai bermakrifat ketimbang Asia.
Nirwan Dewanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini