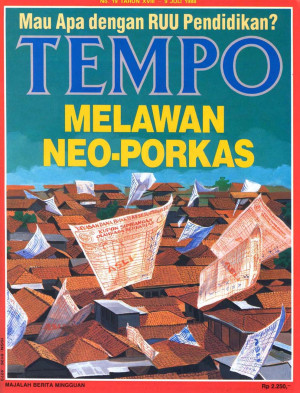Buku ini adalah sebuah contoh, di balik sebuah peristiwa besar selalu ada cerita-cerita, yang bukan sekadar data dan fakta, dari warga negara yang namanya tak bakal dicatat sejarah. Ibu Yang, Ibu Ma, dan Ibu Xiao adalah tiga wanita Guiyang yang digencet Revolusi Kebudayaan di RRC, di zaman Mao. Liang Heng, penulis buku Anak Revolusi -- kisah awal-awal Revolusi Kebudayaan, pernah dikutip di rubrik ini juga -- mewawancarai mereka, kemudian menuliskannya menjadi sebuah buku. Heng menyusun buku itu bersama istrinya, Judith Shapiro, seorang wanita Amerika. SAAT itu, akhir Februari, menjelang tanggal 15 Imlek. Seluruh Kota Guiyang dihias indah dengan lampion-lampion kertas. Ada yang kecil sebesar buah labu. Ada yang besar dan rumit sebesar sapi -- kebetulan tahun itu memang tahun kerbau. Ratusan macam bentuk berhubungan dengan tema itu, dari pasangan tanduk asli sampai balon-balon berbentuk kerbau bergantungan dl mana-mana. Ada juga yang berbentuk pesawat terbang atau roket, sesuai dengan tema Empat Modernisasi. Malamnya lampion-lampion itu dinyalakan. Penduduk kota bermunculan dan berjalan hilir mudik memandangi lampu-lampu itu sambil membaca tulisan-tulisan yang pada bergantungan, dan memberi komentar secara kritis. Peristiwa itu merupakan aneka peragaan kreativitas, dan untuk pertama kalinya perayaan itu diadakan setelah kegersangan budaya selama bertahun-tahun. Pasar bebas Guiyang merupakan satu-satunya daerah tujuan semua warga kota pergi berduyun-duyun. Di pasar itu, orang dapat membeli sepotong kain di satu kios, dan pergi ke kios berikutnya buat mengukur dan menjahitkannya menjadi celana. Di kios lain, orang dapat memilih hak-hak sepatu dengan segala ukuran tingginya, dan memasangkannya pada sepatu sendiri di klos sebelahnya. Warung-warung makanan ringan tak terhitung jumlahnya. Tak terkecuali pedagang racun tikus, jamu, dan tukang-tukang ramal buta yang dapat mengintip nasib. Tapi barang yang paling rnerangsang dari semua itu adalah sekarton fetucine dari Italia, dengan merk dagangnya yang hanya bisa didapatkan di Toko Zabar, New York. Di Guiyang, Judy dan saya tidak punya kawan ataupun sanak saudara. Tapi tak sulit bagi kami untuk mendapat kenalan baru. Tidak sampai satu jam, kami sudah ngomong-ngomong dengan orang-orang dari Jiangxi, Hunan, Shandong, dan Anhui. Di antara mereka ada yang telah mukim di sana selama 50 tahun. Ada pula yang baru 20 tahun. Dari semua teman baru kami di Guiyang ada tiga orang yang benar-benar meninggalkan kesan. Ketiganya wanita. Kami berjumpa dengan wanita pertama tak lama setelah tiba. Kami sedang mencari semangkuk mi, karena Judy sudah lama menjadi vegetarian (tak makan daging). Di Cina, sangat sukar mencari makanan untuk orang-orang semacam dia. Buat orang Cina hanya lemak dan daging babi yang membuat makanan jadi lezat. Persoalannya jadi bertambah sulit, karena orang Cina yakin bahwa orang asing hidup dalam gaya yang lebih hebat dari mereka. Berkali-kali Judy memesan makanan khusus, dan tukang masaknya mengangguk-angguk tanda mengerti selera pemesannya. Tapi hasilnya selalu mengecewakan. Setiap kali kami memesan makanan selalu muncul makanan dengan daging. Setelah beberapa kali gagal, kami pergi ke sebuah warung mi reyot yang terletak di tepi jalan. Kedai itu rupanya banyak dikunjungi para petani setelah hari pasar. Di pintu, saya berusaha menjelaskan apa yang diminta kepada seorang pemuda yang duduk di muka sebuah meja kecil. Ketika saya mengulangi pesanan untuk ketiga kalinya, terdengarlah suara berwibawa seorang wanita. "Ada kesulitan apa?" tanyanya. Pemuda itu menjawab sambil berteriak, "Ada orang Amerika yang ingin makan mi sayur. Tidak pakai daging, tidak pakai vetsin, tidak pakai lemak babi. Tidak pakai segalanya." Terdengarlah kemudian suara dengan nada terkejut, "Orang Amerika? Tak ada masalah, dan gampang." Muncullah seorang wanita setengah baya berpakaian kerja katun biru dan memakai pelindung tangan berpola kembang. Kemudian ia mengeringkan tangannya dengan celemek putih panjang ia rupanya mengerti soal yang kami hadapi, lalu mempersilakan kami duduk, dan menjamin dapat membuat pesanan itu. Ketika ia berjalan kembali ke dapur, kami dengar wanita itu menggumam sendiri, "Aih, ketika kau masih muda bukankah kau pernah membuat beberapa mangkuk mi untuk orang Amerika?" Judy menatap keheranan. Tak lama kemudian terhidang dua mangkuk mi putih dengan bau jahe dan kembang kol ditambah semerbak minyak wijen yang murni dan harum. Wanita itu mengatur makanan di muka kami dan tanpa kami minta mencuci dua pasang sumpit dengan air panas. Kemudian ia menarik bangku kecil dan duduk di sebelah mengawasi kami. Sikapnya seolah-olah menganggap kami teman akrab yang datang berkunjung dari jauh. Ketika ia mengobrol dengan kami, saya mengawasinya lebih cermat. Ketika masih muda, ia pasti sangat cantik dengan mata yang besar. Saya hampir tak percaya ketika ia mengatakan usianya lebih dari 60 tahun. Memang, wajahnya penuh kerutan, tapi itu malah membuatnya indah sehingga kulitnya tampak mulus. Rambutnya masih hitam sedangkan punggungnya masih lurus dan kuat. Keramahannya bertambah ketika saya katakan kepadanya saya berasal dari Changsha. "Orang sekampung," katanya, "dan kawin dengan orang Amerika." Waktu kami mengobrol, sering ia melihat dengan cepat ke sekeliling seakan-akan ketakutan campur waspada, kalau-kalau ada orang lain yang menguping. Itu dilakukan oleh banyak orang sejak Revolusi Kebudayaan. Pelanggan yang masih tinggal ternyata hanya beberapa orang petani yang menghirup keras-keras sisa mi mereka. Kemudian kami tahu ternyata kedai itu miliknya. Ibu Yang, demikianlah namanya, bicara dengan penuh semangat tentang hal-hal yang dikatakannya sebagai kebaikan orang Amerika. Ia mengaku orang yang paling tahu bagaimana sesungguhnya orang Amerika. Pemuda sekarang, katanya, mula-mula dididik membenci orang Amerika, kemudian dengan tiba-tiba diajari menghargai hasil kebendaan yang mereka capai. Mereka mengagumi dunia Barat tanpa pengertian yang sesungguhnya. "Saya mengalami masa perang," katanya. "Ketika pasukan Nasionalis hampir lumpuh, orang Amerikalah yang membantu kami tetap hidup. Aku makan di rumah mereka, atau kadang-kadang mereka yang berkunjung. Dan saya membuatkan mi untuk mereka." Ia tersenyum pada Judy. "Jadi, seperti kalian ketahui, aku mengenal bagaimana orang Amerika." "Apakah suami Nyonya ikut kaum nasionalis?" tanya Judy. Ibu Yang mengangguk cepat. Sekelompok petani menuju ke salah satu meja, dan ia segera berteriak, "Makanan sudah habis." "Sejak kapan Anda membuka kedai ini?" tanya saya. Saya heran tak ada minat padanya untuk menjawab. "Sejak pensiun ?" tanya saya lagi. Ia tertawa pilu, dan menjawab dengan nada sarkastis, "Pensiun dari mana? Dari kerja paksa ? " Makin nyata bahwa itu bukan tempat untuk mengobrol. Ibu Yang menuliskan alamatnya di balik selembar bon. "Aku akan senang kalau kalian bisa datang ke rumahku," katanya. Di luar hari sudah gelap dan lentera-lentera sudah dinyalakan. Kami pergi duluan dan berjalan berkeliling yang cukup jauh buat memberi kesempatan padanya menyelesaikan hal-hal di kedai. Rumahnya dekat dengan hotel kami, dekat jalan menuju bukit di atas sungai kecil. Di puncak bukit berdiri sebuah pagoda kayu tua yang berlumut lantaran kurang perawatan. Di seberang sungai menjulang sebuah gedung aneh gaya Rusia tempat kami bermalam. Ibu Yang menyambut kami dengan hangat. Ia telah menyiapkan kue kuning yang terletak di meja bersama biji bunga matahari, jeruk, dan permen keras. Daun teh sudah ditaruh dalam cangkir porselen putih. Ada rokok Kents, yang pasti dibeli dari pasaran bebas. Ia menawari kami rokok, tapi kami menolak. Ia menyalakan sebatang dan menghirupnya dalam-dalam. Wanita Cina jarang merokok, tapi ia merupakan pengecualian. Ia terbiasa dengan kehidupan bebas, tapi perlu keuletan. Ia mengatakan rumah itu dulu milik suaminya. Ketika Revolusi Kebudayaan datang, dua keluarga lain masuk. Ia terdesak ke sebuah kamar kecil, yang dihuninya sekarang. Sambil berbicara ia membuat gerakan ke sana-kemari. Saya melihat perabotan rumahnya antik, tapi banyak yang sudah rusak di sana-sini. Lemari jatinya diberi kaki kayu mentah sepotong hasil ukiran kecil di meja makan telah hilang. Sedangkan cermin di atas tempat cuci makan telah gompal, dan ada retakan memanjang yang ditambal dengan pita putih tebal. Ibu Yang melihat apa yang saya perhatikan. "Semuanya dikembalikan dengan sedikit-sedikit. Banyak yang telah mereka rampas," katanya. Di seluruh Cina Pengawal Merah bisa saja merampas benda-benda "selera borjuis" milik golongan "reaksioner" dari rumah-rumah golongan intelektual dan "golongan jahat" lainnya. Kini sedang dilakukan usaha mengembalikan benda-benda yang disita itu ke pemilik aslinya. Tentu saja banyak benda pecah, dan tak dapat diperbaiki. Saya jadi teringat pada nasib keluarga saya. Mereka membakar buku dan gambar-gambar gulung milik keluarga kami. Semuanya diletakkan pada sebuah waskom besar dan kemudian dibakar. Saya masih ingat bagaimana lukisan dengan maobi (pinsil bulu) yang berwarna jingga kesayangan saya menyala dimakan api. Ketika Ayah pindah ke perumahan surat kabar, saya menyadari tak ada lagi benda berharga dari masa lalu yang tertinggal. Saya meneguk teh hijau yang harum itu sampai habis, dan kemudian bertanya tentang keluarganya. Ia termangu. "Ada sesuatu yang tak dapat lagi kembali," katanya pilu. Seperti kami duga cerita itu muncul lagi. Ia berasal dari Changsha dan dinikahkan lewat perantara dengan seorang pemuda yang diperkirakan akan punya masa depan yang gemilang. Ia adalah seorang putra tuan tanah terkemuka. Suaminya itu kemudian masuk tentara, dan sejak itu selalu ke mana-mana untuk menggempur Jepang dan kaum komunis. Ibu Yang menjalani kehidupan bagaikan seorang janda. Tahun 1938, ketika Changsha dibakar, ia ditinggal sendirian untuk menghadapi kekejaman Jepang. Ia masih berbicara tentang para penyerbu itu dengan penuh kebencian. Meski ia tak mengatakannya, saya yakin ia telah diperkosa. Setelah perang melawan Jepang selesai, suaminya ditempatkan di Guiyang, dan pangkatnya naik jadi jenderal. Kota itu penuh dengan keluarga kaum nasionalis. Begitu kaum nasionalis dikalahkan batalyon suaminya termasuk di antara mereka yang menyerah kepada kaum komunis. Karena itu, ia dan suaminya diperlakukan lebih baik ketimbang mereka yang terus melawan. Mereka bahkan hidup cukup baik setelah "pembebasan". Tak lama kemudian ia melahirkan seorang anak yang diberi nama Xiao Hua. Tapi suaminya tak diperkenankan bekerja. Buat menunjang kehidupan keluarga, ia terpaksa bekerja sebagai pembersih meja pada sebuah restoran pemerintah. Tapi tak lama kemudian hinaan yang lebih besar datang menimpa. 16 Mei 1966 Revolusi Kebudayaan dimulai. "Ketika itu bagaimana aku dapat mengetahui bahwa tragedi besar akan menimpa kami?" tanyanya lirih. "Bagaimana aku dapat mengetahui aku harus memendam amarah selama 10 tahun lamanya dalam hatiku?" Suaminya, yang telah menempur kaum komunis selama bertahun-tahun, punya naluri lebih baik tentang apa artinya kampanye terhadap kaum reaksioner itu. Sementara Ibu Yang pergi ke Komite Lingkungan (semacam RT di sini) untuk mendengarkan pembacaan dokumen tentang kediktatoran proletar terhadap "musuh kelas", ia tinggal di rumah karena menderita demam berat. Ketika kembali, Ibu Yang mendapatkan suaminya masih duduk di meja dengan muka pucat dan berkeringat sambil memeluk radio. "Segalanya sudah berakhir," katanya kepada istrinya dengan wajah ketakutan. "Oh, Tuhanku, semuanya sudah berakhir untuk keluargaku," ujarnya lebih lanjut. Malam itu, suaminya sakit keras. Ia terus mengigau karena demamnya, dan meninggal menjelang fajar. Sebelum badai menerpa, ia sudah mati ketakutan. Ibu Yang menghela napas. "Tentu saja ia beruntung," katanya. Bersama dengan xiao Hua, yang berusia 16 tahun, ia menghadiri satu pertemuan kritik ke pertemuan kritik lainnya. Bagi Ibu Yang masalahnya mudah. Ia sering boleh tinggal di rumah, dan datang ke rapat-rapat kalau di undang. Kewajibannya hanyalah menuduh diri sendiri kalau diminta. Revolusi Kebudayaan justru memukul para siswa, dan tekanan terhadap Xiao Hua makin berat. Setiap hari ia diperintahkan "menarik garis pemisah" antara dirinya dan ibunya yang bekas Kuomintang. "Ia gila dengan kebencian terhadapku," kata Ibu Yang tanpa sadar telah menceritakan kesedihannya. Gadis itu diperintahkan agar setiap malam menulis artikel yang mengungkapkan tentang ibunya, dan harus dilaporkan ke sekolahnya dan ke Komite Lingkungan. Hubungan keluarga di rumah menjadi begitu tegang. Mereka tidur sekamar, tapi tidak saling menegur. Itu berlangsung selama beberapa bulan. "Setiap malam aku dapat mendengar kegelisahannya di tempat tidur. Ia menangis dalam mimpinya. Kadang-kadang ia terbangun dan berteriak-teriak. Mula-mula aku berusaha menenangkan, tapi ia malah marah-marah. Di dalam tidurnya ia mendakwa saya." Ibu Yang menyedot rokoknya dalam-dalam dan sesaat menatap ke luar jendela ke arah cahaya kelabu yang datang dari arah hotel. "Akhirnya aku takut padanya." "Kemudian pada suatu malam aku mendadak terbangun. Kamar terasa amat senyap. Aku bangkit untuk melihatnya. Tempat tidurnya kosong, dan selimut wolnya terlipat rapi. Di lantai berserakan kertas-kertas yang penuh dengan tulisan tangan pengakuannya malam itu. Jendela masih terbuka, dan di meja ada botol pestisida yang sudah kosong." Ibu Yang mengelap matanya yang basah dengan penuh kemarahan. "Aku menghabiskan waktu semalaman untuk mencarinya sepanjang tepi sungai sambil memanggil-manggil namanya. Tak ada yang mau membantu. Keesokan harinya mayatnya ditemukan di pipa pembuangan pabrik." Judy menjulurkan tangannya lewat meja dan meletakkannya di atas tangan Ibu Yang. Ia senang mendapat hiburan itu, dan melanjutkan ceritanya dengan air mata tetap berlinang. "Tahukah kalian, aku menyalahkan diriku. Dalam pikiranku aku mengulangi peristiwa itu sebanyak ribuan kali. Mengapa aku tak bangun lebih dini ? Mengapa aku tak mengetahui bahwa ia begitu nekat? Mengapa aku tak mencegahnya? Semua bagaikan mimpi buruk yang diputar berulang-ulang. Setiap kali pergi tidur, aku teringat pada selimut wol yang terlipat rapi dan jendela yang terbuka." Ibu Yang tampak kelelahan. Saya dan kakak-kakak saya, karena alasan yang sulit diketahui, tidak mengambil pilihan seperti yang diambil putrinya. Tapi saya telah memperlakukan ibu saya yang dicap kontrarevolusioner, ayah saya yang mendapat cap jurnalis borjuis, dengan cara yang sama. Mimpi buruk itu telah berlalu dan ketakutan telah lewat, tapi bagaimana parut luka Ibu Yang danribuan keluarga Cina lainnya dapat disembuhkan? Kasih sayang yang seharusnya kami terima, pengertian dan dukungan yang harus kami berikan, semuanya adalah kesenjangan terlalu lebar yang takkan terisi selamanya. Selama 10 tahun berikutnya, Ibu Yang melanjutkan, ia menjalani kehidupan yang penuh penghinaan. Komite Lingkungan mengatur agar keluarga-keluarga dengan latar belakang buruk tak dikirim bekerja dalam brigade pemetik kubis di pedesaan. Sementara mahasiswa dan buruh berkelahi di antara sesamanya dengan menggunakan bedil, granat, dan tank, ia harus menghabiskan waktunya dengan bermandikan kotoran. Kebanyakan orang yang ada dalam brigadenya adalah bekas Kuomintang, tapi ia tak mempercayai siapa pun. "Sepuluh tahun," keluhnya. "Perut yang penuh dengan amarah ini tak dapat memuntahkannya. Kau tak boleh bergerak, kau tak boleh berbicara, kau tak boleh menunjukkan sedikit pun perubahan pada wajahmu. Setiap orang memata-matai dan dimatai-matai. Malam-malam mereka memecahkan kaca jendelaku dan mengencingi tempat tidurku sambil berteriak: lonte Amerika." Bentrokan-bentrokan di Guiyang selama Revolusi Kebudayaan amat terkenal. Lebih hebat dari yang terjadi di Changsha. Pelayan hotel kami bahkan takut untuk menceritakannya kembali. Berapa yang mati? Sepuluh ribu atau lebih dari itu? Tak ada yang tahu dengan pasti. Bahkan rezim sekarang yang berkuasa pun takkan pernah mengadakan penyelidikan tentang itu. Terlalu banyak dari anak-anak mereka yang menjadi Pengawal Merah radikal. Saya amat terharu akan keberanian Ibu Yang mempercayai kami, dan bercerita tentang penderitaannya. Tapi kami tak mau terus membiarkannya tenggelam dalamkemurungannya, selagi malam makin larut. Karena itu, pembicaraan kami alihkan pada warung mi miliknya. "Apa arti warung mi itu untukku?" ujarnya dengan sikap kebanggaan pra-1949. "Aku, yang dulu pernah makan dalam jamuan-jamuan dengan para Jenderal, sekarang melayani para petani dengan mi. Tapi apa pula pengetahuan seorang wanita umur 60-an untuk menjadi kaya?" Ibu Yang mengakui, sejak Revolusi Kebudayaan berakhir kehidupan orang-orang bekas Kuomintang jauh lebih baik. Sebagai tambahan atas perabotan rumah yang dikembalikan, gaji-gaji dibayarkan kembali. Karcis bioskop khusus kini dibagi-bagikan kepada keluarga-keluarga. Para pejabat menilai kembali kematian anaknya yang dulu disebut sebagai "bunuh diri menghindari hukuman" dan diganti dengan "mati karena siksaan". Demam bisnis timbul. Tapi tak mudah bagi Ibu Yang untuk terjun ke dalam usaha pribadinya itu. Buat memperoleh izin ia terpaksa melalui pintu belakang. Menjilat saja tak cukup, tapi harus juga tahu bagaimana menyampaikan bingkisan ke tangan birokrat yang benar. Ia punya seorang kenalan yang kenal dengan keluarga seseorang di kantor pengurusan bisnis lokal. Untuk itu ia harus mengundang kenalannya tersebut makan malam, dan menyampaikan maksudnya dengan cara tak langsung. Kenalannya itu kemudian menyampaikan apa yang diinginkan Ibu Yang sambil mempersembahkan bingkisan khusus darinya. Seluruh urusan itu merupakan jaringan komunikasi kompleks yang perlu waktu berbulan-bulan. Sesudah warung dibuka, kesulitan lain muncul lagi. Kacang hitam yang lezat dan saus bawang putih buatan Ibu Yang serta sikapnya yang hangat dengan meja yang bersih telah menarik banyak pengunjung datang ke warungnya. Segera saja penghasilannya melambung sampai 300 yuan per bulan. Keberhasilan ini menyebabkan warung milik pemerintah ditinggalkan langganannya. Lalu, seseorang menulis laporan kepada bagian urusan perdagangan, dan menuduh Ibu Yang berusaha membuktikan kapitalisme lebih baik ketimbang soslalisme. Tapi Ibu Yang tak takut lagi. Ia telah banyak membaca koran. Ketika para penyelidik datang, ia menyiapkan mi dengan berpura-pura tak tahu siapa mereka. Setelah mencicipi saus kacang hitamnya, mereka bahkan memberi pujian dengan piagam tertulis. "Piagam itu aku bingkai dan digantung di restoran. Sejak itu aku aman." Tiba saatnya bagi kami untuk pergi. Di luar semuanya senyap kecuali bunyi air selokan. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada Ibu Yang. Pewaris-Pewaris Islam di Guiyang KAMI diberi tahu bahwa di Guiyang ada sekumpulan orang Hui yang beragama Islam, dan juga sebuah masjid. Kami ingin tahu, dan memutuskan buat menemukan mereka. Beberapa kali kami mendapat petunjuk yang salah, sampai akhirnya kelihatan sebuah kubah besar berwarna biru kelihatan dari jauh. Ada sebuah pintu kayu yang terletak di ujung lapangan kecil yang dinamakan Lorong Persahabatan. Saya tak tahu mengapa dan sejak kapan itu dinamakan demikian. Pintu itu terkunci. Baru setelah kami membunyikan lonceng berulangulang, akhirnya seorang gadis kecil kira-kira berusia 15 membukakan pintu. Ia mengatakan Imam Wang sedang sakit, dan di rumah tak ada orang lain kecuali ayahnya. Setelah lama kami membujuknya, barulah ia membiarkan kami masuk. Sebuah lorong batu yang membuka ke langit membawa kami ke pekarangan. Ayah gadis itu, yang ternyata anak Imam Wang, duduk di sebuah bangku kecil, mencuci kemejanya. Umurnya menjelang 30. Gayanya seperti orang Han saja. Ia bahkan tak mengenakan topi putih ciri orang muslim Hui. Ia tampak kebingungan menerima kami. Tapi, ketika kami katakan kami orang asing, ia gembira, lalu membawa kami berkeliling ke ruang sembahyang dan gedung utama. Sambil berjalan, ia mengatakan dengan bangga bahwa departemen urusan bangsa minoritas provinsi telah menyediakan 240.000 yuan buat memugar masjid yang bergaya arsitektur Hui itu. Tapi kami kecewa lantaran dibandingkan dengan masjid yang pernah kami lihat di Kunming, masjid itu sangat lengang. Juga ruang sembahyang yang sudah selesai dipugar kosong dari orang. Ketika kami berdiri di lantai atas sambil memandang Kota Guiyang, pemuda itu mengatakan ia ditarik dari tugas militer dan diberi tanggung jawab baru untuk mengelola masjid tersebut. Ia tak tahu banyak tentang Islam, kecuali peraturan orang muslim dilarang makan babi. Itu tak menjadi masalah lantaran pekerjaan utamanya bagaikan seorang pegawai hotel. Bangunan utama bertingkat lima di kompleks masjid itu berfungsi juga sebagai hotel. Setelah selesai berkeliling, kami tanyakan kepada Wang muda apakah di kota itu ada diskriminasi terhadap orang Islam dan Hui. Ia menjawab, perlakuan khusus, yang katanya diberikan pada mereka, hanya di kertas. Contohnya, sebuah keluarga Han tinggal di lantai atas restoran orang Hui. Setiap hari keluarga Han itu masuk membawa daging babi melalui ruang makan dan dapur restoran tersebut. "Itu menyakitkan hati," katanya. Selesai bicara dengan Wang muda, kami memutari sudut halaman belakang untuk keluar. Di sana kami menjumpai seorang wanita sedang menyapu. Usianya 40-an. Ia mengenakan topi putih, seperti yang dipakai pegawai restoran. Ketika melihat kami, ia menanyakan dengan ketus kalau tidak untuk bersembahyang buat apa datang ke situ. "Kelihatannya kalian bukan dari sini," katanya ketika melihat mantel bulu yang saya beli di Changsha. Ia makin heran ketika melihat Judy, yang semula dikiranya orang Uighur. Ketika kami katakan bahwa kami tinggal di luar negeri, ia kegirangan. "Pernahkah kalian pergi ke Mekah?" tanyanya. Saya saling menatap dengan Judy. "Belum," jawab saya. Judy pun menambahkan, "Kelak mungkin kami akan mendapat kesempatan." Mendadak ia jadi ramah. Atas undangannya kami duduk di bangku kayu sambil minum teh panas. Tak lama kemudian kami terlibat dalam percakapan asyik. tapi dia lebih banyak bercerita tentang dirinya. Ia berasal dari Kota Shadian, Yunnan. Leluhur bangsa Hui datang dari Asia Tengah, dan selalu setia terhadap tradisi keagamaan mereka. Di Yunnan mereka hidup dengan daai. Revolusi Kebudayaan kemudian merusakkan segala-galanya. Masjid Shadian di bakar Pengawal Merah. Segala benda yang berhubungan dengan keagamaan diambil atau dirusakkan. Imam mereka dihina dan diseret ke kota. Mereka tak pernah melihatnya lagi. Setelah itu, tim propaganda datang, dan mengajarkan agar setiap orang jadi bangsa Han. "Tapi, dengan diam-diam kami menentang. Di rumah, kami tetap salat, dan menyucikan diri," kata wanita dari keluarga Ma itu. Perjuangan bangsa Hui justru terjadi pada 1975 ketika keadaan di Cina secara umum sudah aman kembali. Mereka dipojokkan di luar batas kesabaran mereka, ketika sekretaris partai di Kota Shadian, yang berpenghuni 800 keluarga itu, berusaha memaksa orang Hui makan babi. Ketika ditolak, ia melemparkan kepala seekor babi ke pekarangan mereka, dan kemudian menceburkannya ke sumur mereka. Air sumur mereka kena najis, dan tak ada pilihan bagi mereka kecuali bertindak. Sekelompok pria pergi ke rumah sang sekretaris dan mengancamnya. Ia melarikan diri, dan ketika kembali membawa sekelompok tentara untuk mengintimidasi orang-orang Hui. Penduduk malah makin marah dan memukuli serdadu-serdadu itu. Tak lama kemudian partai mencap seluruh kota kecil itu sebagai pemberontak, dan Tentara Pembebasan Rakyat yang bersenjata lengkap pun datang. Orang Hui melawan dengan senjata-senjata curian. Tapi mereka bukan tandingan untuk melawan tentara profesional. "Pertempuran berlangsung dengan singkat," kata Ibu Ma. "Suami dan anak-anakku terbunuh pada hari pertama. Ratusan lainnya mati tertembak. Banyak dari mereka yang kehilangan nyawa, karena membawa granat dan menjatuhkan diri di antara musuh. Mereka adalah pahlawan perjuangan bangsa Hui untuk mempertahankan agama mereka." tambah Ibu Ma. Apa yang terjadi di Shadian memang jauh lebih seru dibandingkan dengan di tempat-tempat lain. Hanya sedikit orang yang berhasil lari dari Shadian. Seluruh kota disapu bersih, begitu pula desa-desa di sekitarnya. Ribuan orang mati terbunuh. Ibu Ma sekarang sendirian di dunia ini. Karena takut dikejar-kejar, ia tak tahu akan ke mana. Mulanya ia hanya berjalan pada malam hari, dan mengemis dari petani, yang memberinya makanan dan ubi. Tapi sebagian lagi melepaskan anjing mereka untuk menakut-nakutinya. Akhirnya, ia menemukan jalan ke Kumning, ibu kota provinsi. Pada mulanya, ia bertemu dengan para pengemis yang mangkal di sekitar restoran menunggu sisa-sisa makanan bekas tamu. Pernah seorang pcngemis lain hendak menjualnya kepada orang, tapi ia berhasil melarikan diri. Setelah kematian Mao dan tergulungnya Komplotan Empat pada 1976, ia memberanikan diri naik kereta api ke Guiyang. Di kota itu, ia punya saudara sepupu. Keluarga sepupu itu menyembunyikannya selama beberapa bulan. Ibu Ma menarik napas dalam-dalam. "Ada kesenjangan besar antara janji kebebasan dan prakteknya," katanya. "Satu hal yang baik adalah masjid kami dipugar. Suatu hal yang baik juga bahwa orang-orang muda dihimpun untuk menggantikan para Imam. Tapi saya sangsi akan kebisaan orang-orang muda itu." Ia mengambil contoh Wang muda yang baru saja kami ajak bercakap-cakap. "Ia seorang anak baik. Tapi sangat menakutkan kalau ia kelak jadi imam kami," katanya. "Masjid ini kini telah menjadi kehidupanku dan penghiburku," katanya lirih. "Aku tak punya apa-apa lagi, tapi itu saja sudah cukup. Genangan darah itu masih belum kering untukku." Setelah Revolusi hebudayaan 28 Hari KE mana pun pergi, kami selalu mencari kelompok dansa. Bukan karena kami senang berdansa, tapi sasana dansa di suatu tempat merupakan barometer akan setiap pernyataan kebebasan secara umum. Di Guiyang, poster-poster yang mengumumkan adanya pesta-pesta dansa menempel di mana-mana. Kami memilih yang diselenggarakan oleh Kelompok Nyanyi dan Tari Provinsi, karena Judy sendiri adalah seorang penari balet yang serius. Bahkan ia bersahabat dan berhubungan erat dengan anggota-anggota kelompok sendratari Hunan. Kami masuk setelah membayar dua yuan setiap orang. Band sedang memainkan musik ringan. Musik semacam itu amat umum di Cina. Tapi, selama kampanye antipolusi spiritual, pada musim gugur 1983, musik itu dicap "melemahkan semangat kaum muda". Saya menarik dua kursi. Supaya tak terlihat mencolok, kami duduk di belakang band. Tapi Judy sudah telanjur ketahuan sebagai orang asing. Seorang wanita setengah umur datang dan mengajaknya berdansa -- di Cina, dansa sesama jenis umum saja. Wajahnya bulat gemuk dan rambutnya, meski dikeriting, sudah bercampur uban. Dia mengenakan jaket kulit imitasi dengan risleting buatan Cina. Menurut etiket, Judy tak boleh menolak, maka tak lama kemudian mereka sudah berputar-putar dalam irama waltz yang rendah. Saya hampir tak melihat Judy beristirahat sepanjang malam. Baru ia hendak berjalan mendekati saya, seorang lain datang mendekat. Rupanya, setiap orang ingin berdansa dengan orang asing. Wanita yang pertama mengajak Judy berdansa datang lagi. Ia duduk di sebelah saya, dan banyak bertanya tentang saya. Ia makin tertarik ketika saya katakan bahwa kami sudah menikah. Rupanya, ia telah membaca tentang kami dari majalah hiburan Setelah Delapan Jam. Saya pikir hidup wanita itu sangat urakan. Jarang wanita seusianya mengenakan pakaian semacam itu. Juga sangat tak biasa di Cina, karena dia datang ke pesta dansa tanpa pengantar. Sikapnya agresif, tapi mengasyikkan sehingga agak sukar juga untuk menolaknya. Saya katakan pada diri saya bahwa saya bisa tahu banyak darinya tentang keadaan baru di Cina, dan bagaimana pendapatnya. Saya membelikan bir untuk Ibu Xiao, wanita yang mengajak Judy berdansa itu. Kata Ibu kiao, baru tahun lalu mereka bisa bebas mengadakan pesta dansa. Keadaan negara "dikekang" dan "dilepas" secara bergantian. "Selama gerakan antipolusi spiritual," katanya. "mereka menangkapi banyak hanya karena kesalahan-kesalahan kecil, seperti apa yang perbuat sekarang." Betapa seringnya kami mendengar kampanye yang diceritakan dengan campuran antara humor dan kepahitan. Tujuh tahun seteah kejatuhan Komplotan Empat, kampanye antipolusi spiritual itu singkat, tapi gemanya cukup mengerikan. Kejadian dengan cepat dijuluki "Revolusi Kebudayaan 28 Hari", meski sebenarnya berjalan sekitar dua bulan. Itu dimulai oleh suatu sidang Dewan Propaganda Komite Sentral Partai pada musim panas 1983. Di Guiyang, cerita Ibu Xiao, waktu itu orang tak bisa melintas di jalan dengan mengenakan celana cutbrai tanpa menjadi sasaran gunting petugas sekuriti umum. Pria juga tak boleh berambut gondrong. Mereka yang mengenakan sepatu bertumit tinggi, tumit sepatu itu akan dipatahkan polisi. Blue jeans dianggap lambang polusi spiritual, begitu juga bersolek, minyak wangi, dan Hampir semua yang dipengaruhi Barat tidak aman. Ia sendiri hampir mendapat kesulitan besar. Ia, ceritanya, dengan sekitar 200 temannya senang mengadakan pesta dansa. Tapi mereka dituduh sebagai jituan -- gang pengacau yang beroperasi tanpa restu pemerintah. Pokoknya, ia yang tak bisa mereka kendalikan dituduh sebagai unsur yang dapat menggulingkan Partai Komunis. Ia tertawa. "Apa yang mereka sebut pornografi mungkin takkan mengejutkan buat seorang anak berusia sembilan tahun di Barat. Tapi di sini segalanya adalah politik." Karena kami ingin banyak mendengar cerita dari Ibu Xiao, ia di bawa masuk ke hotel dengan cara menyelundupkannya. Di hotel Ibu Xiao makin banyak omong dan kisah hidupnya nyembur bagaikan pancuran. Dulu, ia bersuamikan seorang buruh di pabrik yang mencetak kotak kertas. Selama Revolusi Kebudayaan, segala yang dicetak, mulai dari kotak kemas pasta gigi sampai kardus rokok, diberi kutipan karya-karya Mao. Pada 1967, seseorang di pabrik melakukan kesalahan tragis. Slogan patriotis memuji Ketua Mao, Wanshou Wujiang (hidup sepuluh ribu tahun), telah salah cctak. Huruf wan tertukar dengan huruf u, yang bentuknya hampir sama, sehingga berarti "Ketua Mao hidup tanpa tahun". Meski para penyelidik tak pernah tahu siapa yang bersalah, suami Ibu Xiao, yang ketika itu bertugas, dimintai tanggungjawab. Ia ditahan dan dikritik. Hanya karena ada keraguan ia tak ditembak. Ibu Xiao menolak menceraikannya, sehingga ia dipecat dari pekerjaannya. Ia menjadi anggota "masyarakat hitam", kelompok terbuang, mereka yang tanpa keanggotaan organisasi. Terpaksalah ia berganti-ganti pekerjaan -- mulai dari pengumpul bekas kotak pasta gigi, memelihara lebah, sampai menjadi pengemis. Waktu mengemis itulah ia pernah ditangkap. Dua tahun setelah suaminya ditangkap, Ibu Xiao mendengar suaminya mati di penjara. Tak diketahui penyebab kematiannya sakit, dipukuli, atau kelaparan. Ibu Xiao tak berharap lagi untuk bekerja buat pemerintah. Mana mungkin ia mendapat suami lagi kalau dengan hanya melihat latar belakang hidupnya orang sudah tak berminat padanya. Kalaupun mendapat suami, siapa yang menjamin ia bukan kontrarevolusi? "Kini semuanya telah kutinggalkan," katanya. "Yang ingin kulakukan sekarang adalah terjun ke dunia bisnis." Judy bertanya, "Bisnis apa yang Anda maui?" Ia menjawab ingin menjadi pemandu wisata dan bergaul dengan orang asing. Ambisi yang tak praktis. Bisnis turis yang menjadi salah satu sumber utama devisa negara masih dikontrol ketat. Lagi pula, Guiyang bukan pusat wisata, dan tak mungkin banyak orang asing datang ke sana dalam waktu dekat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini