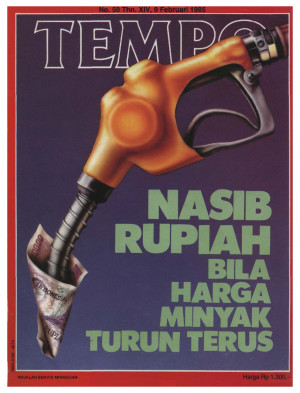BOJONEGORO 1900-1942 Oleh: Dr. C.L.M. Penders Penerbit: Gunung Agung, Singapura, 1984, 144 halaman SEJARAWAN C.L.M. Penders adalah warga negara Australia asal Belanda, yang sekarang menetap di Brisbane. Salah satu karangannya adalah biografi Presiden Sukarno. Kini ia menulis keadaan ekonomi dan tingkat kemakmuran rakyat Bojonegoro, yang terletak di pesisir Jawa Timur, selama penjajahan Belanda pada abad ke-20 (1900-1942). Daerah ini diambil Penders sebagai contoh karena unsur kebetulan. Dalam arsip ko nial di Belanda banyak sekali bahan mengenai kemakmuran daerah Bojonegoro. Laporan dan penelitian pemerintah Hindia Belanda mengenai Bojonegoro banyak, karena daerah ini dianggap salah satu daerah miskin yang parah - seperti daerah Gunung Kidul pada awal 1960-an. Periode 1900-1942 itu juga terkenal dengan periode "politik etis", yakni usaha pemerintah kolonial menaikkan taraf kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya di Jawa. Faktor yang menyebabkan lahirnya politik itu, antara lain masuknya Indonesia dalam zaman modern, munculnya gerakan-gerakan rakyat, dan perkembangan politis dalam negeri di Belanda. Dari 1830 sampai 1870, Indonesia (Jawa) telah dieksploatasi melalui sistem Tanam Paksa, yakni pendirian perkebunan yang menghasilkan barang ekspor untuk pasaran dunia, seperti teh, kopi, gula, dan nila. Perkebunan-perkebunan ini didirikan, dikuasai, dan diurus oleh pemerintah kolonial, sedangkan pemasarannya dilakukan oleh Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM), badan dagang semipemerintah. Mengenai cara memperoleh tanah dan tenaga kerja bagi perkebunan-perkebunan itu dilaksanakan secara politis - erat hubungannya dengan kekuasaan negara kolonial - dan pelaksanaannya melalui lembagalembaga feodal Jawa, tempat para priayi berhak atas tanah dan tenaga kerja rakyat. Sistem Tanam Paksa oleh para pengkritiknya, yakni golongan swasta kapitalis Belanda, dikatakan mendatangkan kemiskinan, bahkan kelaparan, di Pulau Jawa, khususnya di daerah-daerah sistem itu dilaksanakan. Para pengkritik ini terdiri dari kaum liberal yang memenangkan kursi mayoritas dalam Parlemen Belanda pada 1870. Mereka ini, melalui undang-undang, tahap demi tahap mendorong penjualan perkebunan-perkebunan negara di Hindia Belanda kepada swasta, baik Belanda, Cina, maupun Indo. Pada 1900, tiba-tiba para politisi di Belanda dan para pejabat di Hindia Belanda insaf bahwa sistem liberalisme, yang menyerahkan semua pada kekuatan pasar - baik upah buruh perkebunan, sewa tanah, pemasaran hasil perkebunan, serta investasi pada perkebunan - tidak membawa kemakmuran bagi rakyat Jawa. Tapi kenyataannya, tidak seluruhnya yang diserahkan pada kekuatan pasar. Sebab, para pejabat Hindia Belanda (BB= bestuurs beambten), pangreh praja, serta lurah tetap mengadakan tekanan pada rakyat untuk "kerja" bagi modal swasta itu. Menurut penelitian Penders, imbalan upah, sewa tanah, dan lainnya bagi rakyat tidak seimbang, bahkan rendah sekali. Dengan sendirinya, proses itu menimbulkan kemiskinan di Bojonegoro, dan daerah-daerah lain di Jawa. Hal itu terlihat jelas pada penjualan tembakau, satu-satunya hasil agraris komersial bagi petani Bojonegoro. Tembakau Bojonegoro, yang dikenal sangat rendah kualitasnya, sekalipun pada akhir abad ke-19 tetap laku, kemudian merupakan "senjata yang makan tuan". Pasaran tembakau itu hancur pada abad ke-20. Untuk meningkatkan kualitasnya, modal tidak ada gunanya lagi, karena tanah telah kehilangan kesuburan oleh penanaman tembakau berkualitas rendah ini. Para pengusaha yang memasarkan tembakau Bojonegoro, juga petani, akibatnya menjadi korban. Apakah ini disebabkan pandangan sempit penguasa, atau memang kesempatan yang kecll, maka petani menghasilkan tembakau bernilai rendah ini, kurang dijelaskan oleh Penders. Pada 1900, kemiskinan di Bojonegoro, seperti juga di bagian lain di Jawa, tak terkendali lagi. Politik kaum liberal Belanda, yang percaya pada pasaran bebas, terbukti gagal mendatangkan kemakmuran di Jawa. Akibatnya, mereka dikalahkan partai kaum Protestan dalam pemilihan umum. Untuk pertama kali, dan satu-satunya gubernur jenderal dari partai politik Kristen, Idenburg (1916-1921), diangkat. Tugas utamanya melaksanakan politik etis. Karena kebijaksanaan sebelumnya telah menyebabkan "kekurangan kemakmuran" di Hindia Belanda (baca: Jawa dan Madura). Dalam pidato tahta pada 1900, Ratu Wilhelmina menyebut "utang budi" (ereschuld) pada koloni. Utang budi itu, antara lain, atas dasar fakta bahwa selama abad ke-19 koloni Hindia Belanda telah mengumpulkan pajak, yang kemudian dikirimkan ke Belanda guna membantu neraca anggaran belanja. Bagi Indonesia, pengakuan utang budi dari Ratu Wilhelmina ini penting artinya. Sebelumnya, dana yang mengalir dari koloni ke negara induk tak pernah disebutsebut, apalagi "dibayar" kembali. Tapi, sejak politik etis dijalankan, pemerintah Belanda mulai memberikan bantuan kepada pemerintah Hindia Belanda. Faktor penting lain, dengan politik etis, Belanda untuk pertama kali melihat satu pemerintah di Indonesia mencoba mengurus kemakmuran rakyatnya. Artinya: mencampuri urusan rakyat secara aktif guna menaikkan taraf hidup mereka. Resep politik etis ini dicantumkan dalam semboyan tiga program: transmigrasi, irigasi, dan edukasi. Tapi, secara keseluruhan, seperti dikatakan Penders, politik etis gagal mengangkat kemakmuran rakyat. Kegagalan ini khususnya dapat dilihat di Bojonegoro. Dari 1937 sampai 1940, Bojonegoro dilanda kelaparan, dan penyakit-penyakit lain akibat kemiskinan yang menyebabkan daya tahan rakyat memburuk. Sayang, Penders tidak memberikan analisa lengkap mengenai kegagalan program politik etis meningkatkan taraf hidup penduduk. Padahal, analisa ini penting, dan mungkin relevan bagi politik pembangunan masa kini. KEGAGALAN politik etis diduga akibat terlalu banyak program dibebankan pada penduduk yang sudah parah. Bahkan ada yang melihat program politik etls semacam perpaJakan baru. Hasil nyata, misalnya perbaikan mutu ternak penduduk dengan pemberian bibit unggul, tidak ada. Bantuan pemerintah pusat datang hanya bila ada malapetaka, misalnya kelaparan. Faktor lain, depresi ekonomi yang melanda dunia secara hebat pada 1930-an, sangat memukul Hindia Belanda, yang perekonomiannya tergantung dari ekspor. Di samping itu, juga sikap tak acuh penguasa terhadap nasib rakyat. Bahkan ada penguasa yang mengatakan, kalau rakyat ditimpa kelaparan, maka itu salah mereka sendiri. Dalam kasus Bojonegoro, menjelang akhir penjajahan Belanda, Penders melihat kesalahan pada struktur pemerintahan yang patrimonial dari pangreh praja. Mereka, menurut program politik etis, harus bertindak sebagai birokrat modern, seperti pejabat Belanda. Tapi pangreh praja itu kelihatan tidak terlalu percaya akan modernisasi dan program etis. Pada 1930-an itu, ada beberapa pangreh praja yang korup serta memerintah sewenang-wenang, dan ini dibiarkan Belanda. Kegagalan politik etis ini, sebetulnya, tak terlepas dari sikap pejabat-pejabat Belanda yang membiarkan korupsi dan kesewenangwenangan, baik di antara mereka maupun di kalangan pangreh praja. Untung, segera masuk pengaruh gerakan politik, terutama dari Sarekat Islam, yang kemudian mengubah jalan pikiran rakyat, juga di Bojonegoro, sehingga berani menentang Belanda. Onghokham
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini