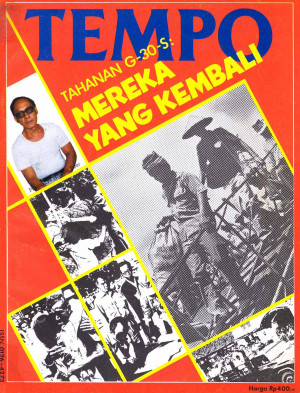SIAPA bilang penata tari itu dilahirkan? Bakar memang harus ada.
Tapi ketrampilan menata gerak dan-memadukannya dengan unsur
pentas yang lain, jelas diperoleh lewat latihan dan pengalaman
--bisa lewat sekolah, ataupun luar sekolah.
Festival Penata Tari Muda yang kedua ini, diselenggarakan Dewan
Kesenian Jakarta, 15-17 Desember yang lalu, boleh dipandang
sebagai pemberian kesempatan lewat luar sekolah. Dan ternyata,
bagi pesertanya sendiri memang dipandang penting. Kata Wahyu
Santoso, 28 tahun, mahasiswa Akademi Seni Karawitan Indonesia
(ASKI) Surakarta: "Ide saya sudah setahun mengeram. Undangan
festival inilah yang membantu saya memecahkan ide itu." Dia
menampilkan Rudra satu bentuk tari yang mencoba mengungkapkan
berbagai rasa (sedih, gembira, marah dan lain-lain) tanpa
mengaitkannya dengan satu cerita.
Tujuh penata tari muda tampil Wahyu yang telah disebutkan Tri
Nardono dari Akademi Seni Tari Indonesia Yogyakarta Gusmiati
Suid (ASKI Padang Panjang) I Made Netra (Bali), Wiwiek dan
Djoko (Jakarta) Sulistyo Tirtokusumo (Jakarta). Kesemuanya
saja, dilihat dari usia mereka -- rata-rata lahir tahun 50-an --
memang sedang berada di puncak semangat mencipta. Sementara
pengalaman dalam seni tari pun telah cukup. Jadi wajar, kalau
karya mereka tak lagi hanya merupakan pelampiasan emosi atau
alat rekreasi. Bahkan sejumlah pengamat tari, antara lain drs
Soedarsono (Direktur ASTI Yogyakarta) dan Sedyono Humardani
(Ketua Pusat Kebudayaan Jawa Tengah), meragukan ketepatan
predikat "muda." Sebagai karya tari, karya mereka sudah cukup
mantap.
Toh, kelemahan tetap bisa ada. Terutama dalam hal bentuk,
yang-memang indah tapi kurang berkait dengan gagasan pokoknya.
Ini kentara sekali pada Empiri Tri Nardono.
Arak-arakan Kematian
Yang menarik, ada yang memanfaatkan betul bahan tari tradisi.
Ternyata tari tradisi memberi kemungkinan sangat luas untuk
berbagai pengungkapan. Wiwiek dan Djoko meramu tari tradisi
Betawi -- kembang topeng, topeng kedok dan pencak silat Betawi
--menjadi Gado-gado Jakarta: cukup manisdan segar. Iringan musik
tradisi yang sederhana justru menambah penampilan tarinya
semakin menonjol. Tapi, entah karena ini sebuah "gado-gado",
sepertinya penata tari merasa sulit menutup karyanya.
Penutupan (ending) yang tepat memang seringkali menentukan
berhasil atau tidaknya sebuah karya tari. Mejangeran karya
Netra, 29 tahun, adalah sebuah contoh yang bagus. Orang yang
pernah menggarap Cak, Tarian Rina bersama Sardono W. Kusumo ini,
memilih tari Janger -- yang dibanding tari-tari Bali yang lain
tari itu kurang menuntut ketrampilan teknis menari. Toh, dia
bisa menggarap keseluruhan karyanya ini cukup memikat, terutama
dengan ditampilkannya adegan topeng dan arak-arakan kematlan
sebagai penutup.
Apabila Rudrah dan Empiri mencoba beranjak dari tari tradisi
Jawa, Ario Jipang karya Sulistyo justru hendak melekat pada
tradisi itu. Kisah sejarah Jawa yang populer ini, digubah
Sulistyo dengan gaya Wireng dan Bedoyo. Dan pertempuran Ario
Jipang dengan Sutowijoyo utusan Sultan Pajang jadi terasa halus.
Sulistyo telah menentukan batasannya sendiri. Di dalam batasan
itulah ia mencoba mencipta. Tentu tak mudah terlihat bagi yang
tak paham benar Wireng dan Bedoyo. Apalagi cerita di sini hanya
dijadikan titik tolak menyuguhkan suasana saja. Lihat misalnya
adegan perang tanding Ario Jipang lawan Suto Wijoyo. Pentas
sunyi, iringan gamelan berhenti. Ini, justru efektif. Suasana
yang tumbuh dalam kesunyian itu justru memberi peluang bagi
imajinasi untuk berkembang. Dan betapa sengitnya rasa saling
benci antara mereka yang sedang bertanding.
Semua ini berhasil lahir di jaman Ismail Marzuki, berkat kondisi
psikologis yang diberikan TIM sejak semula. kebebasan berkreasi.
Sal Murgiyanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini