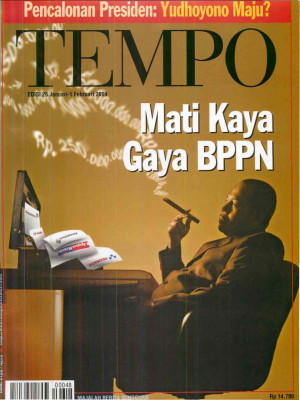Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kalimat gong xi fat cai mendadak jadi populer. Ibu rumah tangga, mahasiswa, presenter beken di layar televisi, hingga Presiden Megawati ikut latah mengucapkan ungkapan yang kurang-lebih berarti "semoga keberkahan melimpah" itu. Warna merah, atraksi barongsai dan liong pun mendominasi pelbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Ya..., pekan lalu semua orang seperti hanyut dalam kehebohan perayaan tahun baru Imlek.
Memang Imlek tahun ini terasa spesial. Meski banyak kota tak diguyur hujan saat perayaan tahun baru Cina ini-yang secara tradisional dipercaya sebagai pertanda banyak rezeki-kendurinya tetap meriah. Bahkan sampai membuat seorang Harry Tjan Silalahi khawatir akan muncul dampak negatif akibat perayaan Imlek yang dianggapnya cenderung wah tersebut. Bagi tokoh berusia 70 tahun yang tetap mengaku sebagai Tionghoa ini, ada potensi destruktif bila perayaan Imlek kebablasan. "Akan jadi bumerang yang merugikan," ujarnya.
Harry Tjan tentu tak asal bicara. Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini telah terlibat dalam perdebatan sengit tentang identitas warga Indonesia keturunan Cina sejak ia berusia muda.Pria yang dilahirkan dengan nama Harry Tjan Tjoen Hok di Yogya ini,diterima menjadi anggota marga Silalahi ini pendukung gagasan yang berani agar setiap anggota etnis Tionghoa melebur ke suku Indonesia yang ada. Kubu yang lain, yang didukung Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), berjuang agar warga keturunan Tionghoa diakui sebagai etnis tersendiri seperti puak asli Indonesia lainnya.
Belum jelas benar apa dampak Imlek pada perdebatan lama ini. Mayang belum juga usai ia, untuk memahaminya lebih dalam, pekan lalu wartawan TEMPO Setiyardi mewawancarai Harry Tjan Silalahi di kantornya, di Jalan Tanah Abang III, Jakarta. Selama sekitar dua jam, aktivis pembauran di Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa ini menjawab semua pertanyaan dengan kalem.
Berikut kutipannya.
Perayaan Imlek begitu meriah. Fenomena apa sebenarnya?
Ya, perayaan Imlek memang sangat meriah. Tak cuma di Indonesia, di Asia Tenggara dan di Negeri Cina juga meriah. Situasi ekonomi memang telah membaik. Khusus di Indonesia, tentu saja hal ini merupakan salah satu buah dari reformasi. Tapi saya harap hal ini tidak kebablasan. Saya ingin masyarakat yang merayakan Imlek tetap "tahu diri". Kalau tidak, akan jadi bumerang yang sangat berbahaya.
Apa yang Anda maksud "kebablasan" tersebut?
Overdosis. Bila setiap hari, hingga pukul 12 malam, orang menggelar barongsai dan liong, itulah salah satu bentuk perayaan yang kebablasan. Sebuah pesta-pora di tengah masyarakat yang kebanjiran juga dapat diartikan sebagai kebablasan. Menyembelih babi di tengah perkampungan muslim juga bentuk aksi yang kebablasan. Saya sangat mengkhawatirkannya.
Anda menilai perayaan Imlek kali ini sudah kebablasan?
Sekarang belum, masih dalam batas yang bisa diterima. Tapi, ada tren kuat bahwa perayaan Imlek memang hampir kebablasan. Tentu saja, soal dosisnya, para pemimpin formal dan informal harus dapat merumuskannya.
Bagaimana kalau yang terjadi justru akulturasi budaya?
Kalau memang sudah terjadi akulturasi budaya, kita justru harus bersyukur. Di media massa, saya melihat foto seorang ibu berjilbab dengan anaknya yang mengenakan pakaian khas Tionghoa. Barongsai juga banyak dimainkan orang pribumi dan bisa jadi mata pencarian. Soal itu sih baik-baik saja. Yang saya cemaskan bila terjadi resistensi dan dampak yang berlebihan.
Tampaknya Anda merasa trauma dengan kekerasan rasial?
Tentu saja saya tak boleh melupakan bahwa potensi kekerasan rasial tetap ada. Itu juga manusiawi. Saya berusaha mengurangi faktor pemicu disintegrasi. Caranya praktis: kalau barongsai keluar dilempari batu, jangan dipertunjukkan. Begitu juga kalau bahasa Cina diomongkan di tempat umum diprotes, ya, jangan dilakukan.
Benarkah potensi konflik rasial di Indonesia masih sangat besar?
Indonesia adalah negara yang paling pluralis dalam segala bentuknya. Tanpa ada manajemen konflik yang baik, potensi konflik horizontal tetap terbuka lebar. Karena itu, perbedaan etnis dan kultural harus dikelola dengan baik. Proses nation building yang sedang kita lakukan merupakan proses yang tidak pernah selesai.
Anda bicara tentang nation building. Mengapa Orde Baru justru "mematikan" kebudayaan Tionghoa?
Pada awal Orde Baru, hubungan Indonesia dan RRT sangat buruk. Orde baru menilai PKI sebagai pelaku pemberontakan G30S. Dan kita tahu bahwa PKI sangat dekat dengan RRT. Sebaliknya, saat itu The Gang of Four (Julukan bagi empat pemimpin radikal Partai Komunis Cina yang saat itu berkuasa: Yao Wenyuan, Jian Qing, Zhang Chunqiao, dan Wang Hongwen. Tahun 1981 keempatnya ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pemerintah Cina-Red.) sangat keras mengkritik militer Indonesia, terutama kepada Soeharto dan A.H. Nasution.
Nah, suasana tegang meningkat drastis. Orang Tionghoa di Indonesia dianggap akan menjadi koloni kelima dari RRT. Kebetulan Baperki, organisasi massa Tionghoa terbesar, memiliki aliran politik yang dekat dengan PKI dan RRT. Ini menyebabkan Angkatan Darat memutuskan bahwa orang keturunan Tionghoa memiliki security risk. Mereka diawasi ketat.
Apa saja bentuk pembatasan dari pemerintah?
Orang Tionghoa tak boleh menerbitkan surat kabar. Soalnya, aparat tak mampu mengawasinya karena ditulis dalam bahasa Tionghoa. Ekspresi yang khas Tionghoa juga tidak boleh dipertontonkan ke luar. Tahun-tahun pertama Orde Baru memang tak ada pengganyangan karena ada kebijakan untuk menahan diri. Tetapi, seperti biasa, banyak aparat yang mencari uang dari etnis Tionghoa. Filosofi kebangsaan akhirnya menjadi fulussofi (ideologi mencari uang. Red.).
Mengapa pada 1967 Soeharto meminta orang Tionghoa mengganti nama?
Soal itu Pak Harto sebetulnya tidak salah. Presidium kabinet memberikan kesempatan kepada orang Tionghoa untuk dapat mengganti nama dengan mudah. Cukup dengan pernyataan di kantor kecamatan. Sebelumnya, penggantian nama harus lewat pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Bahwa kemudian aturan itu disalahgunakan adalah hal yang biasa. Aparat menyalahgunakannya agar mendapat uang. Sebaliknya, keturunan Tionghoa mengganti nama untuk korupsi dan kolusi.
Lantas, Apa yang mengubah keadaan menjadi begitu terbuka?
Reformasi 1998. Gus Dur mulai sedikit membuka keran keterbukaan. Gus Dur bahkan mengaku dirinya sebagai keturunan Tionghoa. Lucunya, suatu kali Gus Dur bilang keturunan "Liem", di lain waktu menyebut keturunan "Tan". Saat bertemu dengan Gus Dur, saya bilang mbok ya konsisten. Ha-ha-ha....
Selain itu, dunia memang sedang menghendaki pluralisme kultural. Ini buah dari globalisasi dan kemajuan teknologi telekomunikasi. Orang mulai ingin dihargai aliran dan identifikasi pribadinya. Sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan fenomena yang luar biasa. Ada 1.062 suku di seluruh Indonesia. Padahal, dulu cuma sekitar 18 kelompok besar. Ini berarti bahwa orang ingin menunjukkan identitasnya.
Telah lama ada "sentimen negatif" penduduk pribumi terhadap etnis Tionghoa. Mengapa tak dapat dihilangkan total?
Kebencian dan pembantaian merupakan akibat dari belum diterimanya etnis Tionghoa. Situasi ini bisa meledakkan kerusuhan rasial. Akibatnya sangat mengerikan. Masalah penerimaan ini merupakan buntut dari sejarah lama. Sejak zaman Belanda sudah dibuat sekat-sekat. Ada tiga kelas masyarakat: Eropa (Belanda dan Jepang), Timur Asing (Arab, Cina, India) dan inlander (pribumi). Mereka dibatasi dan punya tempat sendiri-sendiri agar gampang diatur. Nah, sisa politik lama ini masih ada sampai sekarang.
Apakah kebencian dan diskriminasi masih Anda rasakan hingga kini?
Hari ini saya memperpanjang paspor. Saya diminta menunjukkan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dan beberapa surat lainnya. Padahal, saya cuma memperpanjang paspor-mereka toh telah menyimpan file saya. Kalau orang seperti saya saja bisa dibegitukan, bagaimana dengan keturunan Tionghoa yang lain? Selain itu, undang-undang tentang catatan sipil dan hukum perdata juga masih membedakannya. Beberapa pejabat memang lebih suka kondisi ini karena ada kesempatan mendapat uang.
Soal diskriminasi sebenarnya terjadi di mana-mana. Inggris, yang sangat nondiskriminatif, akhirnya juga melakukannya. Ketika banyak orang Pakistan dan Ghana yang sukses berdagang, muncul gerakan anticolour people. Begitu juga di Belanda, saat orang dari Suriname dan Ambon berdatangan. Rupanya, kalau sudah menyangkut sepiring nasi, rasionalitas sering menjadi hilang.
Meski banyak keturunan Tionghoa yang baik-sebut saja Kwik Kian Gie, Arief Budiman, dan Anda sendiri-stigmatisasi Tionghoa masih terasa sangat negatif. Mengapa?
Itu hal yang biasa. Orang akan selalu menyebut orang Batak kasar. Padahal, banyak orang Batak yang halus, seperti Cornel Simanjuntak, Binsar Pasaribu, dan Sitor Situmorang. Jadi, yang paling gampang dinilai adalah sisi negatifnya. Makanya, orang seperti saya harus selalu memberikan pencerahan. Ini tugas nation building yang tak akan pernah selesai.
Tapi bukankah banyak keturunan Tionghoa yang "bermasalah"...?
Ya, memang ada satu-dua orang yang bermasalah. Tapi mereka jadi berani karena merasa memiliki beking.
Mengapa banyak pengusaha etnis Tionghoa memiliki beking?
Ini soal biasa. Beking merupakan langkah untuk survival biasa. Semua kelompok minoritas memang punya kecenderungan seperti itu. Yang lemah berlindung pada yang kuat. Tentu saja dalam hal ini uang yang berbicara. Sekarang, agar kehidupan berbangsa ditinggikan, kita harus mengatakan right is right, wrong is wrong.
Apa usul Anda untuk keturunan Tionghoa agar nation building berjalan?
Mereka bekerja menurut profesinya secara baik. Jangan mengelompok secara berlebihan, seperti mendirikan perkumpulan berdasarkan suku yang ada di Tiongkok: Hokian, Hakka, dan lain-lain. Orang Tionghoa harus menanamkan solidaritas nasional. Bukan dalam arti sempit, tapi dalam konteks kemanusiaan terhadap sesama. Kalau masyarakat kebanjiran, harus ada concern bahwa mereka juga kebanjiran. Ada perang di Aceh dan gempa di Irian harus ikut merasakannya.
Apakah hal tersebut sudah dilakukan?
Ada yang sudah melakukannya, tapi masih banyak yang belum. Ini butuh penyadaran terus-menerus. Orang Tionghoa harus di-wong-kan dengan cara memberi mereka peran tertentu.
Benarkah etnis Tinghoa menguasai 80 persen perekonomian Indonesia?
Jumlah etnis Tionghoa saat ini sekitar 3 persen atau 6 juta jiwa. Mereka memang mendominasi sektor perdagangan. Tapi tidak mungkin menguasai 80 persen perekonomian. Nah, dominasi terhadap perdagangan, terutama di kota-kota besar, kerap menimbulkan kecemburuan.
Bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, membuat program "pemberdayaan ekonomi" bangsa Melayu. Mengapa kita tak mencobanya?
Malaysia memang harus melakukannya. Etnis Tionghoa mencapai jumlah 30 persen dari penduduk. Itu kekuatan yang sangat besar. Sedangkan kita, yang cuma memiliki 3 persen etnis Tionghoa, rasanya tak perlu meniru Malaysia. Kalau saja pemerintahnya adil dan bijaksana, persoalan kesenjangan ekonomi ini selesai. Masalahnya, pejabat pemerintah sering memanfaatkan keturunan Tionghoa itu untuk jadi ATM pribadi.
Tapi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan etnis Tionghoa. Dulu mereka tidak punya pilihan lain kecuali "jadi orang kaya". Soalnya, dulu ada pembatasan untuk berperan di bidang lain, terutama di birokrasi. Untuk itulah, saya mempropagandakan agar keturunan Tionghoa punya kesempatan yang luas untuk jadi pegawai negeri, militer, petani, dan lain lain.
Bagaimana hasilnya?
Lumayan. Sebenarnya sudah banyak tentara yang keturunan Cina. Adik saya tentara lulusan Akabri. Jenderal polisi perempuan yang pertama adalah keturunan Tionghoa. Orang seperti Benny Moerdani pernah bilang, "Keturunan Cina yang sudah masuk Akabri harus punya kesempatan yang sama."
Apa pekerjaan rumah yang masih belum selesai?
Sewaktu Gus Dur membuka keran, sebetulnya belum terlalu besar. Selain itu, visinya tidak jelas karena baru berupa pernyataan. Tapi itu permulaan yang baik. Gus Dur telah melakukan breaking the ice. Kita yang harus melanjutkannya. Soal tuntutan Tan Joe Hoek (bekas pemain bulu tangkis nasional-Red.) supaya SBKRI ditiadakan, misalnya, sampai hari ini belum terealisasi.
Meski tak lolos seleksi di KPU, saat ini sudah ada Partai Tionghoa. Apa hal itu memang perlu?
Kalau boleh memilih, saya lebih setuju sikap Alvin Lie yang masuk Partai Amanat Nasional. Kalau orang mau berpolitik, seharusnya menanggalkan simbol agama dan etnis. Identitasnya harus kebangsaan Indonesia. Yang membedakan satu dengan yang lain adalah programnya. Lagi pula, Partai Tionghoa akan menjadi partai yang kecil. Bisa apa mereka?
Omong-omong, apakah Anda masih merasa Tionghoa?
Meski dalam keluarga tidak ada perasaan sebagai Tionghoa, tentu saja saya tak bisa bersikap kirno alias mungkir Cino. Ha-ha-ha.... Saya merasa tetap harus mendampingi orang-orang Tionghoa. Biasanya mereka mendapat misunderstanding. Seperti untuk wawancara ini. Jadi, identifikasi dan afiliasi saya lebih sebagai pendamping.
Anda masih ikut merayakan Imlek?
Ah, tidak. Imlek sebetulnya bersifat sangat kultural. Itu permulaan musim tanam. Jadi sebetulnya yang merayakannya adalah para petani.
Ini soal lain. Bagaimana dengan pilihan politik Anda?
Soal presiden, kriteria saya adalah orang yang memiliki spiritual quotient yang tinggi, dari lingkungan Islam demokrat. Dulu saya pikir orang seperti Nurcholish Madjid cocok jadi presiden. Sayangnya, Cak Nur tak punya kendaraan yang kuat. Sekarang cuma naik bajaj. Sedangkan Megawati naik mercedes dan Wiranto naik volvo. Jadi susah untuk mengejarnya.
Bagaimana prediksi perolehan suara partai politik dalam pemilu mendatang?
Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan naik. Sayangnya, PKS adalah kelompok yang kecil. Sedangkan PDI Perjuangan akan turun. Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang akan repot. Semua partai akan kekurangan uang, kecuali PDI Perjuangan.
Apakah pemerintahan Megawati berhasil?
Pemerintahannya sebenarnya tidak dimusuhi. Tapi, dia tidak berhasil karena cuma diam. Pemikirannya terlalu sederhana, seperti "persatuan" dan "jangan gontok-gontokan". Mungkin karena kapasitasnya memang cuma sejauh itu.
Anda masih aktif di CSIS. Bagaimana nasibnya sekarang?
Selama orang masih butuh pemikiran, I hope CSIS still exist. Dulu, memang tak ada lembaga seperti ini. Makanya hasil analisis CSIS dipakai oleh para pejabat Orde Baru. Kami juga menyampaikannya kepada Presiden Soeharto. Kemudian, banyak yang buka warung seperti CSIS, misalnya lembaga seperti CIDES (lembaga yang menjadi onderbouw dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Saya tak bisa bilang bahwa orang lain memakan lahan saya. I can not claim. Itu sangat sombong. Saya cuma bilang saya menyajikan sesuatu. Ada daftar menunya.
Benarkah CSIS sangat di-back up dan menjadi think tank Soeharto?
Di CSIS memang ada Ali Moertopo dan Sudjono Humardani. Mereka adalah orang berkuasa yang dekat dengan Soeharto. Soal duit kami cari sendiri. Pak Sudjono Humardani memang sering menghubungkan dengan orang-orang yang memberikan bantuan finansial ke CSIS. Tapi itu masa lalu. Ke depan, kami harus dapat membiayai lembaga ini dengan mencari proyek sendiri.
Harry Tjan SilalahI
(mendapat marga Silalahi dari sahabatnya, Abertus Bolas Silalahi-bekas Ketua Partai Katolik)
Tempat tanggal lahir:Yogyakarta, 11 Februari 1934
Pendidikan: Fakultas Hukum UI (lulus 1962)
Karier:
- Ketua Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia (1961-1962)
- Pendiri Universitas Trisakti (1962)
- Ketua Partai Katolik (1971)
- Anggota DPA (1978-1983)
- Direktur CSIS (1971-sekarang)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo