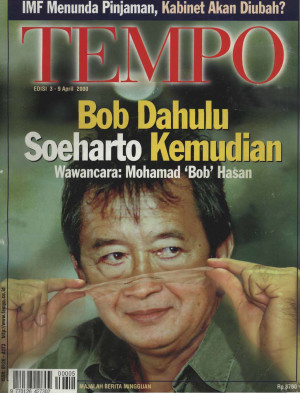Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pria yang banyak mendapat aplaus itu bernama Ichlasul Amal, orang nomor satu di universitas tersebut. Namun, orasi yang dia ucapkan kali itu bukan pidato seorang rektor. Ichlasul hadir di sana sebagai salah satu dosen dan karyawan UGM yang menggelar demo. Mereka menentang kebijakan pemberian tunjangan jabatan struktural bagi pegawai negeri sipil yang dinilai sangat tidak adil.
Peristiwa di balairung itu hanya sebagian kecil dari dinamika kehidupan Ichlasul, 58 tahun, sebagai Rektor UGM. Sejak memimpin universitas itu dua tahun silam, Ichlasul menunjukkan solidaritas yang tinggi kepada warga kampusnya. Ia hadir bersama mahasiswa ketika UGM berdemo menentang Soeharto dan menuntut pembentukan presidium dalam pemerintahan yang baru. Ichlasul, bersama mahasiswanya, ikut meramaikan gelombang manusia di Alun-Alun Utara Yogyakarta tatkala ada aksi damai sejuta umat yang menuntut Soeharto lengser. Lalu, ketika kabinet berganti, Ichlasul menolak menjadi menteri kabinet Habibie karena solider dengan para civitas academica.
Tak aneh, ayah dua anak ini amat populer di kampusnya. Para mahasiswa bahkan menginap di halaman rumahnya tengah malam untuk "mencegah" sang Rektor meninggalkan Yogya—ketika beredar kabar ia menjadi menteri kabinet Habibie. Gadjah Mada dan Yogya agaknya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup pria kelahiran Jember, Jawa Timur ini.
Ichlasul masuk UGM pertama kali pada 1961 sebagai mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Enam tahun kemudian, ia lulus dan menempuh studi pascasarjana di Northern Illinois De Kalb University, Amerika Serikat. Gelar master bidang politik ia peroleh pada 1974. Setelah itu, doktor lulusan Monash University (1985) ini memulai karirnya sebagai birokrat kampus. Ia menjadi Direktur Pusat Antar-Universitas (PAU) Studi Sosial UGM (1986-1988), Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM (1988-1994), lalu Direktur Program Pascasarjana UGM (1994-1998). Dan sejak 1998, ia resmi memimpin bekas almamaternya sebagai Rektor UGM ke-11.
Setelah menjadi rektor, penggemar tenis ini pindah ke lantai dua Gedung Pusat UGM. Kantornya, yang menghadap ke sebuah hutan, adalah ruangan bernuansa cokelat yang menyimpan banyak jejak masa lalu. Foto para bekas rektor—sebagian besar sudah meninggal—tergantung rapi di salah satu dindingnya. Meja kerja rektor serta seperangkat kursi tamu di situ adalah perabot yang diboyong dari Kampus UGM di Pagelaran Keraton Yogyakarta—setengah abad silam. Di ruang itulah Ichlasul merancang cita-cita tentang kemandirian kampusnya. "Kini sudah tidak ada tekanan dari pusat. Tapi juga tidak ada aliran proyek seperti dulu. Jadi, kita harus belajar mandiri," ujarnya kepada TEMPO.
Di ruang kerja penuh buku, ensiklopedia, serta vandel itu, Ichlasul tampil jauh dari keformalan seorang pejabat eselon: hem lengan panjang tanpa dasi. Untuk makan siang, ia cukup menyantap nasi bungkus yang dibelikan stafnya di warung Padang. Menu yang sama pula yang ia sajikan ketika diwawancarai wartawan TEMPO, R. Fadjri, di ruang rektor di lantai dua Gedung Pusat UGM, pekan lalu. Semua pertanyaan dijawab Ichlasul dengan gaya yang tak berubah sejak ia masih mahasiswa: spontan, lugas, tak bertele-tele. Petikannya:
Apakah Anda ikut menggerakkan demo para dosen dan karyawan di Balairung UGM, Sabtu, dua pekan lalu?
Saya hanya memfasilitasi, ha-ha-ha…. Wong, saya itu sedang memimpin sidang senat, lalu mereka minta agar rektor ikut.
Sebelum demo, apakah mereka berkonsultasi dengan Anda?
Tidak. Itu inisiatif mereka sendiri. Mereka memprotes keras kebijakan tunjangan struktural pemerintah. Seorang kepala biro, misalnya, mendadak mendapat tunjangan struktural Rp 5 juta, yang tadinya berjumlah Rp 250 ribu. Demo itu sudah mengancam kepala biro… yang disuruh bekerja sendiri. Perbedaan ini akan menimbulkan protes tertutup yang lebih berbahaya. Saya tidak bisa memarahi mereka karena gaji para karyawan kecil sekali. Yang besar kan kepala bironya.
Apa saja pengaruh perbedaan tunjangan tersebut?
Timbulnya ketidakadilan serta perbedaan yang sangat mencolok. Hal ini amat terasa dalam organisasi universitas. Namun, rektor tidak bisa mengendalikan organisasi sepenuhnya karena pusatlah yang menentukan eselonisasi.
Bisa memberikan beberapa contoh perbedaan yang mencolok itu?
Kita punya enam kepala biro (kabiro). Di salah satu biro yang tugasnya hanya mengumpulkan informasi, kabironya mendapat tunjangan struktutal Rp 5 juta. Ada kabiro kemahasiswaan di bawah pembantu rektor (PR) III yang tiba-tiba mendapat Rp 5 juta. Padahal, PR-nya saja tidak begitu. Kepala bagian (kabag) di fakultas—termasuk kepala tata usaha—mendapat tunjangan Rp 1 juta, padahal sebelumnya cuma sekitar Rp 100 ribu atau Rp 150 ribu.
Berapa bagian dari tunjangan ini menetes ke bawah?
Kabiro dan kabag punya banyak staf. Nah, para staf ini sama sekali tidak mendapat apa-apa. Ini kan perbedaan yang terlalu mencolok.
Lalu, apa tunjangan Anda sebagai rektor?
Saya hanya mendapat tunjangan fungsional, yang diberikan karena kita mengajar, sejumlah Rp 500 ribu. Sedangkan tunjangan sebagai rektor tidak ada. Dulu, sekitar 1998, pernah ada keputusan presiden (keppres) yang dikeluarkan Presiden Habibie bahwa ada tunjangan jabatan Rp 1 juta untuk semua profesor. Kenyataannya, tidak pernah ada realisasinya.
Jadi, demo kemarin itu rupanya membawa aspirasi yang sama?
Sebetulnya, pagi hari, saya sudah ditelepon Direktur Jenderal Anggaran (Departemen Keuangan). Katanya, tunjangan ini mau disamakan, tapi nanti akan dijadikan satu dengan DPR dan macam-macam.
Apa saja hak-hak Anda sebagai rektor yang hilang jika tunjangan ini tidak jadi disamakan?
Artinya, rektor serta dekan tidak mendapat tunjangan struktural. Tunjangan fungsional para guru, yang tadinya sekitar Rp 500 ribu, cuma dinaikkan menjadi Rp 900 ribu. Maka, guru-guru besar yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja memprotes cukup keras. Begitulah, semacam kecemburuan sosial.
Apa upaya mengatasi masalah ini?
Sudah saya sampaikan kepada PR II, apa tidak mungkin tunjangan struktural diberikan dalam bentuk block grant (paket bantuan yang diatur sendiri). Universitas akan menentukan sendiri pembagian ke tiap-tiap unit sehingga tidak menimbulkan persoalan.
Tapi jumlah block grant itu sendiri apa tidak menjadi soal baru?
Yang penting, departemen anggaran tahu berapa uang yang harus dikeluarkan untuk sebuah unit dengan hitungan "struktural" tadi. Pengaturannya serahkan ke universitas. Efisiensi organisasi akan menjadi jauh lebih bagus dan pembagian bisa lebih merata.
Bagaimana hubungan sistem ini dengan otonomi kampus?
Kita dapat mengatur sendiri mana fakultas yang memerlukan banyak dosen dan mana yang tidak—suatu hal yang selama ini tidak bisa kita lakukan. Kita juga bisa menentukan sikap jika ada dosen yang malas-malasan.
Berapa rata-rata gaji dosen UGM saat ini?
Gaji saya sekitar Rp 1,1 juta. Tunjangan fungsionalnya sekitar Rp 500 ribu. Lalu mendapat tambahan dari mengajar sana-sini, honorarium, dan seminar-seminar. Tapi itu masih jauh sekali kalau dibandingkan dengan gaji anak saya. Soal lain adalah masalah kesehatan yang masih menjadi satu dengan masalah kepegawaian. Saya sendiri merasa, kalau ada dosen yang kesehatannya kurang bagus, kita tidak bisa berharap banyak. La, mau membayar asuransi kesehatan sekitar Rp 60 ribu per bulan saja tidak bisa.
Ada jabatan dengan gaji dan gengsi besar: menteri departemen. Mengapa jabatan ini Anda tolak ketika Anda ditawari Habibie pada 1998?
Seperti yang pernah saya katakan, ada banyak faktor yang menyulitkan saya menerima jabatan itu.
Bisa Anda ceritakan kembali peristiwa tersebut?
Suatu ketika—setelah Habibie menggantikan Pak Harto sebagai presiden pada Mei 1998—saya ditelepon Pak Amien Rais pada pukul tiga pagi. Dia memberitahukan bahwa saya akan dijadikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Siangnya, pas saya mau rapat, Pak Muladi (Menteri Kehakiman Kabinet Habibie) menelepon. Katanya, saya harus mau dan saya diminta berbicara sendiri sama Pak Habibie. Saya lalu bilang, "Insya Allah."
Apa yang Anda lakukan setelah itu?
Ketika saya ketemu teman-teman di rapat, saya minta pendapat mereka, bagaimana saya harus bersikap terhadap tawaran itu. Pak Loekman Soetrisno (guru besar sosiologi pedesaan) bilang, "Macam-macam saja." Teman-teman yang lain berkata, "Tergantung hati nurani Pak Amal." Tapi mereka menyarankan lebih baik tidak.
Dan Anda setuju dengan saran mereka?
Saya putuskan menolak tawaran itu. Sebab, dari perjuangan reformasi yang begitu intens di kampus, tiba-tiba, kayaknya saya meninggalkan teman-teman. Kesannya saya ngotot selama ini hanya karena ingin jadi menteri. Saya juga masih rektor baru, sehingga akan banyak kesulitan kalau kampus mendadak ditinggal begitu saja.
Ada alasan lain di luar soal memimpin UGM?
Tuntutan UGM terhadap bentuk pemerintahan baru waktu itu adalah presidium agar semua kekuatan bisa diakomodasi—dan tuntutan itu tidak terpenuhi. Saya mencoba menghubungi Pak Amien dan Pak Habibie berkali-kali, tapi tidak berhasil. Akhirnya, saya berbicara dengan Pak Sofyan Effendi (Ketua Badan Kepegawaian Negara) dan menitip pesan bahwa saya tidak bisa menerima jabatan itu dengan alasan soal presidium tadi.
Bagaimana reaksi para mahasiswa?
Rupanya, mahasiswa mendengar kabar ini. Malam itu, mereka menelepon ke rumah. Anak saya yang menerima. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa saya tidak bersedia menerima jabatan itu. Tapi mereka tidak percaya. Keesokan paginya, ketika saya bangun, sekitar 20 mahasiswa menanti di depan rumah saya. Mereka takut kalau pagi-pagi saya berangkat, sehingga mereka datang pukul dua pagi dan tidur di luar pagar.
Mereka mau mencegah Anda pergi ke Jakarta?
Ha-ha-ha.... Ketika itu, kondisinya memang sulit sekali. Kalau saya pergi, siapa yang mau menggantikan dalam keadaan mahasiswa masih ramai begitu? Yang berminat juga jarang. Kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Bambang Soehendro, "Lebih gampang mencari orang yang jadi menteri ketimbang yang jadi rektor."
Omong-omong, apa enaknya menjadi rektor pada zaman sekarang?
Kalau dulu, seorang rektor seorah-olah dikendalikan oleh pusat. Tapi dana-dana mengalir dari pusat. Di zaman Pak Sukadji Ranuwihardjo (Rektor UGM 1973-1981), katanya, sampai gatelen (tidak tahan lagi). Di satu pihak mahasiswa begini, di lain pihak pusat mengendalikan. Di zaman Pak Daoed Joesoef (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1978-1983) juga serba susah karena tekanan dari atas begitu banyak.
Memangnya sekarang kampus, setidaknya UGM, sudah bebas tekanan?
Tekanan memang tidak ada. Pusat tidak mengendalikan kita. Malah, kita yang menekan pusat. Tapi susahnya soal anggaran. Proyek-proyek seperti dulu sudah tidak ada lagi. Jadi, kita harus mencari uang sendirian, berpikir bagaimana memutarkan uang itu. Kita harus belajar mandiri dalam arti yang sesungguhnya.
Di luar soal hilangnya tekanan, perubahan apa lagi yang terjadi di kampus sekarang, terutama di kalangan mahasiswa?
Sebagian besar mahasiswa pada dasarnya apolitis. Pertimbangan mereka lebih rasional: menyelesaikan kuliah dengan cepat dan mencari kerja. Ini amat berbeda dengan ciri mahasiswa pada 1960-an, yang amat intens dalam kegiatan politik.
Seperti apa aktivitas politik mahasiswa di masa itu?
Mulai 1963, aktivitas itu mulai terjadi. Polarisasi antara mahasiswa beraliran kiri dan kanan amat tinggi. Saya masuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sempat aktif di pers HMI. Kampus terpecah ke dalam golongan kiri dan kanan. Begitu tingginya aktivitas politik di UGM, sampai orang bilang, "Kalau mau menguasai Indonesia, harus menguasai UGM." Kampus menjadi arena perang dalam pengertian sesungguhnya.
Seperti apa, misalnya?
Di Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta (ketika itu, kampus UGM masih bertempat di Pagelaran Keraton Yogyakarta), itu antara mahasiswa pendukung dan anti-Bung Karno. Saya ingat betul, ketika ujian sedang berlangsung, sebagian mahasiswa sudah berperang di alun-alun. Begitu ujian selesai, mereka menyusul ke alun-alun. Di sana, mereka mengambil posisi dalam garis demarkasi yang jelas antara kelompok mahasiswa yang bermusuhan secara politik.
Apa yang terjadi setelah itu?
Lempar-lemparan batu, bahkan pakai tombak segala. Anehnya, di dalam kampus tidak pernah terjadi bentrokan. Begitu keluar, perang tak terhindarkan. Organisasi ekstra-universitas amat berperan, seperti HMI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia.
Bagaimana kesepakatan (deal) dengan penguasa pada masa itu?
Penguasa juga terkotak-kotak berdasarkan ideologi. Misalnya, kita dekat dengan seorang pejabat militer karena kesamaan ideologi. Tapi, ketika penggantinya punya ideologi berbeda, kita jadi bermusuhan. Saya dan beberapa kawan pernah ditangkap polisi dalam sebuah konflik. Tapi, karena polisinya satu ideologi, kita tidak diapa-apakan. Malah, kita kerasan di kantor polisi.
Lalu, apa yang membuat perubahan intensitas gerakan politik mahasiswa pada masa sekarang?
Jatuhnya komunisme. Memang masih ada kelompok mahasiswa yang terinspirasi oleh ideologi marxisme atau kapitalisme dalam polarisasi gerakan mahasiswa kiri dan kanan. Selain dua ideologi besar itu, di Indonesia ada ideologi yang mau tidak mau disebut Islam atau nasionalis. Tapi, dalam implementasinya sekarang, Islam dan nasionalis tidak mudah terkait dengan ideologi besar tadi.
Apa ciri dari gerakan mahasiswa sekarang?
Menentang apa saja yang keluar dari kelompok establishment (pemerintah). Ini ada kaitannya dengan kondisi psikologis anak muda yang selalu memunculkan peran dalam proses politik. Nah, di negara berkembang, peran yang paling gampang adalah menentang kemapanan. Ekspresi politiknya bukan ideologi, melainkan situasional dan lokal.
Bicara politik, sejauh ini tampaknya Anda tidak memilih afiliasi politik tertentu. Mengapa?
Sejak mahasiswa, saya sudah aktif di HMI. Dan di masa itu, HMI sudah menyatakan independensinya terhadap Masyumi, yang kerap disebut sebagai "partainya HMI". Lalu, ketika masuk ke lingkungan pendidikan, saya tidak berminat sama sekali masuk ke salah satu partai pada masa Orde Baru.
Anda tidak pernah terlibat Golkar?
Golkar memang kerap meminta saya memberikan ceramah. Terakhir, UGM menyelenggarakan pertemuan antarpartai sebelum pemilu yang lalu sehingga saya harus bisa menunjukkan memang saya nonpartisan. Sekarang ini, saya setengahnya nonpartisan.
Lalu, yang setengahnya lagi apa?
Belum ada yang menarik untuk yang setengahnya lagi. Sekarang partai lebih berorientasi pada figur ketua. Sehingga, saya pikir, yang cocok adalah menjadi nonpartisan. Partai-partai sekarang tidak punya basis ideologi yang jelas.
Mari kita pindah ke soal akademik. Ipong S. Azhar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM dibatalkan gelar doktornya pada Maret 2000. Apa komentar Anda?
Sebenarnya, itu hal biasa. Ini bukan karena saya salah satu pembimbingnya. Tapi, menurut saya, Gadjah Mada tidak perlu jatuh merek karena kasus ini. Ini sama saja kalau UGM kecurian, apa lalu harus merasa jatuh? Kan, tidak perlu? Di sini ada semacam moral hazard. Keputusan membatalkan gelar doktor Ipong bukan karena masalah akademik saja, tapi juga menyangkut moral.
Bagaimana ceritanya disertasi Ipong bisa lolos begitu saja?
Ini manipulation by design. Jadi, kita tidak bisa tahu. Proses pendahuluannya sudah lewat ujian luar biasa. Maklum, kalau Pak Loekman yang membimbing, disertasi bisa dikembalikan berkali-kali sampai yang dibimbing teler betul. Pada waktu itu disepakati agar ada interview dalam metode pembuktiannya. Tapi kita tidak tahu kalau ternyata untuk interview itu dia mengambil data dari orang lain.
Apa tidak ada mekanisme yang bisa mengontrol?
Tidak mungkin. Soalnya, yang dicontoh itu data dan persis. Mestinya, kalaupun ia menggunakan data orang lain, harus bisa di-rephrase. Artinya, dibuat kalimat baru. Secara ilmiah juga tidak apa-apa, apalagi ada footnote-nya. Dulu, ada satu bab disertasi saya yang di-rephrase dari buku Herbert Feith.
Apa langkah UGM untuk mencegah terulangnya kasus ini?
Ini suatu proses dalam masalah akademik yang memerlukan kejujuran.
Jadi, tidak ada jaminan.
Pengacara Ipong pernah mengancam mau menggugat kalau gelar itu dibatalkan. Apa jawaban Anda?
Apa pun yang terjadi, universitas harus siap menghadapinya.
Mengapa universitas tidak memberikan kesempatan kepada Ipong untuk memperbaiki disertasinya?
Tidak. Kesalahan akademik masih bisa dipertimbangkan, misalnya salah menuliskan data. Tapi moral tidak bisa dikoreksi.
Seberapa sering UGM mengalami kasus semacam ini?
Sudah beberapa kali. Yang kita panggil dua orang. Yang satu lagi—dalam kasus tesis S-2—mengaku terus terang karena sakit. Sebetulnya yang nyontek bukan dia karena dia membayar orang untuk membantu. Nah, orang ini yang meniru data dari skripsi lain. Kasus ini bisa kita maafkan karena tidak sepenuhnya dia punya maksud seperti itu. Dia sudah mau dikeluarkan. Untuk menyelamatkan kuliahnya, dia minta bantuan temannya.
Anda pernah menemukan sendiri kasus seperti ini?
Pernah ada kasus dua orang mahasiswa yang menulis paper. Saya terkejut karena judulnya bisa sama dan isinya sama. Mereka saya panggil satu per satu. Dan mereka sama-sama mengaku tidak menyontek. Terakhir, baru ketahuan bahwa dua orang ini tidak saling kenal, tapi meniru sumber yang sama.
Menurut Anda, apa yang bisa dipetik dari kasus semacam ini?
Sekali lagi, kalau menyangkut kejujuran, tidak ada satu cara pun yang bisa membasmi. Dalam komunitas yang sangat terhormat saja hal ini masih bisa terjadi.
Sebagai pembimbing Ipong, bagaimana Anda menerima kenyataan ini?
Tidak apa-apa. Pembimbing utamanya Pak Umar Kayam. Saya jadi pembimbing keduanya. Ketika Umar Kayam tidak sanggup lagi mengikuti karena kesehatannya, ia meminta saya menggantikannya. Dalam proses itu, saya minta bantuan Pak Nasikun—dari Fisipol UGM—dan Pak Loekman Soetrisno. Proses pembimbingannya sangat intensif. Namun, pada saat-sat akhir, Ipong lama tidak ketemu saya. Sekitar dua setengah tahun dia menghilang. Saya pikir dia di lapangan. Terakhir, tiba-tiba disertasi itu sudah jadi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo