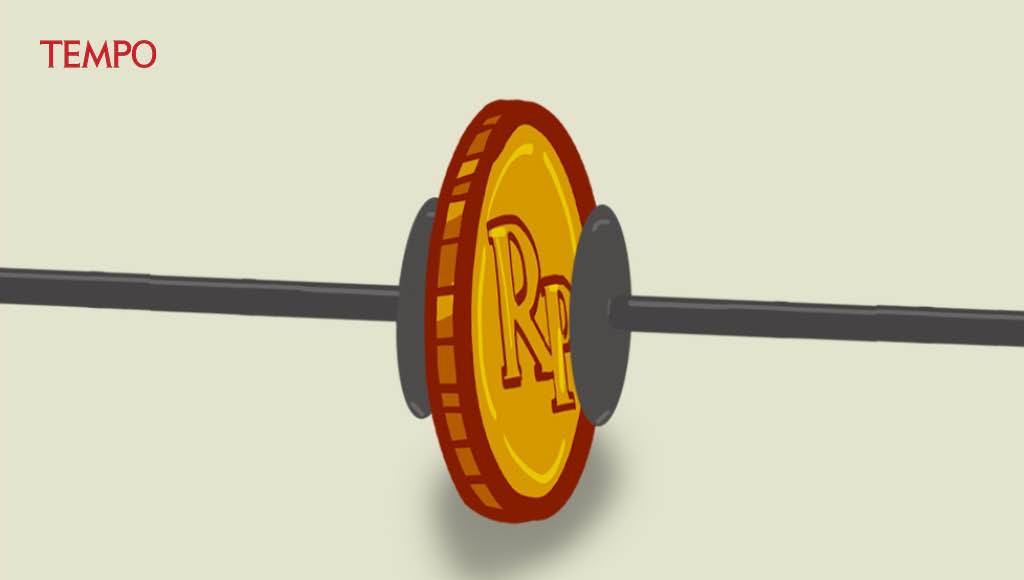DUA pemegang saham utama PT Abattoir Surya Jaya, Pemda Surabaya dan Pemda DKI Jakarta, kini sedang tarik urat. Perusahaan patungan yang bergerak di bidang jasa pemotongan hewan itu mulai jadi pusat perhatian gara-gara dinyatakan bangkrut oleh direksinya. Lebih dari Rp 800 juta uang perusahaan tak bisa dipertanggungjawabkan. Utang kepada pemerintah, dan pihak Belgia, juga tak bisa dibayar. Krisis perusahaan yang melibatkan banyak kepentingan itu, tentu, belum akan berakhir, sekalipun pekan ini H.M. Djoewaeni, direktur produksinya, bakal diberhentikan -- diganti seorang pejabat dari Pemda Surabaya. Adalah Djoewaeni yang, belum lama ini, menyatakan rumah pemotongan hewan itu sudah tidak mampu lagi memenuhi segala kewajibannya, ketika ada acara dengar pendapat dengan DPRD. Laporan keuangan hanya menyebut rugi Rp 100 juta pada 1982 dan 1983 rugi Rp 250 juta, tidak lebih dari itu. "Uang yang ada di kas tinggal Rp 3 juta," kata Djoewaeni. Usaha melacak laporan keuangan Surya Jaya, yang dilakukan akuntan publik, mengalami banyak kesulitan gara-gara sejak berdiri, 1971, perusahaan patungan itu sudah tujuh kali ganti direksi, dan sekali mengadakan pengalihan saham. Akibatnya, kondisi pembukuan sulit diperiksa: bukti-bukti transaksi banyak yang tak memenuhi syarat. Sebagai sebuah rumah pemotongan hewan (RPH), dengan perlengkapan modern dari Belgia, Surya Jaya tampaknya kurang hoki. Mesin piawai miliknya itu jadi seperti tak berguna, gara-gara sapi yang dipotong di situ jumlahnya selalu berada di bawah kapasitas. Pernah terjadi, selama 1983, sapi yang dipotong hanya berjumlah 1.600 ekor. Padahal, konon, kapasitas mesin yang dimilikinya mampu memotong 600 ekor sapi sehari. Langkanya pemilik ternak mau memotongkan sapi di situ, agaknya, karena Surya Jaya memasang tarif terlalu mahal: Rp 15 ribu untuk setiap pemotongan sampai jadi daging. Dibandingkan dengan RPH Cakung milik Perusahaan Daerah Dharma Jaya, Jakarta, yang memasang Rp 6.000, tarif Surya Jaya memang kelewat mahal. Akibatnya bisa diduga: perputaran dana perusahaan terganggu. Sadar akan prospek yang kurang baik itu, maka PT Wirontono dan Bhirawa Development Corp., yang masing-masing menyetor Rp 50 juta untuk mendirikan perusahaan bermodal Rp 200 juta itu mengundurkan diri. Pembelinya, di tahun 1982 itu, adalah Induk Koperasi Unit Desa. Masuknya Inkud ke situ, rupanya, mengundang Departemen Keuangan memberi tambahan modal. Uang sebesar hampir Rp 800 juta disuntikkan ke Surya Jaya, yang diambil secara bertahap, dari persetujuan Rp 1,3 milyar. Pemakaian uang itu, yang dilakukan antara 1982 dan 1983, ternyata tidak jelas. "Uang sebanyak itu dijadikan bulan-bulanan, hingga sisanya tinggal Rp 3 juta," kata Djoewaeni, yang masuk ke situ pada 1984. Asmawi Manaf, Kepala Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal (BPIPM) DKI Jakarta, kesal betul melihat kekacauan di sana. Ia baru sadar laporan keuangan dari direksi lama, yang selama itu dipegang pihak Pemda Surabaya, ternyata hanya merupakan laporan "ABS". Sebagai komisaris, Pemda Jakarta, yang seharusnya ikut mengawasi, hanya menerima laporan jarak jauh. "Ke mana perginya uang sebanyak itu? Kalau perusahaan dikatakan oke, tapi mana perinciannya?" kata Asmawi, bekas Wagub DKI Jakarta itu. Reorganisasi kemudian dilakukan: jabatan direktur utama dan komisaris utama lalu dipegang pihak Jakarta. Sebagai komisaris utama sejak Juli 1985 itu, Asmawi Manaf minta seluruh direksi sebelum periode itu memberikan pertanggungjawaban keuangan. Toh, tidak lancar. Dalam keadaan terdesak seperti itu, Surya Jaya kemudian minta pihak Belgia agar mengundurkan tagihan utang pokoknya sebesar Rp 1 milyar, dan bunganya yang membesar Rp 6 milyar. Bahkan, untuk membantu agar Surya Jaya bisa bernapas, Departemen Keuangan menyuntik lagi Rp 170 juta. "Dana itulah yang kami kembangkan," kata Djoewaeni. Tapi masa depan Surya Jaya tetap merupakan teka-teki. Lihat saja keadaan yang dihadapi rekannya, RPH Dharma Jaya. Perusahaan milik Pemda Jakarta ini, tiap hari hanya memotong 400 ekor sapi dan kerbau yang dikirim secara tetap oleh 30 pedagang. "Padahal, untuk mencapai titik impas, kami harus memotong sedikitnya 800 ekor," kata Drh. Mustafa Said, direktur utamanya. Sasaran itu tidak tercapai, gara-gara, "Di sini masih banyak tempat pemotongan liar." Mesin modern yang diperoleh dari kredit IGGI, dengan kemampuan memotong 110 ekor hewan per jam, sekarang jadi lebih banyak dimakan angin. Mungkin karena September 1984 lalu tarif potong dinaikkan dari Rp 2.900 jadi Rp 6.000, maka jumlah sapi dan kerbau yang dipotong di Cakung turun dari 182 ribu pada tahun 1981 (tahun 1983 pernah 200 ribu) jadi sekitar 160 ribu ekor, tahun lalu. Begitulah hidup dari dua RPH di Surabaya dan Jakarta. Keadaannya terlihat kembang kempis, lantaran banyak orang tak peduli membeli daging berstempel atau tidak. Pemilik ternak sendiri juga bersikap demikian - ketentuan yang mengharuskan semua daging seharusnya lolos dari tempat resmi dianggap hanya merepotkan saja: baik mengenai tarif bantai maupun tetek bengeknya. Bantai sendiri, mendingan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini