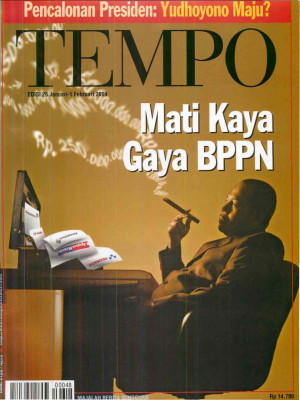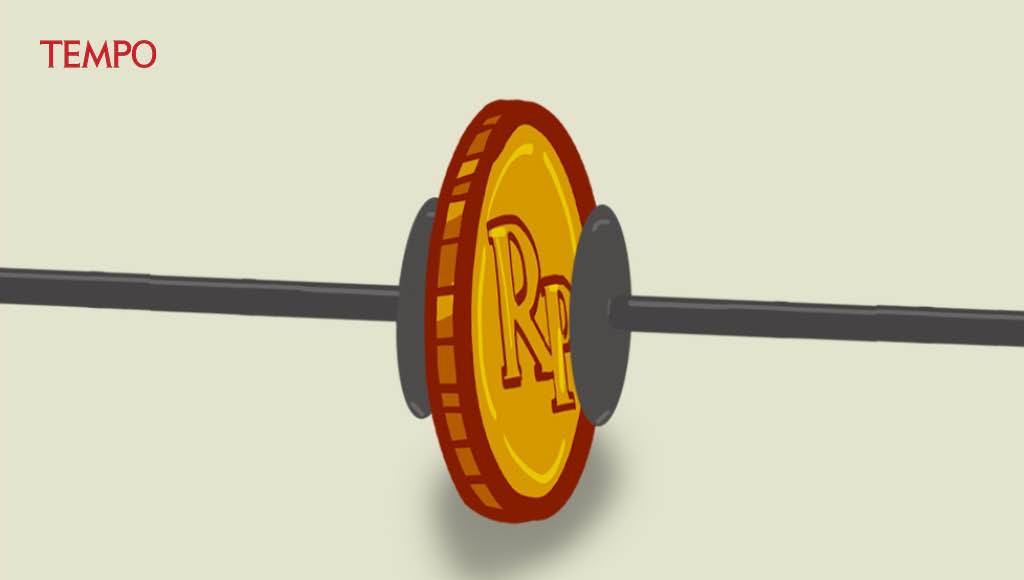Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jarum jam baru beranjak menunjukkan pukul enam pagi ketika Mubin Usman dan truk pick-up tuanya melaju dari Depok menuju Glodok, Jakarta Barat. Ia mengangkut puluhan pohon jeruk yang ditanam dalam pot-pot berukuran besar dan sedang. Didampingi dua orang anak buahnya, pemilik "Wijaya Tani" ini tampak gembira dan bersemangat memulai harinya, pagi itu.
Hari-hari menjelang Imlek, tahun baru menurut penanggalan Tionghoa, merupakan sumber kebahagiaan tersendiri bagi Usman. Meski ia tak merayakannya, hari besar itu memercikkan peluang bertambahnya rezeki. Soalnya, pada saat itulah tanamannya (pohon jeruk) laku keras.
Sepuluh hari menjelang Imlek, ayah tiga anak ini sudah asyik nongkrong di samping truknya, menjajakan pohon-pohon kebanggaannya.
Kendaraannya gampang dikenali di tengah padatnya Jalan Pancoran, Glodok, oleh warga Tionghoa yang mencari aneka kebutuhan hari besar itu. Truknya ia parkir begitu saja di pinggir jalan, dengan pohon-pohon masih bertengger dalam bak. Sebagian dijejerkan di tepi jalan. "Pokoknya asal ada tempat ramai, ya, di situ saya berhenti," ujarnya sambil tersenyum lebar.
Usman memang layak bangga. Kala barang impor dari Hong Kong, RRC, dan Taiwan menyerbu pasar, ia tetap pede menjual pohon jeruk produk lokal. "Aduh segernya," cetus seorang ibu menatap pohon-pohonnya sambil tercengang. Pengunjung pasar acap berhenti sejenak dan bertanya ini-itu pada Usman atau karyawannya. Ada saja orang yang tertarik "me-booking" beberapa pohon. Maklum, tanaman di pot bakal susah ditenteng ke sana kemari kalau si pembeli masih ingin berkeliling pasar.
Rata-rata pohon jeruk yang dijual berumur 2-5 tahun dengan tinggi beragam dari 30 sentimeter hingga satu meter. Jenisnya adalah kinkid atau nagami, yang bibitnya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. "Katanya, sih, aslinya berasal dari dataran Tiongkok juga," kata Usman.
Sebagian pohon sudah ditata daun dan dahannya sedemikian rupa sehingga terlihat lebih rapi dan cantik. Sebagian lagi berupa pohon biasa dengan cabang dan daun yang masih alami. Buahnya juga tampak bergantungan di sana-sini. Ada yang masih hijau, ada pula yang sudah agak kekuningan.
Gagasan menjual pohon jeruk menjelang Imlek ini bermula dari usahanya menjual tanaman dengan berkeliling. Waktu berdagang di Senayan, beberapa kali ia didatangi warga Tionghoa yang mencari pohon jeruk. "Mereka memerlukannya untuk merayakan 'Lebaran'-nya orang Tionghoa."
Sepanjang pengetahuannya, pohon jeruk melambangkan keberuntungan. Namun, pohon jeruk acap digunakan sebagai tempat untuk menggantungkan amplop angpao. "Jumlah angpao menunjukkan jumlah anak dan cucu yang dimilikinya."
Usman menjual pohon jeruknya bervariasi dari Rp 50 ribu hingga Rp 300 ribu. Dalam sehari, rata-rata ia bisa menjual 10-11 pot pohon jeruk. Bahkan tahun lalu saja semua pohon yang dibawanya ludes. Padahal biasanya ia mengangkut 20-25 pot dengan berbagai ukuran. "Kita bahkan sampai minta agar ditambah," cerita salah seorang karyawannya. Pembelinya termasuk beberapa hotel berbintang, seperti Borobudur dan Shangri La.
Bisnis musiman menjelang Imlek memang marak beberapa tahun terakhir. Sejak dibebaskan pemerintah lima tahun lalu, perayaan tahun baru yang juga disebut "Sin Tjia" ini kian meriah. Tengok saja pusat-pusat pecinan di berbagai daerah di penjuru negeri. Lampion, hiasan naga, kue dan permen, tiruan pohon mei hwa, dan pernak-pernik lainnya bisa ditemukan di mana saja. Warna merah dan emas mendominasi pertokoan dan mal di kota-kota besar. Dan peluang bisnis pun terbentang lebar.
"Khusus Imlek ini, omzet kami naik sekitar 300 persen dari hari biasanya," kata Edy, yang membantu ayahnya, Ahua, mengelola Toko Putra Jaya di Jalan Gajah Mada, Pontianak, Kalimantan Barat. Sehari-harinya toko Ahua menjual barang kebutuhan sembahyang, seperti dupa, setanggi, uang-uangan kertas, dan lainnya. Saat Imlek, mereka lalu menjual pelbagai barang kebutuhan Imlek.
Hal senada diakui pula oleh Ho Peng Hay, yang menjual lampion di Pasar Glodok. Peng-peng—sapaan akrabnya—menceritakan bahwa usaha menjual atribut khas Imlek sudah merupakan bisnis keluarganya sejak bertahun-tahun lalu. "Sejak sebelum Glodok meleduk."
Pada hari biasa, bersama saudara-saudaranya, ia menjual barang antik khas Tionghoa berupa patung kuningan beraneka rupa. "Jualan barang begituan belum tentu sehari dapat duit," tuturnya.
Begitu Imlek tiba, mau tak mau usahanya kelimpahan rezeki. Tak pelak, persaingan makin ketat. Pohon jeruk Usman saja sudah mulai dikepung serbuan pohon jeruk impor yang lebih apik. Jika tak jeli dan kreatif, tak mudah pula berjualan pernak-pernik khas Imlek, yang umumnya sudah dibanjiri produk dari Taiwan, Cina, Hong Kong, Malaysia, ataupun Singapura.
Untuk menyiasati agar barang dagangannya tetap diminati, Peng-peng mendekor sendiri lampionnya. Saat diimpor, lampion itu—yang ia sebut tenlung—masih polos. Hanya ada hiasan kuningan di sumbu atas dan bawahnya. Supaya tampil beda, ia merangkai lampionnya menjadi dua tingkat. Ukurannya pun lebih mungil, hanya berdiameter kira-kira 15 sentimeter. Di antara dua lampion, ia membubuhkan kawat yang memancang sekitar 10 sentimeter di kiri dan kanan sebagai tempat gantungan hiasan ucapan "Gong Xi Fa Cai" dalam aksara aslinya. Ia memberikan hiasan gantungan berupa petasan mainan atau buah jeruk tiruan berwarna emas di bawahnya. Tak lupa, lampion itu dilengkapi bohlam plus kabelnya.
"Untuk lampion seperti ini, memang hanya kami yang membuatnya," kata Peng-peng seraya sibuk menempelkan kertas emas.
Peng-peng memetik keuntungan Rp 10 ribu-Rp 15 ribu per lampion. Setiap harinya, ada sekitar 15 buah yang ia hasilkan dan rata-rata terjual sekitar 10 buah.
Meski begitu, Peng-peng tak akan lupa sulitnya berdagang di masa lalu. Kucing-kucingan dengan aparat adalah hal biasa. "Kami khawatir sekali semua barang bakal diangkut mereka. Itu berarti rugi jutaan rupiah," tuturnya mengenang. Biasanya petugas bertanya ini-itu, lalu mengangkut sebagian barang dagangannya. "Kami mau periksa apakah barang-barang ini ada muatan politisnya," kata Peng-peng menirukan ucapan petugas. Lelah bermain petak umpet, akhirnya mereka "bernegosiasi". Ujung-ujungnya, ya, duit lagi.
Kendati demikian, kebebasan merayakan datangnya musim semi itu tak sepenuhnya menyembuhkan luka lama akibat diskriminasi selama berpuluh tahun. Peng-peng, misalnya, tetap menyebut dirinya orang Betawi asli.
Ia terpaksa menghilangkan nama marganya, "Ho", dan menggunakan nama ibu agar surat-surat kependudukannya lengkap. Tangannya bergetar saat menuliskan namanya. Nama marganya, yang sempat ditulis, dilingkari. "Peng Hay saja," ujarnya lirih.
Xin nian kuai le (selamat tahun baru), Ho Peng Hay. Gong xi fa cai (semoga rezeki melimpah atasmu).
Dara Meutia Uning, Harry Daya (Pontianak)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo