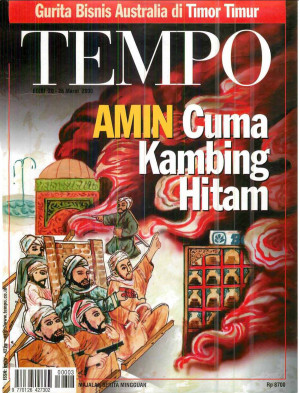Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perekonomian dunia yang kalang-kabut ketika harga minyak meroket pada awal 1970-an tentunya masih lekat teringat. Ketika itu negara-negara Arab produsen minyak sepakat mengembargo negara industri karena jengkel melihat dukungan mereka terhadap Israel. Dunia pun dilanda resesi. Rendahnya suplai karena melemahnya proses produksi membuat harga-harga merangkak naik. Kejadian itu terulang—meski dengan skala lebih rendah—ketika suplai minyak dunia anjlok setelah serbuan Irak ke Kuwait pada Oktober 1990.
Namun, zaman telah berubah. Kenaikan harga minyak yang terjadi beberapa waktu terakhir tak ubahnya lengkingan peluit di padang pasir, nyaris tak berakibat apa-apa. Padahal, minyak Pantai Utara (brent), yang menjadi patokan harga minyak dunia, pada 8 Maret silam menyentuh angka US$ 32 per barel, sebelum akhirnya melorot lagi menjadi US$ 30. Apa pun alasannya, harga itu adalah yang tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Selama dua tahun silam, harga brent cuma US$ 13 sampai US$ 16 per barel.
Produsen minyak pun seperti menangkap durian runtuh. Minyak Minas Indonesia, yang pada semester pertama 1999 bersikutat di angka US$ 15,2 hingga US$ 17,93 per barel, misalnya, memasuki bulan September mulai dihargai US$ 21,96. Harga itu pelan-pelan merambat naik hingga Februari lalu mencapai US$ 26,49. Padahal, patokan harga minyak dalam APBN cuma US$ 20 per barel. Lumayanlah.
Kenaikan harga kali ini dipicu oleh banyak hal. Negara anggota OPEC masih setia dengan pagu produksi yang sebesar 22,97 juta barel per hari. Jumlah itu diperoleh setelah melalui perundingan sangat alot guna mendongkrak harga. Pada saat bersamaan, suplai dari Norwegia, produsen terbesar kedua setelah Arab Saudi, masih utuh di dalam tangki-tangki di pelabuhan pengiriman karena dicegat badai Laut Utara. Para buruh minyak di Nigeria pun celakanya sempat ngambek sehingga produksi kilang minyaknya macet selama beberapa hari. Walhasil, suplai minyak dunia seret.
Gangguan-gangguan itu mestinya berakibat serius. Permintaan akan minyak pada saat seperti ini sedang tinggi-tingginya. Maklum, stok di negara maju telah menipis karena telah dikuras untuk menutup lonjakan kebutuhan energi selama musim dingin lalu. Musim semi adalah saat negara-negara di belahan bumi utara mulai mengisi tandon minyak mereka kembali. Di samping itu, mesin yang sempat menganggur gara-gara krisis ekonomi di beberapa negara selama dua tahun terakhir juga mulai bergerak kembali (kecuali Indonesia tentunya). Maka, hukum ekonomi yang elementer kembali berlaku: ketika suplai berkurang dan permintaan meningkat, harga pun melonjak.
Namun, mengapa perekonomian dunia seakan-akan tak bereaksi, bahkan cenderung adem-ayem? Menurut majalah The Economist edisi 11 Maret, harga minyak sebenarnya memang seperti laju kereta roller-coaster: selalu mengalami lonjakan setelah sebelumnya terjerembap. Harga pada awal 1999 dalam arti riil (setelah disesuaikan dengan inflasi) adalah yang terendah sejak 1972. Dengan hitung-hitungan ini, kenaikan harga kali ini sebenarnya cuma separuh tingkat harga pada 1981.
Penurunan produksi yang dilakukan oleh OPEC kali ini juga sifatnya sukarela, bukan akibat gonjang-ganjing keadaan seperti dulu-dulu. Dengan begitu, reaksi pengusaha dan konsumen juga tak sampai tergopoh-gopoh, yang kerap malah mendongkrak harga.
Faktor perkembangan ilmu dan teknologi juga mengambil peran. Konservasi energi kini menjadi ideologi di hampir setiap negara sembari terus berusaha meningkatkan penggunaan energi alternatif nonmigas seperti batu bara, gas, air, angin, bahkan nuklir. Dengan menggunakan data anjloknya pertumbuhan sektor migas dalam PDB di Indonesia, ekonom CSIS Pande Radja Silalahi menyebut penggunaan migas di negeri ini sejak 1981 menurun hingga 45 persen.
Alasan lainnya adalah semakin menurunnya aktivitas industri berat di negara-negara maju. Sebaliknya, industri piranti lunak dan internet semakin diminati karena mampu mengisi pundi-pundi kekayaan perusahaan lebih cepat dan lebih banyak. Sementara itu, resesi pada 1970-an yang juga karena lonjakan harga minyak terjadi saat perekonomian negara-negara kaya sedang memanas dan inflasi sudah mulai meninggi. Begitu suplai minyak seret, perekonomian pun seperti bangunan yang terbakar: harga-harga langsung membubung hingga sulit dijangkau pasar.
Apakah ini berarti kenaikan harga minyak sudah bisa dihiraukan sama sekali? Tunggu dulu. Menurut bekas Gubernur OPEC (1986-1988) Purnomo Yusgiantoro, peranan minyak sampai kini masih belum tergantikan, terutama di sektor transportasi. Dari total kebutuhan minyak di AS yang 17 juta barel per hari, 10 juta barel di antaranya dialokasikan untuk transportasi. Separuh bahan bakar pembangkit listrik di Jepang juga masih berupa minyak bumi. Maklum, selain minyak masih sangat populer, energi alternatif seperti batu bara dan gas masih dianggap lebih mahal. Energi nuklir masih membikin ngeri. Di samping itu, minyak kini tak sekadar menjadi bahan bakar, tapi juga bahan baku, antara lain untuk industri petrokimia. Jadi, "Minyak secara absolut masih dominan," kata Purnomo, yang kini Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional.
Resesi akibat lonjakan harga minyak sebenarnya seperti hukum karma. Menurut Purnomo, resesi itu baru akan terasa dalam jangka waktu enam bulan atau setahun kemudian. Sebenarnya, lejitan harga minyak membawa dua siklus. Siklus pertama terjadi ketika ia mendongkrak biaya produksi di negara industri. Akibatnya, pada siklus kedua, harga produk ekspor negara-negara itu pun melonjak, termasuk barang-barang modal yang diimpor oleh negara berkembang. Proses inilah yang meledakkan resesi.
Hingga saat ini, lonjakan harga memang baru menyenggol perekonomian AS. Seperti dilaporkan oleh harian International Herald Tribune, lonjakan harga minyak telah mendongkrak indeks harga konsumen bulan Februari di AS hingga 1 persen, (kenaikan tertinggi dalam 10 tahun terakhir), karena meningkatnya biaya bahan bakar, pemanasan ruang, dan lainnya. Indeks harga di tingkat produsen bahkan telah menembus lonjakan 4 persen, yang terjadi setelah invasi Irak ke Kuwait pada Oktober 1990.
Kunci masalah sebenarnya adalah soal kurun waktu berlakunya harga yang tinggi itu. Bila hal itu bertahan lama, analisis Purnomo memang tak bisa dipandang sebelah mata. Kenaikan harga minyak dapat menurunkan output perekonomian karena menekan pendapatan riil dan belanja rumah tangga. Ia juga dapat menggiring ke arah perubahan terms of trade yang memindahkan pendapatan dari konsumen ke produsen.
Laporan dari OECD menyebutkan, kenaikan harga minyak akan men-dorong laju inflasi di Eropa. Sebab, pasar kerja yang ketat cenderung merespons peningkatan harga. Jepang lebih tragis karena ketergantungannya pada minyak bumi membuat setiap kenaikan US$ 10 per barel minyak akan meraibkan output hingga 0,4 persen. Tapi yang bakalan paling menderita adalah emerging economies, karena total penggunaan energi per unit PDB mereka empat kali lipat ketimbang negara maju. Pada 1973, negara-negara ini hanya mengonsumsi 29 persen dari suplai minyak dunia. Angka itu kini mencapai 43 persen.
Negara maju pun mau tak mau memang harus sedia payung sebelum hujan. Akhir Februari lalu Menteri Energi Bill Richardson bahkan harus pergi ke Arab Saudi untuk melobi produsen terbesar itu agar turut mengendalikan harga minyak. Negara-negara industri juga telah meminta OPEC agar melonggarkan keran kuota hingga 2-3 juta barel per hari.
Bagi OPEC sendiri, urusan kuota dan harga minyak ibarat orang memegang burung. Kalau harga terlalu rendah, mereka kelimpungan. Tapi, harga yang terlalu tinggi malah menjadi bumerang. Makanya, dengan jumlah pasokan minyak dunia saat ini, harga yang dianggap paling pas adalah US$ 17,18 sampai US$ 25 per barel. Untuk menanggapi permintaan negara maju, OPEC memang merencanakan tambahan suplai sebanyak sejuta barel, yang akan diputuskan dalam pertemuan di Wina 27 Maret nanti. Ini lebih untuk mengetes pasar.
Tambahan suplai sejuta barel itu akan berlaku mulai April, ketika permintaan minyak dunia biasanya mulai melemah karena tandon negara-negara utara sudah terisi penuh. Kalau cara ini gagal menekan harga, barangkali kuota memang harus dilonggarkan. Jika terjadi sebaliknya, keran kilang memang harus diketatkan kembali.
Candra, Oman Sukmana, dan Dwi Wiyana (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo