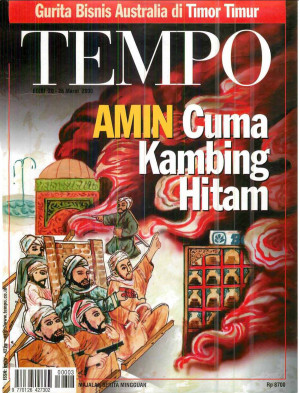Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
| When Cultures Collide | ||
| Penulis | : | Richard D. Lewis |
| Penerbit | : | Nicholas Brealey Publishing, London, 2000 |
Hidup sudah memasuki era mobilisasi pesat. Dalam rentang waktu kurang dari 24 jam, seseorang bisa pindah dari satu lahan budaya ke lahan budaya lain. Kegiatan bisnis pun ikut malang-melintang di permukaan bumi. Kaum pengusaha merasa, jika mereka tidak menyingsingkan lengan baju dan mulai membongkar lapisan muka dari budaya berbagai negara, mereka akan terisolasi dari kegiatan global yang sangat krusial dalam pertumbuhan ekonomi ini.
Di beberapa negara industri maju, pendidikan dan latihan untuk mengembangkan kepekaan terhadap budaya lain sudah menjadi lazim. Yang paling banyak memanfaatkan pendidikan dan latihan ini adalah para eksekutif dari perusahaan, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah yang berencana melintasi perbatasan negara, yang juga berarti melintasi budaya.
Richard D. Lewis, peneliti sosial, pakar budaya, dan presiden sebuah lembaga pendidikan bahasa dan kepekaan lintas budaya di Inggris dengan cabang di 35 negara lain, dengan jeli melihat peluang untuk menyosialisasikan keterampilannya. Pada 1989, Lewis memulai sebuah penerbitan triwulanan, Cross Culture, yang sirkulasinya kian tahun kian luas. Akhirnya, Januari lalu, Lewis menerbitkan bukunya, When Cultures Collide.
Sejak awal, Lewis sudah mengakui betapa banyaknya perangkap jika seseorang menggunakan stereotip dangkal dalam menilai anggota suatu budaya. Karena itu, Lewis memberikan contoh persepsi yang berdasarkan stereotip. Contoh-contoh ini didampingi daftar elemen dari dalam budaya yang menyebabkan terbentuknya sebuah tingkah laku. Namun, dia juga menekankan realitas ciri-ciri kolektif dengan penjelasan yang logis.
Menurut Lewis, kita adalah hasil pembinaan orang tua kita, yang menurunkan nilai-nilai moral, yang diserap dari komunitas tempat tinggal kita. Lingkunganlah yang kemudian membentuk norma-norma dasar, apa yang baik dan apa yang buruk, dan menyesuaikan tingkah laku kita dengan norma-norma itu.
Lewis juga berusaha mengupas ciri-ciri budaya dari berbagai penjuru dunia dan membaginya ke dalam tiga kategori: budaya linear-aktif, multi-aktif, dan reaktif. Bisa dibayangkan bila seorang pengusaha Amerika Serikat (kelompok linear-aktif) bernegosiasi dengan seorang pengusaha Indonesia (kelompok reaktif). Sang pengusaha Amerika Serikat akan merasa geregetan karena mitra negosiasinya tidak membuka kartu sejak awal seperti dirinya. Akibatnya, pengusaha ini merasa selalu meraba-raba dalam kegelapan. Dalam upayanya mengetahui posisi mitranya, dia pun mendesak sang mitra untuk membuka kartunya. Di pihak lain, sang pengusaha Indonesia merasa terpojok sehingga tidak merasa mantap. Dia perlu waktu untuk memikirkan saran mitra negosiasinya dan masih harus mengadakan pengecekan kepada atasannya. Jika proses ini berlangsung tanpa rasa saling mengerti dari kedua pihak, negosiasi akan buntu.
Sebelum mencapai tahap negosiasi serius, setiap pihak harus merasa cukup nyaman dan mantap sehingga perlu menyimak bahasa nonverbal pihak lain. Lewis menuturkan satu anekdot yang cukup berarti. Dalam sebuah pesta koktail di Tokyo, dia melihat bagaimana seorang pengusaha Brasil berbicara dengan seorang Jepang sambil erat-erat memegangi lengan pengusaha Jepang itu untuk menunjukkan rasa persahabatannya. Yang diajak berbicara malah mengambil langkah surut sambil menjaga keseimbangan tubuhnya, sementara tangannya memegang gelas minuman. Namun, sang pria Brasil tetap maju. Dalam rentang 20 menit, mereka sudah menempuh jarak setengah ruangan, sebelum si Jepang akhirnya minta maaf dan mencari perlindungan ke kamar kecil dengan tangan yang masih menggenggam gelasnya.
Lumrah kalau orang merasa budayanyalah yang paling andal dan normal. Bila ada pergesekan yang membawa sengketa, masing-masing cenderung merasa bahwa budaya lawanlah yang salah.
Kelemahan dari buku ini, Lewis tidak mengkaji setiap budaya secara merata. Dalam memaparkan budaya Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Finlandia, Lewis bagai menelusuri jalan raya dan lorong-lorong sempitnya karena kajiannya begitu mendetail. Sementara itu, budaya negara lain dibahas selintas seolah dia hanya seorang penumpang mobil yang menyaksikan pemandangan dari balik kaca mobil.
Dewi Anggraeni
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo