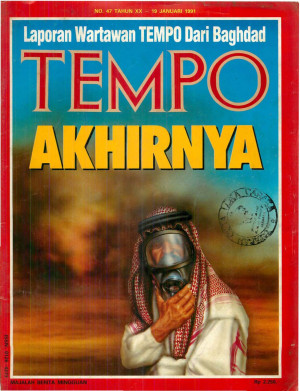BENDERA putih sudah dikibarkan oleh Gappri ke arah SK Menteri Perdagangan yang mengatur tata niaga cengkeh. Artinya: Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia menerima tata niaga baru tersebut. Tapi, seperti dikatakan oleh Ketua Gappri Soegiharto Prayogo, pihaknya tetap tidak bersedia duduk dalam BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh). Ditambahkannya, pernyataan penolakan itu sudah dikirimkan kepada Menteri Perdagangan sebelum SK resmi keluar. "Tembusannya kami kirimkan ke Pak Harto sebagai laporan. Bukan kami mengirimkan penolakan itu kepada beliau," kata Soegiharto kepada TEMPO Senin pekan ini. Di BCN (Badan Cengkeh Nasional), Gappri juga tetap mewakilkan suaranya lewat Departemen Perindustrian. "Karena Departemen Perindustrian sudah duduk di BCN, kami tidak perlu lagi ada di situ. Saya percaya, Departemen Perindustrian akan memperhatikan nasib Gappri," Soegiharto menegaskan. Nasib itu terutama masih belum jelas, ketika menjelang panen besar Februari ini, patokan harga cengkeh belum juga diumumkan Pemerintah. Dan, tampaknya setiap pihak "mengunggulkan" harga yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Gappri mengharapkan franko pabrik Rp 9.500, sedangkan kalau harga dasar ke petani Rp 7.000-Rp 8.000 per kg, seperti diisyaratkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kumhal Jamil, maka harga ke pabrik bisa lebih dari Rp 10.000 per kg. Lalu, kalau harga patokan itu Rp 10.000, seperti diusulkan anggota BPPC Jantje Worotitjan, cengkeh itu akan tiba di tangan fabrikan dengan harga sekitar Rp 13.500. Dalam hal ini BPPC yakin, pihak pabrik rokok tidak akan merugi. Seperti diungkapkan Ketua BPPC Tommy Soeharto kepada TEMPO, ketika harga cengkeh Rp 8.000 per kg pertengahan tahun lalu, PR Gudang Garam malaporkan ke Bea Cukai bahwa harga beli cengkehnya (sebagai komponen produksi) menjadi Rp 13.500 per kg. Terlepas dari harga, harus diakui bahwa tak ada negara di dunia yang meributkan tata niaga cengkeh, kecuali Indonesia. Bahkan dalam Seminar 25 Tahun Pembangunan Ekonomi Orde Baru di Hotel Sari Pan Pacific, Jumat pekan silam, tata niaga baru itu tak urung dikritik juga. Seorang pakar ekonomi menyatakan dengan terus terang bahwa tata niaga untuk komoditi seperti cengkeh sebenarnya tidak perlu. "Cengkeh itu kan bukan beras," ujarnya menggebrak. Cengkeh memang bukan beras, tapi Indonesia sudah telanjur jadi produsen cengkeh terbesar sekaligus konsumen terkuat. Rempah berwarna cokelat ini memang sangat vital bagi industri kretek, dan sanggup menyetor cukai Rp 1,77 trilyun ditambah PPn plus PPh, total Rp 3 trilyun. Pada dasarnya, Indonesia mengisi 70% pangsa pasar internasional, dengan produksi rata-rata sampai 80 ribu ton per tahun. Menurut hasil survei Pusat Penelitian Cengkeh (PPC) Bogor, negara lain yang menghasilkan cengkeh adalah Zanzibar (7.000-12.500 ton per tahun), Madagaskar (7.000-11.000 ton per tahun), Brasil (3.000-8.000 ton), Sri Lanka (1.000-2.500 ton), serta India, Comoros, Malaysia, dan Grenada masing-masing di bawah 2.000 ton per tahun. Sebagai konsumen terbesar, Indonesia menelan 69.000 ton cengkeh. Di peringkat kedua mungkin Singapura, dengan daya serap 9.640 ton. Yang lain, jauh di bawah itu. Konsumen di negeri kita, jelas, adalah pabrik rokok kretek. Lalu, siapakah yang disebut petani cengkeh? Ketua PPC Dr. Ir. Syafril Kamala mengatakan kepada TEMPO, petani cengkeh adalah mereka yang rata-rata memiliki lahan seluas 0,7 ha, berisi 96 pohon. Dari segi kepemilikan, perkebunan cengkeh kita dibagi menjadi tiga kategori. Perkebunan swasta (pada 1989 menguasai lahan 17.805 ha), perkebunan negara (5.426 ha), dan perkebunan rakyat (738.977 ha). Pada 1980, muncul istilah petani berdasi, yakni kaum pemilik modal yang tergiur oleh harapan emas dari kembang cengkeh. Mereka cenderung memilih lahan di lokasi yang dekat dengan sarana transportasi. "Petani berdasi kebanyakan beroperasi di Jawa dan Lampung," kata Syafril Kamala. Menurut pengamatannya, mereka ini menguntungkan petani kecil. Soalnya, ketika panen, mereka tidak buru-buru menjual sehingga harga tidak jatuh. Dari sudut stabilitas harga itu pula, Syafril melihat, "Kehadiran BPPC diperlukan sekali. Dengan demikian, akan tercipta suatu harga patokan." Sebagai kekuatan yang hendak menjaga stabilitas harga, unsur swasta dalam tubuh BPPC didukung oleh pengusaha yang berkaliber juga. Mereka yang tergabung dalam konsorsium bernama PT Kembang Cengkeh Nasional (KCN) itu adalah: Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Robby (Ketek) Sumampow, Yusni Radius Prawiro, Tonny Hardianto, dan Jantje Worotitjan. Perusahaan yang bergabung dalam KCN adalah: PT Bina Reksa Perdana (BRP), PT Wahana Dana Lestari, PT Rempah Jaya Makmur, PT Sinar Utara Agung (SUA), dan PT Agro Sejati Bina Perkasa. Masing-masing menguasai 20% saham KCN. Dua perusahaan terakhir berada di bawah naungan Tjia Ing Tik, seorang pengusaha dari Sulawesi Utara, yang lebih banyak tinggal di Singapura. Presiden Direktur SUA Jantje Worotitjan mengatakan, "Dalam bidang perdagangan hasil pertanian, kami cukup profesional." Yang diekspornya, dari lada sampai jagung. SUA didirikan pada 1980, tapi cabang-cabangnya sudah ada di Singapura dan AS. Kantornya terletak di sebuah gedung berlantai tiga di Jalan Majapahit, Jakarta. Adapun BRP didirikan pada 1970, tapi baru pada tahun 1988 aktif membeli cengkeh -- setahun setelah Tommy Soeharto masuk ke sana. Direktur BRP Tonny Hardianto mengatakan, sampai saat ini cengkeh yang sudah dikumpulkan KCN ada 60 ribu ton. Kalau nanti Gappri selama setahun belum juga bersedia membeli stok itu, BRP masih punya dana untuk membeli cengkeh dari petani dengan harga di atas patokan saat ini (Rp 6.500). Dari harga tersebut, kata Tonny, BPPC akan mengambil fee Rp 500 per kg. Berapa modal BRP? Ia enggan menyebutkannya. MC dan Bambang Aji (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini