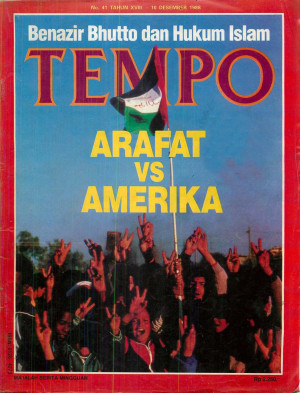KOMPAS, 27 Juli 1988, memuat pernyataan Menteri Muda Perindustrian Ir. Tungky Ariwibowo tentang tingkat upah buruh Indonesia yang rendah, namun tidak perlu dipertahankan. Pada hari yang sama, Bisnis Indonesia melaporkan jatuhnya harga rotan, yang barangkali disebabkan karena adanya larangan ekspor rotan mentah ke luar negeri. Ada hubungan yang menarik dari kedua berita itu. Pertama, bahwa orientasi ekspor pada industri kita telah memberikan cakrawala yang lebih cerah bagi kesejahteraan masyarakat kita. Kedua, bahwa ternyata cakrawala yang cerah hanya akan tampak oleh mereka yang berdiri pada ketinggian yang cukup. Mereka yang berada di bawah batas ketinggian itu sama sekali tidak akan melihat cakrawala cerah itu. Siapakah mereka? Para tetani dan pekebun kita. Begitu papanya mereka, sehingga angan-angan hidup layak saja bahkan sudah menjadi barang mewah bagi mereka (itu sebabnya KSOB dan TSSB berhasil menjual impian kepada masyarakat papa kita). Bahkan mereka sering pula dituding sebagai faktor yang menggayuti pendulum ekonomi kita, dan membuat kita sulit beranjak ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Sulit bagi Indonesia untuk mencapai tahap NIC (newy indstrialized contry) kalau sektor agrikultur masih jadi bagian terbesar dari produksi domestik. Dan dengan nilai tukar dolar yang makin meninggi, sebetulnya makin merosot tingkat penghasilan rata-rata bangsa kita. Coba tengok kisah anjloknya harga rotan. Siapa yang menderita? Tak lain adalah para rimbawan yang setiap hari keluar-masuk hutan mengumpulkan rotan. Padahal, ketika harga rotan selangit, mereka tidak ikut menikmati margin besar, yang mengendap di kantung-kantung para tengkulak. Dan ketika harga rotan turun, para tengkulak yang ingin mempertahankan koceknya akan ganti menekan para pengolah rotan agar menurunkan harga beli, bahkan menunda-nunda pembayaran. Pada saat ini para pekebun singkong sedang bergembira karena akan segera panen. Kita juga tahu bahwa gaplek adalah komoditi yang gampang dijual dan cukup baik harganya. Indonesia bahkan sampai saat ini belum mampu mencukupi kuota pasar Eropa dalam hal gaplek. Tapi apakah angin surga itu bertiup juga ke arah petani singkong? Nyatanya, harga mereka tetap saja ditekan oleh para tengkulak. Para transmigran di Lampung, misalnya, terpaksa antre menjual singkong basah ke sebuah pabrik aci dengan harga rendah. Kalaupun mereka olah menjadi gaplek, tak ada truk untuk mengangkutnya ke gudang-gudang di kota, yang bisa mengekspornya ke Eropa. Lagi pula, biarlah uang sedikit, karena kebutuhan sehari-hari tak dapat ditunda. Menjadi tak terlalu aneh kalau kita kemudian mendengar bahwa Indonesia sebagai negara penghasil karet nomor dua -- kalau tidak sudah nomor tiga di dunia -- ternyata tidak mempunyai cukup lateks pekat untuk menghidupi produksi dalam negeri. Soalnya. untuk memproduksi lateks pekat, terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pekebun. Menyadapnya harus lebih pagi. Susu karetnya harus ditampung dalam mangkuk-mangkuk yang bersih. Pengangkutannya ke emplasemen harus hati-hati. Dan berbagai persyaratan lain yang memang memerlukan usaha ekstra dari petani. Tetapi apakah semua itu akan menghasilkan nilai tambah bagi mereka? Ternyata tidak. Margin yang diperoleh pengusaha lateks pekat tidak menetes ke lapis di bawahnya. Ekspor adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih cerah. Itu sudah lama kita akui. Di Indonesia, untuk pertama kali pada tahun 1987 lalu, ekspor nonmigas melebihi ekspor komoditi migas. Tapi apakah kenyataan itu akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan bangsa kita? Tak dapat dipungkiri bahwa gaji buruh yang bekerja di sektor industri ekspor memang lebih baik daripada buruh lainnya. Tapi belum tentu bisa menjadi lebih baik lagi bila kesejahteraan di sektor hulu belum diperbaiki. Contohnya? Mari kembali ke soal lateks pekat. Gara-gara AIDS, kondom dan sarung tangan karet laris bukan kepalang. Banyak pengusaha Indonesia ikut menyerbu sektor ini. Tapi karena lateks pekatnya harus diimpor dari Malaysia, produsen Indonesia itu menjadi kurang mampu menggaji buruhnya lebih baik. Ketergantungan bahan baku impor pada kebanyakan industri kita telah terbukti menjadi rem yang terlalu pakem untuk menunda kenaikan upah buruh. Industri tekstil kita telah membuktikannya. Industri otomotif kita pun -- setidaknya dahulu -- menghadapi persoalan serupa. Industri rotan yang tengah digalakkan pada saat ini bukan tak mungkin akan juga menghadapi kesulitan bahan baku, bila para pengolah rotan tidak cukup termotivasi, karena harganya yang buruk. Lalu, apa ya perlu menteri khusus untuk menangam persoalan kaum papa, yang menjadi penghambat kemajuan kita ini? Bondan Winarno"
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini