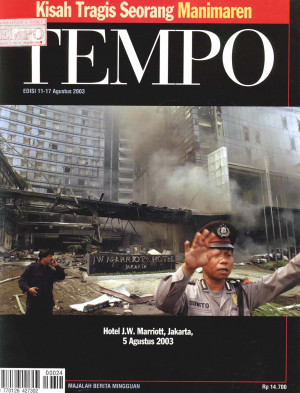Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tidak ada berita gembira yang bisa dipetik dari pidato kenegaraan Presiden Megawati Soekarnoputri di depan sidang MPR/DPR, Jumat pekan lalu. Sekalipun begitu, terselip satu kepastian yang tentu membuat "kelompok garis keras" merasa antusias. Kepastian itu adalah mengenai kerja sama Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan berakhir Oktober depan.
Dampak dari pemutusan kerja sama dengan IMF ialah fasilitas Paris Club tidak lagi tersedia. Ini berarti Indonesia tidak lagi mendapat keringanan pembayaran utang—satu hal yang akan memberatkan beban anggaran negara sepanjang tahun 2004. Tanpa fasilitas Paris Club, tahun depan Indonesia harus membayar utang US$ 3 miliar atau sekitar Rp 26 triliun. Jumlah ini tidak kecil, belum lagi beban pembayaran surat utang negara yang mencapai Rp 18,9 triliun. Selain itu masih ada defisit sekitar Rp 25 triliun.
Tangan mencencang, bahu memikul, kata pepatah lama. Masalahnya bukan karena Indonesia enggan memikul, melainkan lantaran pundak yang digayuti beban utang sudah mulai lecet dan di sana-sini terkelupas. Singkat cerita, keuangan negara sudah berdarah-darah. Pemerintah tidak bisa lari dari kenyataan ini, dan karena itu pula barangkali Anggito Abimanyu, Kepala Badan Analisa Departemen Keuangan, sampai jatuh sakit. Pejabat yang berperawakan tinggi kurus ini terkapar selepas menyelesaikan penyusunan naskah Kajian Strategi Pasca-Program Letter of Intent (LoI) IMF.
Tugas khusus itu dirampungkan Anggito dan sejawatnya dalam waktu enam bulan terakhir. Ekonom lulusan Universitas Gadjah Mada itu memang bekerja sampai larut malam. Kadang kala ia mesti begadang mengikuti rapat dan diskusi di Departemen Keuangan ataupun di rumah dinas Menteri Keuangan Boediono. Semua kesibukan ini merupakan bagian dari persiapan pemerintah menyambut berakhirnya kerja sama dengan IMF. Indonesia tak lagi menjadi "pasien rawat inap" IMF, berarti tak perlu lagi mengunyah resep LoI seperti terjadi lima tahun terakhir.
Dengan mengikuti post-program monitoring, Indonesia bersedia tetap diawasi, ibarat pasien yang masih harus "berobat jalan". Untuk menunjukkan keseriusan berobat itulah pemerintah menyusun program ekonomi pengganti LoI. "IMF sendiri sebetulnya tak mewajibkan," kata ekonom Mohammad Ikhsan.
Sekilas, format white paper itu—begitu program ekonomi ini disebut—mirip LoI. Dalam naskah yang diperoleh TEMPO, tertera bahwa program ekonomi itu terdiri atas tiga bagian: Program Stabilitas Ekonomi Makro; Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan; dan Program Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Penciptaan Lapangan Kerja.
Menurut sumber TEMPO di pemerintahan, tiap program disusun oleh kelompok kerja yang berlainan. Program Stabilitas Ekonomi Makro, contohnya, disusun oleh Kelompok I, yang dipimpin oleh Anggito dan Halim dari Bank Indonesia. Kelompok II, yang dipimpin Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Darmin Nasution dan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) Herwidayatmo, menyusun Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan. Sedangkan Kelompok III dipimpin Deputi Ketua Bappenas Sukarno dan menyusun Program Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Penciptaan Lapangan Kerja.
Selasa pekan lalu, tim penyusun melakukan presentasi di depan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. Keesokan harinya, naskah program ekonomi itu diserahkan ke Sekretariat Negara untuk selanjutnya diterbitkan dalam bentuk instruksi presiden.
Apa saja isinya? Ternyata tak ada yang baru. Untuk stabilitas ekonomi makro, pemerintah masih berkutat pada konsolidasi fiskal demi keberlangsungan fiskal sampai 2006. Dalam program ini sudah termasuk pengendalian inflasi dan volatilitas nilai tukar rupiah dan pemantapan neraca pembayaran melalui kecukupan cadangan devisa.
Dalam pandangan ekonom Dradjad Wibowo, program ekonomi itu sudah bagus tapi masih terlalu konservatif. "Pertumbuhan ekonomi tahun depan mestinya bisa dipacu hingga 5 persen dengan meningkatkan penerimaan pajak," katanya. Hal itu masuk akal karena potensi pajak kita lumayan besar. Lagi pula, bertambahnya penerimaan pajak bisa digunakan untuk menambal defisit anggaran yang mencapai 1,2 persen dari PDB.
Untuk Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan, malah ada kebijakan sisa LoI yang belum dilaksanakan, yaitu penanganan tindak pidana pencucian uang. Padahal soal ini sangat penting. Pekan lalu Duta Besar Amerika Ralph L. Boyce bahkan sempat menegur Gubernur Bank Indonesia karena lamban menangani aksi pencucian uang.
AS bahkan melontarkan ancaman: Indonesia bisa terkena sanksi berupa tindakan balasan lewat Patriot Act 311, yang dapat berakibat fatal bagi perekonomian. Gubernur BI terkesan lamban karena revisi Undang-Undang No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum selesai. "Ini gara-gara Menteri Kehakiman tak mengerjakan PR-nya merevisi undang-undang tersebut," tutur Mohammad Ikhsan, mengungkapkan sebab-musabab keterlambatan itu.
Dradjad Wibowo juga menyoroti rencana pembentukan Badan Pengelola Aset (BPA), yang akan mengambil alih sisa aset-aset BPPN.
"Kita punya pengalaman buruk dalam soal pengalihan aset," ungkap Dradjad, "karena biasanya di sana terjadi manipulasi nilai aset." Manipulasi itulah yang membuat tingkat pengembalian (recovery rate) aset menjadi rendah.
Dradjad juga mengkritik rencana divestasi bank-bank di bawah BPPN. "Saya heran kenapa mesti ngebut menjual saham bank," ujarnya, "padahal obligasi rekapitalisasi di bank-bank itu belum ditarik." Memang, bila saham bank telanjur dijual, pemerintah akan sulit membeli kembali obligasi tersebut, karena pemilik barunya belum tentu setuju.
Kebijakan yang kurang matang terlihat dalam Program Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Penciptaan Lapangan Kerja. Di sini perencanaan ekonomi pemerintah terlihat mengambang. "Kebijakan pemerintah terlalu umum dan sumir," demikian Dradjad mengecam. Di situ juga terselip program pembentukan Komisi Antikorupsi warisan LoI sebelumnya yang, entah mengapa, sampai kini masih tertunda.
Berkomentar mengenai kebijakan yang terlalu umum dan sumir itu, Dradjad memberi contoh penanganan masalah investasi dan ekspor. Dalam white paper hanya tertera rencana membentuk Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Ekspor. "Tim itu pun baru dibentuk September mendatang, mungkin baru akan bekerja tahun depan dan tak ada kejelasan cara kerjanya untuk mencapai sasaran," tutur pengamat yang selalu bicara apa adanya ini.
Upaya pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) juga memprihatinkan. Pemerintah memang berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UKMK dengan mengajukan sejumlah rancangan undang-undang. Tapi semua itu baru akan dilakukan akhir tahun depan. "La, apa sekarang pemerintah tidur saja?" ujar Dradjad dengan nada agak berang.
Kebijakan pengentasan masyarakat dari kemiskinan lebih menyedihkan lagi. Seluruh rencananya sangat umum dan mengawang-awang. Hasilnya pun cuma berupa dokumen.
Kritik serupa disampaikan oleh Ikhsan. Ia terutama menyoroti kebijakan yang mengambang dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Ambil contoh kebijakan peningkatan investasi swasta di bidang kelistrikan. Di sana tertera rencana memberlakukan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 untuk pembangunan sarana penyediaan listrik PLN yang bekerja sama dengan swasta. Tapi, ada embel-embel "sambil menunggu peninjauan keppres tersebut".
Dengan embel-embel itu, investor tentu bersikap menunggu. "Mereka tahu aturan itu akan berubah sehingga lebih baik menunggu aturan yang baru sebelum melakukan penanaman modal," kata Ikhsan.
Aura ketidakpastian juga menyeruak dari kebijakan tentang daftar negatif investasi (DNI). Di sana tercantum rencana meninjau DNI. Tapi tak jelas apakah akan ada pengurangan atau penambahan. Akibatnya, investor tak tahu di Indonesia bakal ada liberalisasi ekonomi atau justru penguatan kembali gelombang regulasi.
Sumber TEMPO di pemerintahan menyebutkan, kebijakan dari Kelompok Kerja III memang paling alot pembahasannya. "Soalnya, kelompok ini harus menampung aspirasi berbagai departemen dan kementerian negara," ia menjelaskan. Dalih serupa disampaikan Menteri Keuangan Boediono. "Semua usul itu harus kita tampung dulu," ucap Boediono, "kemudian dirumuskan kembali secara detail."
Situasi serupa juga pernah terjadi ketika masih ada IMF dengan LoI-nya. Ketika itu pejabat IMF dengan tekun mendatangi tiap departemen dan instansi pemerintah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.
Kini, ketekunan sulit dicari. "Kebijakan yang sumir seperti ini seolah-olah membenarkan pendapat bahwa kita memang baru bisa bekerja dengan baik bila dimandori asing," kata Dradjad, sedih bercampur kecewa.
Nugroho Dewanto, Setri Yasra
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo