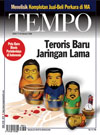Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PT PERTAMINA sepertinya tak pernah kekurangan masalah. Setelah didera kelangkaan dan lonjakan harga bahan bakar minyak, perusahaan milik negara itu kembali dihadapkan pada urusan baru di seputar tudingan penggelembungan biaya subsidi BBM.
Tudingan terkini itu berembus dari Pejompongan, Jakarta Pusat, tempat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkantor. ”Saya tidak mengerti mengapa orang tidak percaya pada Pertamina,” kata Direktur Utama Pertamina, Widya Purnama. Lho?
Keluhan Widya berkaitan dengan hasil audit terbaru BPK yang menyatakan menemukan pembengkakan biaya subsidi BBM untuk tahun 2004 sebesar Rp 3,64 triliun. ”Temuan itu berdampak koreksi terhadap biaya subsidi BBM tahun 2004,” tulis BPK dalam laporannya yang diserahkan ke DPR RI, Senin pekan lalu.
Akibatnya, menurut BPK, subsidi BBM 2004 yang harus dibayarkan pemerintah tidak lagi sebesar jumlah yang dicantumkan Pertamina, Rp 80,4 triliun, tapi turun menjadi tinggal Rp 76,7 triliun (lihat tabel).
Temuan ini didapat setelah BPK mengaudit penghitungan biaya pokok pengadaan minyak mentah dan distribusi, yang dilakukan Pertamina dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Dalam laporan itu, BPK menyebutkan ada sejumlah komponen biaya tambahan yang sengaja dimasukkan oleh Pertamina dan BP Migas sehingga membuat subsidi BBM menggelembung.
Setelah dilakukan klarifikasi, Pertamina dan BP Migas hanya mengakui telah terjadi kesalahan perhitungan Rp 936,05 miliar. Adapun sisanya, Rp 2,7 triliun, kedua lembaga itu menolak mengakuinya.
Ketua BPK, Anwar Nasution, menyatakan lembaganya sedang mendiskusikan perbedaan perhitungan itu dengan Pertamina dan BP Migas. Jika nanti tak tercapai kata sepakat, keputusan akhir akan diserahkan kepada DPR. ”Harus diputuskan secara politik,” ujarnya.
Salah satu akar persoalan ini menyangkut patokan perhitungan biaya pokok pengadaan BBM yang harus dibayar Pertamina. Ada dua jenis patokan biaya, yaitu berdasarkan harga pasar (Inkid) dan harga kategori DMO (domestic market obligation).
Harga DMO dikenakan pada minyak yang diperoleh dari sumur milik Pertamina sendiri, atau pada minyak jatah pemerintah yang harus disetorkan oleh para perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di Indonesia.
Para kontraktor asing itu diharuskan menyerahkan 25 persen produksinya ke pemerintah guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk membelinya, negara—dalam hal ini BP Migas—cukup membayar 15 persen dari harga pasar, plus fee sesuai dengan usia sumur minyak.
Selanjutnya, Pertamina membeli minyak DMO itu dari BP Migas dengan harga pasar. Selisih harga 85 persen itu yang kemudian disetorkan BP Migas ke kas negara.
Di sinilah persoalannya. Menurut temuan BPK, ada sejumlah kerancuan pencatatan jenis minyak DMO dan Inkid dalam laporan pengadaan BBM yang dibuat Pertamina dan BP Migas.
Salah satunya adalah, minyak mentah jatah pemerintah yang berasal dari sumur-sumur Pertamina sendiri dalam perhitungan biaya pokok BBM dikategorikan Inkid. Ini berarti pengadaannya dipatok dengan harga pasar.
Semestinya, kata BPK, dikategorikan DMO dengan tarif pengadaan 15 persen dari harga pasar. Dari sini saja, biaya subsidi BBM membengkak Rp 245,9 miliar. Kesalahan ini, menurut BPK, termasuk yang diakui oleh Pertamina untuk dikoreksi.
Contoh lainnya, BP Migas tidak memasukkan minyak mentah DMO dalam perhitungan biaya pokok BBM, yang berasal dari Conocophillips (121,7 ribu barel) dan Natuna Sea B.V. (46,4 ribu barel). Keduanya dikategorikan sebagai Inkid.
Dengan begitu, otomatis pemerintah tak mendapat pemasukan dari selisih harga jual minyak itu ke Pertamina, yang dipatok dengan harga pasar. Ujung-ujungnya, biaya subsidi membengkak Rp 58 miliar. ”BP Migas sepakat dengan koreksi BPK,” kata BPK.
Di luar itu, masih ada sejumlah temuan BPK yang tak diakui Pertamina dan BP Migas. Nilainya pun sangat besar. Salah satunya menyangkut penjualan minyak mentah DMO jenis Cinta dan condensate ke luar negeri sebanyak 2,7 juta barel oleh BP Migas, yang membuat biaya pokok BBM menjadi lebih tinggi Rp 504,5 miliar.
Semestinya, kedua jenis minyak mentah itu tidak boleh diekspor oleh BP Migas, tapi dipakai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan mengolahnya di kilang milik Pertamina. Menurut BPK, kalaupun minyak jatah pemerintah itu harus dilego dengan harga pasar, mestinya tetap diperlakukan sebagai minyak DMO. Artinya, tetap ada penyetoran uang ke kas negara.
Selain itu, jika Pertamina terpaksa membeli minyak ini dari pasar internasional, seharusnya dikenakan pengurangan biaya—misalnya pengapalan—sebagai faktor penekan (reducing factor) biaya pokok pengadaan BBM di dalam negeri.
Temuan lain adalah soal sistem pencatatan atas pembelian minyak mentah DMO oleh Pertamina—sebagai pengurang kategori Inkid—yang belum dilakukan dengan wajar. Akibatnya, biaya dalam perhitungan harga pokok BBM menjadi lebih tinggi Rp 2,1 triliun.
Anwar Nasution juga mempersoalkan, Pertamina belum memiliki prosedur formal dalam menghitung biaya pokok per jenis bahan bakar. Akibatnya, terjadi ketidakakuratan dalam perhitungan subsidi BBM. ”Sangat memalukan,” katanya, ”Perusahaan yang besar dan sudah tua belum punya standar baku.”
BPK, kata Anwar, terpaksa menghitung ulang harga pokok itu berdasarkan prosedur sementara yang ditetapkan Pertamina. Hasilnya, tarif premium Rp 2.750 per liter, minyak tanah Rp 2.545, solar Rp 2.588, minyak diesel Rp 2.185, dan minyak bakar Rp 2.099.
Widya membantah tudingan itu. Menurut dia, Pertamina sudah memiliki prosedur penghitungan biaya pokok BBM dan subsidi yang baku sejak 2001. Metode ini sesuai dengan standar The American Petroleum Institute. Malah, dia menganggap lucu hasil pemeriksaan BPK. ”Dibilang tak punya metode, tapi BPK menghitungnya pakai punya Pertamina juga,” katanya sewot.
Direktur Pengolahan Pertamina, Suroso, menambahkan bahwa metode itu pun sesungguhnya sudah diajukan ke DPR dan pemerintah sejak beberapa tahun lalu.
Tapi, wakil rakyat menolak, dan lantas hal itu diserahkan ke Departemen Energi untuk dirumuskan kembali formulanya. Masalahnya, sampai kini belum juga rampung. Karena itu, Pertamina terpaksa menggunakan prosedur penghitungan sendiri. Sebab, laporan dari tiap kilang harus tetap ada.
Atas dasar itu, juru bicara Pertamina, Mochamad Harun, mempertanyakan tudingan BPK. ”Pertamina sudah dizalimi,” ujarnya. Alasannya, setiap tahun isu ini selalu diembuskan bahwa Pertamina tidak bisa menghitung. ”Kami cuma dijadikan komoditas politik.”
Harun juga mengatakan, soal pengkategorian minyak DMO atau Inkid bukan menjadi tanggung jawab Pertamina. Sebab, urusannya lebih berada di pundak BP Migas. ”Kami hanya pemain yang membeli minyak dari BP Migas dengan harga pasar,” ujarnya.
Tanggapan sebaliknya datang dari pejabat BP Migas yang menolak disebutkan namanya. Menurut dia, pihaknya mengekspor minyak Cinta dan condensate justru atas permintaan Pertamina. Sebab, kedua jenis emas hitam ini tidak bisa diolah oleh kilang Pertamina. ”Mau tidak mau harus dilego ke luar negeri ketimbang mubazir,” katanya.
Kebijakan itu pun, kata pejabat tersebut, ada aturan tertulisnya. Meski dijual ke negara lain, tetap wajib diperlakukan sebagai minyak DMO dan ada pencatatan keuangannya tersendiri. Persepsi ini yang sulit dipahami BPK. ”Padahal sudah dijelaskan berkali-kali,” katanya.
Lalu, soal dana penggelembungan subsidi BBM senilai Rp 3,64 triliun yang kini diributkan, pejabat itu pun menegaskan uang itu tidak lari ke mana-mana. Kalau saja BPK lebih teliti, katanya, lembaga pemeriksa ini akan menemukan bahwa uangnya ada di penerimaan kas pemerintah.
Tapi, sikap pemerintah tampaknya sudah bulat. Departemen Keuangan berkeras agar koreksi angka subsidi itu tetap dilakukan. Sebab, kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Mulia P. Nasution, audit BPK sudah final. ”Urusan Pertamina keberatan, itu diselesaikan tersendiri,” ujarnya.
Setali tiga uang, Kepala Humas BPK, Barlean Suwondo, pun berpendapat hasil pemeriksaan sudah tuntas. Jadi, tak bisa lagi diganggu gugat.
Stepanus S. Kurniawan, Bagja Hidayat, Muhammad Fasabeni
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo