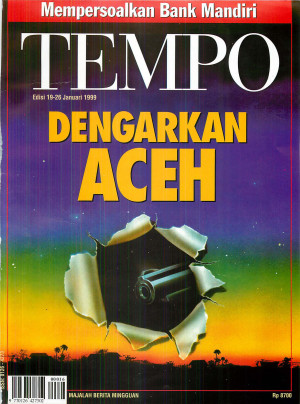Glodok, suatu siang, awal Januari 1999, sepintas tak pernah berubah wajah. Petak-petak itu, kardus-kardus yang berdesakan itu, tampak masih seperti dulu. Ada lemari es berbagai ukuran, televisi, dan ada komputer teronggok dalam pajangan. Ada label harga, kartu diskon yang bertebaran tak beraturan. Jauh di sudut, seorang lelaki memencet tombol kalkulator. Menelpon. Di petak lain, seorang perempuan gemuk merenung-renung menunggu pembeli. Sebuah kipas belacu mengibas seperti ingin menciptakan kesejukan di lehernya. Mengelap kepengapan yang mengendap dari langit-langit.
Itu hanya pandangan sepintas. Tetapi sesungguhnya ada dua peristiwa besar yang telah menggilas pusat perdagangan elektronik Glodok, Jakarta Barat, yang mengklaim dirinya terbesar di Asia Tenggara.
Lihatlah bekas jilatan lidah api yang masih membekas di dinding bangunan toko-toko di sepanjang jalan. Lihatlah reruntuhan jembatan yang menghubungkan dua bangunan Glodok terkemuka. Lihatlah lubang-lubang pada kaca jendela yang tak kunjung diganti. Dan lihat pula lorong-lorong melongo seperti pasar malam di waktu siang. Api yang menghanguskan dinding seperti meniti catatan nasib yang sudah pasti. Dan yang paling menarik?suatu pemandangan yang tiba-tiba saja menjadi bagian ''permanen" dari kawasan Glodok sejak bulan Mei?adalah beberapa petugas dengan seragam loreng yang hilir-mudik sembari menenteng senjata. Ini seperti sebuah kawasan yang hancur setelah meletus perang.
Glodok merayap tertatih-tatih. Pembeli sepi, kardus-kardus pembungkus hanyalah kertas kotak kosong tanpa barang. ''Pertokoan ini tinggal menghitung hari," kata seorang pedagang.
Kerusuhan bulan Mei agaknya telah merobohkan sebuah jaringan pusat perekonomian yang berjaya untuk ratusan tahun lamanya (baca boks Sebuah Napak Tilas ke Glodok). Tapi peristiwa kerusuhan itu sebetulnya hampir seperti sebuah klimaks tragedi ekonomi negeri ini. Sebelumnya, sejak akhir Desember 1997, Glodok mulai diterpa angin krisis ekonomi akibat harga dolar yang meroket. Maka krisis moneter dan kerusuhan Mei kemudian membuat Glodok terkapar, meregang napas.
Sebutlah Anton, pemilik toko di Glodok Blok C yang biasa berjualan pesawat televisi, VCD-player, compo, tape recorder dari berbagai merk yang penuh sesak memenuhi tiga lajur rak tokonya. Anton, bersama lima orang anggota keluarganya yang membantunya di toko, saat ini lebih banyak duduk daripada melayani pembeli. ''Memang sepi, tapi beberapa hari terakhir ini ada peningkatan," tutur Anton. Ia seperti mencoba menimbun harapan. Tokonya memang tak terbakar. ''Tapi barang saya terjarah habis," katanya. Ia merugi, tentu. ''Sampai ratusan juta," katanya.
Seratus, lima ratus juta. Semiliar dua, sama saja. Kerugian bukan cuma angka-angka. Catatan statistik. Dengan kerugian finansial itu pun, Anton masih merasa beruntung. Sedikitnya, ''Saya tak sampai ingin bunuh diri," katanya menerawang.
Mengapa tidak terbang ke luar negeri seperti yang lain?
''Banyak teman saya yang semakin bangkrut setelah mengungsi sementara di Australia," kata Anton. Anton sadar, untuk itu orang tak cuma perlu uang, tapi juga nyali dan kemampuan untuk bersaing. Lalu, apa sisa yang dia miliki untuk bertahan dan menyangga kehidupan Glodok yang sudah porak-poranda? Tak ada pilihan lain, Anton ''cuti" enam bulan. Ia mengumpulkan modal. Minta pinjaman kanan kiri, dari keluarga. Kredit bank? Tak mungkin. Untuk Anton, bunga bank terlalu tinggi.
Tapi Anton tetap harus bekerja, walaupun dengan ketakutan. Demonstrasi yang sampai melibatkan aparat keamanan selalu membuat Anton takut. Apalagi dengan insiden Ketapang awal Desember lalu, yang menjadikan etnis Cina sebagai sasaran, membuat Anton mengkeret lagi.
Sin Phin, 32 tahun, yang berjualan barang-barang elektronik di Glodok sejak 1990, juga baru mencoba bangkit. Isi tokonya juga ludes dijarah hingga kerugian yang dideritanya mencapai Rp 200 juta. ''Untung" saja, dia masih memiliki sisa barang di gudang lantai tiga yang tak ikut terjarah. Namun, dengan kondisi krisis ekonomi seperti sekarang, pembeli yang datang hanya lebih sering mencuci mata belaka. Penjualannya turun 50 persen dibandingkan dengan sebelum kerusuhan Mei lalu. Dulu, penjualan bisa mencapai Rp 60 juta, tapi sekarang ia hanya bisa mendapatkan Rp 30 juta per bulan. Selain penurunan penjualan, Sin Phin mengaku barang-barang yang dipajang di tokonya tidak lagi ramai. ''Saya tidak menyimpan stok banyak, itu hanya kardusnya, siapa tahu terjadi lagi," katanya merujuk pada kerusuhan Mei.
Berjualan gaya ''kardus" ini memang terjadi akhir-akhir ini, antara lain, akibat dua hal: ngeri penjarahan dan juga karena krisis ekonomi. Ferry, pemilik toko komputer, mengaku bahwa para pengunjung kini tawar-menawar harga komputer atau printer hanya dengan melihat sampel (barang contoh yang dipajang), dan kemudian Ferry mengambil barang pesanan dari distributor.
Glodok di tahun 1999 mungkin mencoba meraih jiwa yang dulu pernah dimilikinya. Sebuah jiwa yang hidup antara lain karena kerja keras dan keuletan. Orion, Glodok Plaza, dan Harco dengan tersengal mencoba meniupkan roh masa lalu, tetapi rasa takut pengunjung dan daya beli yang mendera konsumen akan menggagalkan usaha itu. Dengan para penjual yang hidup sambil ''menghitung hari", tampaknya Glodok 1999 membutuhkan puluhan tahun untuk berjaya kembali.
Bina Bektiati, Agus S. Riyanto, dan Dwi Arjanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini