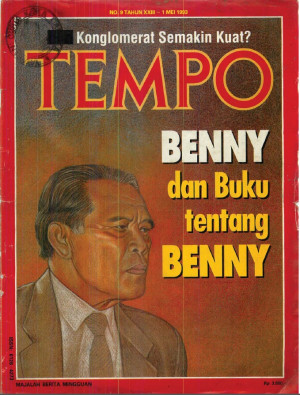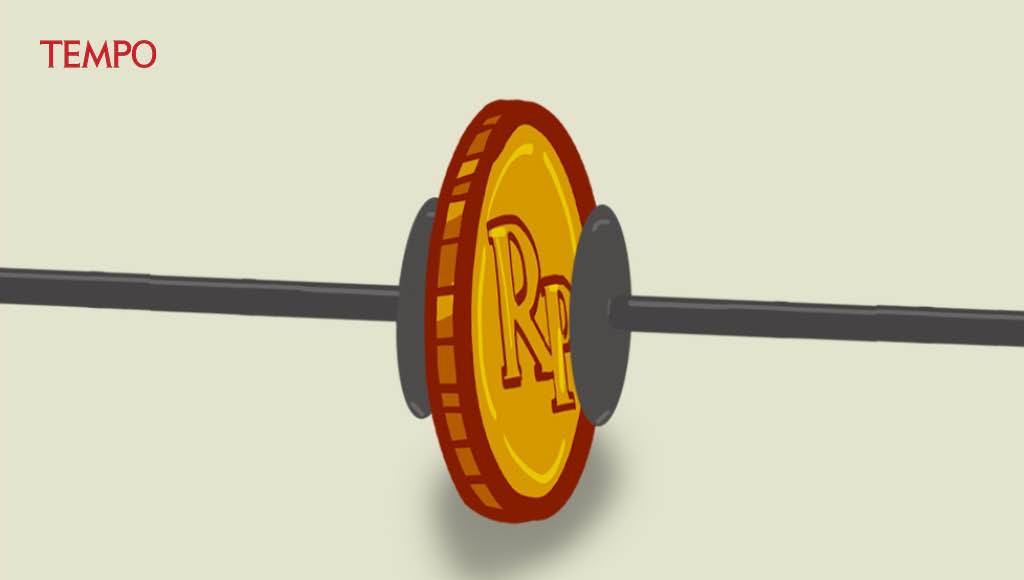SEKITAR enam puluh pengusaha berdatangan ke Sumba Room, Hotel Borobudur, Kamis pekan silam. Mereka membuang satu hari penuh di situ, untuk mengikuti seminar ''The 1993 Indonesia Business Summit'' yang diselenggarakan oleh Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI). Topik yang dibicarakan memang gagah, yakni Restrukturisasi Konglomerat Indonesia. Dan para panelis juga meyakinkan. Ada Drs. Sumargono yang Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (d/h Oei Tiong Ham Concern) dan Jan Darmadi dari Jan Darmadi Corp. Selain itu, ada beberapa pakar, yakni Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Hasnan Habib, dan Wahjudi Prakarsa. Mengawali seminar, Direktur PDBI Christianto Wibisono menyampaikan satu makalah lengkap dengan penilaian kuantitatif maupun kualitatif atas konglomerat dan kinerja mereka. Menurut penelitian PDBI, pada lima tahun terakhir, sebanyak 29 konglomerat telah menciutkan unit usaha mereka, 8 tidak melakukan perubahan apa-apa, dan 109 grup malah meningkatkan unit perusahaannya. Angka-angka itu sungguh mengejutkan. Sementara beberapa grup besar seperti Bentoel, Mantrust, dan Summa goyah kalau tidak mau dikatakan hampir tersungkur, rupanya kelompok usaha yang lain melaju dengan ekspansi masing-masing. Rupanya, kebijaksanaan uang ketat tidak sampai membawa banyak korban seperti yang dibesar-besarkan selama ini. Dugaan itu ternyata tidaklah tepat benar. Memang banyak yang menambah unit usaha, tapi bersamaan dengan itu mereka juga melikuidasi unit-unit yang merugi. Sepanjang periode yang sama, 52 grup usaha berekspansi kurang dari 50%, 33 grup meningkatkan usaha 51100%, dan 53 grup berkembang 200%. Sedangkan perusahaan yang dilikuidasi dalam 20 tahun terakhir ada 676 unit, tapi hanya 53 unit yang merupakan milik konglomerat. Untuk sementara diperoleh kesan, bahwa selain ada grup yang kedodoran, sejumlah besar grup lain ternyata cepat melakukan konsolidasi. Memang, selama periode uang ketat (1990-1992), mereka ''jalan di tempat'' dan melakukan berbagai penyesuaian yang dianggap perlu. Intinya sesudah ekspansi jor-joran sejumlah konglomerat melakukan konsolidasi (termasuk likuidasi), penataan manajemen, lalu kembali ke bisnis inti. Banyak yang tampil lebih ramping dan mantap dalam segi manajemen, tapi dari segi produk belum bisa dicatat adanya keunggulan yang berarti. Bisnis rokok kretek dan minuman ringan memang menakjubkan, karena bisa besar tanpa proteksi. Tapi konglomerat yang bergerak di industri manufaktur umumnya belum menunjukkan keunggulan teknologi. Selain bisa besar karena proteksi, mereka belum menjurus ke riset dan pengembangan. Padahal, bila mau menang bersaing dalam era globalisasi, keunggulan teknologi harus diutamakan. Konglomerasi dalam penilaian Christianto meskipun mengandung kelemahan struktural dari segi organisasi dan kelemahan daya saing karena dimanjakan oleh proteksi kini menjelang Pembangunan Jangka panjang Tahap II ditantang untuk meningkatkan peran sertanya sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Harapan ini kedengarannya terlalu muluk, tapi konglomerasi itu sendiri bukanlah sosok bisnis yang tidak bisa diperbaiki. Dewasa ini beberapa konglomerat dengan kontrol keluarga yang ketat, selain bertahan, juga bisa berkembang. Contohnya, Citra Group (Ciputra dan keluarga) dan Femina Group (Sofjan Alisjahbana dan keluarga). Selain itu, ada Risjadson Group dan Brazali Group. Bersisian dengan mereka, beberapa grup usaha yang sepenuhnya mengandalkan manajemen profesional ternyata juga maju pesat, seperti Gramedia Multi Utama, Tigaraksa, dan Bukaka (lihat Kini Maju Taipan Baru). Jadi, manakah model yang tepat? Oei Tiong Ham pemilik konglomerat terbesar di Asia pada awal abad ke-20 telah merumuskan jawaban untuk masalah ini ketika grup itu berada pada puncak kejayaannya. Waktu itu Oei Tiong Ham Concern telah memanfaatkan tenaga profesional yang disekolahkan ke Belanda. Andai kata konglomerat itu tidak diambil-alih oleh pemerintah Republik Indonesia, mungkin model bisnis keluarga dengan manajemen profesional ini masih bertahan sampai sekarang. Bahwa manajemen keluarga mengandung banyak kelemahan, hal ini juga sudah diwaspadai Oei Tiong Ham pada masa itu. Pengusaha legendaris ini telah dengan lugas memisahkan pemilikan dan kepengurusan grupnya yang waktu itu sudah berekspansi ke Cina dan benua Eropa. Dalam surat wasiatya seperti diungkapkan oleh Dirut RNI, Drs. Soemargono Oei Tiong Ham menetapkan bahwa 9 dari 26 anaknya berhak menjadi pewaris bisnis. Selebihnya yang 17 orang hanya dibagikan uang kontan, tanpa mendapat hak dalam pemilikan saham ataupun hak untuk mencampuri manajemen perusahaan. Andai kata William Soeryadjaya, misalnya, bisa bertindak selugas Oei Tiong Ham, tentulah ia tidak akan kehilangan kerajaan bisnisnya (Astra) secara demikian mengenaskan, Desember lalu. Kasus Summa telah membuat orang kembali mempertanyakan ketangguhan konglomerat di Indonesia. Apakah mereka bisa tumbuh tanpa proteksi, bagaimana struktur manajemen dan permodalannya. Juga, apakah bisnis mereka didukung oleh teknologi yang memadai, serta bagaimana penelitian dan pengembangannya? Ada beberapa faktor yang berpengaruh besar terhadap ketangguhan konglomerat di Indonesia. Pemilikan, misalnya, masih dikuasai oleh keluarga. Permodalannya relatif belum kuat, struktur keuangannya mudah goyah, juga belum memisahkan pemilik dengan pengurus. Semua kelemahan itu adalah faktor internal, sedangkan faktor eksternal, misalnya terlihat pada sistem perpajakan yang belum mendukung dan pasar modal yang belum matang. Berbagai kelemahan internal dan eksternal itu tentulah erat kaitannya dengan sejarah pembentukan kongkolerat di Indonesia paling tidak selama PJPT I. Doktor Wahyudi Prakarsa makalahnya banyak menganalisa aspek manajemen berpendapat bahwa konglomerat bisa terbentuk karena ada campur tangan pemerintah. Dengan kata lain, iklim usaha yang ada memang memungkinkan pembentukan konglomerat. Contoh paling jelas ialah Salim Group. Semua orang tahu, salah satu divisi usaha Salim Group yang memproduksi tepung terigu telah memperoleh proteksi Pemerintah sejak tahun 1970-an. Dari proteksi yang berkepanjangan itu, Liem Sioe Liong diperkirakan telah memperoleh rente ekonomi triliunan rupiah, untuk kemudian bisa dimanfaatkannya dalam pengembangan usaha di sektor lain. Ketika mengembangkan bidang otomotif di bawah bendera Indomobil Group proteksi pun diperolehnya lagi, sama seperti yang diperoleh perusahaan otomotif lainnya. Dalam kasus Salim Group, segi-segi negatif dari konglomerasi pun muncul, misalnya menyangkut mekanisme pembentukan harga katakankah terigu dan bahan pembuat mi instant. Kalau Indofood (penghasil Indomie) membeli tepung terigu hasil Bogasari Flour Mills dan bumbu masak produksi Indomiwon Citra Inti, misalnya, harga yang berlaku tentunya kurang realistis. Transaksi intern (di antara perusahaan di bawah satu payung) menurut para ekonom juga tidak menghasilkan kegiatan ekonomi yang wajar. Kini Salim Group dikelola oleh manajemen yang kuat, di bawah CEO (Chief Executive Officer) Anthony Salim. Kabarnya, Anthony (anak lelaki nomor tiga) dipilih untuk memimpin karena memang dianggap mampu. Ia pernah mendapat pendidikan formal dalam bidang bisnis, termasuk dua tahun belajar di London. Kedua kakaknya, Albert dan Andre, konon tetap diakui haknya sebagai pemilik, tapi tidak terlibat dalam kepengurusan. Dengan reorganisasi tersebut, Salim Group kini menjadi kelompok usaha yang sejak 1980-an sudah memisahkan pemilikan dan pengurusan. Restrukturisasi semacam itu kemudian juga dilakukan oleh Lippo Group. Untuk pengembangan grupnya, Mochtar Riady (didampingi Stephen Riady, James Riady, dan Roy Tirtadji) sudah membuat rencana jangka panjang. Intinya, secara bertahap pemilikan keluarga akan diperkecil. Selebihnya, dimiliki oleh publik melalui bursa saham, seperti Lippo Pacific Finance, Lippobank, dan Metrodata. Menurut Mochtar, itulah konsep konglomerasi yang aman. ''Bila konglomerat merupakan suatu lembaga, kesinambungannya bergantung pada sistem, bukan pada seseorang,'' kata bankir yang bertangan dingin ini. Bakrie Group melakukan pengalihan ke manajer profesional Tanri Abeng pada pertengahan tahun 1992. Sebelum itu, situasi Bakrie sama saja dengan banyak konglomerat di Indonesia, yang mencampurkan entrepreneurship (sebagai pemilik) dengan manajemen. Sejak tahun lalu, ketiga anak almarhum Ahmad Bakrie (Aburizal, Nirwan, dan Indra) hanya bertindak sebagai komisaris. ''Dengan demikian, tidak ada kekuasaan mutlak. Saya, misalnya, yang memimpin dewan direksi tidak mutlak kekuasaannya, karena ada dewan komisaris yang mengawasi,'' ujar Tanri Abeng. Bahaya kekuasaan tunggal di tangan pemilik bisa terlihat jelas dalam kasus perusahaan rokok Bentoel. Para pimpinan Bentoel ketika itu (sebelum diambil alih oleh Rajawali Wira Bhakti Usaha), meminjam uang kepada 30 bank asing US$ 150 juta dan kepada bank lokal Rp 400 miliar. Pertengahan tahun 1991 pihak Bentoel tiba-tiba menyatakan tak sanggup membayar utang. Rupanya, dari pimpinan lama, yang adalah keluarga pemilik, ada yang menggunakan dana Bentoel untuk bisnis properti di luar negeri dan merugi. Kecenderungan ekspansi ke pelbagai bidang usaha, di luar bisnis utama yang sudah dikuasainya, memang merupakan penyakit para konglomerat. Mantrust, misalnya, dari bisnis makanan (kaleng, jamur, dan susu) kemudian melebar ke penerbangan, production house, dan banyak lagi, hingga akhirnya rontok sendiri. Asia Permai Group pernah kejangkitan penyakit serupa. Grup ini menyambar sektor yang belum dikenalnya, antara lain otomotif, penjamin emisi, mebel rotan, dan sarung tangan lateks. Kebetulan, bos Asia Permai, Mohammad Amid, segera menyadari kecerobohan itu dan pada pertengahan 1992 ia melikuidasi 16 dari 32 perusahaannya. ''Terus terang saja, kami terlalu mengikuti trend pasar. Begitu ada peluang, langsung masuk, tanpa memikirkan bahwa itu bisa memecahkan konsentrasi,'' kata Amid. Kini ia mengaku tak latah lagi dan Amid memilih jadi presiden komisaris. Jabatan presiden direktur diserahkannya ke Soekaryo, pensiunan perwira tinggi yang pernah menjadi Sekjen Departemen Kesehatan dan Direktur Utama Kimia Farma. Dari berbagai kasus tersebut, bisa disimpulkan bahwa restrukturisasi, melalui konsolidasi usaha dan pembenahan manajemen, tak dapat tidak adalah satu keharusan bagi konglomerat, kalau mereka memang mau bertahan. Dan sesudah tahap ini terlampaui, masih harus diuji lagi apakah mereka dapat menjawab tantangan PJPT II dan arus globalisasi. Mohamad Cholid, Max Wangkar, Siti Nurbaiti, dan Dwi S. Irawanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini