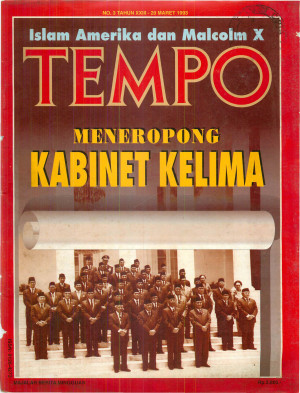PASANGAN Tramo dan Tiah sudah delapan tahun mendambakan anak. Oktober silam seharusnya mereka sudah bisa menimang bayi. Tetapi orok dalam kandungan 10 bulan itu meninggal sebelum sempat dilahirkan. Untuk mengeluarkan bayi itu, dokter harus melakukan decapitatie (memotong bagian leher bayi). Sebetulnya dalam dunia kedokteran tindakan itu dibenarkan. Hanya sayangnya, sebelum memotong bagian leher bayi itu, dokter tidak melakukan prosedur memberi tahu keluarga (informed consent). ''Ini salah. Pemberitahuan ini wajib dilakukan sebelum operasi,'' kata Profesor R. Prayitno, ahli kandungan di Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo, Surabaya. Salah prosedur itulah yang kini di jadikan alasan oleh penduduk Desa Sukorambi, Jember, Jawa Timur itu untuk menggugat Dokter Santoso Gunawan Rp 106.150.000. Menurut Tramo, 32 tahun, sebelum ditangani Santoso, istrinya sempat diurus oleh dua bidan. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak, karena posisi bayi dalam kandungan melintang. Lalu mereka menyarankan agar Tramo membawa Tiah ke puskesmas Sukorambi. Lalu bidan piket di puskesmas tersebut menginfus Tiah. Sekitar pukul 08.00, kata Tramo, Dokter Santoso, kepala puskesmas Sukorambi, datang bersama istrinya, Dokter Weni. Tetapi yang memeriksa kandungan Tiah bukan Santoso, melainkan Weni. Santoso langsung masuk ke ruang kerja. Menurut Tiah, Weni hanya memegang-megang perutnya. Bayi itu, kata Weni, akan lahir pukul dua siang. Weni lalu meninggalkan puskesmas bersama suaminya. Ketika matahari hampir terbenam, Weni baru muncul lagi. Ia langsung mengurus Tiah. Ibu ini dimintanya mengejan. Tiah merasa ada yang keluar dari tubuhnya. Tetapi belum sampai seluruh tubuh bayi keluar, Weni meninggalkan ruangan. Weni, katanya, mau mengambil alat kedokteran di rumah dan berjanji segera kembali. ''Saya merasa ada yang menggantung di antara dua kaki saya,'' kata Tiah. Tiah tidak tahu apa yang terkatungkatung di bawah tubuhnya. Tapi ia mengaku cemas sekali. Sekitar pukul 22.00 Santoso masuk ke kamarnya. Weni tidak kelihatan. Tindakan operasi dilanjutkan suami Weni. Santoso dibantu bidan Habsah dan mantri Eddy. Tak lama kemudian, kata Tiah, ''Saya mendengar suara kres, kres, kres, seperti suara gunting di bawah tubuh saya.'' Tapi waktu itu wanita berusia 24 tahun ini mengaku tenang, karena mengira dokter sedang memperlebar jalan keluar bayi. Kemudian ia baru curiga melihat Habsah menangis, lalu menutupi tubuh Tiah dengan kain batik. Apalagi ia merasa ada sesuatu masuk lagi ke dalam perutnya. Santoso mengatakan bayinya sudah lahir, tetapi cacat. Tiah disarankan tidak melihat bayinya itu. Tapi Tiah memaksa. ''Saya mau lihat. Walaupun cacat, dia darah daging saya,'' katanya, seraya menangis, kepada K. Candra Negara dari TEMPO. Setelah itu, ia menjerit ketika bidan memperlihatkan kepadanya bayinya yang berkelamin laki-laki itu tidak berkepala. ''Saya masih melihat darah menetes dari leher anak saya,'' ujarnya. Rupanya yang dia rasakan masuk kembali ke tubuhnya adalah kepala bayi yang tidak sempat dikeluarkan. Santoso kemudian menemui Tramo dan menyuruh lelaki itu membawa istrinya ke RSU Dokter Soebandi di Jember, untuk mengeluarkan kepala bayi. Sembilan hari Tiah dirawat di rumah sakit itu. Tindakan decapitatie, menurut Prayitno, ditempuh adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu. Apabila ibunya mengejan terus sementara bayi makin mendesak keluar, akibatnya kandungan ibu bisa pecah. Ini membahayakan ibunya. Dalam kondisi seperti ini, nyawa ibu harus didahulukan. Pada dasawarsa 1970, decapitatie kerap dilakukan dokter, karena ketika itu peralatannya belum lengkap. Prayitno sendiri tak tega melihat bayi lahir tanpa kepala. Kini, dengan kemajuan sarana pelayanan kesehatan, untuk mengeluarkan bayi yang sudah tewas dilakukan operasi Caesar. Tapi peralatan seperti itu hanya dimiliki rumah sakit besar, dan jarang ada di puskesmas. Lalu apa pertimbangan Santoso melakukan operasi itu di puskesmas? Padahal, menurut bidan piket, sejak diperiksa pertama kali sudah ketahuan bayi itu sudah meninggal. Santoso menolak menjelaskannya. ''Semua sudah ditangani bupati,'' katanya. Setelah peristiwa itu, Tramo yang cuma sempat duduk di kelas III SD ini meminta bantuan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Jember untuk membantu kasus ba yinya. Tadinya ia mengaku merelakan kematian anaknya itu, walaupun Santoso hanya memberi uang duka Rp 130.000. Persoalan baru muncul ketika Tramo dipanggil petugas Komando Rayon Militer (Koramil). Kesalahannya, mengapa ia menerima tamu tanpa melapor ke kepala desa. Tamu yang dimaksud adalah dua wartawan yang kemudian menulis berita itu. Tukang batu ini mengaku tersinggung karena oknum petugas itu juga mengancamnya. ''Saya memang orang kecil, tapi tidak mau di ancam-ancam,'' katanya. Itulah alasannya menemui LKBH, yang kemu dian membentuk tim dengan anggota empat pengacara. Tim ini semula menawarkan jalan damai. Santoso diminta bertemu Tramo. Tetapi alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, itu menolak. ''Bahkan Santoso menuduh kami memeras dan menantang untuk menyelesaikan kasus ini di pengadilan,'' kata Pramukhtiko, pengacara LKBH, kepada TEMPO. Jawaban sama juga disampaikan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Karena menemui jalan buntu, pertengahan bulan silam LKBH memasukkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jember. Polisi sudah memeriksa para saksi, tetapi belum menentukan siapa yang menjadi terdakwa. Bupati Jember Prijanto Wibowo belum pula bisa ditemui karena sibuk melakukan safari Ramadan. Konon, ia juga menyiapkan pengacara untuk Santoso. Bupati itu yakin, Santoso telah melakukan semua prosedur profesi kedokteran. Sri Pudyastuti R.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini