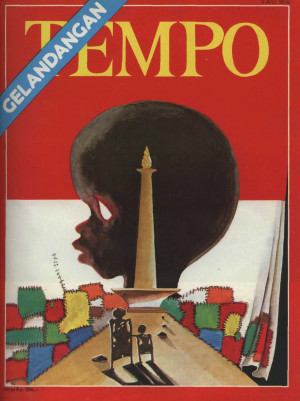BERAPA banyak sesungguhnya Jakarta menyelimuti orang- orang
yang disebut 'tuna wisma/karya'? Susah dijabarkan dengan angka.
Mereka yang lebih gampang disebut 'gelandangan' itu
menggerayangi hampir seluruh tubuh ibukota dengan kebandelan
yang tak mungkin dilawan dengan gertak sambal saja. Dengan mata
yang nanar, tubuh yang lusuh, bagaikan gombal mereka bergulung
di bawah jembatan, di emper toko, kaki lima bahkan di
tempat-tempat yang lebih terang-terangan seperti taman-taman dan
sepanjang jalan raya -- dengan keranjang dan japitan untuk
memungut puntung.
Kota yang ramai ini bagai ibu yang terlalu ramah, dengan segala
jenis kesempatan hidup tak mungkin dijumpai di pedalaman.
Sementara orang boleh memaki bahwa segala keperluan hidup
sekarang ini luar biasa tingginya, toh di lepitan-lepitan yang
tidak sulit dijumpai tetap terbuka kehidupan yang sungguh murah.
Di sana orang boleh kenyang satu hari dengan seratus perak --
sambil membuka ketawa menyaksikan lalu lintas yang gemuruh,
kalau mau. Kemiskinan yang menggigit daerah-daerah di Jawa
terutama, tetap momok terbesar yang menyepak mereka ke Jakarta.
Dan di sini mereka hidup dengan "tata baru" hampir tanpa
tanggung jawab, tanpa basa-basi, dan maunya tanpa merugikan
orang lain. Tapi apa boleh buat. Ibukota yang mau disebut kota
metropolitan. Berkata: "Tak ada tempat buat kamu
Untuk membebaskan Jakarta dari gelandangan, sampai keluar
Instruksi Presiden yang mengharuskan bebas gelandangan seluas
radius 3 km dari tugu Monas. Secara bertahap, sebagaimana
dilakukan terhadap belantara becak di jalan raya, demikian pula
dilepaskan gunting untuk mencukur kawasan ibukota sampai klimis.
Tahun lalu tak kurang dari 200 kali operasi dilancarkan. Wakil
Kepala Dinas Sosial DKI. Sofyan Yahya, mengaku ada kemerosotan
pesat dalam jumlah gelandangan. Ini hanya menunjukkan angka 4
sampai 5.000 orang, sementara tahun 1968 mencapai 20 sampai 25
ribu. Angka ini sulit dipercaya, karena dari DGI (Dewan
Gereja-gereja di Indonesia) yang melakukan pengumpulan
gelandangan tidak dengan cara cidukan tetapi berdialog langsung
disodorkan angka 100.000 (seratus ribu) untuk yang disebut kaum
gelandangan --tanpa rumah dan pekerjaan yang ada di Jakarta.
Tapi selisih ini normal, mengingat catatan formil punya
katagori-katagori tertentu. Belum lagi dipertanyakan siapa yang
sesungguhnya bisa disebut gelandangan. Apa ini lebih banyak
menampilkan soal kondisi hidup atau sepak terjang, atau
kedua-duanya, sehingga jelas hubungannya dengan yang dinamakan
tuna karya, tuna wisma, tuna susila, gembel maupun yang disebut
kere.
Agustinus Suharto, yang selama menjadi gelandangan bernama
Wibowo Santoso, berkata: "Gelandangan itu ada tiga, pak.
Gelandangan betulan, orang yang menyamar sebagai gelandangan,
yang siangnya compang-camping tapi malamnya "jentel?', dan
ketiga GTT atau Gelandangan Tingkat Tinggi yang memakai pakaian
bersih dan meminta-minta sumbangan ke rumah orang dengan surat
ini dan itu". Ia sendiri, yang mengaku berpengalaman sebagai
gelandangan tingkat rendah di Semarang selama 8 tahun, kini
sedang menunggu di Semper, Priok, untuk ditransmigrasikan ke
Kalimantan. Ia menyanggah dengan keras cap yang menghitamkan
gelandangan sebagai kaum yang sudah rusak mentalnya. Ia
mengingatkan perkumpulan yang pernah disebut 'Gembel Berjuang'
-- alamat Menteng Raya 31 -- pimpinan Erwin Kelana ( 1962- 1966)
yang menghadap Pemerintah untuk diberikan tanah tempat mereka
membangun hidup.
Sebaliknya seorang petugas di Panti Asuhan III Pondok Bambu
berkata dari balik kaca matanya: "Gelandangan memang tidak mau
dituduh sebagai gelandangan sekarang, karena mereka tahu itu
dilarang. Saya yang berkecimpung dengan mereka sejak belum punya
anak sampai ada 8 anak sekarang, melihat sendiri bahwa hidup
sebagai gelandangan sudah menjadi pekerjaan. Mereka kebanyakan
profesional". Ia melirik sejumlah gelandangan yang
dikonsentrasikan menanti pengembalian ke daerahnya, lalu berkata
seakan ia sudah jenuh menghadapi mereka: "Ada 3 aksioma di
kalangan mereka: nyolong, bohong dan seks bebas". Petugas ini
menyatakan ketiga penyakit itu sulit sekali disembuhkan. Apalagi
ada istilah BADAK di kalangan mereka yang berarti: 'Biar Aku
hidup Dalam Alam Kepuasan' -- untuk wanitanya. Serta
diartikan: 'Biar Aku Dosa Asal Kenyang' -- untuk lelaki. Iapun
berkata dengan sedih: "Yang tak habis saya fikir, mereka tidak
memikirkan hari depan".
Mungkin duduk soalnya sangat berbeda dari mata gelandangan
sendiri. Amrin tua, yang tidur di samping rel kereta daerah
Senen selama puluhan tahun, adalah seorang gelandangan
profesional. Dia masuk Jakarta sejak Belanda dikalahkan Jepang.
Hidupnya tak lebih menanjak dari seorang yang sibuk mencari
makan dalam satu hari. Tubuhnya sehat, rohaninya pun sehat --
karena selama gubuknya nempel di kompleks pelacuran Planet, ia
bersumpah-sumpah tak pernah menyewakan kamarnya untuk
"begituan". Sekarang, sambil tidur di alam terbuka bersama
isteri dan 3 anaknya, ia terima pekerjaan membersihkan selokan
yang menghasilkan Rp 2000 sebulan, ditambah bertanam bayam dan
sawi di sekitar daerah rel yang bisa memberikan Rp 4000 sebulan.
Pada saat Jakarta melakukan pendaftaran gelandangan untuk
memperoleh kartu kuning tanda hak memilih, ia begitu aktif
sehingga tampaknya lebih dari petugas. Sambil menyandang sarung
dan memakai topi, mukanya yang kasar tapi ramah berhasil menarik
teman-temannya mencatatkan diri sejumlah 952 selama 3 malam --
padahal sebelumnya petugas hanya memperkirakan gelandangan di
sekitar itu hanya 600. Diam-diam iapun sudah memiliki tanah di
Bekasi yang dicanangkannya untuk menampung hari tuanya --
padahal sekarang pun ia sudah tergolong tua.
Warga Jakarta yang bukan gelandangan, di samping mengulurkan
uang receh dari mobil, atau melemparkan sisa makanan, ada juga
yang berfikir agak jauh. Di antaranya mengumpulkan gelandangan
anak-anak, dan menampungnya dalam sebuah asrama untuk diberi
hari depan dengan kesempatan sekolah. Sejak 3-4 tahun yang lalu,
S.S. Lumi yang menyebut usaha sosialnya KDM (Kampus Diakonia
Modern) di Kali Baru, sudah pernah menampung sampai 160-an
anak-anak terlantar yang merangkaki jalan raya ataupun yang
sudah pintar untuk datang sendiri menyerahkan diri. Kini masih
ada 20 anak yang sedang dalam asuhannya (10 SMP, 8 SD dan 2 tak
sekolah) ditambah suami-isteri bekas pengumpul kertas yang
mangkal di belakang stasiun Senen. Tetapi usaha-usaha semacam
ini masih terlalu sedikit.
Sementara itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur sibuk pula
menjatuhkan hukuman berdasar pasal 504 dan 505 KUHP, sehingga
berjejallah kaum gelandangan di LPK Pondok Bambu untuk menjalani
hidup tak bebas rata-rata selama 2 bulan. Kemudian mereka
dikirim ke Panti Asuhan III, juga di Pondok Bambu, sampai mereka
dianggap pantas untuk dikembalikan ke asalnya, atau dipindah ke
Semper kalau mereka mau dan memenuhi syarat untuk
ditransmigrasikan. Mungkin karena usaha ini pun tidak begitu
mempan, Menteri Sosial HMS Mintareja sampai mengemukakan di
hadapan Komisi VIII/DPR-RI bahwa untuk para gelandangan
diperlukan perundang-undangan baru--karena pasal 504 dan 505
KUHP masih terlalu ringan.
Memakai gincu, kebaya merah muda, Sasih duduk dengan sendu di
samping Waskan, suaminya yang tanpa kaki kanan. "Pokoknya kalau
bisa, saya mau bawa pulang dia sekarang. Di rumah tidak ada yang
ngurus anak-anak", ujarnya. Puluhan pasang mata dari muka yang
pucat, kuyu, haus perhatian, malas dan sedikit rasa dengki, ikut
berbinar seperti mengucapkan hal yang sama. "Saya bukan
gelandangan. Saya datang untuk mencari anak saya dari isteri
pertama di daerah Senen", tambah Waskan. Ia mengaku bekas
pejuang Angkatan 45 yang bertempur di daerah Kuningan dalam
kesatuan Siliwangi. Dengan rasa sesal ia mengutarakan rasa
rindunya pada rumah di kampung Goa, Cirebon, di mana ia bekerja
sebagai tukang pateri, tambal ban dan reparasi lampu. Ia
memiliki sepetak kebun singkong dan tiga orang anak yang harus
difikirkan masa depannya. Lebih dari 2 bulan disekap -- yang
menyebabkan isterinya sekali menjenguk harus menyerahkan 2 kali
Rp 700 kepada kondektur bus Cirebon-Jakarta -- memang pantas
membuat dia rindu rumah. Ia mengaku dikeruk di daerah Senen
tatkala baru saja turun dari bus.
ADAPUN pemandangan berikut ini terlihat pada pukul sebelas pagi
di Panti Sosial III Pondok Bambu daerah Klender. Pada saat lebih
100 orang yang dianggap' gelandangan baru saja menyelesaikan
sarapan. Dengan lauk sayur tempe dan mengaku kurang makan, para
penghuni yang menunggu waktu untuk dikembalikan ke tempat
asalnya itu menampilkan wajah kotor ibukota yang sebenarnya.
Mereka pernah menggerayang bagai tikus-tikus kota yang diburu
oleh team penertiban. Wajah mereka lebih banyak menolak sikap
yang seakan-akan menghukum kemiskinan sebagai dosa. Beberapa di
antaranya memperlihatkan kesehatan yang bobrok dengan kudis di
seluruh tubuh. Tapi sementara itu mereka,dengan gaya priyayi,
masih menghembuskan asap rokok yang berasal dari kebaikan hati
orang-orang yang menengok. Benar di antaranya ada juga yang
tersekap karena kesialan ditabrak peraturan, padahal memang tak
ada niat untuk hidup sebagai gelandangan. Tetapi semuanya ini
memandang dengan air muka yang sama kepada setiap orang yang
datang, dengan satu harapan: pulang. Tapi ke mana?
Benar-benarkah mereka memiliki tempat di Republik ini, ke mana
mereka tidak hanya bisa pulang, tapi juga hidup wajar?
Kasan, suami Kanisah yang dahulunya nangkring sebagai pengumpul
kertas di daerah Senen, ngotot bilang punya rumah kontrakan di
Cengkareng. "Sumpah! Saya bayar 7.500 setahun. Saya mau pulang
ke sana. Di sini badan saya sakit kurang makan", ujarnya dengan
mata memelas, sambil menarik celana panjangnya -- yang ia
dapatkan dengan 15 hari tidak makan. Sementara teman hidupnya
yang bernama Kamisah masih meneruskan pengembaraannya di Senen
Raya sebagai pengumpul kertas. Kasan ini sudah beberapa kali
kena garuk, tetapi beberapa kali pula berhasil menyogok para
petugas. Selalu berjanji untuk pulang, tapi selalu saja tampak
kembali ke emperan toko di Senen Raya sebagai pengumpul kertas.
Ia punya radio, jam tangan, kadangkala memelihara anjing
kecil,dan tak jarang menampung gelandangan lain -- yang
kelihatannya belum lama mencium udara ibukota yang metropolitan
ini. Tak heran kalau Kasan merasa tak betah dikurung dalam
barak-barak ramai, terutama karena campur dengan orang lain --
sementara di daerah operasinya ia dikenal sebagai "orang berada"
di kalangan kaki lima. Kata pulang yang dimaksudkannya
barangkali kembali kepada dunia lepas yang menjadi kesukaannya,
karena di sana ia, bisa merasa sedikit seperti seorang
"priyayi". Bayangkan: harga diri.
Sri Sudinah, yang ngotot tak suka menyebut diri gelandangan,
bertekad pula untuk pulang ke Tegal. Padahal ia sudah 6 kali
keluar masuk Panti, bahkan oleh petugas sampai diantar sendiri
ke daerahnya. Nenek usia 68 tahun ini, jangan main-main, memang
bisa berbahasa Belanda. Dan ada kemungkinan lari dari rumahnya
karena tekanan jiwa. Ia mengaku punya 3 cucu yang sekolah di
negeri Belanda, rumahnya di Tegal sering dapat tamu dari luar
neger, sehingga ia tak betah tinggal di rumah, katanya.
Terakhir ia ditangkap di Pasar Tanah Abang waktu belanja.
Tatkala Jaksa dengan main-main mengancamkan hukuman 6 tahun agar
dia kapok. jawabnya: "Biarin. Sampai mati juga tak apa". Dan
waktu di Panti Asuhan ditakut-takuti akan ditahan seumur hidup,
ia berkata tenang: "Lari. Kan punya kaki". Tetapi tatkala
ditawarkan hendak masuk ke Panti Wreda di Cipayung, tempat
kumpul orang-orang jompo. ia cepat menolak: "Tuan, saya ngarep
betul kembali ke Tegal, saya sudah kapok, saya nggak bakal
gelandangan lagi, habis ada larangan besar. Betul tuan!" Tetapi
Mokhtar, salah seorang petugas di Panti itu, cepat-cepat
bilang: "Lihat saja nanti. Kalau diantar pulang, kita belum
kembali dia sudah duluan di sini". Menurut Mokhtar, kebiasaan
pegang uang menyebabkan semua isi Panti ingin sekali segera
"pulang" -- kata mana lebih baik diartikan kembali
menggelandang.
Juga Pulung bin Uding. Ini pemuda yang cacad kaki kirinya karena
dipatuk ular tanah, berniat pulang ke Rangkasbitung. "Saya tak
akan ke Jakarta lagi. Saya kapok". Ia memakai kopiah, bahasa
Indonesianya tidak lancar, mukanya jernih, maklum terkenal
paling rajin menunaikan shalat sehingga para petugas sendiri
jadi malu. Dua bulan menjalani hukuman di LPK dan baru 13 hari
di Panti Sosial, ia mengaku gentayangan ke Jakarta untuk mencari
saudaranya.Tertangkap sebagai pengemis selagi makan di warung --
bahkan belum sempat bayar. Baru seminggu di Jakarta ia sudah
berhasil mengumpulkan Rp 18 ribu -- bahkan beberapa saat sebelum
tertangkap ia masih menerima pemberian sebanyak Rp 2000. "Uang
saya semuanya diambil oleh petugas LPK", katanya mengadu, dengan
tak berdaya. Jumlah pemberian ini, yang mungkin disebabkan oleh
belas orang melihat cacad raganya serta juga kepintarannya untuk
memilih lokasi di Mesjid Istiqlal pada hari Jum'at, menimbulkan
kesangsian: benarkah sesudah dibebaskan kembali ia tidak tergoda
meneruskan debutnya di Jakarta sebagai pengemis yang kaya.
"Kebiasaan kita untuk menderma langsung sebenarnya kurang kena",
ujar Rochiyat dari Panti Sosial II Pondok Bambu. Itu tentunya
bisa dinasihatkan juga kepada gelandangan sejenis Pulung bin
Uding itu.
Dari Pondok Bambu, yang tak berniat pulang di antaranya adalah
pemuda Syarif dari Ciamis, berusia 5 tahun. Meski wajahnya
kelihatan "blo'on, ia bisa baca tulis dan rapi juga tutur baha-
sanya -- walaupun memang kelihatan sangat minder. Janda Jamilah.
sesama gelandangan yang tersekap di Pondok Bambu, berhasil
memikat hatinya juga memberinya ketetapan untuk bersedia
ditransmigrasikan. Lantaran persyaratan transmigran ada 3 (tidak
cacad fisik, bebas G.30 S PKI dan harus sudah berkeluarga),
Syarif tak panjang fikir langsung melaporkan maksudnya -- dengan
terlebih dahulu menyatakan diri berdua sebagai suami-isteri.
"Saya akan bertangggung jawab terhadap Jamilah seumur hidup".
kata Syarif. Dalam pada itu pimpinan Panti hanya memberi
komentar: "Kami masih akan menilai keseriusan mereka itu".
Tak berapa lama kemudian, Syarif dan Jamilah sudah tampak di
Panti Pendidikan calon Transmigrasi DKI di Semper. Bersama 30
lainnya yang pernah menyerahkan diri ke Panti Sosial Jelambar
ataupun yang tergaet pembersihan, dia harus menjalani latihan 20
hari. Kemudian tergantung kapal-kapal datang. Semper, yang lebih
merupakan asrama dengan penerangan listrik, memang tidak
membayangkan sama sekali keadaan daerah yang bakal mereka
kunjungi sebagai petani atau peladang. Memang ada juga
latihan-latihan pertanian, tetapi ada terasa tidak cukup untuk
mempersiapkan seorang Syarif yang biasa gelandangan -- sementara
Jamilah yang Betawi asli ini bekas isteri seorang guru yang
boleh dibilang tak pernah memegang cangkul, konon pula kapak
untuk menebas hutan. Sehingga mengirimkan para gelandangan ke
daerah transmigrasi kadang disangka sebagai "pembuangan" atau
pengusiran halus, bukan pemberian kesempatan untuk hidup lebih
wajar dengan bekal yang cukup -- dalam lingkungan yang sama
sekali baru. Lihatlah di panti ini banyak WC yang bumpet oleh
kotoran manusia, kamar mandi yang terbengkalai dan diseraki
kotoran mereka yang rupanya bingung mencari tempat buang hajat
besar, yang antara lain menunjukkan bahwa mereka ini belumlah
bebas dari "mental gelandangan". Bola-bola lampu yang raib,
disikat oleh transmigran sebelumnya sesaat menjelang mereka
berangkat. Juga tulisan-tulisan iseng di tembok dan pintu yang
lebih menunjukkan hasrat hubungan seksuil daripada persiapan
untuk membuka daerah yang masih perawan. Apalagi kalau ditengok
pasangan Pak Ja]i dan Ipah, bekas pengumpul kertas yang
berhasrat memperbaiki nasib dengan berkata: "Laksana burung, di
mana dipatok di-situ kita duduk. Sekarang saya menyerah". Tapi
usianya sudah 60 tahun, meskipun di kertas dinyatakan baru
50-an.
Edy Supriatna, anak muda dari Ciamis bekas pengumpul barang
rongsokan di Jembatan Lima, berkata: "Saya ini orang tani Oom.
Soal-soal tani sudah biasa, kita tidak akan ragu-ragu lagi". Ia
tidak memamerkan janji-janji. Ia hanya mengatakan kalau dulu ia
ingin ke Jakarta untuk mencari pengalaman kini ia ingin lebih
jauh dari Jakarta lagi. Di sampingnya ada Yati, yang
diketemukannya di stasiun dan bersedia ikut ke mana saja. Belum
lagi adik tirinya yang bernama Didi Supriadi (18 tahun), yang
kebetulan ditemukannya di jalanan sebagai pemungut puntung
rokok. Dengan menahan air mata ia langsung pergi ke Jelambar
setelah mendengar dari beberapa rekannya ada kemungkinan untuk
menjadi transmigran. Didi sendiri yang masih sangat belia udah
berhasil juga mendapat pasangan dalam asrama Semper: seorang
wanita seperti tante-tante yang cukup genit, yang sebetulnya
pantas menjadi ibunya. Mereka ini kuat dan muda, serta tampak
dari air muka berperangai baik. Tapi betulkah Edy tidak akan
tergoda untuk membandingkan hidupnya kelak sebagai petani,
karena penghasilannya sebagai tukang barang rongsokan bisa
mencapai Rp 500-Rp 700 sehari -- menurut pengakuannya?
Menurut Sofyan Yahya. Wakil Kepala Dinas Sosial DKI itu, pada
tahun ini tercatat 1.638 jiwa yang sudah ditransmigrasikan.
Dalam pembersihan-pembersihan yang terakhir diketemukan banyak
yang tak memenuhi syarat untuk dikirim karena cacad atau sudah
gaek. Proyek transmigrasi memang dimaksudkan akan membawa
perubahan bagi mereka, di samping untuk membersihkan DKI dari
gelandangan. "Mereka mengganggu ketertiban umum", ujar Sofyan,
mengulangi konsideran SK Gubernur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini