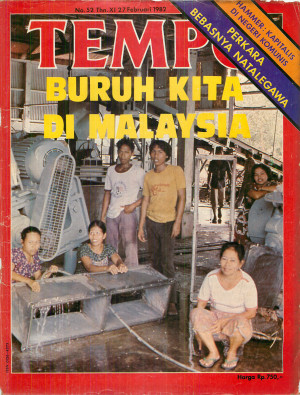SUARA penyanyi Hetty Koes Endang terdengar dari rumah panggung
di celah-celah perkebunan karet. Sejumlah rumah menghiasi ruang
tarnunya dengan wayang kulit dari miniatur rumah Toraja.
Di halaman samping beberapa rumah terlihat kawatak, kain tenun
khas Timor, tengah dijemur. Sepintas, suasana kompleks
perkebunan karet Borneo Abaca Ltd (BAL) Estate di dekat Tawau,
Sabah (Malaysia) itu mirip perkampungan buruh perkebunan di
Sumatera Utara.
Bedanya, buruh asal Indonesia di perkebunan karet BAL itu
terlihat lebih makmur. Rantai emas melilit leher hampir setiap
gadis dan ibu rumah tangga. Tape recorder, radio dan relevisi
berwarna mudah dijumpai di setiap rumah. Bahkan video tape, yang
di Indonesia masih dimiliki kalangan terbatas, sudah memasuki
beberapa rumah orang yang lebih mampu.
"Mana mungkin anak saya bisa menjadi orang kalau cuma menjadi
buruh perkebunan di Indonesia," kata Tawi bin Talitia, 56 tahun,
kepada TEMPO. Lelaki tua yang meninggalkan kampungnya,
Mattirowal di Mare, Bone, Sul-Sel sejak 1956 itu, memang boleh
menepuk dada.
Dari 6 orang anaknya, dua menjadi guru SD di Tawau, seorang
bekerja pada perpustakaan Desa Semporna, sekitar 50 km dari
Tawau--sementara 2 anaknya yang lain masih duduk di SD. Anaknya
yang sulung hampir tamat Fakultas Komunikasi Geografi Universiti
Kebangsaan Selangor. Dari tetesan keringatnya menderes (menakik)
karet, Tawi juga bisa menyekolahkan adik iparnya sampai tamat
IKIP di Ujungpandang.
Selepas sembahyang subuh, pukul 06.00 ia sudah siap di bawah
pohon karet dengan pisau deres dan dua tong kaleng. Tugas
menakik karet hanya dilakukan sampai pukul 12.00. Gajinya 9,2
ringgit (sekitar Rp 2.750) sehari atau 239 ringgit sebulan
dengan 26 hari kerja. Tapi Tawi--juga kebanyakan buruh dari
Indonesia yang memburu duit--sering lembur sampai pukul 14.00
atau lebih. Tarif lembur satu jam 1,34 ringgit. Dengan begitu
sebulan paling tidak ia bisa mengantungi 300 ringgit. "Dengan
hidup hemat, sebulan kami cukup mengeluarkan uang 150 ringgit
untuk sekeluarga," katanya.
Tabungannya bertambah besar terutama karena untuk menyekolahkan
anak-anaknya Tawi tak perlu mengeluarkan biaya. "Di Sabah tak
perlu membayar uang sekolah. Bahkan anak-anak mendapat jatah
susu, pakaian, buku dan lain-lain," tambahnya. Ia cuma
menyediakan uang transpor dan uang jajan.
Niat mencari duit di negeri orang itu timbul karena Tawi sulit
mencari nafkah di kampung halamannya. Apalagl musibah melanda
keluarganya ketika gerombolan Kahar Muzakkar membakar rumah dan
mengangkut harta benda Tawi. Dengan bekal pas-pasan, 1956 Tawi,
bersama beberapa temannya, menyeberang ke Tarakan di Kalimantan
Timur lewat Pare-pare dengan perahu kecil. Dari Tarakan mereka
terus ke Nunukan, pulau kecil di perbatasan Kal-Tim dan 8abah.
Dari sini mereka menyusup Tawau dengan perahu selama 4 jam.
Sampai di Tawau segala macam pekerjaan diterimanya mencuci
piring, menjaga keamanan dan kemudian memburuh di perkebunan
karet.
Setelah diterima sebagai buruh perkebunan, ia mendapat perumahan
sederhana. Seketika itu pula ia menjemput istri dan
anak-anaknya. "Ini prestasi yang lumayan, 23 tahun bertahan
sebagai penderes karet," kata Tawi. Jika telah bekerja 25 tahun,
ia berhak menikmati pensiun berupa pesangon 1.200 ringgit. Untuk
hari tuanya, kecuali mengharap kiriman anaknya yang sudah
bekerja, Tawi juga berniat mengolah sawah di kampung
kelahirannya yang telah ia beli beberapa tahun lalu.
Bagi buruh di Bal Estate agaknya tidak terlalu penting mengejar
karir mencari kedudukan yang lebih tinggi. "Kami hanya mencari
duit," kata Kia Tkan, 45 tahun, lelaki asal Adonara, Flores.
Jabatannya mandor di perkebunan Bal. Di tangan kirinya melingkar
arloji merk Omega, hadiah pimpinan perusahaannya. "Semua buruh
yang telah mengabdi selama 25 tahun terus menerus mendapat
penghargaan sebuah Jam tangan Omega," katanya kepada TEMPO di
rumahnya, Kampung Mawar, Tawau. Bertugas sebagai penderes sejak
1956, sejak 10 tahun lalu ia menjadi mandor.
SEHARUSNYA Kia sekarang sudah berhak menjadi staf perkebunan.
Tapi jenjangnya terhambat karena ia hanya memegang identity
Card (ID) berwarna merah. Artinya, Tokan tetap memegang paspor
Indonesia. Tapi ia sudah mendapat izin tinggal di Malaysia.
"Banyak mandor lebih muda, tapi bisa naik karena memegang kartu
biru atau menjadi warga negara Malaysia," katanya.
Sebenarnya gampang saja bila Tokan ingin mengajukan permohonan
jadi warga negara setempat, karena ia sudah lama tinggal di
sana. Tapi "sampai sekarag saya belum mau. Saya dilahirkan di
kampung dan mau mati di kampung saya saja." Risikonya ia harus
puas dengan jabatan mandor. "Jabatan paling tinggi untuk warga
negara Indonesia cuma mandor," tambahnya.
Dan sebagai mandor ia mengawasi 80 buruh. Gaji sebulan 424
ringgit plus mendapat rumah berukuran 8 x 6 meter. Sedang
istrinya, Isah, wanita asal Madura. juga membantu suaminya
dengan bekerja di tempat penitipan bayi di areal perkebunan itu
upahnya 6 ringgit sehari. "Dua tahun sekali kami pulang
kampung," kata wanita yang gemerlapan dengan gelang dan kalung
emas itu.
Untuk persiapan hari tua, Tokan telah membeli 5 hektar kebun
kelapa dan 3 ekor kerbau di Adonara. Dua anaknya kini, duduk di
SD dan dua lagi di SlTP Tawau.
Berbeda dengan buruh-buruh yang dimandorinya, Tokan bekerja dari
pukul 06.00 sampai 13.00. Perusahaan juga menjaminnya dengan
asuransi: santunan 7.000 ringgit bila ia meninggal selama
bertugas. Pengobatan seluruhnya ditanggung perusahaan. "Selama
sakit kami masih tetap mendapat gaji penuh," kataya.
Walau buruh dipikat dengan berbagai jaminan dan gaji cukup
tinggi, mereka tidak diikat oleh perjanjian kerja. "Begitu kami
sampai di sini, langsung disuruh bekerja," kata Abdul Gafar, 29
tahun. Pemuda asal Sanggalia, Maros, Sul-Sel ini, masuk
kebunkaret di Bal Estate 9 Maret 1981. "Pokoknya setiap bulan
menerima gaji." Gaji yang dikantunginya sekitar 300 ringgit
sebulan. Tabungannya cepat membengkak karena istrinya, Nuraini,
juga ikut bekerja sebagai penyemprot hama dengan gaji 5,65
ringgit sehari.
Suami-istri Gafar meninggalkan karnpung halaman dengan modal Rp
200.000. "Itu untuk mengurus surat-surat, termasuk paspor dan
makan selama perjalanan. "Modal itu sekarang sudah kembali." Dia
merencanakan, membeli sawah di kampungnya dari uang tabungan.
"Kalau sudah punya sawah dan tabungan, saya akan pulang saja."
Perkebunan ternyata bukan satu-satunya sumber penghidupan orang
Indonesia yang merantau di Malaysia. Suryani, 54 tahun, sebulan
bisa menerimaupah 400 ringgit sebagai babu Restoran Tomato di
Tawau. Makan dan tempat tinggal untuk janda asal Malang Ja-Tim
ini sepenuhnya ditanggung majikannya. Sebagai babu, ia bisa
membiayai sekolah 4 anaknya yang ia tinggalkan di Malang: tiga
orang di SMA dan yang sulung kuliah di sebuah perguruan tinggi
di Malang. "Setiap bulan saya kirim 150 ringgit untuk biaya
anak-anak," katanya.
Lain halnya dengan Yani, 21 tahun. Wanita berkulit hitam manis
ini mengeruk duit melalui kamar Hotel Angs di Tawau. Ia memang
seorang pelacur. Sejak mengenal Sabah dua tahun lalu, Yani
sebulan sekali bisa pulang kampung di Jawa Timur untuk menengok
anak tung galnya dan orang tua sekaligus memperpanjang visa. Jam
kerja ia tentukan sendiri. Bahkan tarif juga diputuskan sendiri,
100 ringgit tiap tarnu. "Sehari bisa menerima 6 tamu," katanya
kepada TEMPO. Hasil bersih sehari bisa 300 ringgit. "Enaknya, di
sini saya tak perlu malu seperti di Malang," katanya, tertawa
lebar.
Hujan duit di negeri orang memang memikat orang yang lagi sulit
mencari rezeki di negeri sendiri. Aisyiah, 25 tahun, wanita dari
Desa Moroangin, Kecamatan Maiwa.Fnrekang, Sul-Sel, terpikat pula
mengadu nasib di Sabah, menyusul saudaranya yang sudah agak lama
mendahului. Modalnya: uang tunai Rp 15. 000 dan surat jalan dari
lurah. Tentu saja ia terhambat untuk melintas perbatasan karena
tidak punya paspor. "Untuk mengurus paspor perlu duit banyak,"
ujarnya. Selama masih di Nunukan, ia mencari duit dengan bekerja
sebagai penjual karcis bioskop. Setelah menangguhkan niatnya
menyeberang ke Sabah selama 13 bulan, Aisyiah berhasil
mengumpulkan Rp 30.000. Pertengahan 1976 semua surat yang
diperlukan sudah di tangan. Ia menyeberang dan menuju Tawau.
Pekerjaan pertama yang diperolehnya menjual karcis bioskop
dengan gaji 100 ringgit. Dan saat itulah ia bertemu dengan
Udding, pemuda asal Desa Wattae, Pancalautang, Sidrap, Sul-Sel,
buruh kebun kelapa sawit di Apasbalung, Tawau. Tahun itu pula
mereka menikah.
Tidak lama kemudian, pasangan muda ini angkat kaki dari Tawau.
Dari uang tabungan ,mereka menyewa tanah 2 hektar seharga 200
ringgit selama satu musim (4 bulan). Semangat mereka untuk
berwiraswasta dikembangkan di sini. Tanah yang disewa dari
penduduk asli itu ditanami cikui atau semangka. "Ketika itu di
sini orang belum ada yang menanam cikui," kata Aisyiah kepada
TEMPO. Keruan saja, setelah panen, semangka dari kebunnya laku
keras. Mereka berhasil mengeruk uang sekitar 6.000 ringgit (Rp
1,8 juta). Dari uang panen semangka-Udding bertambah semangat.
Ia menyewa 10 hektar lagi. "Tapi untungnya sekarang tidak
sebanyak dulu, karena sudah banyak orang yang menanam cikui,
kata Aisyiah. Hidupnya makmur. Setahun sekali mereka pulang
kampung.
AISYIAH sendiri memang kelihatan gemerlapan dengan emas yang
menghiasi leher, tangan, jari dan kakinya. Untuk mengurus 10
hektar kebunnya ia mempekerjakan 10 buruh dengan gaji
masing-masing 200 ringgit sebulan. Aisyiah sudah punya 8 hektar
sawah dan sebuah rumah mungil di kampung asal. "Saya tetap akan
pulang kampung kalau sudah punya modal," katanya.
Cerita sukses orang Indonesia mencari nafkah di negeri orang ini
punya daya tarik yang besar bagi orang di Sul-Sel, Nusa Tenggara
Timur dan juga Sumatera. Untuk memenuhi keinginannya, sering
calon buruh itu menyerahkan bulat-bulat nasibnya kepada
perantara atau calo yang memang secara teratur mengirim buruh ke
Malaysia. Yayah, 30 tahun, misalnya. Pemuda asal Kirikan Jambi
ini terdampar di Tawau lewat calo. Orangtuanya sebenarnya
mengirimnya ke Yogyakarta untuk kuliah di IAIN -- 1977. Tapi
setelah tingkat III ia kandas: orangtua tidak mampu mengirim
biaya. Setelah luntang-lantung di Yogya, awal 1981 ia berangkat
ke Tarakan untuk dapat menembus Tawau. Di Tarakan ia
mengumpulkan bekal dengan menjahit pakaian sekaligus nguping
bagaimana caranya masuk Malaysia. Ia menghubungi Haji Mustafa
yang sering mengirim buruh ke sana. "Semua surat sudah
dibereskan calo itu," katanya.
Sesampainya di Tawau, ia langsung ditugasi menebas rumput di
perkebunan kelapa sawit. Sarjana muda IAIN ini cukup puas dengan
pekerjaannya sebagai buruh kasar bergaji 6,90 ringgit sehari.
Cuma sialnya, sebelum mulai bekerja ia mesti meneken utang 380
ringgit, yaitu biaya mengurus paspor serta biaya
keberangkatannya ke Tawau. "Utang itu harus dicicil setiap bulan
50 ringgit. Sebelum lunas, paspor ditahan Pak Haji," katanya.
Akhir tahun lalu pangkatnya meningkat menjadi tukang deres
karet. Sebulan ia bisa mengantungi 400 ringgit. Cita-citanya
sederhana. Setelah uang terkumpul, ia pulang kampung untuk
membuka usaha kecil-kecilan. "Ijazah kami tak laku di perkebunan
karet ini," katanya.
Aaslinya Sukma Permana -- Tapi pemuda Tanjungpinang _ itu
berganti nama Yusuf bin Yunus setelah berada di Malaysia
"Supaya terasa lebih Melayu," katanya. Ijazah memang tidak
pernah digaetnya. Namun ia punya keahlian membuat tembok. Ketika
di Tanjungpinang, upahnya Rp 1.500 sehari. Ini lumayan untuk
hidup sebagai bujangan. Tapi pemuda berusia 25 tahun itu tergiur
juga akan cerita teman-temannya yang baru pulang dari Malaysia.
Di seberang sana, upah tukang batu 25 ringgit sehari atau Rp
7.000.
Dengan speed boat Yusuf bersama 10 temannya menyusup ke Johor
Lama, sebuah kampung di sebelah tenggara Negara Bagian Johor.
Taikong, atau calo, yang membawanya dari tanah air, langsung
menyerahkannya kepada seorang penadah, orang Malaysia. Seminggu
mereka disembunyikan di sebuah bangsal buruk di kebun karet.
Tapi cita-citanya untuk jadi tukang batu ouyar setelah ia
dilempar ke perkebunan kelapa sawit di Felda (The Federal Land
Development Authority) Air Tawar V.
"Apa boleh buat. Daripada kelaparan," katanya kepada TEMPO di
Johor. Setiap hari ia menanam kelapa sawit dengan upah 0,10
ringgit sebatang. Sehari penuh kadang-kadang bisa mengumpulkan
10 ringgit. Dari menancapkan bibit kelapa sawit, ia lantas
banting stir. Walau belum pernah membawa truk, ia nekat minta
pekerjaan sopir. Setiap hari Yusuf mengangkut kelapa sawit dari
kebun sampai pabrik sejauh 50 km. Gajinya lumayan, 18 ringgit
sehari.
Pekerjaannya berganti-ganti Dari sopir truk, sopir traktor
sampai buruh di pabrik bata. Dan setelah 2 tahun mengembara di
Malaysia kini ia menjadi pemborong pembangunan rumah murah di
Sungai Mas, Kota Tinggi Johor. Bahkan Yusuf, yang sudah fasih
berbahasa setempat, kini mempekerjakan 30 huruh yang sebagian
besar dari Indonesia. Ia kelihatan mentereng dengan mobil yang
dibelinya 7.000 ringgit. Tempat makannya pun di restoran Desaru
Holiday, tempat rekreasi mewah di ujung Tenggara Johor. "Biar
kalah sabung, asal menang sorak," katanya tertawa lebar.
Tapi tidak semua orang Indonesia yang memburu duit di Malaysia
bernasib baik. Sebagian besar, sekitar 75%, bekerja di
perkebunan kelapa sawit, karet, cokelat dan kopi. Selebihnya
sebagai buruh pada proyek pembangunan jalan, konstrulesi dan
lain-lain. "Betapa pun uletnya bekerja, seorang buruh di kebun
kelapa sawit sehari paling banter cuma mendapat 20 ringgit,"
ujar M.Nur, 32 tahun, kepada TEMPO di perkebunan swasta Johore
Silica Estate, sekitar 100 km dari Kota Tinggi, Johor. Orang
muda asal Bengkalis Riau ini memang sudah bertekar mengadu nasib
di Malaysia. "Kalau di kampung, menjadi buruh, mengangkat batu
segala, malu," katanya.
Di perkebunan kelapa sawit Nur bertugas sebagai penyemprot hama.
Jam kerja dari 7.00 sampai 13.00. Upahnya 11 ringgit sehari. Dan
kalau hujan terus-menerus, para buruh tetap mengurung diri di
barak. Artinya tidak mendapat duit. "Praktis penghasilan cuma
untuk makan," katanya. Biasanya ia bisa mengumpulkan uang 300
ringgit sebulan. Tempat tinggalnya yang disediakan perusahaan
lumayan. Sebuah rumah beton dua kamar. Setiap kamar dipakai
bersama 7 orang. Pakaian kumal untuk bekerja di kebun kelihatan
bergelantungan di samping rumah. Setiap bulan ia bisa menabung
150 ringgit, sisa biaya hidup.
Seorang buruh berpengalaman dan trampil sehari bisa mengumpulkan
200 tandan kelapa sawit. Tapi Thamrin, 20 tahun, pemuda asal
Lombok, baru di perkebunan itu melihat kelapa sawit. Sehari
paling banter ia cuma berhasil menurunkan 40 tandan atau
mendapat 5 ringgit. "Untuk bayar utang saja tidak cukup,"
katanya. Karena itu ia memilih pekerjaan lain, menyemprot hama.
Mulanya Thamrin memang - tergoda ke Malaysia oleh ajakan orang
lain, yang menjanjikan bahwa dia akan bisa menabung Rp 1 juta
setahun di Negri itu. Tertarik oleh janji muluk, Thamrin meminta
semua perhiasan ibunya untuk dijual. Dengan modal Rp 150 ribu ia
diberangkatkan seorang calo lewat Tanjungpinang menuju Malaysia.
Karena sudah kepalang basah, Thamrin tidak mundur. "Biar menjadi
umpan nyamuk, saya teap bertahan," katanya. Gangguan utama di
tengah hutan kelapa sawit itu memang nyamuk. Tapi ia toh sempat
bangga, karena mempunyai tabungan 1000 ringgit setelah bekerja
setahun. Dengan uang simpanan itu Desember lalu ia pulang
kampung menengok ibunya yang tengah sakit.
TAPI yang membuat para buruh yang masuk seca tidak sah
gelisah adalah razia polisi. Suryani, 18 tahun, terdampar di
Malaysia karena ikut suaminya yang bekerja di Felda Air Tawar
III. Wanita Bugis yang baru 3 bulan kawin itu bekerja menanam
bibit dan memotong pelepah kelapa sawit. Sehari bisa mendapat 12
ringgit. Suatu hari, perutnya berontak karena memang sudah hamil
tua. Ia memberanikan diri pergi ke rumah sakit Kota Tinggi untuk
memeriksakan perutnya. Belum sempat mendapat pertolongan, dua
polisi mendatanginya. Ia ditangkap dengan tuduhan hamil di luar
perkawinan dan pendatang haram. Suryani berusaha meminta maaf
dan mengeluarkan isi dompetnya untuk menyogok polsi agar
dibebaskan.
Ia tetap diperiksa. Surat nikah ia tunjukkan. Tapi tuduhan
sebagai pendatang haram tetap dijatuhkan. Polisi membebaskan,
dengan perintah segera meninggalkan Malaysia. "Perut sudah
begini sakit, mana mungkin berangkat," katanya. Ia kembali ke
perkebunan, dan dua hari kemudian lahirlah anaknya yang pertama
di barak. "Saya tidak kembali ke rumah sakit. Takut ditangkap
lagi," katanya. Karena dikejar-kejar polisi sebagai pendatang
haram, setelah bayinya berumur 5 bulan, Suryani dan suaminya
meninggalkan Malaysia. "Inilah harta yang kami bawa pulang,"
katanya pada TEMPO di Johor Lama, sesaat sebelum masuk perahu
menuju Batam di tengah hujan lebat. Ia menunjukkan bayinya yang
dibungkus kain, melangkahkan kaki, mengakhiri petualangan
sebagai pendatang haram.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini