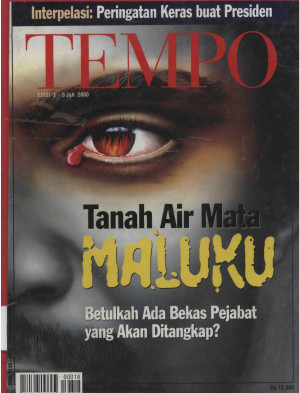MENGAPA obat harus mahal? Jawabannya bisa beragam. Di Indonesia, rata-rata bahan baku obat harus diimpor, sehingga hampir tidak mungkin menjualnya lebih murah. Mungkin dalam biaya impor, selain bea masuk, ada beberapa pos pengeluaran lain, termasuk pungutan, resmi ataupun tidak. Industri farmasi sendiri terdorong untuk memberikan nilai tambah pada obat, dengan ekstravitamin dan semacamnya, yang berdampak pada lonjakan harga. Lalu, dalam distribusi, biasanya ada promosi dan rekayasa pasar, yang lagi-lagi mendongkrak harga.
Pemerintah, sejak awal 1990-an, berusaha meredam kecenderungan tingginya harga obat. Pada masa itulah dikampanyekan pemakaian obat generik—dan kampanye ini masih berlanjut sampai sekarang. Tujuannya baik: untuk membuat obat terjangkau bagi rakyat kecil.
Namun, krisis ekonomi telah merusak segalanya. Lonjakan harga obat hampir mencapai 200 persen. Pada awal 1998, saat kurs rupiah terbanting ke belasan ribu per dolar, misalnya, antibiotik Amoxcillin 500 miligram berharga Rp 3.000 per butir. Padahal, sebelum krisis, harga pil ini hanya Rp 1.100 tiap butir.
Kini, gejolak harga obat mulai bisa dikendalikan. Namun, harga obat—rata-rata 1,5 hingga 2 kali lipat harga sebelum krisis—tetap dirasakan kelewat mahal. Tidak rasionalnya harga obat juga terlihat pada perbedaan antara harga obat paten dan generik. Obat paten—dengan kandungan zat aktif persis sama—bisa berharga 2-6 kali lipat obat generik.
Guna memangkas ketidakwajaran harga, Departemen Kesehatan (Depkes) menggodok rambu-rambu yang bakal diresmikan bulan depan. "Supaya harga obat lebih masuk akal," kata Sampurno, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Depkes. Ia menjamin, aturan ini bukanlah penyeragaman. Depkes hanya mengharuskan pengusaha farmasi melaporkan rincian komponen produksi obat—misalnya ongkos riset, pemasaran, dan promosi. Berdasarkan rincian ini, Depkes bisa menegur produsen yang sewenang-wenang melambungkan harga.
Menurut Sampurno, selama ini, promosi berperan sebagai komponen utama pendongkrak harga. Untuk obat yang beredar bebas—seperti obat flu dan obat batuk—televisi menjadi alat promosi utama. Memang, ongkos iklan televisi mahal. Tapi, dengan skala produksi massal, harga jual obat bebas bisa ditekan semurah mungkin. Sedangkan untuk yang paten, peredaran obat hanya melalui resep dokter. Alhasil, dokter terbawa dalam strategi promosi farmasi. Produsen pun agresif mengumbar imbalan bagi dokter yang mau bekerja sama.
Nah, promosi yang merangkul dokter ini membuka peluang kolusi. Dengan iming-iming hadiah berupa barang, uang, atau perjalanan mengikuti konferensi ilmiah di luar negeri, dokter meresepkan obat yang dikehendaki pengusaha. Obat generik, yang praktis tanpa imbalan apa pun, jadi terlupakan. Kelak, melalui perangkat aturan yang baru, Depkes melarang model promosi yang tidak etis semacam ini. Dokter atau pengusaha yang terbukti melanggar akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. "Hukumannya lumayan, maksimum 5 tahun penjara atau denda Rp 2 miliar," kata Sampurno.
Merdias Al-Matsier, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), membenarkan adanya promosi yang tidak etis seperti itu. Salah satu caranya, dokter menyetor kopi resep kepada produsen. Untuk setiap butir obat, sang dokter kebagian untung beberapa ratus rupiah. Kalau target penjualan terpenuhi, hadiah menggiurkan sudah menanti. Dalam hal ini, organisasi profesi seperti IDI tak bisa berbuat banyak. "IDI hanya memberikan sanksi moral. Kami mengembalikan persoalan ini kepada hati nurani dokter," kata Merdias.
Namun, Anthony Sunarjo, Ketua Gabungan Pengusaha Farmasi, membantah bahwa promosilah biang mahalnya obat. Seperti diketahui, perusahaan farmasi—sebagian besar multinasional—mematok 30-35 persen dana untuk pos promosi. Anthony juga tidak menampik adanya kerja sama dengan dokter. "Bertepuk toh tak mungkin cuma dengan satu tangan. Kedua pihak terlibat untuk membuat obat jadi laris," katanya. Tapi, ia memastikan, total pos promosi tak lebih dari 35 persen, sesuai dengan standar perusahaan farmasi dunia.
Menurut Anthony, komponen utama pendongkrak harga obat adalah riset. Sejak senyawa aktif dipatenkan, perusahaan farmasi menanam ratusan juta dolar untuk riset yang bertahun-tahun. Pengusaha, tentu saja, berkepentingan menggenjot harga agar investasi beranak-pinak. Dengan demikian, Anthony yakin, regulasi harga obat tak bakal berjalan mulus. Katanya, regulasi tidak akan membuat harga obat jadi murah, malah sebaliknya. "Ini zaman perdagangan bebas. Obral peraturan bisa membuat investor lari," katanya, setengah menakut-nakuti.
Tapi pihak konsumen tidak harus menyerah begitu saja. Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) merintis terobosan ala general purchasing alliance (GPA) yang diterapkan pemerintah Australia. Kelak, Persi menjadi semacam agen tunggal yang memasok kebutuhan seribu rumah sakit anggotanya. Nah, dengan pembelian partai ekstrabesar, otomatis harga jual obat bisa ditekan. Siapa menyusul?
Mardiyah Chamim, Hani Pudjiarti, Darmawan Sepriyossa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini