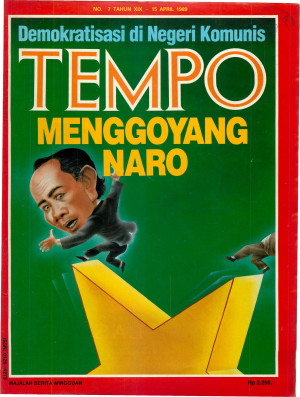FROFESI kedokteran digugat. Kali ini bukan oleh pasien, melainkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Penggugatnya adalah Ketua IDI dr. Azrul Azwar. Dikatakannya, standar profesi dokter di Indonesia masih belum tertib. Pernyataan rendah hati dan jujur ini diutarakannya pada sambutan acara Simposium Perdarahan Non-Traumatik, yang terselenggara dalam rangka HUT RS Pelni, Jakarta, pekan lalu. Belum tertibnya standar profesi ini tentu berkaitan erat dengan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit (RS). Akibatnya, pelayanan di RS tertentu sering berbeda dengan pelayanan di RS lain. Bahkan servis di satu bagian RS, di bagian penyakit dalam, misalnya, sering pula tidak sama dengan servis di bagian bedah. Akibatnya, banyak terjadi perbedaan tindakan dalam pemeriksaan, perbedaan peralatan yang digunakan, dan perbedaan biaya -- hingga bisa menyebabkan terjadinya penyelewengan yang merugikan masyarakat. Ini menurut Azrul. Contohnya, karena tidak ada pedoman standar pelayanan, kasus pengelolaan operasi usus buntu di tiap rumah sakit bisa bervariasi. Ada RS yang merawat pasien usus buntu selama 3-5 hari saja -- karena kocek si pasien pas-pasan -- walaupun bekas jahitannya belum kering. Sedang pasien yang kantungnya tebal bisa dirawat sampai 20 hari, padahal sudah sembuh. "Penyelewengan-enyelewengan seperti ini yang tidak kita kehendaki," ucap Ketua IDI itu. Jadi, perlu disusun standar pelayanan kedokteran. "Stadar itu tidak saja dapat dipakai untuk mengukur mutu pelayanan, tapi juga buat kepentingan pembelaan di pengadilan," ajarnya lagi. Di samping itu, ada standar pekerjaan dokter yang sejauh ini juga belum dibakukan. Meskipun mirip, sebetulnya standar pekerjaan dokter lebih terkait dengan standar profesinya. Memang ada yang rancu memakai istilah standar profesi dokter. Biasanya standar ini dianggap hanya terbatas sebagai pedoman "perlengkapan" di ruang praktek, seperti pengukur tekanan darah atau stetoskop. Padahal, standar profesi itu bukan standar perlengkapan. Wakil Azrul, yang juga bekas Ketua IDI, dr. Kartono Mohamad, ketika dihubungi TEMPO menyatakan bahwa standar profesi beda dengan standar perlengkapan, dan beda pula dengan standar pekerjaan dokter. Menurut Kartono, standar profesi dokter justru menjadi dasar bagi pekerjaan atau pelayanan kesehatan yang dilakukan seorang dokter. "Standar profesi itu sebetulnya suatu tolok ukur untuk menentukan apakah seseorang memenuhi kriteria profesi atau tidak," kata Kartono. Adapun standar pekerjaan dokter berguna untuk menentukan apakah seseorang telah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan profesinya atau tidak. Dengan kata lain, "Apakah dia menjalankan profesinya dengan benar atau tidak." Standar profesi lebih menyangkut soal pengetahuan dan keterampilan dokter, sedangkan standar pekerjaan terkait pada pekerjaan dokter sehari-hari di lapangan. "Artinya, orang yang memenuhi standar yang pertama -- katakanlah ia pandai dan terampil sesuai dengan standar profesinya -- belum tentu menjalankan pekerjaannya dengan baik," kata Kartono. Repotnya, tolok ukur profesi dokter, menurut "dwitunggal" Azrul -- Kartono, selama ini hanya dilihat dari ijazahnya. "Selama ini, kalau sudah lulus pendidikan, sang dokter -- sebagaimana pengacara dan arsitek -- dianggap sudah memenuhi standar profesi," ujar Kartono. Padahal, belum jelas apakah dokter lulusan universitas swasta sama mutunya dengan lulusan universitas negeri, sementara lulusan universitas negeri yang satu dengan yang lain juga sering tidak sama. Maka, pengukuran mutu itu jadi sulit, berhubung belum adanya standar yang baku. Sehingga, ketika sebuah universitas mesti menerima dokter lulusan luar negeri untuk melakukan adaptasi, masalah ini jadi terasa kian perlu dibenahi. Sebetulnya, kata Azrul, sudah ada dokter yang menerapkan standar-standar itu secara bagus. "Tapi karena standar dokter yang satu berbeda dengan dokter yang lain, maka ini bisa merugikan masyarakat," ujar Azrul. Itulah sebabnya, perlu ada penyeragaman semua standar. Dan itu sudah lama disiapkan IDI, bersama ke-18 perhimpunan dokter spesialis dan 12 perhimpunan dokter yang dinaunginya. "Mudah-mudahan setahun lagi standar-standar itu sudah siap," janji Azrul. Juga disiapkan sistem pengawasannya. "Kita memang butuh sistem pemantauan yang baik, misalnya dengan membentuk dewan dokter di rumah sakit." Kelak, bila standar baku sudah ada, maka bisa dinilai apakah seorang ahli anestesi, misalnya, sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar atau tidak. Menurut Kartono, bisa dilihat apakah anestesiolog itu sudah melakukan tahapan-tahapan pekerjaan yang benar, mulai dari pemeriksaan darah, foto ronsen, lalu pemeriksaan fisik sebelum pembiusan, dan detail-detail pekerjaan lain selama operasi berlangsung. Bahkan sesudah operasi selesai pun, ahli itu mesti melakukan pengawasan yang ketat, yang biasa dilakukan di recovery room. "Jika ia tidak melakukan semuanya sesuai dengan standar prosedur, berarti ia belum menjalankan profesinya sesuai dengan standar pekerjaannya," kata Kartono. Kejelasan apakah seseorang telah menjalankan tugasnya menurut standar profesi semakin penting artinya bila terjadi kasus malapraktek. Bila ahli anestesi tadi dituduh melakukan malapraktek, misalnya, maka dengan mudah bisa ditinjau seberapa jauh ia telah melakukan tahap-tahap pembiusan -- termasuk persiapan dan follow-up-nya -- sesuai dengan standar ahli anestesi. Digarisbawahi oleh Azrul semua standar itu kelak akan berguna tidak saja bagi dokter dan RS, tapi juga bagi masyarakat. Rumah sakit, misalnya, akan mudah mengembangkan diri. "Karena RS punya pedoman pelayanan, ia bisa menghemat banyak biaya," kata Azrul. "Sebaliknya, pasien tak perlu membayar ongkos perawatan yang tidak semestinya."Syafiq Basri, Priyono B. Sumbogo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini