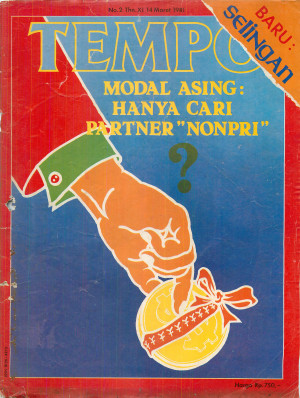STASIUN tak selamanya menjadi lambang kesibukan. Buktinya
stasiun keretaapi Sentolo. Terletak di tengah sawah, 17 km di
barat Kota Yogyakarta atau 13 km di timur Wates (Jawa Tengah),
stasiun ini bukanlah tempat lalu-lalang penumpang.
Pemandangan sehari-hari di sana: bangunan stasiun yang berukuran
6 x 6 meter dengan dua pasang rel yang membentang lurus di
depannya. Lalu sawah. Kemudian Soetomo. Akhirnya seorang juru
telegram yang bisa merangkap berbagai tugas lain.
Di malam hari, stasiun kecil itu bagai sebuah kubu di tengah
hutan gelap, dikerubungi kunang-kunang dan suara kodok. "Meski
stasiun kecil, jangan dianggap sepele," kata kepala stasiun (KS)
Sentolo, Soetomo "sebab, keamanan perjalanan keretaapi di
sekitar ini, banyak tergantung pada kami."
Soetomo mengingatkan peristiwa tabrakan KA di antara stasiun
Notog dan Kebasen (Purwokerto) Januari lalu. Kejadian itu,
tambah Soetomo, menunjukkan betapa penting peranan
petugas-petugas di stasiun kecil, khususnya KS dan PPKA
(Pimpinan Perjalanan KA).
Bukan Nampang
Dan memang, menurut Kepala PJKA, Ir. Pantiarso, kecelakaan yang
menewaskan 7 penumpang dan puluhan luka-luka itu, disebabkan
kelalaian PPKA Kebasen. Kata Pantiarso, seperti diberitakan
Sinar Harapan pekan lalu, "PPKA stasiun Kebasen tidak cermat
menghentikan KA-21 yang datang dari jurusan Yogya." Dan itu satu
kesalahan besar, tambah Kepala PJKA itu. Karenanya PPKA Kebasen
itu dibebas-tugaskan tak lama setelah kejadian tadi dan akan
segera diadili.
Karena itu, meskipun bertugas di stasiun kecil, sebagai KS yang
merangkap PPKA, Soetomo selalu sibuk. Lebih-lebih malam hari,
saat-saat kereta-api banyak lewat. "Yang paling berat antara
pukul 8 malam sampai pukul 4 pagi," tutur Soetomo. Karena pada
jam jam sibuk itu pula kantuk susah dilawan.
Di stasiun Sentolo hampir tak pernah ada KA yang berhenti,
kecuali kalau kebetulan harus bersilangan. Namur yang selalu
menyibukkan KS maupur PPKA adalah melayani alat-alat komunikasi
yang berhubungan dengan stasiun sekitarnya: adakah rel aman,
artinya tidak sedang dilewati KA. Jika aman, kereta boleh terus.
Sebaliknya kalau sedang dilewati KA, kereta yang lain harus
menunggu. Dan seterusnya.
Di Sentolo terdapart 3 macam alat komunikasi. Telepon, telegrap
dan yang terakhir sistem blok -- satu sistem sinyal yang akan
menyala dengan sendirinya bila suatu jalur rel sedang dilewati
kereta. Dari ketiga jenis alat ini, paling tidak 2 yang harus
dipakai untuk pengecekan. "Tapi setelah terjadi tabrakan di
Purwokerto, ketiga alat ini dipakai terus berganti-ganti, agar
lebih meyakinkan," kata Soetomo lagi.
Untuk menghentikan kereta jika rel tidak aman, PPKA juga
menggunakan 3 macam cara. Yaitu sinyal, bendera merah (untuk
siang hari) dan lampu ting merah (untuk malam). "Kalau semua
cara untuk menyuruh berhenti sudah dipakai, kereta masih juga
berjalan, itu berarti masinisnya sudah benar-benar gila," ucap
Soetomo. Tapi ia senang juga mendengar rencana PJKA untuk
memakai radio yang dapat menghubungkan awak kereta dengan
stasiun terdekat.
Dalam keadaan apa pun, setiap ada kereta lewat, Soetomo berdiri
di pinggir rel. "Tugas itu bukan untuk nampang," ungkapnya pula
"tapi semata-mata untuk mengawasi kereta, kalau-kalau ada
rangkaian yang tak beres dan masih adakah semboyan akhir."
Semboyan ini, atau lazim juga disebut semboyan 21, adalah tanda
merah pada gerbong terakhir kereta itu. Kalau tanda itu tak ada,
berarti ada rangkaian KA yang terlepas dan PPKA harus
menghentikan kereta dengan menggoyang-goyangkan sinyal di ujung
rel stasiun.
Soetomo yang berasal dari Godean, Kab. Sleman, Yogyakarta, juga
merangkap sebagai KS Rewulu, beberapa KM di timur Sentolo. Ia
lulus SPG Yogya tahun 1973. Tapi rupanya ia tak berniat jadi
guru, "karena saat itu masa depan guru masih suram," katanya.
Karena itu ia melamar di PJKA Eksploitasi Tengah di Semarang dan
diterima. Begitu selesai masa pendidikan, ia ditempatkan di
stasiun Rewulu dan Sentolo, sampai sekarang.
Dengan masa kerja 8 tahun (termasuk masa pendidikan), setiap
bulan ia mendapat penghasilan Rp 57.000 -- termasuk tambahan Rp
150 setiap berdinas dan uang lembur yang Rp 125 per jam. Dengan
seorang istri dan satu anak, cukupkah? "Jelas cukup," jawabnya
tegas. Sebagai KS ia menempati rumah dinas.
Yang paling menyenangkannya seba ai karyawan PJKA adalah
disiplin. "Karena disiplin PJKA begitu ketat, saya merasa telah
menjadi orang yang paling berdisiplin," ungkapnya. Satu contoh
kecil saja: kalau PPKA lupa memakai topi merah ketika berdiri di
depan stasiun, masinis ada hak untuk tetap melarikan kereta,
walaupun sinyal ditutup. "Artinya, karena disiplin, tak ada
istilah lupa," tambah Soetomo.
Kelancaran sarana perhubungan darat sedikit banyak telah
mempengaruhi jumlah penumpang KA. Terutama kereta jarak dekat
yang biasa berhenti di stasiun-stasiun kecil. Apalagi karena KA
jarak dekat ini kebanyakan masih dibawa lokomotif tua yang kalau
sudah kepayahan tak segan-segan mogok di tengah sawah. Padahal,
sementara itu, mobil-mobil angkutan umum, terutama kolt, bagai
kesetanan menganjurkan penumpang sampai ke pelosok-pelosok desa.
Karena itu tak heran jika stasiun Sukorejo selalu sepi. Stasiun
kecil di antara Surabaya-Malang ini, dilalui KA 10 kali setiap
hari. "Tapi penumpang dari Sukorejo lebih senang naik kolt atau
bis dari pada kereta, untuk ke jurusan Malang maupun Surabaya,"
tutur KS Sukorejo, Slamet. Dan loket di stasiun itu pun jarang
buka. Kalau ada satu-dua calon penumpang, mereka langsung masuk
ke ruang kerja Slamet untuk membeli karcis.
Tak beda dengan stasiun-stasiun lain, Sukorejo juga sudah
memiliki alat komunikasi lengkap, termasuk sistem blok.
Karenanya Slamet beranggapan, hampir tak mungkin terjadi
tabrakan. "Kalau pun terjadi juga, pasti ada sesuatu yang sangat
tidak beres," ucapnya.
Slamet, 54 tahun, sejak 1966 menempati posnya di Sukorejo.
Dengan 8 orang anak, ia mengaku lebih seperdua dari usianya
habis di sela-sela rel kereta. "Tapi tahun ini saya sudah MPP,"
ungkapnya dengan suram, "sebab tahun 1982 saya dipensiun."
Dengan gaji Rp 96.000 sebulan, tak ada pengalaman luar biasa
yang didapatnya selama di PJKA. "Paling-paling tak enak hati,
kalau dimaki penumpang, karena kereta terlambat datang atau
mogok di tengah jalan," katanya. Misalnya terjadi akhir tahun
lalu. Sebuah loko keretaapi Surabaya-Malang mogok di tengah
malam tak jauh dari stasiun Sukorejo. Meskipun Slamet sudah
berpayah-payah mencari kolt dan bis untuk mengangkut para
penumpan yang tak sabar, tak urung ia kena pisuh juga.
"Seakan-akan saya yang menyebabkan lok itu mogok," keluhnya.
Namun Slamet menerima saja semua makian itu. "Saya sudah tua dan
toh tak lama lagi pensiun," ia menambahkan.
Hallo Cirebon, bagaimana 120, nongkrong? Sindanglaut 120 . . .
nongkrong Cirebon, bagaimana 121, . . . aman Songgom. O, ya, ya.
Hampir setiap hari kata-kata itu menvembur dari mulut Sumedi ke
arah alat telepon yang dipegangnya. Pada saat-saat seperti itu
KS Luwung tadi sedang mengecek kereta-api yang akan melintas,
baik dari Cirebon maupun Sindanglaut. Stasiun Luwung terletak di
lintasan jalur KA Jakarta-Yogyakarta, antara Cirebon dan
Sindanglaut.
Bertugas di Luwung sejak 1972, Sumedi, 44 tahun, mengaku memang
lebih senang berada di stasiun kecil. Karena, katanya, dengan
gaji Rp 80.000 sebulan untuk menanggung istri dan 10 anak, tak
mungkin ia dapat tenteram hidup di kota besar. Bahkan di tempat
tugasnya sekarang, ia mengh abiskan waku senggangnya untuk
mengolah sawah di tanah PJKA tak jauh dari stasiun. "Hasilnya,
1,5 ton padi setiap panen, cukup untuk makan," tutur Sumedi.
Stasiun itu selalu sepi. Karenanya Sumedi merasa senang juga
kalau terjadi persilangan dan ada KA cepat yang harus berhenti
di stasiunnya. "Suasana jadi ramai," katanya. Hanya di saat
serupa itu ia bisa susah kalau ada penumpang yang menanyakan
kamar kecil. "Soalnya WC di sini sudah lama mati," tambah Sumedi
menyesal. Ia dan teman-teman sekerjanya, harus menyelinap di
tengah sawah, tiap kali hendak buangair.
Sudah 24 tahun Sumedi hidup dengan kereta-api. Sejak di Luwung
memang tak banyak yang dia kerjakan. Tak ada kereta yang
berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di sini. Semua
ditampung stasiun Cirebon dan Sindanglaut. Bahkan, mulai pukul
15.00, nyaris tak ada lagi yang perlu diawasi Sumedi dan anak
buahnya di stasiun ini. Sebab sesudah jam itu, tugas stasiun
Luwung diambil-alih Cirebon dan Sindanglaut.
Tapi lewat jam itu, di rumah juga hampir tak ada yang dikerjakan
Sumedi --selain bercengkerama dengan anak-anak dan istrinya.
"Malam di sini sangat sepi, tak ada hiburan," kata Sumedi.
Mungkin karena itu, hampir tiap 2 tahun sekali istrinya
melahirkan anak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini