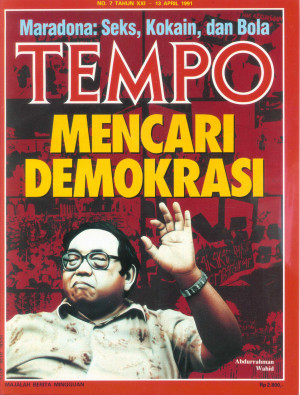HARAPAN bekas bos Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. John Naro, 62 tahun, untuk menguasai kembali tanah miliknya seluas 2,6 ha di Kampung Sawah, Palmerah, Jakarta Barat, hampir pupus. Selain diduduki oleh rakyat, tanah itu ternyata juga sarat perkara. Kecuali Naro, seorang swasta lain, Eddy Tandyowidjojo dan Oditurat Jenderal ABRI, mengklaim tanah itu sebagai miliknya. Puncaknya, baru-baru ini, BPN membatalkan sertifikat HGB Naro untuk tanah tersebut, yang dikeluarkan sejak 25 Juli 1979. Tak ada jalan lain, Wakil Ketua DPR/MPR yang bekas calon wapres itu terpaksa kembali ke pengadilan. Melalui Pengacara Gunadi Ramelan, kali ini Naro menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. "Mana bisa Kepala BPN membatalkan keputusan instansi yang lebih tinggi (Menteri Dalam Negeri dan Gubernur DKI Jakarta), yang telah mengabulkan pemberian sertifikat tersebut?" kata putra Naro, Hussein Naro. Tanah itu, yang berasal dari eigendom (hak milik Barat), letaknya memang strategis, di sudut persimpangan jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak dengan Jalan S. Parman. Semula tanah itu merupakan bagian dari satu paket tanah seluas 9 ha milik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hatta, pada 1976, Naro membeli 4,7 ha dari tanah itu dari Ketua PBNU, waktu itu Kiai Idham Chalid, dengan harga Rp 165 juta. Seluas 2,1 ha dari tanah itu terkena proyek jalan tol, sisanya (2,6 ha) menjadi milik Naro. Hebatnya, pada 1980, lewat proses hibah, Naro memperoleh lagi sisa tanah PBNU, seluas 4,3 ha (seluas 2,5 ha menjadi milik Naro, sisanya untuk jalan tol). Pada 1979, Naro pun berhasil memperoleh sertifikat HGB atas tanah miliknya seluas 2,6 ha tadi. Untuk itu, ia menyetor Rp 42 juta lebih ke kas negara dan memberikan ganti rugi kepada para penggarap. Rencana Naro, pada awal 1992, di atas tanah itu sudah berdiri hotel berbintang lima "Crown Plaza", yang bernilai Rp 116 milyar. Ternyata, rencana itu berantakan. Naro tak kunjung bisa menguasai kembali tanah tersebut. Hingga kini tanah itu tetap "diduduki" sekitar 1.500 keluarga, yang menurut Naro cuma berstatus penggarap. Selain itu tanah tersebut juga sarat perkara. Eddy Tandyowidjojo, misalnya, mengaku membeli 82.460 m2 dari tanah tersebut pada 1971, juga dari PBNU. Sementara itu, Oditurat Jenderal ABRI juga mengklaim sebagai pemilik sah seperempat bagian dari tanah itu. Hal itu sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tertanggal 21 Mei 1985, dalam kasus korupsi bekas anggota ABRI, almarhum Markono. Sebab itu, Naro menggugat Oditurat Jenderal di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sementara gugatan itu disidangkan, pada November 1990, tiba-tiba BPN membatalkan sertifikat Naro. Rupanya, tindakan BPN itu berdasarkan permohonan Oditurat Jenderal. "Seharusnya BPN menghormati proses peradilan," ujar Hussein Naro. Lagi pula, kata Hussein, ayahnya memperoleh tanah tersebut sesuai dengan prosedur. Karena itu, ia menimpakan segala "kekalahan" itu pada Kepala BPN, Soni Harsono. "Itulah kalau Kepala BPN insinyur perkapalan, bukan orang yang mengerti hukum agraria," kata anggota FPP-DPR itu, dengan nada keras. Menurut Soni Harsono, BPN membatalkan sertifikat Naro itu karena banyak pihak yang mengklaim sebagi pemiliknya, sehingga statusnya tumpang tindih. Kecuali itu, prosedur penerbitan sertifikat itu juga keliru. Panitia pembebasan tanah waktu itu, katanya, menyatakan tanah itu milik Naro. Padahal, sejak 1975 tanah itu sudah disita Oditurat Jenderal. Namun, kata Soni lagi, instansinya belum memutuskan tanah itu pastinya milik siapa. Termasuk bagian tanah mana yang milik Naro dan mana yang milik pihak lain. Sampai kini BPN masih meneliti kasus tanah tersebut. Prinsipnya, "Sertifikat tanah harus diterbitkan sesuai dengan riwayat tanahnya," ujar Soni. Kasus tanah Naro memasuki babak baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini