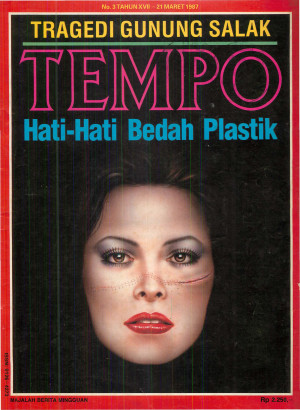TAK sedikit yang berharap. Bahkan tak kedengaran yang menolak ketika akhir 1981, KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), itu lahir. Hukum acara, yang telah melahirkan lembaga baru praperadilan, itu bukan hanya menyebabkan hakim bisa menguji dengan seketika keabsahan polisi menangkap dan menahan orang. Juga, hakim bisa memutuskan ganti rugi bagi tersangka yang ditahan atau dituntut dengan sewenang-wenang oleh polisi dan jaksa. Namun, pekan lalu, segala keampuhannya itu dipertanyakan oleh ratusan orang peserta simposium Evaluasi Pelaksanaan KUHAP yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, Ikadin, dan organisasi hakim, Ikahi, di Jakarta. Karena, antara lain, dari banyak pencari keadilan yang memohon praperadilan, hanya segelintir yang dikabulkan hakim. "Seakan-akan antara polisi, jaksa dan hakim sudah ada jaringan untuk menggiring agar terdakwa memang bersalah," kata Nyonya Muria S. Doko, advokat dari Trisula Kupang. Kritik itu sebenarnya tidak baru. Tapi yang menarik, Hakim Din Muhammad dari Ikahi, dalam makalahnya, membenarkan banyak kasus praperadilan yang masuk ke pengadilan, terutama menggugat wewenang polisi, berakhir dengan kekalahan pemohon. Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tempat ia bertugas, misalnya, dari 18 permohonan praperadilan yang masuk dalam lima tahun ini, hanya sebuah yang dikabulkan. Si pemohon adalah seorang tersangka, yang ternyata tidak bersalah -- tapi sempat mendekam di tahanan -- lalu mendapat ganti rugi Rp 200.000. Data di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu agaknya bisa menggambarkan warna praperadilan di pengadilan-pengadilan Indonesia. Di Pengadilan Negeri Medan, kata Din, dari 29 permohonan -- 27 gugatan ke polisi -- hanya satu yang dikabulkan. Data yang lebih lengkap diungkapkan oleh penyanggah dari Polri, Mayor Pol Wagimin Prijawibawa. Dari 140 permohonan praperadilan di Indonesia, sejak 1984 sampai 1986, katanya, hanya 20 permohonan yang dikabulkan hakim. Sebab itu, Hakim Din risau dan mengharapkan peserta simposium mencari jalan keluarnya. "Agar lembaga itu tidak menjadi hidup segan mati tidak mau," kata Din, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebagai hakim, Din tentu saja tidak semata-mata hendak menyalahkan para hakim. Sebab, kata Din, di Negeri Belanda, tempat asal nenek moyang hukum pidana Indonesia, dari 29 permintaan ganti rugi akibat penahanan dan penangkapan tidak benar, hanya 4-5 kasus yang dikabulkan hakim. Hakim Din lebih cenderung menganggap kegagalan lembaga itu akibat lubang-lubang dari perundang-undangan itu sendiri. Penangkapan dan penahanan, misalnya, Din menganggap tidak mendapat perhatian khusus dari pembentuk undang-undang. Untuk menahan orang, polisi, katanya, cukup memenuhi syarat asal mendapat bukti permulaan yang memadai -- tidak pula ada kriterianya -- sementara untuk penyitaan dan penggeledahan diperlukan izin dari hakim. "Menjadi pertanyaan, mengapa tindakan yang begitu mendasar terhadap kebebasan seseorang tidak diberikan syarat -- seperti untuk penggeledahan," katanya. Padahal, di negara lain, yang mempunyai juga lembaga semacam praperadilan, setiap penahanan harus dengan izin hakim atau jaksa. Tentu bukan hanya kesalahan pembuat undang-undang sehingga lembaga yang sangat diharapkan menjamin hak asasi tersangka itu menjadi "macan kertas". Faktor pelaksana-pelaksananya juga menentukan seperti pernah diungkapkan Ketua Mahkamah Agung Ali Said, ketika undang-undang itu dilahirkan. Berdasarkan laporan wartawan TEMPO dari berbagai daerah, selama lima tahun KUHAP berlaku, faktor pelaksana banyak menentukan -- sehingga lembaga itu menjadi tidak berwibawa. Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, misalnya, sebuah perkara praperadilan terpaksa digugurkan hakim gara-gara Kapolres Tapanuli Selatan, Letkol Pol Ansyar Roem, yang digugat bekas tersangka karena menahan tidak sah dan menganiaya di tahanan, menolak untuk diadili lembaga itu. Semula Ansyar tidak mau diadili karena ia meragukan keabsahan izin praktek pengacara yang menggugatnya. Ternyata, setelah izin praktek itu diperlihatkan hakim di sidang, pihak polisi tetap menolak peradilan itu -- karena telah melewati waktu 7 hari seperti ditentukan undang-undang. Setelah dua bulan bersitegang, akhirnya, Hakim Djauti kembali membuka sidang. Tapi lagi-lagi wakil pihak polisi menolak. "Kami belum mendapat petunjuk dari Kapolri," kata mereka. Akhirnya, Djauti menyerah, ia menggugurkan sidang itu dengan alasan pengacara lalai menunjukkan izin prakteknya (TEMPO, 9 Maret 1985). Nasib terdakwa, yang diwakili para pengacara di praperadilan, juga tidak lebih baik dari kuasanya. Beberapa terdakwa tidak bisa hadir di sidang bukan atas kemauannya sehingga perkaranya gugur. Salah satu dan kasus itu adalah lenyapnya Udin, tersangka pemerasan, sehari sebelum pengadilan mendengar keterangannya dalam gugatan praperadilan terhadap Kapolda Jawa Barat. Ternyata, sejak malam itu, ia sudah mendekam kembali di tahanan polisi, sehingga perkaranya terpaksa dibatalkan hakim (TEMPO, 31 Maret 1984). Adakah gara-gara itu orang enggan ke praperadilan? Mayor Pol Wagimin Prijawibawa menuding ulah "penjual jasa" bantuan hukumlah, sebenarnya, yang menyebabkan banyak gugatan praperadilan ditolak hakim. Sebab, banyak persoalan yang digugat itu sesungguhnya "Mereka hanya menitikberatkan dari segi finansialnya, dengan berkedok luhur membela hak asasi," kata Wagimin. Karni Ilyas, Laporan Eko Yoeswanto (Biro Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini